REALISME SOSIALIS PRAMOEDYA
ANANTA TOER
(Telaah dalam Novel Tetralogi)

SKRIPSI
DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS USHULUDHIN
UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARA SATU
DALAM AQIDAH FILSAFAT
Oleh
Nur Laela Faristin
NIM : 00510152
DI
BAWAH BIMBINGAN:
Drs. Sudin, M. Hum.
Shofiyulloh, Mz. M. Ag.
AQIDAH FILSAFAT FAKULTAS
USHULUDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
2005
ABSTRAK
Realisme sosialis adalah
salah satu aliran dalam sosialisme yang bergerak dalam kancah sastra atau
kesenian. Semangat realisme sosialis ialah untuk memenangkan sosialisme di
tengah masyarakat. Maka di dalam sastra aliran realisme sosialis, realitas
masyarakat adalah inspirasi untuk membuat karya. Yang di maksud dengan realitas
masyarakat ialah kaum proletar, dan
di atas pundak kaum sastrawan realisme sosialis tertanam tanggung jawab yang
tidak ringan yaitu memberi penyadaran kepada masyarakat yang tertindas sehingga
masyarakat tersebut berjuang untuk melawan sistem yang menindas tersebut.
Demikian pula di dalam novel tetralogi, yang terdiri dari empat jilid. Yaitu
Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak langkah dan yang terakhir adalah Rumah
Kaca. Ke empat novel tersebut berisikan perjuangan orang Indonesia
Hal tersebut untuk menjaga
ke objektifan sebuah tulisan yang di dalamnya berisikan lahirnya
organisasi-organisasi yang ada di Indonesia Indonesia Indonesia
DAFTAR ISI
HALAMAN
JUDUL……………………………………………………………………i
HALAMAN NOTA
DINAS……………………………………………………………ii
HALAMAN
PENGESAHAN………………………………………………………….iii
HALAMAN PERSEMBAHAN……………………………………………………….IV
HALAMAN
MOTTO…………………………………………………………………..V
KATA PENGANTAR
…………………………………………………………………VI
ABSTRAKSI.…………………………………………………………………………VIII
DAFTAR
ISI……………………………………………………………………………IX
BAB I: PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Masalah……………………………………………………1
2.
Rumusan
Masalah………………………………………………………….10
3.
Tujuan dan kegunaan
Penelitian….………………………………………..10
4.
Telaah
Pustaka……………………………………………………………..11
5.
Kerangka
Teori…………………………………………………………….13
6.
Metode
Penelitian………………………………………………………….15
7.
Sistematika
Pembahasan…………………………………………………..18
BAB II : BIOGRAFI PRAM DAN KARYA-KARYANYA
1.
Selayang Pandang Perjalanan
Hidup Pramoedya…………………………20
2.
Setapak Sejarah Menuju Realisme
Sosialis……………………………….22
3.
Sepenggal Cerita Lahirnya Novel
Tetralogi……………………………….42
BAB III :
REALISME SOSIALIS SEBAGAI PANDANGAN PRAM DALAM NOVEL TRETALOGI
1.
Realisme Sosialis Pramoedya dan
Paradigma Realisme Sosialis dalam Sastra ………………………………………………………………………51
2.
Pandangan Pramoedya tentang
Realisme Sosialis dalam Novel Tetralogi………………………………………………………………..…..59
3.
Faham Realisme Sosialis dalam
Realitas Empirik…………………………76
BAB IV : PANDANGAN SUBTANSIAL REALISME SOSIALIS DALAM NOVEL
TETRALOGI
1.
Realisme Sosialis Sebagai Upaya
Membentuk Paradigma dan
Orientasi Kehidupan………………………...……………………………..86
2.
Pandangan Pramoedya Ananta Toer
tentang Organisasi sebagai
Sikap Melawan
Imprealisme……………………………………………….92
3.
Pandangan Pramoedya Ananta Toer
tentang Jurnalistik sebagai
Jalan Efektif Membangun
Kesadaran…..………………………………...101
BAB V : PENUTUP
1.
Simpulan………………………………………...……………….……….107
2.
Saran-saran………………………………………...………………..…….108
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bangsa Indonesia Indonesia Indonesia
Tetapi krisis tersebut tidak menimpa setiap warga Indonesia
Kesenjangan ekonomi jelas terlihat di
negeri ini, yang kaya bisa hidup laksana di surga, namun yang miskin hidup
dengan penuh kesengsaraan. Karena perbedaan hidup antara orang kaya dengan
orang miskin dapat melahirkan ketidak adilan dari segi ekonomi antara orang
kaya dan orang miskin. Orang kaya bisa mengupah buruh dengan rendah, sehingga
buruh tersebut tidak mampu membeli barang yang dibuatnya dan bila buruh meminta
kenaikan gaji meski hanya 500 rupiah ancamannya adalah PHK. Dari kesenjangan
tersebut banyak masyarakat yang melakukan segala macam cara untuk mencari
kekayaan. Moral sudah tidak lagi dipakai untuk mendapatkan harta, selagi masih
ada kesempatan maka dengan segera meraihnya. Entah itu melanggar hak asasi
manusia ataupun tidak.
Kesenjangan ekonomi tersebut tercipta
karena sistem yang lebih memihak pada pemilik modal, sedang kaum lemah atau
miskin kurang mendapat akses untuk merubah ekonominya. Dalam hal ini kajian
realisme sosialis banyak memotret tentang perbedaan tersebut. Novel Tetralogi sebagai
sebuah aliran realisme sosialis sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam.
Terutama ketika aliran tersebut telah
menjadi sebuah novel, pertentangan antara masyarakat miskin dengan pemilik
modal sangat terlihat. Sehingga pembaca tidak pernah bosan untuk terus
mengikuti alur yang ada dalam cerita, sebab permasalahan yang diangkat dalam
novel aliran realisme sosialis tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang dihadapi
sehari-hari. Tidak sebagaimana sinetron-sinetron di layar kaca, yang lebih
sering menampilkan kekayaan padahal masih banyak masyarakat kita yang hidup di bawah
garis kemiskinan, aliran realisme sosialis dalam novelnya sama sekali tidak
menceritakan hal-hal yang menjual mimpi. Aliran realisme sosialis dalam
novelnya lebih sering menampilkan keadaan yang sebenarnya.
Keadaan masyarakat yang tertindas
oleh pemilik modal, atau para petani
yang terampas tanahnya sehingga petani tersebut harus menjadi buruh.
Tugas aliran tersebut tidak saja berhenti sampai di sana
Sebagai mana pendapat salah satu
tokoh yaitu Maxim Gorki, sebagai mana yang di catat oleh Lukacs, karya sastra
yang sejati adalah karya sastra yang populer, karena sastra yang sejati akan
mampu membuka jalan bagi manusia untuk berkembang menjadi manusia yang benar.
Dengan demikian misi utama karya sastra adalah mengugah kesadaran manusia.[1]
Hal tersebut juga dilakukan oleh
Pramoedya Ananta Toer, sebagai pengarang yang menganut faham aliran realisme
sosialis, Pramoedya Ananta Toer juga menuliskan pertentangan antara orang miskin
dengan orang kaya. Daya tarik novel Pramoedya Ananta Toer karena pertentangan
tersebut juga dirangkai dengan pergolakan masa pergantian zaman, yaitu masa
revolusi kemerdekaan. Sehingga semangat perlawanan terhadap segala hal yang
menjajah dapat dibaca secara jelas.
Dari segi penokohan, nampaknya
Pramoedya Ananta Toer juga cukup selektif. Pramoedya Ananta Toer tidak terlalu
banyak meramaikan karyanya dengan nama-nama yang tidak perlu. Pramoedya Ananta
Toer hanya membatasi nama Minke, keluarga dan orang di sekelilingnya. Yang
lebih menarik novel karya Pramoedya Ananta Toer (selanjutnya akan di tulis
Pram) ini juga menulis sejarah lahirnya organisasi-organisasi di Indonesia
Karakteristik Pram dalam
mendiskripsikan situasi psikologis dan sosiologis tokoh-tokohnya sedemikian
memikat. Dengan sudut pandang orang pertama (aku), misalnya saja, Pram
memperkenalkan sang tokoh utama, seperti ini:
“Orang memanggil aku: Minke”jelas
nama yang sangat aneh, tidak lazim. Kalau ini nama ningrat Jawa, lalu artinya
apa? Sebab, nama-nama ningrat Jawa sendiri selalu mempunyai arti[2].
Ternyata, nama Minke diberikan ketika
dia sekolah di ELS. Saat itu, ada seorang gadis bernama Vera yang mencubit
pahanya sebagai tanda perkenalan. Karena tidak mampu menahan sakit, Minke pun
menjerit kesakitan, gurunya Meneer Ben Rooseboom membentak melotot: “Diam kau,
monk…!”. Saat itu, Minke merupakan satu-satunya murid pribumi, sedangkan guru
dan teman-temanya jelas adalah bangsa Eropa (Belanda Totok). Karena itu, Minke
sebenarnya merupakan sebutan yang merendahkan terhadap golongan pribumi, untuk
menunjukkan sebagai monyet (monkey)[3].
Pelajaran sejarah yang ada sudah
sering menuliskan nama-nama pahlawan nasional yang sudah terkenal, seperti Pangeran
Diponegoro, Cut Nya Dien, dan masih banyak lagi. Tetapi di dalam novel tetralogi
tersebut sama sekali tidak di sebutkan nama para pahlawan nasional, justru
dalam novel yang terdiri dari empat jilid yaitu, Bumi Manusia, Anak Semua
Bangsa, Jejak Langkah dan yang terakhir Rumah kaca, menggambarkan tentang
perjuangan orang-orang kelas bawah dan tokoh yang diberi nama Minke sebenarnya
adalah tokoh jurnalis pertama di Indonesia yaitu Tirto Adhi Suryo.
Makna yang lebih penting dari novel tetralogi ini adalah, bentuk roman
sejarah mengarahkan pembaca tidak hanya untuk interprestasi karya sastra, monel
teralogi juga mengantarkan kepada makna sejarah yang terjadi pada saat itu. Pengarang berusaha melakukan apa yang
diharapkan dari sejarawan yang baik, yang juga harus berusaha memperlihatkan
kaitan dan hubungan antara segala macam kejadian dan data yang dikumpulkannya
serta memunculkan gambaran total. Pembaca dibuat tergoda untuk menganalisis
setiap kejadian, agar tidak hanya memihak partai secara literer, melainkan juga
politik Indonesia
Faham realisme sosialis telah mengilhami Pram
yang sering kali melahirkan pemikiran yang kritis terhadap apa yang sedang
terjadi saat itu. Semangat terhadap perlawanan sistem kolonialisme dapat
dirasakan dalam karya-karya Pram. Karena dalam novel Pram, bukan hanya sekedar
tulisan fiksi semata. Namun karya-karya Pram juga lahir berdasarkan realitas
yang ada. Sebab menurut Pram penulis hidup di tengah-tengah “ masyarakatnya”,
yang di maksud dengan masyarakatnya adalah orang yang secara ekonomi terindas
dan mereka memerlukan dorongan semangat untuk melakukan perubahan ekonomi.
Masyarakat memberi materi-materi kepada penulis. Penulis yang berhasil, diharap
memberikan pengaruhnya pada kondisi dan kehidupan sosial. Itu hubungan
timbal-balik. Jadi kalau ada pengarang yang hanya berdasarkan fantasi, itu
namanya ‘setengah gila’.[5]
Hal yang menarik novel tetralogi
tersebut dibuat saat Pram berada di balik terali besi, Pram di penjara di Pulau
Buru . Pulau Buru terletak sekitar 1.500 kilo
meter ke arah timur dari Nusa Kambangan[6].
Karya novel tetralogi justru karya yang
paling monumental atau menjadi karya puncak dari sebuah penulisan yang dilakukan
oleh Pram.
Tetralogi juga menjadi karangan Pram,
yang menjadi polemik dan bahan pembicaraan, karena secara politis, novel ini
menjadi begitu istimewa dan fenomenal. Novel Tetralogi menurut Pram ditulis
secara lisan pada tahun 1973, karena ditulis dalam penjara di Pulau Buru dan
kemudian ditulis secara sistematis sebagai cerita utuh pada 1975. Keempat buku
tersebut; Bumi Manusia, kemudian Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, serta Rumah
Kaca dilarang penerbitannya oleh oleh rezim Orde Baru semenjak 1981 yang
ironisnya, larangan yang dikeluarkan pihak Kejaksaan Agung itu sampai sekarang belum pernah dicabut seperti
saat ini[7].
Novel tetralogi banyak sekali
mendapatkan piagam penghargaan terutama dari luar negeri, sebab di dalam negeri
Pram sendiri masih di cap sebagai agen pemberontak atas keterlibatannya dalam
Lekra. Lembaga Kesenian Rakyat sebagai wadah kesenian PKI Maka secara otomatis
ketika PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan semua anggotanya di penjara
ataupun dibunuh, maka Lekrapun secara otomatis juga dibubarkan dan dinyatakan
sebagai organisasi kesenian yang terlarang, dan semua anggotanya juga dipenjara
atau dibunuh.
Pram sendiri menggambarkan, bahwa masuknya
Pram sebagai anggota Lekra tidaklah sebagaimana yang digambarkan orang, Pram
masuk Lekra secara sukarela. Menurut Pram ia tidak pernah bergabung dengan
Lekra mulai dari bawah, melainkan diundang dan kemudian menjadi anggota. Inilah
yang dianggap Pram sebagai kesulitannya, ia menganggap dirinya diambil begitu
saja oleh Lekra. Padahal banyak orang lama Lekra yang tidak suka akan diri Pram[8].
Jika dihubungkan dengan realitas yang
ada, novel Pram sangat menampilkan kenyataan yang dialami oleh masyarakat
terutama kelas bawah, penderitaan-penderitaan mereka tanpa malu-malu ditampilkan
secara jelas. Hal tersebut tidak lepas dari aliran yang dianutnya yaitu
realisme sosialis sebab paham realisme sosialis berasal dari sosialisme
Marx konsep tentang manusia. Oleh
karenanya, jelaslah bahwa, menurut konsep tentang manusia ini, sosialisme bukan
sebuah masyarakat yang tersusun atas individu-individu yang diatur dan secara otomatis
mengabaikan apakah mereka memiliki pendapatan yang cukup atau tidak. Sosialisme
bukanlah masyarakat dimana individu tersubordinasikan oleh negara[9].
Pemerataan ekonomi masyarakat di bawah tanggung jawab negara, sehingga tidak
terjadi ketimpangan ekonomi.
Marx menjelaskan seluruh elemen pokok
sosialisme. Manusia berproduksi dengan cara bekerja sama, bukan berkompetisi, yang
berarti bahwa dia berproduksi secara rasional tanpa teralienasi, dan dia
berproduksi di bawah kendalinya sendiri[10].
Teori di atas saat ini sedang di
terapkan di Cina, sebagai negara penganut faham komunis teori tersebut ternyata
sungguh mampu mengatasi persaingan global yang sekarang sedang terjadi. Seperti
di Cina teknologi elektronik, itu menjadi home
industri, semisal dalam hal industri kendaraan, satu desa membuat rangka
kendaraan saja, desa lainnya membuat ban dan desa yang lainnya membuat bahan yang
diperlukan untuk membuat alat transportasi. Setelah itu masyarakat menyetorkan
hasil buatannya kepada pabrik yang di kelola oleh pemerintah, bagian
pemasaranpun dilakukan oleh pemerintah. Sebagai mana yang terjadi sekarang, Indonesia
Pada awal tahun 1840, istilah
“sosialis” dan “komunis” tidak punya arti yang jelas. Kini “sosialisme”
berarti, bertentangan dengan “kapitalisme”. Konsep tentang kapitalisme sebagai
suatu bentuk masyarakat yang mapan,
tidak ada, sampai Marx menemukannya. Dalam bukunya Das kapital, Marx mengurai tema-tema buku tersebut yaitu hubungan
antara kapitalis dengan upah kerja atau kerja upahan, hubungan antara kapitalis
dengan pekerja[11].
Dalam realitas masih banyak buruh yang tidak mendapat gaji
yang memadai, para buruh tersebut hidup di bawah garis kemiskinan. Meski
pemerintah sudah mengaturnya dalam peraturan daerah, tetapi kenyataannya masih
banyak gaji buruh yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Apalagi untuk
menjaga kesehatan yang sangat mahal, tentu saja kaum buruh kesulitan. Banyak
juga kasus para buruh yang tidak dibayar gajinya dengan alasan perusahaannya gulung
tikar.
Adapun hubungan skripsi yang akan
diangkat oleh penulis dengan jurusan
Aqidah Filsafat adalah, skripsi tersebut akan membahas masalah novel
tetralogi dengan memakai pisau analisis realisme sosialis. Realisme sosialis
tersebut adalah salah satu aliran dalam filsafat, sesuai dengan jurusan yang
ditempuh oleh penulis. Sebab induk dari realisme sosialis adalah sosialisme,
yang di cetuskan oleh seorang filosof bernama Karl Marx.
B. Rumusan
Masalah.
Dengan uraian panjang lebar pada
latar belakang diatas, penulis sesungguhnya ingin merumuskan permasalahan
sebagai berikut,
“ Bagaimana pandangan realisme sosialis Pramoedya Ananta
Toer dalam novel tetralogi? “
C. Tujuan
Penelitian dan Kegunaan Penelitian
Dari awal melakukan penelitian ini
penulis merasa tertarik meneliti
realisme sosialis yang terkandung dalam novel Tetralogi, diharapkan
nantinya mampu mengetahui apa yang dimaksud realisme sosialis dan mengetahui
bagaimana pandangan Pram tentang realisme sosialis dalam novel tetralogi.
Diharapkan dengan penelitian ini
dapat memiliki kegunaan baik yang bersifat teoritis maupun praksis. Secara teoritis,
penelitian ini akan merupakan sumbangan yang cukup berharga bagi pengembangan
ilmu pengetahuan, terutama studi ilmu-ilmu sosial, khususnya filsafat sosial.
Secara praksis, sebagai sebuah landasan teoritis, penelitian ini tentunya diharapkan
mampu memberi sumbangan yang berharga, yang kaitannya dalam upaya mewujudkan
tatanan masyarakat yang demokratis, terciptanya civil society, yang dapat menghargai perbedaan serta terbuka
terhadap kritik. Di samping itu juga untuk menambah wacana kepustakaan, khususnya
tentang pemikiran Pram dan umumnya terhadap studi ilmu-ilmu sosial.
Terakhir, yang tidak kalah
pentingnya, bahwa penelitian ini juga memiliki kegunaan formal, yakni untuk
memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan Strata satu (S-I)
di bidang Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
D. Telaah Pustaka
Sepengetahuan penulis ada dua skripsi
yang mengangkat tokoh Pramoedya Ananta Toer. Pertama yaitu skripsi yang ditulis
Ahmad Hambali yang berjudul “Pandangan
Pramoedya Ananta Toer tentang
Humanisme”[12].
Yang kedua Arif Sarwani “Teori pembebasan
dalam novel gadis pantai”[13].
Skripsi pertama mencoba menggambarakan tentang sisi humanisme dalam sudut
pandang Pramoedya Ananta Toer, sedang skripsi yang kedua menggambarkan teori
pembebasan dalam novel “Gadis pantai”
karya Pramoedya Ananta Toer.
Sedangkan A.Teeuw, kritikus sastra
dan pengamat sastra Indonesia modern berkembangsaan Belanda, dalam bukunya yang
berjudul Citra Manusia Indonesia dalam
Karya Pramoedya Ananta Toer telah mengulas secara umum karya Pram, kajian
atau penelitian yang dilakukan oleh A. Teeuw lewat buku Citra Manusia Indonesia dalam Karya Pramoedya Ananta Toer sebagai
pengantar untuk karya-karya Pram atau lebih khusus lagi sebagai kritik sastra
yang bertujuan memberikan tanggung jawab pembacaan terhadap karya sastra Pramoedya[14].
Lewat buku tersebut, Teeuw melakukan
pengkajian terhadap karya-karya sastra Pram dalam usahanya untuk mencitrakan
masing-masing tema yang terkandung dalam karya sastra Pramoedya. Dalam kajian
itu, Teeuw lebih menyoroti tema utama yang menjadi alur cerita dalam karya
sastra Pram. Telaah yang dilakukan Teeuw lebih berdasarkan pada kajian sastra
dari pada telaah yang bersifat filosofi.
Karya lain yang bisa dikatakan
sebagai kajian dari sudut sastra yang berupaya menelusuri kreativitas Pram dan karya seninya adalah karya dari Bahrum
Rangkuti, yang berjudul Pramoedya Ananta
Toer dan Karya Seninya. Karya ini secara umum mencoba mengkaji beberapa
karya Pramoedya yang dilihat dari segi gaya
Karya lain lagi yang secara khusus
mengupas dan menganalisis karya sastra Pramoedya adalah Analisa Ringan Kemelut Roman Pulau Buru
Bumi Manusia Pramoedya Ananta Toer. Buku ini secara khusus membicarakan
seputar kemelut pelarangan terbitnya roman Bumi
Manusia di tahun 1980-an dan analisa ringan dari sejumlah satrawan akan isi
novel tersebut. Sebuah roman yang cukup bagus dan berbobot, bahkan
dinominasikan untuk mendapatkan hadiah nobel di bidang sastra[16].
Adapun karya ilmiah yang lain, adalah
Eka Kurniawan yang diterbitkan dalam sebuah buku dengan judul Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme
Sosialis, ini mencoba meneliti ideologi estetis (sastra) yang dianut oleh
Pramoedya[17]. Eka
Kurniawan lebih menitik beratkan pada sejarah realisme sosialis yang mempengaruhi pemikiran Pramoedya Ananta
Toer, sedangkan dalam skripsi ini realisme sosialis dijadikan pisau analisis
untuk membedah novel tetralogi.
E. Kerangka Teori
Dalam kajian realisme sosialis
menggambarkan pertentangan antara klas proletar
dan juga klas borjuasi menjadi sebuah
masalah yang senantiasa diakui, dan masalah realisme sosialis itu lahir dari
sebuah realitas yang ada pada masyarakat. Meski dalam novel Tetralogi berlatar
belakang awal abad 20 dan akhir abad 19, pertentangan antara kelas borjuasi
dengan proletar itu sampai sekarang masih terjadi.
Istilah ini digunakan pertama kali pada
tahun 1905 di Uni Soviet. Realisme sosialis muncul dalam sebuah artikel anonim,
yang berjudul Notes on Philistinisme. Dalam
tulisan tersebut yamg disebarluaskan untuk menentang pemerintah berhubungan
dengan peristiwa “Minggu Berdarah” pada tanggal 22 Januari 1905, Gorki kemudian
ditangkap tetapi tidak lama kemudian dilepas karena membanjirnya protes-protes
internasinoal atas penangkapannya.[18]
Realisme sosialis, seperti nampak
pada namanya, adalah istilah yang terdiri atas dua kata yang di majemukkan.
Realisme sebagai istilah kesenian dan sastra pada umumnya bukanlah realisme
sebagaimana dikenal oleh dunia Barat selama ini, tetapi realisme sesuai dengan
istilahnya menurut tafsiran sosialis. Realisme sosialis sesuai dengan
istilahnya dengan sendirinya bukan realisme Barat. Pembedaan ini perlu karena
antara kedua realisme ini bukan hanya terdapat perbedaan tafsiran, tetapi yang
lebih penting untuk diketahui adalah adanya perbedaan dalam perkembangannya[19].
Istilah ini baru diumumkan pada tahun
1934 di hadapan Kongres I satrawan Soviet di Moskwa, melalui ucapan Andrei
Zidanov:
“Dalam
pada itu kenyatan dan watak historik yang konkret dari lukisan artistik mesti
dihubungkan dengan tugas pembentukan ideologis dan pendidikan pekerja-pekerja
dalam semangat sosialisme. Metode kerja sastra dan kritik sastra ini kita
namakan metode realisme sosialis”[20]
Sesui dengan teori materialisme
dialektika Karl Marx, tindakan adalah
yang pertama dan fikiran adalah yang kedua. Aliran ini berpendapat bahwa tidak
terdapat pengetahuan yang hanya merupakan pemikiran tentang alam, pengetahuan
selalu dikaitkan dengan tindakan. Pada zaman dahulu, menurut Karl Marx, para
filosof telah menjelaskan alam dengan cara yang berbeda-beda. Kewajiban manusia
sekarang adalah untuk mengubah dunia, dan ini adalah tugas misi yang bersejarah
dari kaum komunis[21].
Secara historis sosialisme mempunyai
gagasan yang menuntut adanya pemerintahan yang lebih baik dan berusaha
membuktikan kepada kelompok kaya dan pemilik modal bahwa eksploitasi itu tidak
bermoral. Sosialisme pada awalnya adalah sebuah reaksi minoritas terhadap
pelaksanaan etika kapitalis dan pengembangan masyarakat industri[22].
Sosialisme merupakan produk dari
perubahan-perubahan sosial yang mengubah masyarakat-masyarakat Eropa di akhir
abad kedelapan belas dan kesembilan belas. Inti dari sosialisme bukanlah
semata-mata bahwa produksi itu harus dipusatkan di tangan negara itu harus
seluruhnya merupakan peran ekonomi, di dalam masyarakat sosialis, pengelolaan
atau tata pelaksanaan ekonomi harus menjadi tugas dasar negara[23].
F. Metode
Penelitian
Setiap penelitian pasti menggunakan
metode[24],
agar memudahkan sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, untuk
memfokuskan kajian dalam penelitian tersebut.
1.
Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (library research) oleh
karena itu, pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan teknik
dokumentasi.
2.
Sifat penelitian.
Penelitian ini bersifat deskriptif:
yaitu Peneliti menguraikan secara teratur seluruh konsep buku[26].
Di sini peneliti menulis dengan berurutan tentang realisme sosialis yang
terkandung di dalam buku tersebut.
3.
Pengumpulan Data-data.
Teknik yang digunakan untuk
penelitian ini adalah dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang
diambil dari buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang
akan diteliti dan juga dari data sekunder yang secara tidak langsung
membicarakan masalah yang akan diteliti, namun masih relevan untuk dikutip
sebagai pembanding.
Adapun prosesnya adalah melalui
penelaahan kepustakaan yang telah diseleksi agar sesuai dengan kategorisasinya
dan berdasarkan content analisys (analisis
isi). Kemudian data tersebut di sajikan secara deskripsiptif.
4.
Analisis Data.
Metode yang dipakai dalam menganalisa
data agar diperoleh data yang memadai adalah dengan menggunakan analisa data
kwalitatif, dalam operasionalnya data yang diperoleh digeneralisir,
diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif dan
deduktif[27].
Deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari data yang umum ke data yang
khusus. Aplikasi dari metode tersebut dalam penelitian ini adalah bertitik
tolak dari gagasan tentang realisme sosialis dalam novel tretalogi Pram.
Sementara induktif adalah penalaran dari data yang khusus dan memiliki kesamaan
sehingga dapat di generalisirkan menjadi kesimpulan umum.
Untuk memperoleh suatu hasil
penelitian yang valid secara ilmiah dalam sebuah penulisan karya ilmiah, tentu
saja di perlukan metode sebagai sarana untuk memperoleh akurasi data yang dapat
di pertanggung jawabkan secara akademis serta menghasilkan karya ilmiah yang
sistematis. Demikian pula dengan penelitian ini. Adapun metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini, antara lain ;
- Deskriptif
Yaitu metode dengan memaparkan isi
naskah. Pemaparan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi detail-detail dari
suatu peristiwa atau pemikiran tokoh (deduktif)[28].
Juga dipakai corak induktif yakni dengan menganalisis keterkaitan semua bagian
dan semua konsep pokok satu persatu. Disini akan diuraikan secara teratur aspek
realisme sosialis dalam karya Pram.
- Interpretasi.
Metode interprestasi
yaitu metode untuk menyelami data yang terkumpul untuk kemudian menangkap arti
dan nuansa yang dimaksud tokoh secara khusus. Di sini akan diselami arti, makna
dan konsep realisme sosialis yang terkandung dalam karya Pram.
- Kesinambungan Historis.
Metode ini dipakai untuk melihat
beberapa faktor yang mengkonstruksi pemikiran sang tokoh (Pramoedya). Faktor
tersebut bisa bersifat internal yang menyangkut latar belakang tokoh dan
eksternal yang menyangkut pengalaman dan konteks zaman sang tokoh ketika
membuat karya novel tetralogi. Termasuk di sini adalah konteks jaman dan tokoh
dalam novel tersebut.
G. Sistematika
Pembahasan.
Bagian ini menguraikan garis besar (out line) dari skripsi ini dalam bentuk
bab-bab yang secara sistematis saling berhubungan. Sehingga ditemukan jawaban
atas persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini
disusun dalam lima
Bab pertama, adalah Pendahuluan yang
akan memberi gambaran skripsi ini secara keseluruhan. Dalam bab ini berisikan
uraian singkat mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Kerangka Teori dan Sistematika
Pembahasan.
Bab kedua, adalah sebuah upaya mengenal
kehidupan dan kreatifitas Pram. Hal ini dilakukan sebagai satu upaya
penelusuran atas latar belakang keluarga, pendidikan dan hubungannya dengan
proses kreatifitas Pram dalam penulisan karyanya. Disamping itu juga di
selidiki peran-perannya dalam masyarakat yang dianggap sangat mempengaruhi
karya-karyanya.
Bab ketiga yang berisikan pembahasan
menjelaskan tentang realisme Sosialis dalam pandangan Pram, dan sekelumit
cerita yang mengandumg unsur Realisme sosialis dalam novel Tetralogi. Tidak
kalah penting, kesinambungan novel tersebut dengan keadaan masyarakat yang terjadi pada saat ini.
Bab keempat merupakan inti dari skripsi
yaitu analisis realisme sosialis yang terkandung dalam novel Tetralogi.
Bab lima
BAB
II
BIOGRAFI
PRAMOEDYA ANANTA TOER.
A. Selayang
Pandang Perjalanan Hidup Pramoedya.
Pramoedya Ananta toer, anak sulung
bapak Mastoer dan Ibu Oemi Saidah. Ayahnya yang lahir pada 5 Januari 1896[29]
berasal dari kalangan yang dekat dengan agama Islam, seperti misalnya jelas
dari nama orang tuanya, Imam Badjoeri dan Sabariyah. Ayah Mastoer menjadi naib
di sebuah desa di Kediri
Sedangkan ibunya adalah anak penghulu
Rembang yang lahir pada tahun 1907 [31]
dari selirnya, setelah melahirkan anak, selirnya itu diceraikan dan diusir dari
kediaman penghulu. Anak selir itu bernama, Oemi Saidah, diasuh dalam keluarga
Haji Ibrahim dan Hazizah. Saidah lulus HIS pada 1922, namun tidak mendapat izin
melanjutkan studi ke Van Deventersscholl (sekolah kerajinan untuk gadis) di
Semarang seperti yang diharapkannya, sebab sudah bertunangan dengan guru Toer
yang tidak bersedia menunda perkawinan pak Toer yang umurnya baru 15 tahun.[32]
Pramoedya Ananta Toer lahir di Blora,
jawa tengah 6 Februari 1925[33].
Pram begitu mencintai ibunya, menurut Pram ibunya dianggap sebagai “wanita
satu-satunya di dunia ini yang kucintai dengan tulus, dikemudian hari menjadi
ukuran Pram dalam menilai setiap wanita’ dan yang tidak kalah penting Pram juga
mencintai neneknya, ibu kandung ibunya. Maka tidak heran jika banyak sekali
dalam novel-novel Pram menampilkan tokoh perempuan.
Walaupun ayahnya menolak untuk
menyekolahkan Pram, tetapi Pram masih sempat belajar kejuruan radio di
Surabaya, berkat usaha ibunya yang mulai berdagang padi dan lain-lain. Namun
pada hari ujian akhir terdengar kabar yang mengejutkan, pesawat terbang jepang
menyerang pelabuhan Pearl Harbour, dengan demikian Perang Dunia II juga mulai
berkobar di daerah Asia Timur dan Lautan Pasifik[34].
Pada 2 Maret 1942 tentara Jepang yang
mendarat di pantai utara Jawa telah mencapai Blora. Tentara Belanda melarikan
diri tanpa perlawanan. Pada awalnya tentara Jepang disambut dengan meriah oleh
penduduk setempat. Karena pemerintahan Belanda tiba-tiba menghilang, terjadi
semacam anarki, took-toko Cina dirampas dan serdadu Jepang ikut mencuri barang-barang penduduk,
dan melampiaskan hawa nafsunya. Namun dalam waktu beberapa hari tentara Jepang mengembalikan
ketertiban umum dengan keras[35].
Pada awal penjajahan Jepang, Pak Toer
dan keluarganya ditimpa musibah Ibu Oemi Saidah yang lama mengidap penyakit TBC
sejak beberapa bulan semakin parah dan meninggal pada 3 Juni 1942.Satu hari
kemudian disusul oleh anak bungsunya, Soesanti, yang baru berumur tujuh bulan.
Pada saat peristiwa tersebut Pram tidak berada di Blora. Kematian ibunya bagi
Pram merupakan kehilangan yang paling menyedihkan[36].
Pengalaman dengan orang disekitarnya
pada waktu ibunya meninggal dan hal-hal yang terjadi sesudahnya menjadikan Pram
kehilangan kepercayaan pada sesama manusia, dan Pram merasa tidak betah lagi di
Blora. Pada saat ziarah ke kuburan ibunya, Pram pamit kepada almarhumah ibunya
dan Pram berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik.
B. Setapak
Sejarah Menuju Realisme Sosialis
Atas nasehat ayahnya, bersama
adiknya, Pram berangkat ke Jakarta
Berkat ijazah mengetiknya, Pram
diterima di kantor berita Jepang Domei sebagai juru ketik. Di tempat kerja pandangan
Pram semakin luas. Pram sempat membaca berbagai macam informasi yang masuk
redaksi. Keuntungan terbesar Pram adalah kesempatan memanfaat buku rujukan yang
ada di ruang redaksi. Ensiklopedia belanda yang terkenal dengan nama Winkler Prins membuka matanya terhadap
dunia ilmu pengetahuan[38].
Namun, hasil yang Pram Ananta Toer
peroleh tidak memuaskannya. Karena tidak mempunyai ijazah sekolah menengah,
Pram tidak dapat kenaikan pangkat. Pekerjaan di kantor semakin membosankan dan
Pram mulai sadar bahwa pekerjaan baru sebagai stenograf sebab Pram merasa menempuh karier sebagai hamba,
bukan sebagai manusia bebas. Apalagi saat Pram diminta untuk mengerjakan
sebagai stenograf buku baru Mohammad
Yamin, mengenai Gajah Mada, Pram semakin memberontak karena merasa diperlakukan
sebagai kuli. Sehingga Pram beberapa kali minta berhenti, namun tidak pernah
dikabulkan. Pram lalu meninggalkan tugas tanpa seizin Jepang, dan hal tersebut
dianggap sebagai dosa yang hanya bisa ditebus dengan jiwa, Pram kemudian melarikan
diri lewat Blora , kemudian di Kediri
Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta Indonesia Indonesia sana Indonesia sana Indonesia
Pram juga ikut menggambungkan diri
dengan pertahanan kampung. Ikut menyerbu tangsi marine Jepang, sampai akhirnya
terkepung oleh tentara Australia
Pada 1 januari 1947 Pram berhenti
dengan resmi dari tentara. Pram pada masih tinggal di Cikampek, menuggu gaji
yang sudah 7 bulan tidak dibayar. Tetapi gaji tersebut tidak pernah dibayarkan.
Dengan tanpa uang Pram menuju ke Jakarta
Pada waktu upacara di Lapangan
Merdeka, Pram hadiri bersama tunangannya seorang gadis yang Pram lihat pada
tahun 1946 di Cikampek. Pram melamar
gadis tersebut ketika masih berada di dalam penjara, meskipun dengan ‘bersyarat’,
namun lamaran itu diterima. Setelah pembebasannya, Pram mengunjungi rumah gadis
tersebut kemudian tinggal di sana
Pada pekan buku Gunung Agung,
September 1954, Pram berkenalan dengan Maimunah, anak H.A. Thamrin, saudara
kandung nasionalis terkenal Mohammad Husni Thamrin. Dengan cepat Pram
berhubungan akrab. Kemudian Pram menikah dengan Maimunah, wanita yang membawa
kebahagiaan dan harapan baru dalam hidup Pram. Maimunah ternyata berani
menempuh hidup yang sangat bergejolak dengan Pram, Maimunah tabah membela dan
memperjuangkan suami dan keluarganya, juga dalam kemalangan dan kesusahan yang
paling berat yang menimpa Pram, dan sampai sekarang ibu Maimunah setia
mendampingi Pram[43].
Pengalaman pertama dari segi
perkembangan kepengarannya dihayati oleh Pram sebagai sesuatu yang penting dan
juga positif. Pada masa suram tersebut ada undangan dari Senat Mahasiswa
Fakultas Sastra Universitas Indonesia
Kehidupan Pram dengan pernikahan yang
kedua ini membaik. Setelah bulan mereka mendapat rumah yang lumayan, anak
pertama hasil pernikahan keduapun lahir, disusul dengan anak yang kedua, dan
yang penting juga kontak social, terutama dengan dunia kepengarangan makin
berkembang. Orang yang paling sering mengunjunginya ialah A.S. Dharta, penulis
marxis, yang aktif dalam Lekra sejak didirikan (1950). Pram mulai membuka mata
bagi pentingnya politik, juga dalam dunia seni.
Peristiwa yang amat menentukan bagi
Pram berlangsung pada Juli 1956. Pram mendapat kunjungan wakil kedutaan Cina
yang membawa undangan menghadiri peringatan hari wafat kedua puluh Lu Hsun,
pengarang revolusi Cina yang terkenal. Dengan persetujuan dr. Prijono, menteri
Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu, Pram menerima baik undangan itu.
Perjalanan di Cina pada Oktober 1956 menimbulkan kesadaran baru bagi jiwanya[45].
Karena perjalanan tersebut orang
mulai menuduhnya memihak komunis, bahkan telah menjadi komunis. Semangat baru
yang diperoleh berkat pengalaman di Cina mendorongnya menjadi aktif di
Indonesia, ketika berita mengenai konsepsi Presiden Soekarno tentang demokrasi
terpimpin mulai tersiar, Pram menulis karangan yang mendukung politik presiden,
dalam Bintang Merah 24 Febuari 1957,
yaitu organ resmi PKI. Kemudian bersama Henk Ngantung dan Kotot Sukardi, Pram
mengorganisasikan kelompok seniman, lalu pada Maret 1957, mereka bertiga memimpin
delegasi besar menghadap presiden, menyatakan dukungan bagi konsepsi tersebut[46].
Sejak itu, Pram mulai terkenal aktif
di bidang politik. Pram diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Golongan
Fungsional Kementrian Petera (Pengarahan Tenaga Rakyat). Dalam kapasitas itu
Pram melakukan peninjauan kerja bakti di Banten; kerja bakti itu bertujuan
‘memperbaiki jalan yang melintang dari utara sampai selatan Karesidenan Banten,
sepanjang 65 km’.
Sebelumnya, Pram sudah aktif di
bidang lain; Pram ikut mendirikan Panitia Nasional untuk konfrensi pengarang asia afrika, dengan sokongan sebagai instansi pemerintah.
Pada 7 September 1958, delegasi yang dipimpin oleh Pram berangkat ke Tasjkent,
tempat konfrensi diadakan; nampaknya Pram memainkan peran yang cukup penting
dalam penyusunan resolusi dan rencana kerjanya. Seusai konfrensi itu, Pram
mengunjungi berbagai tempat di Uni Sovyet dan Cina, kemudian pulang lewat ibu
kota Myanmar, Rangoon, di mana Pram bentrok dengan staf Kedutaan R.I. yang
menurut Pram tidak bersedia membantu dan melayaninya dengan baik.
Sekembalinya di Indonesia Pram untuk
pertama kalinya dilibatkan secara resmi dalam Lekra: dalam kongres nasional
Lekra yang di adakan di Solo antara 22 dan 28 Januari 1959, Pram terpilih
sebagai anggota pimpinan pleno. Sejak itu namanya tidak lepas lagi dari
organisasi kebudayaan yang berada di bawah naungan PKI. Hal itu terutama tampak dalam pembentukan
Fron Nasional di mana PKI dengan resmi diikutsertakan dan dalam tekanan makin
kuat pada konsep Nasakom. Kongres Solo membawa juga pergeseran fundamental
dalam garis policy Lekra. Pada
kongres itu pimpinan PKI, Nyoto, dalam cermahnya dengan judul ‘Revolusi adalah
Kembang Api’ mengemukakan bahwa politik harus menjadi pedoman di segala bidang
kehidupan, termasuk kebudayaan. Pada tahun berikutnya, Lekra mengambil alih
semboyan ‘Politik adalah Panglima’. Nyoto sebagai dasar keyakinan budayanya,
dan Pram menjadi penyambung lidah ideologi kebudayaan, antara lain lewat
kegiatannya sebagai redaktur Lentera, lampiran
kebudayaan harian Bintang Timur[47].
Tetapi sebelum sempat memainkan peran
terkemuka di bidang kebudayaan, khususnya lesusastraan revolusioner, Pram masih
harus mengalami penderitaan yang pernah Pram sebut sebagai siksaan terberat
dalam hidupnya, yaitu penahanan dalam penjara selama sembilan bulan disebabkan
oleh terbitnya bukunya Hoa Kiau di
Indonesia. Buku yang keluar pada Maret 1960 itu merupakan suntingan kembali
sembilan surat
Sejak 1956, makin banyak terdengar
suara anti Cina di Indonesia Indonesia
Pram dalam Hoa Kiau di Indonesia memihak orang Cina tanpa syarat. Namun,
bukunya bukan pertama-tama polemik politik. Pram menganggap cukup mengambil
pendirian demi tujuan atau ideology politik; Pram mendalami sejarah masalah
orang Cina di Indonesia dengan memanfaatkan banyak sumber ilmiah dan lain-lain.
Dengan panjang lebar Pram menguraikan aspek-aspek positif kehadiran mereka di Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia
Dalam uraiannya Pram menyatakan aspek
kepartaian atau politik praktis tidak menonjol. Alasan terpenting Pram dapat
disimpulkan sebagai berikut: pertama, demi perikemanusiaan, kedua, demi
keadilan orang Cina yang sudah lama berada di Indonesia Indonesia
Yang pasti ikut menentukan pendirian
pro-Cina Pram dan mendorongnya membela orang Cina ialah simpati dan kekaguman
Pram terhadap rakyat cina yang dirasakan Pram sejak kunjungannya di Peking pada
1956 dan yang diperkuat lagi pada kunjungan kedua, pada Oktober 1958. Pram kemudian bersama kawannya dari Cina,
menerjemahkan buku Salah Asuhan, dan
penerbitan buku tersebut mengakibatkan karya Pram dilarang, pada April 1960.
Pram sendiri ketika itu masih sempat ke luar negeri, namun sekembalinya Pram
dari luar negeri, Pram segera dipanggil oleh Peperti (Penguasa perang
tertinggi), diinterogasi oleh Kolonel Sudharmono (yang kemudian menjadi wakil
presiden). Pram kemudian disekap selama dua bulan di rumah tahanan militer di Jakarta surat
Setelah dibebaskan dari penjara
Cipinang Pram cepat mengambil alih kedudukan terkemuka di panggung sastra Indonesia S. Rukiah
menjadi redaktur rubrik kebudayaan Bintang
timur[52]
yang berjudul Lentera. Rubrik yang
pada awalnya hanya setengah halaman itu kemudian diperluas menjadi satu
halaman, bagian terbesar pada edisi hari Minggu terbit disunting oleh Pram. Lentera menjadi media utama tulisan Pram
yang pada periode 1962-1965 menjadi media Pram untuk mengemukakan ide-idenya
tentang pengajaran sastra Indonesia
Minatnya untuk pengajaran sastra juga
dibangkitkan sejak 1962 Pram memberi kuliah sastra Indonesia
Pram juga menulis tentang sejarah
awal gerakan nasional Indonesia Indonesia
Selama periode itu, tulisan Pram
makin polemis dan provokatif dari segi gaya Peking
membawa perubahan mendalam dalam gaya Peking .
Di dalam tulisannya dikatakan bahwa perlu ada perintisan jalan baru ke arah
sastra ‘revolusioner’. Konsekuensinya revolusi ‘adalah pembasmian tanpa batas.’
Sekarang harus ada front antara tenaga-tenaga revolusioner dan yang anti pada
tenaga revolusioner, sehingga perjuangan makin sengit[56].
Ide bahwa waktunya telah datang untuk
konfrontasi total menjadi makin jelas dalam karya kritis Pram yang kemudian;
ide itu pasti diperkuat lagi oleh pengalaman Pram selama dalam penjara pada
1960. Kompromi sudah tidak mugkin lagi, sekarang sudak waktunya memukul dan
menyerang terus menerus. Ide-ide dan tulisan Pram semakin dipengaruhi dengan
ideology Lekra dan garis besar PKI. Walaupun disangsikan sejauh mana Pram
dilihami oleh ajaran komunisme yang resmi. Karya Marx tidak pernah dibaca Pram,
dengan pimpinan PKI Pram jarang bertemu, kalaupun bertemu Pram bentrok dengan
mereka tentang masalah politik. Soekarno pun tidak begitu simpati dengan Pram.[57]
Sebenarnya hanya ada satu risalah
panjang yang membicarkan masalah ideology dalam satra secara eksplisit dan
teori, yaitu prasaran yang disajikan di depan Seminar Sastra, Universitas Indonesia Indonesia
Berdasarkan teori tersebut kemudian
Pramoedya memberi survai sejarah sastra Indonesia
Manikebu diumumkan pada September
1963 dalam majalah Sastra sebagai
manifesto sekelompok budayawan, yang bertentangan dengan pemahaman Lekra.
Konfrontasi itu di perhebat lagi sekitar Konfrensi Karyawan Pengarang
se-Indonesia (KKPI), yang diselenggarakan di Jakarta pada awal maret 1964 dan
yang didukung oleh berbagai badan dan organisasi non-komunis dengan bantuan
angkatan darat. Setiap minggu Lentera melancarkan
serangan seru tidak hanya pada ideology kontrarevolusioner para ‘manikebuis’,
melainkan sering juga pada aspek kehidupan pribadi mereka. Karena PKI dan Lekra
juga makin berkuasa dalam politik, usaha penentang Manikebu ternyata efektif.
Presiden Soekarno secara resmi melarang Manikebu pada 8 Mei 1964, izin terbit
majalah Sastra sebagai corong
Manikebu dicabut.[58]
Dalam pertentangan ideologi yang
semakin tajam itu Pram memainkan peran dominan. Dengan penanya sebagai senjata
yang ampuh dengan suaranya yang lantang, Pram terus menerus giat ‘membabat’ dan
‘menghantam’ musuh yang tidak kunjung menyerah.[59]
Pada 9 Mei 1965, Pram menulis
karangan dalam Lentera dengan judul
‘Tahun 1965 Tahun Pembabatan Total’. Sejarah memang ada ironinya. Judul
tersebut ternyata dalam arti yang terbalik dengan yang dimaksudkan oleh Pram.
Pada 30 September 1965, Gestapu sesungguhnya membawa pembabatan total terhadap
PKI, Lekra dan penganut-penganutnya, bukan hanya pembabatan vocal, melainkan
juga pembabatan fisik. Peristiwa itu juga dengan sendirinya membawa kehancuran
bagi Pram.
Pram mulai bekerja pada ‘The Voice Of Free Indonesia Indonesia
Pada saat itu Pram juga berkenalan
dengan H.B. Jasin, redaktur majalah Pantja
Raja, yang menerbitkan dua cerpen Pram, masing-masing berjudul Kemana?dan Si Pandir. Tetapi kebebasan tidak berlangsung lama. Pada tanggal 21
Juli 1947, Belanda mulai melakukan agresi militer pertama. Pram mendapat order
dari atasannya untuk mencetak dan menyebarkan pamphlet-pamflet dan majalah
perlawanan. Tetapi dua hari kemudian Pram tertangkap oleh marinir Belanda.[60]
Ini pertama kali Pram berkenalan
dengan kehidupan penjara, pengalamannya bermacam-macam. Karena Pram menolak
kerja paksa, Pram dijatuhi siksaan yang sangat kejam, dan adakalanya rejim
penjara amat bengis. Tetapi ada juga segi positifnya, antara lain Pram bisa
berkenalan dengan Profesor Mr. G.J. Resink, guru besar hukum tata negara pada
fakultas hukum yang menjadi bagian Universitas Indonesia
Selama dalam penjara, Pram tidak
hanya sempat menulis dan belajar bahasa Inggris, Pram belajar juga ekonomi,
sosiologi, sejarah filsafat, dan kursus kepustakaan dan perhitungan dagang.
Namun, meski kreativitas Pram berkembang terus selama dalam penjara, sudah
tentu dua setengah tahun sebagai tahanan itu bukan merupakan masa berbahagia
dalam riwayat hidupnya.[61]
Akhirnya Desember 1949, Pram
dibebaskan bersama kelompok tahanan yang terakhir. Namun, pengalaman awal yang
sangat menggembirakan. Peristiwa yang amat emosional dan membanggakan, yang
dihadirinya sendiri, adalah penurunan triwarna Belanda dan penaikan dwiwarna Indonesia
Nampaknya dengan demikian secara
tragis berakhir masa jaya Pram sebagai tokoh terkemuka di dunia kesastraan Indonesia
Di Buru Pram terpaksa tinggal lebih
dari sepuluh tahun. Kehidupan yang pahit dan pengalaman sebagai tapol, terpisah
dari keluarga dan terasing dari dunia sastra Indonesia
Baru pada akhir 1979[64]
Pram dilepaskan, Pram berangkat dengan rombongan terakhir. Sejarah terulang
lagi, sebab tiga puluh tahun sebelumnya Pram juga termasuk kelompok tahanan
terakhir yang dibebaskan dari penjara Belanda. Akhirnya Pram dibebaskan di Semarang Jakarta
Sejak itu Pram ‘bebas’ dari penjara,
tetapi kebebasan yang Pram dapatkan, hanya kebebasan semu. Ruang geraknya
sebagai warga Indonesia kota Indonesia
Namun, tidak berarti riwayat hidup
Pram telah berakhir. Secara paradoksal dapat dikatakan bahwa kehadiran Pram di
Indonesia masih tetap terasa, bahkan ada kalanya menonjol. Dalam tahun
berikutnya dunia sastra kaget denga terbitnya dua buku, Bumi Manusia dan Anak semua
Bangsa, buah tangan dari pulau Buru . Roman
sejarah tersebut langsung meraih sukses besar, dalam waktu singkat sejumlah
cetakan ulang diperlukan, kritik menanggapi buku itu cukup antusias, walaupun
ada juga yang keras menolaknya. Di luar negeri Pram yang sebagai tapol menjadi
lambang demi hak asasi manusia sekarang menjadi terkenal juga sebagai satrawan
berkaliber internasional. Bukunya juga
terbit dalam bahasa Malaysia, demikian pula dalam bahasa asing, pertama-pertama
Nederland, kemudian bahasa Inggris, dan entah berapa bahasa dunia lain. Namun,
di Indonesia pada Mei 1981 kedua buku itu di larang peredarannya oleh Jaksa
Agung, dan nasib yang sama menimpa dua jilid berikut dari tetralogi Karya Buru, masing-masing berjudul Jejak langkah (1985) dan Rumah Kaca (1988).[65]
Peran publik dalam kehidupan sastra
ternyata tidak mungkin bagi Pram, ketika pada 1981 Pram memberikan ceramah di
fakultas sastra UI atas undangan Senat Mahasiswa, tentang ‘Sikap dan peranan
kaum intelektual di Dunia Ketiga, khususnya di Indonesia
Masih ada beberapa buah tangan Pram
lain yang terbit, kebanyakan riset histories yang dilakukan sebelum 1965:
antologi ‘sastra pra-Indonesia’, dengan judul Tempo Doeloe (1982): biografi Tirtho Adhi Soerjo Sang
Pemula dengan antologi tulisan pelopor jurnalistik Indonesia Indonesia
Dalam dasawarsa ini pun masih terbit
dua buku yang meriwayatkan pengalaman dan observasi Pram selama di Buru pertama-tama diterbitkan dalam terjemahan
Belanda, jilid pertama kemudian terbit
dalam bahasa Indonesia Buru ,
sebagian lagi perenungan dan observasi yang bermacam-macam. Bagian kedua, yang
versi aslinya belum diterbitkan, mengenai sejumlah surat
Sekali lagi Pram menjadi pusat
hebohnya sastra besar di Indonesia yang terjadi pada tahun 1995, ketika Pram
dianugerahi ‘ Roman Magsaysay Award for Jurnalism, Literature, and Creative
Communication Arts’ di Manila. Pengurus yang bersangkutan memberikan kehormatan
yang disertai hadiah UU$ 50.000, kepada Pram berdasarkan jasanya sebagai
pengarang.
Penganugerahan hadiah Magsaysay
menimbulkan prahara protes di Indonesia
Di anggap sangat ironis bahwa hadiah
yang memakai nama, Magsaysay, yang seumur hidup memperjuangkan demokrasi dan
hak asai manusia, sekarang diberikan kepada penulis yang selama periode ikut
memimpin Lekra terbukti anti demokratis dan ikut menindas hak. Ketika ternyata
pengurus yayasan tidak menerima protes tersebut.
Di Indonesia terjadi dua front, satu
pro dan satu kontra Pram. Tiga budayawan terkemuka yang tidak mau menandatangi
pernyataan itu, misalnya Ajip Rosidi, Goenawan Mohamad, dan Arief Budiman,
kedua yang terakhir dulu juga penandatangan Manikebu, yang menjadi terror dan
penindasan oleh Lekra.[69]
Bagi Goenawan alasan penting untuk
tidak menandatangi pernyataan protes adalah Pram masih belum bebas, belum
dipulihkan hak-hak sipilnya, masih ada pelarangan terhadap bukunya, pelarangan
bepergian ke luar negeri dan lain-lain.[70]
Heboh sastra terbaru ini membuktikan,
kontroversi lama tetap ada, Pram tetap keras kepala menolak bertobat dan minta
maaf atas kelakuannya sebagai pemuka Lekra. Pram tetap penuh amarah terhadap
kelakuan yang telah Pram derita selama 20 tahun lebih. Lawannya tidak kurang
mendalam rasa dendamnya atas teror pihak Lekra yang mereka derita, dengan Pram
sebagai pemukanya yang paling vocal. Dan di tengah-tengah ada pihak ketiga,
dengan Goenawan Mohammad sebagai wakil terkemuka, yang berseru kepada kedua
kubu agar mereka menepikan rasa curiga.
Demikianlah Pram tetap berada dalam
situasi paradoksal. Pada satu pihak Pram
terpaksa hidup sebagai paria yang sudah tiga puluh tahun lebih kehilangan hak
asasinya sebagai manusia dan warga Negara Indonesia
C. Sepenggal Cerita Lahirnya Novel Tetralogi
Pada akhir tahun 1980[71],
Pram melahirkan karya awal dari rangkaian novel Tetralogi. Yaitu novel Bumi
Manusia, yang pada saat itu Pram baru satu tahun keluar dari penjara di pulau
buru. Sebenarnya ide menulis novel Tetralogi, sudah ada pada awal tahun 1960[72],
tetapi baru diedarkan di masyarakat pada tahun 1980.
Kenapa novel tersebut perlu dibuat,
karena Pram melihat pengajaran sekolah semata tidak cukup untuk membudayakan
kecintaan bangsa pada sejarah pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan.
Dan Pram juga beranggapan semua ucapan tentang patriotisme, kecintaan pada
tanah air dan bangsa, baik itu melalui pembicaraan, pidato, nyanyian atau pun
deklamasi ini tinggal slogan tanpa isi, tidak edukatif, dan juga tidak jujur.[73]
Untuk menyelamatkan novel Tetralogi, karena Pram menulis novel tersebut
ketika masih di dalam penjara. Pram dibantu oleh sahabatnya yang bernama Prof.
Mr. G.J. Resink, biasa di panggil Pram dengan “ Han”.[74]
Karena Resink, yang juga menyelamatkan naskah Perburuan dan Keluarga
gerilja. Resink, menyelundupkan naskah novel itu keluar penjara, demikian
pula yang terjadi pada novel Tetralogi.[75]
Dalam pembukaan buku Bumi Manusia, Pram melegendakan nama
sahabatnya tersebut. “Han, memang bukan
sesuatu yang baru. Jalan setapak ini memang sudah sering ditempuh, hanya yang
sekarang perjalanan pematokan.” Terasa sekali bahwa Pram merasa sangat
berhutang budi, pada sahabatnya tersebut.
Novel Tetralogi tersebut terdiri dari
empat jilid, jilid yang pertama berjudul Bumi
Manusia, Anak semua bangsa, Jejak langkah, kemudian Rumah Kaca. Setiap jilid tersebut saling berkait satu sama lain.
Empat novel tersebut, kira-kira berkisar sejumlah 1600 halaman. Makanya
diperlukan pemisahan-pemisahan, sehingga pembaca tidak akan jenuh.
Tokoh protagonis dalam novel tersebut
bernama Minke, namun sebenarnya tokoh Minke tersebut adalah perwujudan dari
Tirto Adhi Suryo, nasionalis angkatan pertama, yang sampai waktu itu kurang
mendapat perhatian dalam penulisan sejarah nasional[76],
Tirtoadhisoerjo telah jadi wartawan pada usia 21 tahun, dan dia adalah wartawan
pertama kali di Indonesia.
Minke, adalah anak priyayi tinggi.
Pada masa riwayat ini berlangsung menjadi aggota keluarga semacam itu memberi
hak istimewa kepada orang di tanah jajahan, asal ia bersedia menyesuaikan diri
dengan tuntutan rangkap system: pertama, bersikap sesuai dengan hukum-hukum
kebudyaan priyayi dan kedua, tunduk pada kemauan penguasa kolonial yang
memanfaatkan golongan priyayi Jawa untuk mempertahankan kekuasaan dan
kewibawaannya dengan kekuatan fisik yang
minimal. Atas dasar tersebut anak priyayi di perbolehkan masuk sekolak
terbaik yang dimiliki kolonial.
Proses belajar Minke berlangsung
cukup lama, berliku dan berbelit-belit. Minke sekolah ditengah-tengah orang
Belanda, yang selalu bersikap rasialis. Namun dari sekolah tersebut Minke
mempelajari ilmu pengetahuan Eropa, dan Minke terkagum-kagum. Tapi pada
akhirnya Minke kecewa terhadap ilmu pengetahuan tersebut, terutama pada sistem
hukum kolonial yang secara tragis merenggut istrinya. Pada waktu tersebut,
Minke juga bertemu dengan guru bahasa Belanda yang termasuk aliran etis[77].
Dari sana
Semenjak awal Minke sendiri sudah
mempertanyakan nasibnya sebagai golongan pribumi yang selalu dilecehkan.
Sebagai contoh, antara kelahiran Minke dengan Sri ratu Wilhelmina mempunyai
tanggal, bulan, serta tahun kelahiran yang sama, 31 Agustus 1880. perbedaannya
hanyalah pada jam dan kelamin saja. Kalau berdasarkan perhitungan astrologi
(perbintangan), jelas keduanya mempunyai nasib yang sama.[78]
Tetapi apa yang terjadi yang satu
menjadi ratu sementara yang lain menjadi kawulanya. Dengan realitas social
semacam ini, Minke pun sependapat dengan apa yang di katakan gurunya, Juffrouw
Magda Peters yang merujuk pendapat Thomas Aquinas, bahwa astrologi tidak lebih
sebagai lelucon belaka.
Kesadaran sistem yang timpang bukan saja menimpa pada
dirinya, tapi juga pada semua rakyat Indonesia
Sementara itu dalam jilid kedua novel
terakhir, Jejak Langkah dan Rumah Kaca. Novel tersebut, bercerita
tentang lahirnya SDI (Sarikat Dagang Islam), SDI adalah cikal bakal lahirnya SI
(Sarekat Islam) di Indonesia. Kelahiran SDI disebabkan pedagang batik yang ada
di Sala dan Yogya, untuk menangani perkelahian jalanan yang sering meledak
antara kaum Tionghoa dan Jawa.
SI adalah alat untuk melihat kabangkitan
Bumiputera awal abad XX. Gerakan SI bertujuan untuk melawan sisten perdagangan
kolonial Belanda. serpihan-serpihan keterasingan budaya perlawanan yang bebas
masuk ke Hindia Belanda. SI inilah yang pertama kali melancarkan pemboikotan
melalui metode kekerasan. Kiat gerakan ini telah membuatnya popular dan
mendapat dukungan meluas bahkan hingga di luar kota Surakarta surat
Meski pada akhir cerita tokoh Minke
tersebut akhirnya kalah, dan harus dipenjara oleh pemerintah yang berkuasa.
Gambaran pada novel Bumi Manusia,
novel pertama dari tetralogi. Di dalam
novel tersebut Pram mencoba memotret kekaguman orang-orang jawa yang sangat
terpesona pada kemajuan ilmu pengetahuan yang baru dilihatnya. Meski tidak
semua orang Jawa kagum akan kemajuan ilmu pengetahuan tersebut, karena kemajuan
tersebut tidak bisa dinikmati oleh semua orang Jawa. Karena yang bisa menikmati
fasilitas tersebut adalah para priyayi, sebab untuk menikmati hal tersebut
harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit. Dalam novel ini Minke juga bertemu
dengan seorang Nyai yang bernama Ontosoroh, Nyai tersebut sangat kaya dan cerdas.
Sehingga Nyai tersebut mampu mengasai tuannya, Nyai itu juga yang memberikan
pengajran tentang revolusi Perancis yang membuka mata Minke melihat system
feodal.
Namun dalam novel tersebut bukan
hanya sebentuk kekaguman saja, tapi juga perjuangan untuk menentang
ketidakadilan yang diciptakan sistem kolonialisme. Tetapi, ia pun tidak muncul
sama sekali sebagai pemenang yang berhasil menumbangkan ketidak adilan dalam
system ini, melainkan justru harus menghadapi kenyataan pahit: kalah dengan
ditandai direbutnya Annelis dari sisinya. Novel ini ditutup dengan nada yang
sangat pahit: “Kita telah melawan, Nak,
Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.” Justru dari akhir cerita yang
seperti ini, pembaca dibuat menyadari adanya ketidak adilan dalam system
kolonialisme[79].
Dalam novel jilid kedua dengan judul Anak Semua Bangsa, Minke bertemu dengan
seorang Cina. Mereka sepasang kekasih, yang ternyata mereka berdua adalah
pelarian dari negaranya karena berusaha melawan kaisar. Kedua orang Cina
tersebut beraliran sosialis, untuk pertama kali Minke belajar tentang
sosialisme. Hal tersebut juga didukung oleh Nyai Ontosoroh, justru Nyai
Ontosoroh juga menyuruh Minke untuk menulis kepada media Belanda. Hingga pada
akhir cerita jilid kedua ini, Minke diminta untuk mendirikan media sendiri yang
berbahasa melayu. Sebab bahasa tersebut dapat di baca oleh setiap orang
pribumi, sehingga lebih merakyat. Maka lahirlah media yang bernama Medan
Dalam jilid ketiga yang berjudul Jejak
Langkah, Minke mulai aktif menulis. Novel ini juga menggambarkan lahirnya
organisasi-organisasi besar, yang mempengaruhi perjalanan perjuangan Indonesia Indonesia
Hingga pada jilid keempat yang
berjudul Rumah Kaca, di sini Minke mulai sadar bahwa alat perjuangan yang
paling ampuh adalah jurnalistik, tetapi pada saat bersamaan gerak Minke mulai
diawasi oleh Belanda begitu juga dengan organisasi-organisasi yang ada. Jadi
Pram menggambarkan orang Indonesia
D. Penghargaan Yang Diterima Pramoedya
1988: Freedom to Write Award dari PEN American
Center
1989: Anugerah dari The Fund for
Freee Expression, New York
1995: Wertheim Award, “for his
meritorious services to the struggle for emancipation of the Indonesian
people”, dari The Wertheim Foundation, Leiden
1995: Ramon Magsaysay Award, “for
Journalism, Literature, and Creative Arts, in recognition of his illuminating
with brilliant stories the hystorical awakening, and modern experience of the
Indonesian people”, dari Ramon Magsaysay Award Foundation, Manila, Filipina.
1996: Partai Rakyat Demokratik
Award, “hormat bagi Pejuang dan Demokrat Sejati” dari Partai Rakyat Demokratik.
1996: UNESCO Madanjeet Singh Prize,
“in recognition of his outstanding contribution to the promotion of tolerance
and non-violence”, dari UNESCE, Paris, Prancis.
1999: Doctor of Humane Letters, “in
recognition of his remarkable imagination and distinguished literary
contribution, his example to all who oppose tyranny, and his highly principled
struggle for intellectual freedom”, dari University of Michigan, Madison,
Amerika Serikat.
1999: Chanceller’s Distinguished
Honor Award, “for his out standing literary archievements and for his
contributions to etnic tolerance and global understanding”, dari University California Berkeley
1999: Chevalier de I’Ordre des Arts
et des Letters, dari Le Ministre de la Culture et de la Communication
Republique Francaise, Paris, Prancis.
2000: New York New York
2000: Fukuoka
BAB III
REALISME SOSIALIS
SEBAGAI
PANDANGAN PRAMOEDYA ANANTA
TOER DALAM NOVEL TRETALOGI
Bab ini akan menjelaskan tentang
realisme sosialis siapa yang dipotret oleh Pram, dan dipengaruhi oleh siapa
realisme sosialis yang dianut dalam aliran sastra Pram, hal tersebut sangat
diperlukan untuk membelah gagasan-gagasan realisme sosialis menurut Pram yang
terkandung dalam novel Tetralogi.
Sebenarnya hal tersebut tidak semudah
disangka oleh penulis, karena dalam novel tersebut tidak secara terang-terangan
menunjukkan makna sisi realisme sosialis, seperti yang dilakukan oleh Marxim
Gorki seorang tokoh realisme sosialis yang menjadi panutan Pram. Novel tersebut
berlatar belakang sebuah penjajahan, di mana penindasan yang dilakukan oleh
feodalis sangat terasa di dalamnya.
Penulis mencoba menguak makna dari
realisme sosialis dalam novel Tetralogi tersebut, dengan mengacu pada pemikiran
Pram tentang realisme sosialis. Sehingga diharapkan tidak akan mengaburkan
makna realisme sosialis, dan dapat pula memotret pemikiran realisme sosialisnya
Pram dalam novel Tetralogi.
Dalam bab ini akan dibahas tiga
persoalan yang terdiri dari tiga sub,
yaitu sub A, tentang Pramoedya Ananta toer dan Paradigma Realisme Sosialis
dalam Sastra. Sub B, tentang Pandangan Pramoedya tentang Realisme Sosialis
dalam Novel Tetralogi dan sub bab C, tentang
Faham Realisme Sosialis dalam Realitas Empirik.
A. Pramoedya Ananta Toer dan
Paradigma Realisme Sosialis dalam Sastra.
Pemikiran Pram tentang realisme
sosialis, sebenarnya punya tujuan satu, yaitu untuk membangun masyarakat yang
ideal. Masyarakat tanpa penindasan, masyarakat yang merdeka. Dalam arti
terpenuhinya hak-hak sebagai manusia, seperti yang diharapkan oleh sosialisme.
Yaitu manusia yang sama rasa sama rata dan karsa (keinginan).
Namun untuk memperjelas pola pikir
Pram tentang realisme sosialis, perlu dipertegas lebih dahulu tentang sejarah
lahirnya realisme sosialis, dan makna yang terkandung di dalamnya.
Istilah tersebut lahir pertama kali
di Uni Soviet[81],
sebagai penerapan sosialisme di bidang kreasi-sastra. Sastra yang mempergunakan
metode ini karena realisme sosialis adalah metode di bidang kreasi (seni) untuk
memenangkan sosialisme dan lebih penting lagi adalah dengan sikap politik yang
tegas, militan, kentara, tidak perlu malu-malu kucing atau sembunyi-sembunyi,
sesuai dengan nama yang dipergunakannya. Realisme sosialis merupakan bagian
intergral dari kesatuan mesin perjuangan umat manusia dalam menghancurkan
penindasan dan penghisapan atas rakyat pekerja, yakni buruh dan tani, dalam
menghalau imperialisme (penjajahan) kolonialisme (golongan), dan penghisapan
atas rakyat pekerja, yakni buruh dan tani, imprealisme kolonialisme, untuk
meningkatkan kondisi dan situasi rakyat pekerja diseluruh dunia.[82]
Lain halnya dengan realisme Barat,
atau lebih tepatnya dinamai realisme borjuis, merupakan pembatasan terhadap
pandangan seseorang pada realitas-realitas saja[83].
Sedangkan sastra sosialis Indonesia timbul dari orang-orang
Indonesia yang berjiwa sosialisme yang dilahirkan oleh perkembangan masyarakat
itu sediri yang menderita keadilan sosial, mula-mula naluri bertahan terhadap
kematian yang disebabkan karena kezaliman social, dan kemudian pada ia atau
mereka yang mempunyai kegiatan atau rutin kreasi menyalurkannya ke dalam
cerita-cerita, yang pada pokoknya memperingatkan orang, bahwa kezaliman sosial
yang tengah berlaku tidak bisa dipertahankan lebih lama lagi, kalau masyarakat
tidak hendak jadi binasa karenanya[84].
Realisme sosialis adalah sebuah
istilah dengan maknanya yang telah pasti di negara manapun dia ada, hanya
perkembangannya ditentukan oleh kondisi setempat, yakni realisme ilmiah (MDH =
Matrealisme, Dealiktika, Historisme). Realisme dengan hukum perkembangannya dan
sosialisme yang lahir sebagai kemestian disebabkan adanya perjuangan antara dua
macam klas yang bertentangan dan berkembang secara tetap, yakni klas proletaar dan klas borjuis[85].
Realisme sosialis sangat bertentangan
dengan realisme barat, atau lebih tepatnya dinamai realisme borjuis, karena merupakan pembatasan
terhadap pandangan seseorang pada realitas-realitas saja tanpa membutuhkan
kritik. Sebaliknya, realisme sosialis sebagai metode sosialis menempatkan
realitas sebagai bahan-bahan global semata untuk menyempurnakan pemikiran
dialektik. Bagi realisme sosialis, setiap realitas, setiap fakta, cuma sebagian
dari kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri. Realitas tidak lain hanya satu
fakta dalam perkembangan dialektik.
Realisme borjuis mempunyai kecenderungan yang melawan realitas itu sendiri untuk
memenangkan idealisme. Atau bila dipergunakan kata-kata Nikolai Iribudzjakov:
“ Satu ciri stadium baru
kapitalisme dunia adalah keretakan sama sekali dari filsafat borjuis dengan
materialisme dan dengan segala steling-steling-nya yang mengkibatkan orang
menarik kesimpulan yang materialistik.
“ Tapi ini bukan berarti,
bahwa materialisme hilang sama sekali dari pandangan sarjana-sarjana borjuis.
Materialisme itu dapat saja dibuang dari filsafat borjuis, namun ia masih
menyatakan diri jelas-jelas di dalam
fisika. Dan ini bukanlah suatu kebetulan. Karena sebagai mana ditunjukkan oleh
Lenin dengan jelasnya, maka pada parasarjana borjuis dalam ilmu-ilmu alam, para
ahli biologi, dan matematika, yang melakukan studi dilapangan alam materi maka
muncul dan berkuasalah tendensi-tendensi materialistik yang tak dapat
dihindarkan lagi. Dalam paham-paham
falsafinya para sarjana ini mencoba melepaskan diri dari materialisme,
menentangnya, yang mana sebagian di antaranya menyatakan pengikut dari
idealisme subjektif. Tapi penyelidikan-penyelidikan di lapangan ilmu
pengetahuan alam kembali membawa mereka pada kesimpulan, yang bertentangan
dengan wawasan falsafi mereka sendiri serta membenarkan berbagai stelling
materialisme. Ucapan-ucapan materialisme yang spontan di antara para sarjana
ilmu alam borjuis tentu saja tidaklah menjelaskan dan memang tak dapat
menjelaskan watak dari borjuis modern yang pada umunya adalah filsafat idealis”[86]
Demikianlah realisme borjuis menurut
pandangan orang sosialis. Sedangkan realisme sosialis adalah istilah sastra
yang melingkupi adanya front
perjuangan, harus mempunyai watak yang jelas. Yang pertama, militansi sebagai
ciri tidak kenal kompromi dengan lawan. Serta yang kedua, karena segaris dengan
perjuangan politik sosialis, maka dia terus menerus melakukan affensi atas musuh-musuhnya dan
pembangunan yang cepat di kalangan barisan sendiri. Dalam dua artikelnya ini
Gorki membela humanisme proletaar,
humanisme rakyat dengan menudingkan telunjuk pada urgensinya pengusahaan
penghapusan pembagian manusia atas klas-klas (dalam agama Hindu adalah
kasta-kasta, dalam sistem-sistem sosial tertentu dalam pemisahan antara budak
dan orang merdeka serta pelapisan-pelapisannya), melenyapkan setiap kemungkinan
munculnya minoritas yang mengeksploitasi tenaga mayoritas yang produktif dan
kreatif. Serta yang paling penting
adalah menciptakan dunia baru, dunia yang dibangunkan di atas landasan keadilan
yang merata[87].
Jadi watak sastra realisme sosialis
bukan saja nampak dari militansinya terhadap kapitalisme yang dihadapinya
sehari-sehari, tetapi lebih jauh lagi juga militansinya dalam mempertahankan
dan mengembangkan semangat anti kapitalime internasional.
Sastra realisme sosialis tidak pernah
memberikan konsesi atau kompromi dengan musuh-musuhnya, karena yang demikian
sudah menyalahi sosialisme itu sendiri, sedangkan sastra memang bukanlah politik
yang berusaha mendapatkan kemenangan semutlak mungkin atas lawan[88].
Pada segi lain watak ini nampak pada
semangat yang diberikannya pada rakyat, pengungkapan paedagogik dan sugestif,
ajakan dan dorongan untuk lebih tegap dan perwira memenangkan keadilan merata,
guna maju untuk melawan dan menentang penindasan dan penghisapan serta
penjajahan nasional maupun internasional, bukan saja berdasarkan emosi atau
sentimen, tetapi juga berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Terutama memberanikan
rakyat untuk melakukan orientasi terhadap sejarahnya sendiri. Karena di dalam
penghisapan dan penindasan kapitalisme, rakyat kurang cukup mendapatkan makanan
baik bagi perut maupun bagi otaknya, apalagi melakukan orientasi terhadap
sejarahnya sendiri[89].
Dalam militansi seorang pengarang
menurut pandangan Pram yaitu faham realisme sosialis yang telah menguasai
realitas, yang tidak memenuhi harapan dan keadilan, telah menentang realitas ,
dan dengan jalan kreatif mengubahnya menurut tuntutan keadilan. Watak
pengubahan selamanya revolusioner,
karena realisme sosialis tidak mengajarkan orang menerima realitas dan menyerah
kepadanya, tetapi secara berani dan revolusioner
meninggalkan tingkat “manusia alam”, dan dengan paksa atau tidak menyusun dunia
pikirannya sesuai dengan tantangan yang dihadapinya. Kondisi yang dituntut ini
membikin orang terus-menerus jadi revolusioner
yang bersumberkan revolusi yang terus-menerus di dalam jiwa, pengoreksian
terus-menerus atas realitas, dan dengan sendirinya tidak boleh terlena akan
segala perubahan spontan maupun
perubahan semu daripada realitas itu sendiri bagaimanapun kecilnya dan
dia kentara[90].
Pandangan sastra Pram tentang
realisme sosialis telah menjadi ketentuan bahwa pengarang harus belajar dari
rakyat. Banyak cara yang harus dan bisa ditempuh, terutama membaurkan diri ke
dalam gerakan massa
Pola tersebut juga berlaku dalam
Lekra, sebagai salah satu tombak perjuangan PKI dalam bidang seni. Lekra juga
menganut aliran realisme sosialis. Dalam karya sastra para pengarang Lekra yang
dapat digolongkan pada, pertama sastra
manifest, dengan tema melawan, menolak, menentang kapitalisme, feodalisme, dan
menempatkan diri sebagai penentang, penolak, dan pelawan. Kedua, perkembangan “ Ke
Arah yang Normal “ berjalan bersama dengan perkembangan seluruh kekuatan
progresif di dalam masyarakat, kemenangan-kemenangan Lekra baik di bidang
organisasi, karya, dan kekuatan politik, telah menciptakan kondisi-kondisi
social baru. Ketiga, kritik sastra
realisme sosialis mempunyai garapan yang berbeda daripada kritik sastra borjuis. Kondisi-kondisi politik si
pengarang menjadi syarat terutama karena kondisi politik yang tidak baik sudah
pasti akan melahirkan karya satra yang tidak baik pula. Keempat, sesuai dengan logika, dan sesuai pula dengan kenyataan
hidup, estetika mengambil tempat terakhir dalam kehidupan sosial[93].
Lekra berdiri pada tanggal 17 agustus
1950. pengambil inisiatif adalah D.N. Aidit, M.S. Ashar, A.S. Dharta, dan
Njoto. Sebagaimana pernyataan Lekra sendiri, tentang pendirian organisasi ini
kita dapatkan kalimat-kalimat yang berbunyi demikian:
Apa yang berlangsung ketika
revolusi bersenjata dari revolusi Agustus, yaitu periode antara 1945 dan 1950, bergejolak?
Periode itu, dibidang kebudayaan, ditandai oleh banyak seniman, sarjana dan
pekerja-pekerja kebudayaan lainnya yang memihak pada, ambil bagian dalam dan
memberikan sumbangannya kepada revolusi. Pekerja-pekerja kebudayaan satu dengan
revolusi, dan revolusi 1945 adalah suatu revolusi kerakyatan maka hal ini
berarti, bahwa pekerja-pekerja kebudayaan satu dengan rakyat. Tetapi,
partisipasi atau kesertaan mereka itu di dalam revolusi masih bersifat spontan.
Kespontanan itu tentu tidak hanya di lahirkan oleh intuisi, tetapi juga oleh
kesadaran tertentu. Dalam hal ini kespontanan itu baik. Tetapi juga ia membawa
dalam dirinya seginya yang lain, yaitu: belum teratur, belum terorganisir,
singkatnya, belum terpimpin, dan sebagai akibatnya belum bersasaran yang tepat,
sehingga efek dan hasilnya belum cukup besar jadinya.
Demikianlah lekra didirikan
tepat 5 tahun sesudah revolusi Agustus pecah, disaat revolusi tertahan oleh
rintangan hebat yang berujud persetujuan KMB, jadi disaat garis revolusi sedang
menurun. Ketika itu orang-orang kebudayaan yang tadinya seolah-seolah satu
kepalan tangan yang tegak dipihak revolusi, menjadi tergolong-golong. Mereka
yang tidak setia, menyeberang. Yang lemah dan ragu-ragu seakan-akan putus asa
karena tidak tahu jalan. Yang taat dan teguh meneruskan pekerjaannya dengan
keyakinan bahwa kekalahan revolusi hanyalah kekalahan sementara. Lekra
didirikan untuk turut mencegah kemerosotan lebih lanjut dari garis revolusi,
karena kita sadar, bahwa tugas ini bukan hanya tugas kaum politis tetapi juga
tugas pekerja-pekerja kebudayaan. Lekra didirikan untuk menghimpun kekuatan
yang taat dan teguh mendukung revolusi[94].
Jadi estetika dalam realisme sosialis
bukanlah suatu yang mewah, tetapi sesuatu “social
opgave” yang harus dijawab dan dipecahkan dan dirumuskan kemudian dibuat
berdasarkan rumus tersebut. Setidak-tidaknya estetika bukanlah satu pemutlakan
selama yang dapat menikmati hanya klas yang mendapatkan keberuntungan
pendidikan dan pengajaran[95].
Sebagai mana telah diketahui bahwa
Lekra menganut aliran realisme sosialis, maka orang yang ikut terlibat
didalamnya yaitu Pram juga menganut aliran tersebut. Tokoh yang sangat
mempengaruhi pemikiran Pram adalah Maxim Gorki. Pram, mengambil semua metode
realisme sosialis Maxim Gorki. Tanpa ragu Pram mengatakan bahwa istilah
realisme sosialis timbul pertama kali di bumi yang untuk pertama kali
memenangkan sosialisme, di bumi yang
telah menegakkan sosialisme, yakni
Uni Soviet. Tokoh utama yang biasanya mendapat kehormatan sebagai pelopornya
adalah pujangga besar Soviet Maxim Gorki terutama dengan karya utamnya Ibunda[96].
Dalam pandangan Pram, Maxim Gorki
bukan suatu kebetulan yang oleh sejarah di tunjuk sebagai pelopornya. Baik
triloginya Childhood, My Apprenticeship
dan My Universities maupun cerpen-cerpennya, terutama sekali Di Musim Gugur, secara otobiografik
melukiskan pukulan-pukulan dan tindasan-tindasan yang diterimanya dari klas
kapitalis borjuis. Tidak mengherankan
pula bahwa Maxim Gorki berpihak pada neneknya, seorang wanita pengemis dan di
samping neneknya menentang kakeknya, seorang pengusaha di bidang pencelupan[97].
B. Pandangan Pramoedya
tentang Realisme Sosialis dalam Novel Tetralogi
Realisme sosialis sebagai bagian dari
kepentingan umum kaum proletariat yang
menjadi roda kesatuan besar mekanisme sosial demokratik, yang di gerakkan oleh
kesadaran politik seperti yang dikatakan oleh Lenin, menjadi alat yang ampuh di
tangan prajurit-prajurit kebudayaan, karena sastra realisme sosialis selalu revolusioner. Watak pejuang dan
perjuangan ini akan selalu mewarnai kerja sastranya[98].
Dalam novel di
bawah ini, menggambarkan Minke sang tokoh protagonis sedang diberi nasihat oleh
sahabatnya seorang Perancis. Bagaimana kondisi bangsanya yang sangat membutuhkan
tenaga dan juga pikirannya untuk melawan penjajah yang hidup bergelimang harta,
sedangkan rakyat yang lain menderita.
“Ya, memang belum banyak yang bisa ku dapatakan dalam
diriku. Jean marais bercita-cita mengisi hidup dengan lukisan-lukisan, bukan
hanya menyambung hidup. Untuk apa aku menulis, sampai mendapatkan kemasyhuran
sebanyak itu? Kau tidak adil Minke, kalau memburu kepuasan saja bisa
mendapatakan kemashuran. Tidak adil! Orang-orang lain bekerja sampai berkeringat darah,
mati-matian, jangankan mendapatkan kemasyhuran ,hanya untuk dapat makan dua
kali sehari belum tentu bisa”[99].
Kejadian ini ketika
Minke seorang yang jauh lebih terpelajar harus tetap berjongkok dulu ketika
menghadap seorang Bupati, padahal Bupati tersebut jauh lebih bodoh dibanding
dirinya. Terasa sekali semangat feodalisme pada cerita di bawah ini.
“Jadi aku
akan dihadapkan pada Bupati B. god! Urusan apa pula? Dan aku ini, siswa H.B.S.,
haruskah merangkak dihadapannya dan mengangkat sembah pada setiap titik
kalimatku sendiri untukku sendiri untuk orang yang sama sekali tidak kukenal!
Dalam berjalan ke pendopo yang sudah diterangi dengan empat buah lampu itu aku
merasa seperti hendak menangis. Apa guna belajar ilmu dan pengetahuan Eropa,
bergaul dengan orang-orang Eropa, kalau akhirnya toh harus merangkak, beringsut
seperti keong dan menyembah seorang raja kecil yang barangkali butahuruf pula?
God, God! Menghadap seorang bupati sama dengan bersiap menampung penghinaan
tanpa boleh membela diri. Tak pernah aku memaksa orang lain berbuat semacam itu
terhadapku. Mengapa harus aku lakukan untuk orang lain? Sambar geledek![100]
Tulisan di bawah
ini, Pram menggambarkan bagai mana seorang petani yang berjuang mempertahankan
tanahnya dari rampasan Belanda. Petani tersebut harus berjuang sendiri, karena
orang-orang di sekitarnya takut pada Belanda. Yang lebih ironis lagi banyak
juga yang justru membela Belanda, karena mereka mendapat uang ketika membela
kepentingan Belanda.
“Berteriak apa orang-orang itu?”
“yang tinggal di situ, Ndoro.”
“Di rumah genteng itu?’
“Betul, Ndoro.”
“Mengapa diteriaki?”
“Dia tak juga mau pindah dari tempatnya.”
“Mengapa harus pindah?”
“Mereka “ katanya bengis dan benci,
“anjing-anjing pabrik. Ini tanahku
sendiri. Peduli apa hendak kuapakan,” ia seka keringat dari pundak[101].
Cerita di bawah ini ketika Minke
berbincang-bincang dengan seorang petani, petani tersebut menggunakan bahasa
jawa kasar pada Minke. Sebagai seorang anak Bupati Minke merasa tersinggung, di
sini Pram memperlihatkan antara kelas proletar
dan kelas borjuis. Meski pada
akhirnya Minke ditegur oleh seorang Nyai yang bernama Ontosoroh, ibu mertuanya
sendiri. Nyai Ontosoroh tersebut sangat membenci dengan sIstem feodal, serta
menjunjung tinggi cita-cita revolusi Perancis.
“Perasaan tidak enak masih
juga menongkrong dalam hatiku, karena petani yang seorang ini kembali bicara
ngoko. Benar-benar dia petani yang sudah keluar dari golongannya. Dan apa pula
gunanya aku hadapi baik-baik? Tapi kau sudah bertekad hendak mengenal bangsamu!
Kau harus dapat mengenal kesulitannya. Dia salah seorang bangsamu yang tidak
kau kenal, bangsamu yang hendak kau tulis kalau kau sudah mulai belajar
mengenalnya!.[102]
“Dan kau tidak beda dengan orang-orang lain. Kau tidak
lebih tinggi, tidak lebih mulia dari Trunodongso . itu kalau kau benar-benar
mengerti Revolusi Prancis. Bagaimana kau sekarang Minke?”[103]
Semangat Minke
sebagai seorang jurnalis dikritik oleh sahabatnya sendiri, Jean Maramis, dia adalah seorang perancis
yang menetap di Indonesia
Juga kau hendak membelanya terhadap penindasan dengan
bahasa oleh kau sendiri? Ha, kau tak mau menjawab. Kalau begitu memang tepat
kau harus menulis Melayu, Minke, bahasa itu tidak mengandung watak penindasan,
tepat dengan kehendak revolusi Prancis.[104]
Minke ketika
berdialog dengan orang Belanda yang bernama Tollenaar yang sangat menyanjung
Eropa dan juga Amerika Serikat. Hal tersebut dibantah oleh Minke.
“Aku lebih percaya pada Revolusi Perancis,
Tuan Tollenaar. Kebebasan, persaudaraan dan persamaan, bukan hanya untuk diri
sendiri seperti sekarang terjadi diseluruh daratan Eropa dan Amerika Serikat,
tapi untuk setiap orang, setiap dan semua bangsa manusia di atas bumi ini.
Sikap begini dinamai sikap liberal sejati, Tuan.”[105]
Di sini Minke
diberi penjelasan tentang semboyan revolusi Perancis yang sering kali disalah
artikan oleh orang-orang, sehingga mereka bersikap semaunya sendiri. ketika itu
Minke berdialektika dengan seorang pelarian dari Cina yang bernama Yi Me. Yi Me
adalah pemberontak pada akhir abad XIX melawan monarki Tiongkok yang dikuasai
oleh Kaisar Ye Si.
“jangan salah
artikan kebebasan dalam semboyan Revolusi Prancis” “orang Prancis sendiri juga
banyak menyalah artikan, jadi bebas merampok dan bebas tak berkewajiban pada
siapa pun, walhasil jadi sewenang-mewang tanpa batas. Kebesaran hanya untuk
diri sendiri di negeri sendiri! Semua terpelajar pribumi Asia
dalam kebebasannya mempunyai kewajiban-kewajiban tak terbatas buat kebangkitan
bangsanya masing-masing. Kalau tidak, Eropa akan merajalela”.[106]
Minke ketika berbincang-bincang
dengan Trunodongso seorang petani yang dirampas tanahnya oleh feodal yaitu
Belanda dan juga para suruhannya. Termasuk di sini adalah aparat pemerintah,
tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya. Trunodongso berusaha
mempertahankan miliknya dari Belanda
yang mewajibkan tanahnya di tanami tebu.
“Tentu saja ini
tanahmu sendiri,” kataku memberanikan dia dan diriku sendiri.
“Lima bahu, warisan orang tua.”
“Kau benar,” kataku, “ada kubaca di kantor tanah.”
“Nah, ada tertulis dikantor tanah,” ia bicara pada
dirinya sendiri. Ketegangannya mulai surut. Lambat-laun aku lihat ia mulai
kembali jadi petani jawa yang rendah hati.
“ Ya, Ndoro, sebenarnya sahaya sudah cukup bersabar.
Warisan sayaha lima
“Berapa sewa untuk satu bahu?” tanyaku sambil
mengeluarkan alat tulis-menulis dari dalam tas, mengetahui, semua petani Jawa
menaruh hormat pada barangsiapa melakukan pekerjaan tulis menulis. Akupun
siap-siap mencatat.
“Sebelas picis, Ndoro” jawabnya lancar. Mengherankan.
“Sebelas picis, buat setiap bahu selama delapan belas
bulan?” aku terpekik.
“Betul,
Ndoro.”
“Tiga
talen”
“Kemana
yang tiga puluh lima
“Mana
sahaya tahu, Ndoro. Cap jempol saja, kata mereka tidak lebih dari tiga talen
sebahu. Delapan belas bulan, katanya. Nyatanya dua tahun sampai tunggul-tunggul
tebu habis di dongkeli”.[107]
Dialog di bawah ini dilakukan Minke
ketika berbincang-bincang dengan salah seorang mandor pabrik tebu. Tentang
fenomena masyarakat yang lebih senang menjadi buruh, dari pada menjadi petani.
“Tahu
Tuan upah kuli tebu yang baik dalam sehari? Tiga talen sehari. Kalau orang
kerja jadi kuli, dua hari saja, yang diperolehnya sudah melebihi sewa tanahnya
sendiri sebanyak satu bahu. Siapa bilang orang lebih suka menggarap sawah
sendiri daripada jadi kuli tebu? Berapa harga kerja cangkul dalam sehari? Tiga
benggol, tidak lebih.”[108]
Ekspansi Belanda pada Indonesia Indonesia
Pribumi bertombak dan
berpanah akan mati bergelimangan lagi atas perintahnya, entah dimana akan
terjadi. Demi keutuhan wilayah, kata-kata lain dari: demi keamanan modal besar
Hindia. Darah, jiwa, perbudakan, penganiayaan perampasan, penghinaan akan
terjadi lagi di bawah tudingan tangannya.[109]
Kekejaman Belanda
tidak pernah berhenti mesti rakyat sudah sangat menderita, manusia sudah tidak
ada lagi harganya. Perampasan bukan hanya pada ekonomi semata tetapi juga istri
dan anak gadisnya.
Perlakuan sewenang-wenang dalam
perusahaan-perusahaan kereta api, perkebunan, kantor-kantor Gubermen, perampasan
anak gadis dan istri oleh pembesar-pembesar setempat dengan menggunakan
kekuasaan yang ada pada mereka, mengisi permohonan-permohonan pertolongan.[110]
Cerita yang di
bawah ini adalah awal berdirinya organisasi pribumi pertama yaitu Boedi Oetomo,
yang akan menjadi cikal bakal organisasi lain di Indonesia.
Utusan Raden Tomo telah datang kebandung untuk menagih
janji. Ia dan teman-temannya sesekolah telah berhasil membentuk sebuah
organisasi sebagaimana pernah di anjurkan oleh dokter Jawa pensiunan dulu. Juga
olehku sendiri. Nama organisasi: Boedi Oetomo[111].
Boedi Oetomo sebuah organisasi
pribumi pertama, yang bergerak pada bidang pendidikan untuk semua masyarakat.
Karena pada penjajahan Belanda pendidikan hanya boleh dinikmati oleh orang
Belanda, Indo, dan juga dari kaum priyayi. Rakyat jelata tidak bisa sekolah, B.
O melihat hal tersebut sebagai penindasan yang harus dihapuskan. Pendidikan
penting untuk menciptakan masyarakat yang kritis hingga mampu merubah nasibnya.
“Dan bahwa ada gerak dari minus ke plus pada umat
manusia, dan itu dinamai gerak juang? Lupa kau, Koen? Atau B.O yang lupa? Kan
B.O. tidak bermaksud mempertahankan yang ada, agar yang miskin tetap miskin,
yang bodoh tetap bebal, dan yang sakit tinggallah menggeletak menungggu
sakratulmaut?”[112]
Tidak ada tingkatan dalam bahasa
Melayu, dan bahasa tersebut sesuai untuk digunakan dalam sebuah organisasi,
karena dalam sebuah organisasi tidak ada yang lebih senior atau yunior semua punya kedudukan yang sama. Minke tengah
berdialog dengan adiknya yang juga seorang organisatoris.
“Dalam
rapat-rapat cabang yang tahu bahasa Jawa tentu tak diharuskan berbahasa melayu.
Tetapi kalau tingkatnya sudah Kongres atau tingkat Pusat, atau berhubungan
denga pusat, tak bisa tidak harus dipergunakan Melayu.” “Mengapa Jawa harus
dikalahkan oleh Melayu?” “Diambil praktisnya, Mas. Sekarang, yang tidak praktis
akan tersingkir. Bahasa Jawa tidak praktis. Tingkat-tingkat di dalamnya adalah
bahasa presentasi untuk menyatakan kedudukan diri, melayu lebih sederhana.
Organisasi tidak membutuhkan pernyataan kedudukan diri. Semua anggota sama, tak
ada yang lebih tinggi atau lebih renadah.”[113]
S.D.I adalah Serikat Dagang Indonesia
Di
kota-kota sepanjang pesisir utara Jawa Barat telah berdiri cabang-cabang dengan
anggota rat-rata empat puluh sampai seratus orang. Di kota-kota pegunungan
memang lebih sendat. Di Tasikmalaya, Garut dan Sukabumi nampak adanya kegiatan
mengagumkan. Garut mencactat sejarah: disini pernah di adakan rapat umu
propaganda S.D.I. rapat umum pertama.[114]
S.D.I membuat
komitmen dengan para anggotanya tentang garis kebijakan organisasi. Sebagai
organisasi pribumi pertama yang berkonsentrasi masalah ekonomi, dan harus
melawan kebijakan ekonomi Belanda maupun Cina dan juga Arab yang sudah lebih
dulu menguasai ekonomi masyarakat Indonesia
“Organisasi
ini lahir di tanah Hindia sebagai organisasi Pribumi, bukan organisasi segala
bangsa yang bermaksud untuk mrerugikan Pribumi. Tidak ada hak pada siapa pun,
bangsa apa pun anggota atau bukan anggota S.D.I. untuk merugikan Pribumi, baik
pedagangnya atau petaninya, ataupun tukang-tukangnya. Kalau ada cabang yang
punya cara dan jalan sendiri yang sengaja dan diketahui melakukan tindakan
merugikan terhadap pribumi, itu bukan cabang S.D.I. seluruh Hindia dapat
melakukan tindakan serentak terhadap cabang durjana demikian. Aku yakin,
saudara-saudara, dewan pimpinan pusat tidak akan ragu-ragu mengeluarkan
titahnya.”[115]
Minke menyadari pentingnya sebuah
pendidikan untuk rakyat Indonesia Indonesia
Orang Arab, yang sama sekali
tidak pernah mendapat pendidikan Eropa ini, ternyata mempunyai pengetahuan
praktis yang sangat patut untuk kuindahkan dan kupelajari. Putra-putranya ia
kirim ke Universitas Turki, menguasai banyak bahasa modern.[116]
Minke ketika
memikirkan ucapan guru agamanya yang bernama Syeh Ahmad Badjened, dan Minke
membenarkannya. Bahwa dalam berdagang membuat orang jadi lebih demokratis dan
berpengetahuan luas, karena pedagang lebih banyak bertemu orang dan singgah di
berbagai tempat yang berlainan adat istiadatnya.
“Pedagang
orang paling giat di antara umat manusia ini, Tuan. Dia orang paling pintar.
Orang menamainya juga saudagar, orang dengan seribu akal. Hanya orang bodoh
bercita-cita jadi pegawai, kerjanya hanya disuruh-suruh seperti budak. Bukan
kebetulan Nabi s.a.w pada mulanya juga pedagang. Pedagang mempunyai pengetahuan
luas tentang ikhwal dan kebutuhan hidup, usaha dan hubungannya. Perdagangan
membikin orang terbebas dari pangkat-pangkat, tak membeda-bedakan sesama
manusia, apakah dia pembesar atau bawahan, bahkan budak pun. Pedagang berpikir
cepat. Mereka menghidupkan yang beku dan menggiatkan yang lumpuh.”[117]
Minke menolak ketika S.D.I akan
diganti Indisch bukannya Islam, sebab
menurut Minke Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat luas dari pada
Indisch. Karena istilah Indisch sendiri adalah untuk indo eropa.
“Islam
dan dagang mempunyai landasan lebih luas dan lebih mengikat dari pada indisch.
Pikiran-pikiran Tuan bukan tidak kupertimbangkan. Landasannya tidak ada, kurang
jelas. Setidaknya-tidaknya belum aku lihat, hanya berupa cita-cita, bukan
kenyataan. Memang cita-cita bisa menjadi kenyataan di kemudian hari, tetapi
landasannya tetap kenyataan sosial masakini”.[118]
Minke memandang bahwa hanya Islam
yang mampu membangkitkan rasa perlawanan terhadap sistem penjajahan yang
terjadi pada masyarakat Indonesia
Islam,
kataku selanjutnya, yang secara tradisional melawan penjajah sejak semula Eropa
datang ke Hindia, dan akan terus melawan selama penjajah berkuasa. Bentuknya
yang paling lunak: menolak kerjasama, jadi pedagang. Tradisi itu patut di
hidupkan dipimpin, tidak boleh mengamuk tanpa tujuan. Tradisi sehebat dan
seperkasa itu adalah modal yang bisa menciptakan
segala kebajikan untuk segala bangsa Hindia[119].
Rapat S.D.I pertama pada saat itu
Minke, sang tokoh protagonis menjadi ketua. Minke berpendapat bahwa Islam harus
membela yang lemah. Seperti petani, karena dalam banyak kasus petanilah yang
paling menderita dalam kebijakan ekonomi Belanda, dan kebanyakan di antara
mereka bodoh serta buta huruf.
“Tetapi
para petani itu adalah saudara-saudara kita sendiri, sebangsa kita sendiri, yang
hendak diperas tanah dan duitnya secara gegabah oleh perusahaan-perushaan
raksas Eropa, Arab dan Cina. Kalau Tuan-tuan membiarkan ini terjadi, Tuan-tuan
membenarkan pemerasan itu, Tuan-tuan membenarkan kejahatan, apa itu di benarkan
dalam Islam? Kan
Douwager adalah salah satu gubermen
Belanda, dia merasa sudah benar dengan kedatangan Belanda dan sistem ekonomi yang ada. Minke membatah
hal tersebut, karena kebijakan Belanda sangat merugikan masyarakat, meski
ketika Belanda datang mengatas namakan berdagang.
“Eropa
datang berdagang kemari, Tuan, tapi menjauhkan dirinya dari Pribumi. Malah memperdagangkannya.”
“Eropa
datang bukan untuk berdagang dengan kita. Mereka datang dengan meriam dan
bedil.”
“Apa
pun alat yang dibawanya, mereka berdagang.”
“Kalau
sekarang ini aku todong Tuan dengan senapan, aku rampas semua pakaian Tuan,
sehingga tinggal selembar setangan untuk menutup kemaluan, kemudian aku
tinggalkan pada Tuan satu setengah sen, pastilah itu bukan berdagang. Dan
itulah wajah Eropa colonial, sesungguhnya.”
“Tuan
lupa, meriam dan Bedil juga alat berdagang pada jamannya,” bantah Douwager.
“Masih berlaku di banyak tempat sampai sekarang, kalau bangsa sudah ditaklukkan
seperti di Hindia ini, bangsa taklukan dibikin jadi penghasil barang dagangan.
Malah diperdagangkan.”
“Sama
saja, Tuan. Perdagangan terjadi hanya karena suka antara kedua belah pihak yang
berkepentingan. Selama tak ada syarat itu, dan pertukaran terjadi, itu bukan
perdagangan, itu kejahatan”[121] .
S.D.I mulai berganti nama menjadi S.I
( Sarikat Islam), kalau S.D.I hanya membahas masalah ekonomi semata, S.I tidak
demikian, SI juga membahas politik, budaya, dan juga ekonomi.
Dokumen keempat adalah sebuah laporan
panjang dari Sala, memakan tidak kurang dari empat puluh halaman, di tulis oleh
tangan yang mahir, kecil-kecil dan rampak, tapi dalam bahasa Melayu yang sangat
buruk. Laporan itu mencatat tentang terjadinya kegiatan S.D.I. di Sala, yang
menarik perhatian pemerintah putih dan Pribumi: haji Samadi dengan pimpinan
S.D.I. cabang Sala telah mengeluarkan pernyataan, bahwa telah didirikan
perkumpulan bernama Syarikat Islam dengan dia sendiri sebagai pimpinannya.
Tetapi, semua pimpin di dalamnya adalah juga pimpinan S.D.I.[122]
S.D.I diseluruh
daerah juag mengganti nama menjadi S.I, sesuai dengan keputusan organisasi.
Cabang-cabang S.D.I. segera menyesuaikan
diri dengan menamakan diri Syarikat Islam dalam suatu koperensi darurat di
Sala. Arus anggota baru tak dapat kubendung. Aku mengerti, bahwa saat untuk
berorganisasi telah tiba dalam daftar kebutuhan pribumi di Jawa. Tugasku
menghadang ini. Tidak hanya aku saja. Aku kira semua ahli dan penguasa colonial
terheran-heran mengikuti perkembangan Syarikat setelah terjadinya penyerahan
pimpinan dari Minke ke tangan Hadji Samadi.[123]
Belanda untuk mempertahankan
kekuasaanya salah satu strateginya adalah memberi kesadaran mistis kepada
rakyat Indonesia Indonesia
Sudah tepatkah pandangan
Eropa colonial ini? Bukan saja tidak tepat, juga tidak benar. Tetapi Eropa
colonial tidak berhenti sampai di situ. Setelah Pribumi jatuh dalam kehinaan
dan tak mampu lagi membela dirinya sendiri, dilemparkannya hinaan yang
sebodoh-bodohnya. Mereka mengetawakan penguasa-penguasa Pribumi di Jawa yang
menggunakan tahyul untuk menguasai rakyatnya sendiri, dan dengan demikian tak
mengeluarkan biaya untuk menyewa tenaga-tenaga kepolisian untuk mempertahankan
kepentingannya. Nyai Roro Kidul adalah kreasi Jawa yang gemilang untuk
mempertahankan kepentingan raja-raja Pribumi Jawa. Tapi juga Eropa
mempertahankan tahyul: tahyul tentang hebatnya ilmu pengetahuan agar
orang-orang jajahan tak melihat wajah Eropa, wujud Eropa, yang menggunakannya.
Baik penguasa Eropa colonial maupun Pribumi sama korupnya[124].
S.I mulai terpecah karena terlalu
banyaknya anggota, sehingga kontrol terhadap para anggotanya sangat sulit.
Indische Partij, adalah aliran sosialisme yang dibawa masuk oleh orang Belanda
yang di usir dari negaranya, kemudian mereka tinggal di Indonesia
Syarikat aku anggap sebagai gelembung
akibat samudra kehidupan yang telah teraduk unsur-unsur modern, dan pada suatu
kali gelembungan ini akan meletus berpecahan tanpa meninggalkan bekas. Indische
Partij lain lagi. Ia justru mempersatukan unsur-unsur manusia modern di Hindia,
peranakan Eropa dan terpelajar Pribumi sekaligus. Dalam jumlah anggota ia tidak
berarti dibandingkan dengan Syarikat. Dalam kesadaran berpolitik dia lebih
unggul.dalam kesadaran berpolitik dia lebih unggul. Dalam kesadaran berpolitik
Mas Tjokro masih harus banyak belajar dari mereka. Tapi bagaimana pun dua organisasi
itu menyala di angkasa hitam seperti dua bintang, terpisah jutaan mil satu dari
yang lain, tak pernah ada usaha pendekatan, jangankan persinggungan. Yang satu
gemuk dengan kebanyakan anggota dan tak bisa berbuat apa-apa. Yang lain dengan
hanya anggota ratusan orang dan bakal kurus-kering dirongrong oleh
keinginan-keinginan tanpa batas[125].
Tulisan ini tidak untuk mengucilkan
kaum Nasrani, penggambaran Nasrani di sini bukan agamanya. Hanya simbol Nasrani lahir di Eropa, maka Eropa yang
dimaksud oleh Pram. Eropa di sini adalah Belanda, dan juga sekutunya.
Aku tahu, bahwa aku harus mengelakkan
percakapan yang menyudutkan ini. Benar sekali, bahwa pada jamannya agama juga
politik. Bangsa-bangsa Hindia yang Nasarani memang tidak mencari pertengkaran
dengang gubermen yang Nasrani pula, tetapi tulisan-tulisan Raden Mas Minke
menunjukkan contoh-contoh, bahwa juga orang-orang tertentu bisa mencari
pertengkaran dengan bangsanya sendiri, seperti Khouw Ah Soe dan Ang San Mei.
Benar mereka Protestan dan Katholik, tapi mereka bukan karena agama ikut
berusaha menggulingkan dinasti Ching. Mereka digerakkan oleh sesuatu yang lain,
yang bernama Nasionalisme.
Mas Marco Kartodikromo, dia adalah
pencipta Sama Rata Sama Rasa. Dengan slogan tersebut banyak masyarakat yang
berani melawan Belanda, di dukung juga oleh tulisan-tulisannya yang selalu
membakar semangat nasionalisme.
Tulisan di bawah ini memotret saat
terjadinya perpecahan di dalam S.I, perpecahan tersebut melahirkan banyak
organisasi di antaranya PKI.
Mempertentangan dua golongan dari pandangan
dan sikap yang berlain-lainan memang terlalu gampang. Tetapi akibatnya akan
berlarut. Syarikat akan menghadapi mereka sebagai orang Eropa pada umunya, dan
kebencian pukul rata pada Belanda akan menjadi hasilnya. Sedang sayap Marco,
yang selama ini tidak mendapat medan
Pram tidak lupa juga menulis tentang
pemberontakan para karyawan pegadaian, mereka adalah para anggota PKI. mereka
menuntut kenaikan upah dengan cara memboikot tidak masuk kerja, dan cara-cara tersebut
juga diikuti oleh anggota PKI yang lain.
Di Jawa Timur dan Tengah orang
memekik-mekik menuntut kenaikan upah sambil membelot-kerja alias staking.
Pegawai-pegawai pegadaian di beberapa tempat menolak memasuki tempat kerjanya
dan kumpul-kumpul di pelataran, berbaur dengan orang-orang yang hendak
menggadaikan. Buruh beberapa perkebunan kemudian mengikuti.
Bahasa melayu
juga menjadi alat untuk melawan system feodal Belanda, sebab bahasa tersebut
lebih demokratis dari pada bahasa Belanda maupun Jawa.
“ Perhitungan tidak meleset. Hanya dengan
bahasa Melayu bukan Gubermen, dan di antara orang-orang bebas, tidak dengan
orang-orang dengan jabatan negeri, organisasi umum di hindia akan bisa menjadi
besar dan subur. Beberapa kali aku harus bekerja keras meyakinkan Samadi, yang
lebih menghendaki bahasa Jawa. Bahasa melayu, semakin jauh dari pengajaran
Gubermen, semakin jauh dari orang-orang feodal, semakin demokratis dan menjadi
alat perhubungan yang nyaman, memang bahasa bebas untuk orang bebas. Dan hanya golongan
bebas yang akan menentukan nasib bangsa-bangsa Hindia, karena salah satu syarat
untuk persatuan bagi bangsa-bangsa ganda ini adalah dekat mendekati atas dasar
demokrasi[128].”
Perkembangan kesadaran mulai terlihat
di sini, bahwa media jurnalistik adalah alat yang paling ampuh untuk melawan
system yang menindas. Karena jurnalistik mampu membangun opini masyarakat,
tanpa harus pergi ke daerah-daerah tersebut.
Dari semua kegiatan Pribumi itu, ternyata
yang dianggap mahkota kegiatan adalah jurnalistik. Dan barang tentu bukan
jurnalistik sebagaimana dikenal oleh Eropa, tapi menulis di Koran atau majalah
dengan nama terpampang, baik nama benar, nama pena atau inisial. Gejala baru
ini langsung berasal dari Raden Mas Minke, ia pernah mengatakan pada salah seorang
temannya: orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia
akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Ucapan lain dari si Gadis
Jepara: menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dan jurnalistik gaya
Berikut adalah
tulisam Mas Marco Kartodikromo, dengan slogan “ Sama Rata Sama Rasa” yang
begitu kuat tuntutan keadilan :
Dari tulisannya (Mas Marco Kartodikromo)
dapat diketahuai apa sesungguhnya yang selama ini hidup dalam sanubarinya.
Pada
suatu hari dia tak mampu bekerja. Bininyapun tidak, karena telah jatuh sakit
terlebih dahulu. Tinggal anaknya yang berumur sembilan tahun yang masih sehat.
Tak urung punggawa desa memaksa anak umur sembilan tahun itu berangkat juga
mewakili bapak dan emaknya.
Anak
ini menangis sepanjang jalan setapak yang empat kilo meter jauhnya itu. Bukan
hanya karena lapar, kakinya disarangi bubul, dan patek meruyak sepenuh badan.
Dalam iring-iringan yang berjalan lambat-lambat itu terdapat perempuan kurus
yang sedang bunting tua, kakek-kakek yang bertongkat dan terbatuk-batuk,
seorang lelaki yang menggendong anak susuan karena emaknya baru saja mati
kelaparan.
Iring-iringang
calon mayat pada beberapa bulan mendatang semua menuju keselatan. Kekebun nila
Gubermen. Kerja paksa. Tanam paksa! Tanpa upah. Cultuurstelsel
Nama
desa itu adalah Cepu. Bukan Cepu yang sekarang. Desa itu miskin. Tetapi bekas
desa ini sekarang telah jadi distrik yang terkaya di Hindia. Disini aku
dilahirkan. Disini pula aku dengarkan cerita orang-orang tua yang dahulu setiap
hari dalam sekian bulan berangkat kekebun nila Gubermen, tanpa upah, tanpa
jaminan, tidak sempat menggarap sawah dan ladang sendiri. Dan setiap hari ada
saja diantara mereka berjatuhan mati karena sakit dan lapar.
Desaku
seperti desa-desa lain. Semestinya orang hidup bertani, mencari kayu dihutan,
berternak kambing, sapi, ayam dan dirinya sendiri, dan hidup dalam keluarga
besar. Tetapi cultuurstelsel telah
mencerai beraikan keluarga besar itu dan merampas nasi dan jiwa mereka.
Pendeknya
jangan bayangkan Cepu desaku sebagai Cepu distrik yang sekarang ini. Cepu
desaku dilindungi oleh begitu banyak pohon buah, Cepu distrik dilindungi oleh
tiang-tiang listrik dan telfon.
Sianak
berumur sembilan tahu itu sudah bekerja selama sepuluh hari ketika Ia ditemui
dirumahnya yang kosong dimalam hari. Daun-daunan yang ia kumpulkan dari
perjalanan pulang Ia letakkan diatas lantai tanah . tungku dingin. Tak ada
makanan, tak ada orang. Ia berseru-berseru memanggil-manggil bapak dan emaknya
yang sakit tanpa jawaban. Ia pergi kerumah tetangga-tetangga. Melulu
orang-orang sakit saja yang ada. Yang seperempat dan setengah sakitpun pada
pergi.
Menjelang
subuh bapaknya pulang bergandengan tangan dengan orang-orang lain yang sama
kehabisan tenaga, tunjang menunjang agar tak roboh dan tak tersasar dalam kegelapan. Mereka baru pulang dari
menguburkan emaknya.
Sebulan
kemudian lebih banyak lagi orang dikuburkan semacam itu, termasuk bapaknya
sendiri.
Sibocah
itu terus juga melakukan kerja paksa makannya rumput muda, karena itulah yang
termudah didaptnya sewaktu kerja. Lagi pula daun dan buah muda petai cina itu,
biarpun agak berasa, membikin semua rambutnya rontok, dan dalam keadaan kurus
kering tanpa rambut, orang akan kelihatan seperti setan.
Pada
suatu kali orang mendengar kabar, Gubermen telah menghapuskan kebun nila,
menghapuskan kerja tanam paksa. Tetapi desa itu terus juga melakukan tanam
paksa sampai dua tahun lagi. Dikemudian hari dapat aku ketahui, tanam paksa
setelah Gubermen menghapuskannya adalah untuk kepentingan pembesar-pembesar
setempat, Eropa dan pribumi.
Aku
tak tahu bagaimana jalannya maka tanam paksa akal-akalan setempat itu akhirnya
dihentikan. Mungkin juga karena pembagian hasil yang tidak seimbang. Pendeknya
aku tahu. Itu urusan dewa-dewa yang berkuasa. Maka orang kembali mengerjakan
sawah dan ladang yang telah kembali jadi hutan dan semak-semak. Penduduk telah
berkurang lima
Kemudian
menyusul berita-berita, kebun-kebun Gubermen akan dijadikan kebun swasta. Dan
kebun-kebun itu akan jadi milik orang-orang Eropa. Orang-orang desa boleh
bekerja di sana
Sementara
itu si bocah itu telah berumur sebelas tahun, sudah lebih kuat dari tiga tahun
sebelumnya. Berita-berita itu tak pernah menjadi kenyataan. Yang benar:
tanha-tanah perorangan dan desa malah dirampas oleh Gubermen, termasuk
lima-perenam dari milik desa. Juga
katanya untuk perkebunan sawsta. Melihat perampasan itu, petani-petani yang
baru saja bangun dari kematian dan kelaparan, bangkit marah. Di pimpin oleh pak
Samin, seorang desa lain, sebuah pemberontakan tani terjadi.
Si
bocah berumur tiga belas tahun itu menggambungkan diri dengan para pemberontak.
Tapi petani-petani itu dikalahkan dan dikalahkan dengan mudah, oleh polisi
lapangan, yang didatangkan dari kota
Penduduk
lelaki yang terlepas dari penangkapan kembali kedesa semula. Jumlahnya lebih
sedikit lagi, mati dalam banyak pertempuran.
Si
bocah berumur lima
Rasa-rasa
ketenangan dan kedamaian akan berlangsung terus dan tanah-tanah akan
dikembalikan. Ternyata tidak. Tanah-tanah yang dirampas mulai dihutankan dengan
jati. Katanya, tak ada perusahaan Eropa mau mengerjakan tanah rampasan, yang
dianggap terlalu banyak mengandung kapur dan tidak subur itu.
Ternyata
bintang kecelakaan tetap bersinar. Kemudian penduduk diusir dari desa, karena
perusahaan minyak akan mendirikan kantor-kantor dan kilang-kilang di situ.
Penduduk pindah dengan ternaknya, kembali membabat hutan untuk ladang, sawah
dan perumahan. Orang bilang, tanah yang dirampas itu akan diganti dengan uang,
tapi tak seorang pun pernah melihat uang yang dijanjikan tanpa jumlah
disebutkan itu. Bahkan setiap pohon di atas tanah rampasan, katanya, telah
dibayar penuh. Hanya berita belaka.
Desaku
yang sejuk di bawah rerimbunan pohon-pohon buah seperti disulap berubah jadi
tanah lapang. Podok-pondok hilang. Jalan-jalan yang indah dibangun, demikian
juga gedung-gedung. Semua serba indah, hanya bukan milik penduduk desa.
Si
bocah tinggal di desanya yang baru. Disana ia kawin dengan sisa dari
perawan-perawan yang tidak direnggut oleh maut. Dan di antara anak-anak adalah
aku.
Dikemudian
hari, jauh di kemudian hari, dapat kuketahui, bahwa dalam hanya lima tahun,
perusahaan minyak yang bermodal lima
Betapa
anehnya pembagian rezeki dan pembagian nasib bikinan manusia ini. Aku tahu dan
berani membuktikan, bahwa tuan-tuan minyak ini pada mulanya adalah insiyur
Geologi Gubermen di Bandung. Dengan tugas Gubermen mereka melakukan
eksplorasi-eksplorasi di daerah hidup aku, orang tuaku, tetangga dan
sanak-keluarga, di atas tanah nenek-moyangku dilahirkan, dan dikuburkan.
Penduduk desa selalu menyambut pendatang-pendatang itu dengan baik dan ramah,
tak perduli warna kulit dan apa agamanya. Kayu-bakar, kelapa tua dan muda,
buah-buahan kami antarkan ketempat mereka. Setelah sumber ditemukan, mereka balik
kembali ke Bandung, dan : minta keluar dari jabatan Gubermen. Mereka kembali lagi ke Cepu sebagai
nyamuk-nyamuk raksasa yang menyedot darah, daging, tanah kami, dan minyak kami
dalam kandungan bumi nenek-moyangku. Dalam sepuluh tahun perusahaan minyak ini
telah jadi perusahaan berjuta, sedang bekas tuan rumahnya telah kehilangan
tanah dan tetap hidup dalam keadaan yang semakin miskin. Bukan itu saja, dari
petani bebas berbahagia mereka mulai berubah jadi kuli-kuli bekas tamunya.
Ketika
pengeboran-pengeboran baru sedang giat-giatnya dilakukan di sekitar daerah
hidup kami, aku dilahirkan. Bapakku, si bocah berpatek dan berbubul dulu, kini
bukan lagi kuli minyak. Ia jadi lurah. Dan perusahaan minyak menjadi rakus akan
tanah. Mereka takut saingan perusahaan-perusahaan minyak lainnya yang tumbuh
seperti cendawan di sekitar daerah hidup kami. Tanah-tanah yang dirampas mulai
dibayar. Pesaing-pesaing itu takut saling membongkar kejahatannya terhadap
penduduk.
Desa
kami rasa-rasanya telah kehabisan tanah untuk melepas ternak besar kami. Bila
ada salah seekor ternak kami lepas dan memasuki daerah perusahaan minyak,
polisi minyak akan menangkapnya, menyitanya, dan pemiliknya dicari untuk
didenda, seratus kali penghasilan umum dalam sehari, alias ringgit.
Aku
hanya hendak menceritakan, dalam pemerintahan Gubermen masih ada pemerintahan
minyak, dua-duanya harus dipatahkan oleh penduduk desa kami.
Sekarang
ribuan orang dari daerah-daerah lain, segala bangsa, datang mencari penghidupan
di Cepu. Dalam waktu pendek Cepu, yang tadinya terdiri hanya atas tiga desa
berbiak menjadi dua puluh tiga desa, menjadi kota
Hampir-hampir
terjadi pemberontakan lagi di kalangan petani. Mendadak beberapa orang di
antara penduduk desa di tangkapi dan tak kembali lagi untuk selama-lamanya.
Mereka ditangkapi oleh polisi-polisi minyak.
Setelah
itu rasa-rasanya keadaan takkan gelisah lagi. Seakan-akan kembalilah keamanan
yang lama dalam segala kekerdilannya. Baik Gubermen maupun perusahaan minyak
tetap tak berbagi keuntungan dengan penduduk. Dan pada kami tak ada ternak
besar lagi. Peternakan desa pun telah tumpas semasa tanam-paksa.
Kalau
aku seorang Ameri Srikat, Tuan-tuan pembaca yang terhormat, tahulah Tuan-tuan
apa yang akan aku perbuat: tarik pistol dan membela apa yang masih dapat
dibela. Tapi aku hanya seorang bocah pribumi tanpa sarana, tanpa pengetahuan
tentang dunia. Bahkan di mana sesungguhnya desa tempat kelahiranku di
tengah-tengah dunia ini, aku tak tahu. Di mana tempat orang-orang yang
memiskinkan kami aku tak tahu. Aku hanya lulusan sekolah desa tiga tahun,
dididik untuk jadi kuli minyak, bekerja untuk mereka yang telah merampas tanah
leluhurku. Dididik untuk tetap tidak berpengetahuan, dan mematuhi segala apa
saja yang diperintahkan pada kami oleh tuan-tuan kulit putih.
Ketika
bapakku hendak meninggal, ia berpesan dengan sangat:
“
Mereka telah merampas semua dari kita. Jangan, Nak, jangan kau lebih lama jadi
kulinya. Pergi kau ke Bandung
C. Faham Realisme Sosialis
dalam Realitas Empirik
Realisme sosialis, meskipun
berkecimpung dalam bidang sastra, ataupun kesenian semisal lukis, teater,
ketoprak, dan masih banyak lagi. Tapi realisme sosialis selalu berangkat dari
esensi masalah yang dihadapi masyarakat sekitarnya. Seniman yang mampu
merefleksikan ensensi realitas, sehingga seni tidak akan pernah tercerabut dari
permasalahan yang ada pada masyarakatnya.
Seni yang indah menurut Georg Lukacs, seorang tokoh realisme sosialis berasal dari Uni Soviet,
mengungkapkan kebenaran realitas. Kebenaran dalam konsepsi Lukacs adalah jika
realitas dipahami dalam totalitasnya. Pemahaman akan realitas total hanya
terjadi jika seniman mampu memahami gerak dialektik dari realitas. Memahami
adalah mengerti dengan melibatkan seluruh kesadaran diri.[131]
Hal ini yang dilakukan oleh Lekra,
mereka mengirim para anggotnya ke tempat-tempat penting di desa-desa kaum tani
dan ke kampung-kampung kaum buruh. Salah seorang tokoh PKI Njoto SOBSI atau lengkapnya atas nama kaum buruh dengan
semua serikat buruh anggotanya, setelah melukiskan perjuangan kaum buruh juga
dalam melawan kesulitan hidup agar tiada punah
Alangkah baiknya, jika keteguhan tekad kaum
buruh ini dibacakan melalui karya-karya seni sastra, sehingga kaum buruh dapat
lebih satu hati dan satu pikiran dalam perjuangan menghapuskan kepincangan
sosial[132].
Selanjutnya:
Kami
menyatakan terimakasih atas ungkapan-ungkapan yang telah dilakukan oleh
sastrawan dalam bentuk sajak-sajak, cerita-cerita pendek, karikatur-karikatur
dan sebagainya terhadap semua keunggulan perjuangan rakyat Indonesia massa
Dari kutipan di
atas, dapat diambil kesimpulan bahwa antara seni dan realitas itu sangat
berhubungan erat. Sehingga jika seorang seniman ataupun sastrawan ingin
memotret tentang keadaan para buruh dan juga petani maka mereka diharapkan
turun langsung ke lapangan. Agar mereka para seniman tersebut dapat merasakan
apa yang dialami oleh para petani dan juga para buruh. Sehingga para seniman dapat
menggambarkan dengan pasti, dan juga detail setiap peristiwa yang dialami oleh
buruh dan petani tersebut. Sebagai mana pidato Njoto:
“Kami
mengundang para seniman dan sastrawan yang cinta rakyat, baik yang tergabung
ataupun yang tidak tergabung dalam Lekra untuk menyempatkan diri turun kebawah,
bicara dan berunding langsung dengan kaum buruh dan para aktivisnya[134]”.
Seniman dalam
realis sosialis harus juga turut merasakan, pahit dan getirnya, kalah dan
menangnya. Karena dalam kehendak masyarakat itulah terletak yang adil dan benar, karena masyarakat buruh dan juga
petani adalah masyarakat yang paling merasakan dampak kesenjangan ekonomi.
Dalam artian penindasan yang dilakukan oleh para borjuis, entah itu berupa pemutusan
hubungan kerja (PHK) sepihak, ataupun minimnya gaji yang diterima. Sedangkan
bagi petani, harga gabah yang terus turun ataupun pengambilan atas tanah
garapan mereka.
Tugas realisme
sosialis juga memberikan dorongan pada rakyat yang masih pasif, sugestif untuk
lebih berani memenangkan keadilan merata, untuk maju, untuk melawan dan
menentang penindasan dan penghisapan serta penjajahan nasional maupun
internasional, bukan saja berdasarkan ilmu dan pengetahuan, terutama
memberanikan rakyat untuk melakukan orientasi terhadap sejarahnya sendiri.
Karena dalam
penghisapan kapitalisme, rakyat kurang cukup medapatkan dukungan apalagi
melakukan orientasi bagi sejarahnya sendiri. Pemberanian-pemberanian semacam
ini sama halnya dengan penggalangan moral atau spiritual, karena tanpa kekuatan
spiritual tidak ada perjuangan itu bisa kuat.
Salah satu contoh
dari militansi realisme sosialis dapat diketengahkan disini sepenggal tulisan
Mas Marco Kartodikromo seorang jurnalis dan yang menciptakan slogan Sama Rata
Sama Rasa dalam membela klas buruh:
“
Penghisapan yang begini macam kasta buruh haruslah dibantah dengan
sekeras-kerasnya”
“Tidak
usah kita ambil contoh busuk, tetapi sekarang saja cukup. Siapakah yang
menjalankan mesin-mesin? Siapakah yang pergi kesana-kemari untuk mengatur
perdagangan dan lain-lain? Siapakah yang menggalang rumah besar-besar dan
gedung-gedung yang indah-indah itu?
“Sudah
tentu buruh! Si modal tinggal menghisap cerutu saja”.
“Siapakah
yang menjadi soldadu?
“Sudah
tentu buruh!
“Padahal
militerisme bukan kecil artinya dalam dunia kemodalan. Jadi dalam ini perkara
artinya buruhlah yang menjalankan praktik
untuk mengatur negeri. Majikan tinggal perintah-perintah saja sambil menunggu
datangnya laba”.
“Umumlah
memang bahwa buruh tak dapat mencapai pengetahuan yang tinggi-tinggi, sebab
dalam jamannya kemodalan, pengetahuan itu dijual dengan harga yang
setinggi-tingginya. Karena buruh itu miskin, tidak heran kalau mereka pada masa
ini tinggal bodoh.”
“Padahal
pengetahuan-pengetahuan yang bisa membikin kemajuan manusia itu tidak harus
dijual sebagai barang dagangan, tetapi harus diberikan bagi kesejahteraan
negeri. Lagi pula semua pelajaran itu sekarang terisi dengan racun kemodalan
yang bisa menyempitkan angan-angan buruh”.
“Dan
jikalau buruh yang mulai dulu sampai sekarang itu yang menjalankan sekalian
yang perlu buat pergaulan hidup, apakah buruh tak bisa mengatur ketentraman
dengan peraturan yang dirembug dengan teman sejawatnya sendiri?”[135]
Sebagai salah satu
aliran seni yang berlandaskan pada sosialis, maka tidak heran jika yang menjadi
landasan utama atau tinjauan utama adalah masalah ekonomi. Di dalam “ Kata Pengantar ” buku Zur
Kritik der Politischen Okonomie (1859), Karl Marx jelas-jelas mengungkapkan
bagaimana Karl Marx melihat hubungan antara basis ekonomi dan superstruktur
atau struktur atas (termasuk sastra):
Cara
memproduksi kehidupan yang bersifat materi menentukan proses kehidupan sosial,
politik, dan intelektual. Bukan kesadaran manusia yang menentukan
keberadaannya, melainkan sebaliknya, keadaan sosiallah yang menentukan
kesadarannya. Pada tahap perkembangan tertentu, kekuatan produksi material
dalam masyarakat berbenturan dengan hubungan produksi yang ada, atau secara
resmi, hubungan milik tempat mereka bekerja. Karena situasi perkembangan
kekuatan produksi material dalam masyarakat berbenturan dengan hubungan
produksi yang ada, atau secara resmi, hubungan milik tempat mereka bekerja.
Karena situasi perkembangan kekuatan produksi. Hubungan kepemilikan ini menjadi
belenggu bagi mereka. Kemudian, mulailah periode revolusi social. Dengan
perubahan yang terjadi pada basis ekonomi, semua struktur atas tersebut cepat
atau lambat dirombak.[136]
Memang akan sulit
untuk menemukan teori estetika Karl Marx (misalnya dalam bidang sastra),
mengingat Karl Marx tidak pernah mengeluarkan rumusan-rumusan baku
Karena hal
tersebut, maka aliran realisme sosialis lebih banyak berkecimpung dalam seni
yang melawan sistem kapitalis. Dalam artian di sini bagai mana seorang realisme
sosialis mampu membawa penyadaran terhadap penindasan yang terjadi, dan
membakar semangat kaum tertindas, seperti buruh dan petani untuk melawan.
Realisme sosialis
memandang, bahwa tugas seorang seniman bukan hanya memberikan penghiburan
semata. Karena itu realisme sosialis sangat tidak setuju dengan istilah “seni
untuk seni”. Sebab menurut mereka, istilah tersebut adalah ulah para reaksioner
yang lari dari tanggung jawab[137].
Seni justru hadir untuk perjuangan masyarakat yang tertindas di dalam
masyarakat kapitalis, bukan malah melarikan diri. Dalam pandangan seperti
itulah realisme sosialis lahir.
Realisme sosialis
sebagai mana sosialis juga memandang para borjuis dan kapitalis sebagai musuh
utama. Kapitalisme tidak saja membuat pertentangan kelas yang makin melebar
antara pemilik modal dan buruh, namun juga memalsukan kesadaran manusia, hingga
menilai kehidupan melulu dalam ukuran materi. Tak bisa disangkal bahwa dalam
masyarakat kapitalis, seni pun telah direduksi sedemikian rupa, hingga hanya
menjadi komoditas. Seni diperjual belikan, dan keindahan diukur dengan uang.
Kritik-kritik seni dibangun sebatas kepentingan modal[138].
Menurut Lukacs,
kapitalisme telah mengubah kesadaran manusia menjadi kesadaran palsu yang
menjauhkan manusia dari eksistensinya yang bebas, dan sebaliknya mendekatkan
manusia pada karakter materi yang hanya mempunyai nilai fungsional. Realisme
sosialis datang sebagai upaya manusia untuk bebas dari keterasingan yang lahir
dari kesadaran palsu, dan kemudian menghantarnya menuju suatu pemenuhan diri
sebagai manusia utuh.[139]
Sebagaimana yang
telah tercantum di atas, bahwa misi dari realisme sosialis adalah untuk
membangun kesadaran bagi masyarakat yang tertindas, tapi mereka memakai media
kesenian. Hal tersebut diperlukan untuk memudahkan media penyampaian ajaran
Marxis, bagi masyarakat petani, buruh dan kelas proletar lainnya. Inilah tugas
berat yang harus selalu diemban oleh para realisme sosialis.
Seperti yang telah
dilakukan oleh Mas Marco Kartodikromo, seorang wartawan yang kelak juga pelopor
komitmen sosial dalam sastra sebagai mana di catat oleh Pram. Mas marco
Kartodikromo jugalah yang antara lain mempopulerkan semboyan “Sama Rata Sama
Rasa” dalam sebuah artikel yang
dirasakan Belanda sangat tajam, yang membuatnya dijebloskan kedalam penjara. Yang
akhirnya dapat membuat radikalisasi gerakan semakin memuncak, berhubungan
dengan tindakan pemerintah Hindia Belanda yang semakin represif. Dengan
melakukan pengusiran terhadap sejumlah tokoh yang dianggapnya radikal seperti
Mas Marco Kartodikromo, Semoen dan lain sebagainya.
Tujuan realisme
sosialis dalam realitas yang ada adalah 1) Untuk apa dan mengapa ia menulis?
(2) Benar tidakkah materi penulisan, dan bagai mana perkembangan dengan
materi-materi tersebut sesuai dengan arah yang dikehendaki untuk menguntungkan
sosialisme, untuk memenangkan keadilan sosial bagi semua dan setiap orang?
Karena semua dan setiap orang membutuhkanya.[140]
Realiatas harus
mampu dihadirkan oleh karya seni realisme sosialis. Realitas sekarang dialami
rakyat, dan realitas masalah yang pernah terjadi, tidak hanya dibiarkan berlalu
begitu saja. Masyarakat harus sadar bahwa masa sekarang merupakan pusat gerak
sejarah di masa depan. Strategi perjuangan pembebasan rakyat tidak akan
berhasil tanpa memahami realitas-realitas tersebut. Di sini ada kesatuan antara
kesadaran seniman realisme sosialis yang membeberkan realitas dalam
karya-karyanya, dengan kesadaran masyarakat yang tengah menggerakkan perjuangan
pembebasan.
Dalam hal ini,
posisi sastra realisme sosialis selamanya sebagai sastra perlawanan. Jika suatu
realitas sudah tidak lagi memenuhi tuntutan zaman, maka bukan saja harus
dirombak dan diubah, tetapi juga harus diberi realitas-realitas baru sebagai
jawaban atas tantangan zaman tersebut. Memang dalam parkteknya, mengubah dan
merombak realitas yang telah ada, kemudian menciptakan realitas baru, tidak
selamanya sesuai dengan direncanakan. Bahkan adakalanya keliru. Akan tetapi,
satu hal harus tetap dipegang, yakni prinsip untuk memenangkan proletar[141].
Realisme sosialis
adalah salah satu alat perjuangan sosialis, mereka harus melihat segala
permasalah yang ada dengan sifat kritis dan juga revolusioner. Maka ketika
melihat petani yang tertindas ataupun buruh, ada tanggung jawab yang di pikul
para sastrawan atauapun seniman realisme sosialis untuk mengajak mereka mereka
merubah hal tersebut. Karena dalam pandangan realisme sosialis, tidak ada
penindasan yang lahir begitu saja. Semua hal pasti ada sebabnya, untuk itu
bagaimana membangun kesadaran bersama melawan penindasan tersebut. Sehingga
terciptalah keadilan yang merata diatas bumi.
Karena dalam
pandangan para realisme sosialis termasuk Pram, realitas adalah sebuah objek
kajian yang harus diperjuangkan, seperti ketika ada seorang petani yang
terampas tanahnya. Dalam pandangan Pram, hal tersebut bukanlah suatu kebetulan
atau takdir semata, ada yang membuat hal
tersebut terjadi. Sebagai mana pemahaman orang sosialis, bahwa petani yang
terampas haknya tersebut karena pemilik modal yang ingin mengambil tanah petani
tersebut. Maka petani tersebut harus memperjuangkan tanah yang digarapnya,
sebab seorang petani jika tidak memiliki tanah maka dia bukanlah lagi seorang
petani.
Pemahaman tersebut
juga berlaku, untuk buruh atau manusia yang tertindas lainnya. Buruh adalah
orang yang berada paling bawah dalam struktur ekonomi, yang paling atas adalah
pemilik modal. Dan pemilik modal akan berusaha mengambil untung yang
sebanyak-banyaknya salah satunya dengan memberi upah yang rendah pada buruh,
maka agar buruh tidak lagi mendapat upah yang rendah dan terjadi kesenjangan
yang begitu jauh. Buruh haruslah berjuang untuk menuntut haknya, sebagai mana
yang terjadi saat ini. Banyak sekali buruh yang demo untuk kenaikan upah.
Sebagaimana yang di
lakukan Soekarno dalam Manifesto
politiknya, bahwa ekonomi harus diatur sebagai usaha bersama atas dasar
kekeluargaan. Dalam penjelasan lebih jauh tentang hal tersebut, Soekarno
mengingatkan bahwa kapitalisme–kapitalisme serakah baik itu orang Indonesia
BAB IV
Pandangan
Subtansial Pramoedya tentang Realisme Sosialis dalam Novel Tetralogi
Bab keempat ini akan menganalisis
lebih jauh mengenai tentang unsur realisme sosialis yang terkandung dalam novel
Tetralogi, setelah dalam bab-bab sebelumnya diterangkan tentang realisme
sosialis dalam pandangan Pram, yang tercantum dalam tulisannya “ Realisme
Sosialis dan Sastra Indonesia”.
Di dalamnya Pram mengatakan secara
singkat bahwa yang dimaksud dengan realisme sosialis adalah pempraktikan
sosialisme di bidang karya sastra.
Realisme sosialis dalam tafsiran
kesenian Uni Soviet berarti seni yang menggambarkan kemenangan, para pahlawan
dan optimisme membangun ekonomi dan masyarakat sosialis. Seni dituntut untuk mengutamakan
kolektivitas, mangacu pada gambaran masyarakat sedang bekerja atau berjuang,
kecuali saat menggambarkan para pahlawan seperti Lenin dan Stalin. Fungsi seni
ditetapkan sebagai alat mendidik buruh dengan nilai-nilai sosialis yang sejalan
dengan garis politik partai komunis. Karya-karya dari periode ini yang kemudian
dikenal dan dikecam dalam wacana kritik Barat sebagai kultus individu Lenin dan
Stalin[143].
A. Realisme Sosialis sebagai
Upaya Membentuk Paradigma dan Orientasi Kehidupan
Ya,
memang belum banyak yang bisa ku dapatkan dalam diriku. Jean marais
bercita-cita mengisi hidup dengan lukisan-lukisan, bukan hanya menyambung
hidup. Untuk apa aku menulis, sampai mendapatkan kemashuran sebanyak itu? Kau
tidak adil Minke, kalau memburu kepuasan saja bisa mendapatkan kemashuran.
Tidak adil! Orang-orang lain bekerja
sampai berkeringat darah, mati-matian, jangankan mendapatkan kemasyhuran ,hanya
untuk dapat makan dua kali sehari belum tentu bisa[144].
Kutipan di atas
memberi gambaran tentang realisme sosialis, mengenai mental priyayi, yang
melahirkan kelas-kelas dalam masyarakat. Percakapan ini terjadi ketika Minke
harus menghadap seorang Bupati, yang Bupati tersebut jauh lebih bodoh dibanding
dia. Namun karena kelas-kelas yang telah terbangun maka ketika Minke menghadap
tetap harus berjalan sambil berjongkok dan menyembah dahulu. Namun di sini
Minke terlihat sombong atas pengetahuannya atas ilmu pengetahuan yang
dimilikinya, sehingga tidak terlihat pribadinya sebagai seorang sosialis yang
mencita-citakan persamaan hak. Mengenai hal tersebut digambarkan sangat jelas
oleh Pram dalam tulisan ini:
Jadi aku
akan dihadapkan pada Bupati B. god! Urusan apa pula? Dan aku ini, siswa H.B.S.,
haruskah merangkak dihadapannya dan mengangkat sembah pada setiap titik
kalimatku sendiri untukku sendiri untuk orang yang sama sekali tidak kukenal!
Dalam berjalan ke pendopo yang sudah diterangi dengan empat buah lampu itu aku
merasa seperti hendak menangis. Apa guna belajar ilmu dan pengetahuan Eropa,
bergaul dengan orang-orang Eropa, kalau akhirnya toh harus merangkak, beringsut
seperti keong dan menyembah seorang raja kecil yang barangkali butahuruf pula?
God, God! Menghadap seorang bupati sama dengan bersiap menampung penghinaan
tanpa boleh membela diri. Tak pernah aku memaksa orang lain berbuat semacam itu
terhadapku. Mengapa harus aku lakukan untuk orang lain? Sambar geledek![145]
Perbedaan kelas
dalam masyarakat feodal dilakukan oleh pemerintahan kolonial belanda.
Sebagaimana kita tahu bahwa bangsa kolonial dan Eropa menduduki kelas pertama,
kedua kaum cina dan priyayi, ketiga adalah rakyat jelata.
Perbedaan ini
berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat misalnya dalam hal kepemilikan
tanah. Dimana dalam tetralogi, Pram juga tidak hanya mempersoalkan kelas atau
kasta masyarakat, tetapi menggambarkan mengenai kepemilikan tanah sebagai basis
produksi rakyat saat itu yang cenderung dikuasai secara semena-mena oleh
penguasa.
Dalam tetralogi
banyak cerita-cerita Pram tentang nasib seorang petani yang mempertahankan
tanahnya dari pengambilan paksa pemilik modal, karena pemilik modal tersebut
dilindungi oleh hukum yang berlaku, sementara petani tersebut harus berjuang
sendiri tanpa ada yang membelanya.
Dalam beberapa
karyanya Pram juga terinspirasi dari Revolusi Perancis, tentang perlawanan baru
dari buruh yang hampir saja menggusur kekuatan De Gaulle. Kejadian tersebut
bermula dari kaum tani yang dirampas tanah garapannya dan diusir begitu saja.
Mereka tidak hanya harus lepas dari tanah garapannya, tetapi juga terpaksa
meninggalkan desanya untuk mencari penghidupan di kota kota
“Berteriak apa orang-orang itu?”
“yang tinggal di situ, Ndoro.”
“Di rumah genteng itu?’
“Betul, Ndoro.”
“Mengapa diteriaki?”
“Dia tak juga mau pindah dari tempatnya.”
“Mengapa harus pindah?”
“Mereka “ katanya bengis dan benci, “anjing-anjing prabik. Ini tanahku sendiri. Peduli apa
hendak kuapakan,” ia seka keringat dari pundak[146].
Perasaan tidak enak masih
juga menongkrong dalam hatiku, karena petani yang seorang ini kembali bicara
ngoko. Benar-benar dia petani yang sudah keluar dari golongannya. Dan apa pula
gunanya aku hadapi baik-baik? Tapi kau sudah bertekad hendak mengenal bangsamu!
Kau harus dapat mengenal kesulitannya. Dia salah seorang bangsamu yang tidak
kau kenal, bangsamu yang hendak kau tulis kalau kau sudah mulai belajar
mengenalnya!.[147]
Dan
kau tidak beda dengan orang-orang lain. Kau tidak lebih tinggi, tidak lebih
mulia dari Trunodongso . itu kalau kau benar-benar mengerti Revolusi Prancis.
Bagaimana kau sekarang Minke?”[148]
Kesadaran lain
juga lahir dari sang tokoh Minke, misalnya, tentang bahasa yang merupakan sekat
komunikatif antar golongan dan kelas waktu itu. Yang kemudian muncul anjuran
emansipatif dari obrolan Minke dengan seorang perempuan bernama Nyai Ontosoroh. Minke menganggap menulis dalam bahasa melayu
sangat penting untuk mewujudkan persamaan kelas dan pencerahan kaum pribumi
karena bahasa malayu itu tidak mencerminkan watak feodalisme. Tetapi saat ini
bahasa daerah justru mesti dilestarikan terlepas dari perwatakan feodalis
ataupun tidak, seba bahasa daerah adalah warisan dari nenek moyang, siapa lagi
yang akan melestarikan kalau bukan generasi mendatang.
Juga
kau hendak membelanya terhadap penindasan dengan bahasa oleh kau sendiri? Ha,
kau tak mau menjawab. Kalau begitu memang tepat kau harus menulis Melayu,
Minke, bahasa itu tidak mengandung watak penindasan, tepat dengan kehendak
revolusi Prancis.[149]
“Aku lebih percaya pada Revolusi Perancis,
Tuan Tollenaar. Kebebasan, persaudaraan dan persamaan, bukan hanya untuk diri
sendiri seperti sekarang terjadi diseluruh daratan Eropa dan Ameriak Serikat,
tapi untuk setiap orang, setiap dan semua bangsa manusia di atas bumi ini.
Sikap begini dinamai sikap liberal sejati, Tuan.”[150]
“jangan salah artikan kebebasan dalam semboyan
Revolusi Prancis” “orang Prancis sendiri juga banyak menyalah-artikan jadi
bebas merampok dan bebas tak berkewajiban pada siapa pun, walhasil jadi
sewenang-wenang tanpa batas. Kebesaran hanya untuk diri sendiri di
negeri-sendiri! Semua terpelajar pribumi Asia
dalam kebebasannya mempunyai kewajiban-kewajiban tak terbatas buat kebangkitan
bangsanya masing-masing. Kalau tidak, eropa akana merajalela”.[151]
Gelombang emansipasi dari ciri
realisme sosialis dari kutipan di atas, ternyata, tidak hanya mengalir dan
menjalari diri-diri pribadi kaum bumiputra nusantara saja tetapi melampaui
batas teritori geografis itu sampai mencakup Asia malah bukan ke arah Jawa dimana tempat
munculnya pribadi Minke. Ada
Salah satunya yang lain ialah ; jika
dalam hukum ekonomi feodal, dalam system maro atau bagi hasil, biaya
penggarapan tanah sampai pembelian bibit dan pemeliharaan tanaman dibebankan
atau dipikul oleh petani yang menggarap tanah. Sedang tuan pemilik tanah tidak
kehilangan sesenpun untuk biaya produksi. Mereka tinggal menerima saja hasil
pembagian dari hasil produksi tanah miliknya yang di bagi hasilkan atau yang
digarap oleh petani penggarap. Sistem bagi hasil sebenarnya tidak sepenuhnya
merugikan petani, karena untuk saat ini sistem bagi hasil bagi hasil justru
lebih aman karena jika terjadi sesuatu hal atas tanah garapan maka bisa di
tanggung bersama.
“Tentu saja ini tanahmu sendiri,” kataku memberanikan
dia dan diriku sendiri.
“Lima bahu, warisan orang tua.”
“Kau benar,” kataku, “ada kubaca di kantor tanah.”
“Nah, ada tertulis dikantor tanah,” ia bicara pada
dirinya sendiri. Ketegangannya mulai surut. Lambat-laun aku lihat ia mulai
kembali jadi petani jawa yang rendah hati.
“ Ya, Ndoro, sebenarnya sahaya sudah cukup bersabar.
Warisan sahaya lima
“Berapa sewa untuk satu bahu?” tanyaku sambil
mengeluarkan alat tulis-menulis dari dalam tas, mengetahui, semua petani Jawa
menaruh hormat pada barangsiapa melakukan pekerjaan tulis menulis. Akupun
siap-siap mencatat.
“Sebelas picis, Ndoro” jawabnya lancar. Mengherankan.
“Sebelas picis, buat setiap bahu selama delapan belas
bulan?” aku terpekik.
“Betul,
Ndoro.”
“Tiga
talen”
“Kemana
yang tiga puluh lima
“Mana
sahaya tahu, Ndoro. Cap jempol saja, kata mereka tidak lebih dari tiga talen
sebahu. Delapan belas bulan, katanya. Nyatanya dua tahun sampai tunggul-tunggul
tebu habis di dongkeli”.[152]
Ini menandaskan ciri realis-sosialis
pada karya atau malah pada diri pribadi Pram itu. Seperti Pram sendiri katakan
; “Bagi saya, keindahan itu terletak pada kemanusiaan, yaitu perjuangan untuk
kemanusiaan, pembebasan terhadap penindasan. Jadi keindahan itu terletak pada
kemurnian kemanusiaan, bukan dalam mengutak-atik bahasa”. [153]
“Tahu
Tuan upah kuli tebu yang baik dalam sehari? Tiga talen sehari. Kalau orang
kerja jadi kuli, dua hari saja, yang diperolehnya sudah melebihi sewa tanahnya
sendiri sebanyak satu bahu. Siapa bilang orang lebih suka menggarap sawah
sendiri daripada jadi kuli tebu? Berapa harga kerja cangkul dalam sehari? Tiga
benggol, tidak lebih.”[154]
Penindasan bagi Pram bukan keindahan
itu sendiri. Ini juga bukan berarti jika ada derita sengsara disana itulah
keindahan bersemayam. Keindahan, dalam
karya-karya pram ini adalah bukan tempat orang mencari jati diri tidak seperti
dalam novel-novel atau karya-karya sastra yang cendrung romantis-melankolis
atau yang bombastis. Penemuan jati
diri malah mewujud ketika terlibat dalam gairah semangat perjuangan kaum yang
terlemahkan dan pembebasan dari penindasan sama pemahamannya dalam semboyan
Marxian yang berbunyi; “Di dalam kerja engkau merdeka”. Inilah keindahan
itu terletak dalam perjuangan dan gairah
semangat sasatrawi realis-sosialis Pram, mengangkat jati diri pribumi!
Bacalah petikan berikut ini; bukan
indah yang menggoda genit, tapi kenyataan (narasi) pedih dan derita kemanusiaan
yang mengiris dari sekian tragedi sosial akibat kolonialisme. Indah ! –bukan
untuk dielem yang lantas menimbulkan
gairah-gairah yang sentimentil. Akan tetapi kepedihan yang menuntut untuk
dihinggapi kepedulian dan emansipasi. Novel tetralogi banyak sekali menampilkan
kepedihan seolah-seolah itu adalah pengalaman pram yang masuk dalam novel
tersebut., sehingga sering kali hal tersebut melahirkan kebingungan cerita
tersebut pengalaman Tirto Adhi Suryo atau Pram.
Pribumi bertombak dan
berpanah akan mati bergelimangan lagi atas perintahnya, entah dimana akan
terjadi. Demi keutuhan wilayah, kata-kata lain dari: demi keamanan modal besar
Hindia. Darah, jiwa, perbudakan, penganiayaan perampasan, penghinaan akan terjadi
lagi di bawah tudingan tangannya.[155]
Perlakuan sewenang-wenang dalam
perusahaan-perusahaan kereta api, perkebunan, kantor-kantor Gubermen, perampasan
anak gadis dan istri oleh pembesar-pembesar setempat dengan menggunakan
kekuasaan yang ada pada mereka, mengisi permohonan-permohonan pertolongan.[156]
B. Pandangan Pramoedya Ananta
Toer tentang Organisasi sebagai Sikap Melawan Imprealisme
Buah dari
pembacaan atas pemahaman atas pikiran Pram dan proses analisisnya menghasilkan
apa yang menjadi sub-judul B ini. Melalui organisasi proses perjalanan sebuah
kesadaran kelas, status hukum dan politik, begitu kentara dialami oleh bangsa
ini dalam karya Pram, terutama pada sosok Minke. Dari embrio-embrio
tersebut lahirlah organisasi awal di
Indonesia yang bernama Budi Oetomo. Yang digawangi oleh para terpelajar Hindia.
Organisasi tersebut, bertujuan untuk memberi pengajaran pada semua orang tanpa
ada kasta, karena yang boleh sekolah di sekolah yang didirikan Belanda adalah
orang Belanda sendiri, Indo, dan juga para priyayi. B. O meski sebagai pelopor
organisasi pertama tidak cukup mampu untuk mengakomodir semua permasalahan yang
terjadi di masyarakat saat itu.
Utusan Raden Tomo telah datang ke Bandung
“Dan bahwa ada gerak dari minus ke plus pada umat
manusia, dan itu dinamai gerak juang? Lupa kau, Koen? Atau B.O yang lupa? Kan
B.O. tidak bermaksud mempertahankan yang ada, agar yang miskin tetap miskin,
yang bodoh tetap bebal, dan yang sakit tinggallah menggeletak menungggu
sakratulmaut?”[158]
Bentuk perlawanan emansipatoris
terhadap segala hal di dalam karyanya
yang ada unsur pertentangan kelas, salah satunya, bukan hanya terjadi pada
bentuk sosial-ekonomi saja, tetapi juga dalam bentuk bahasa. Inilah awal
kesadaran tentang persamaan dan etos organisasi (kolektifisme) dalam mewujudkan
persatuan melawan hegemoni penjajah. Bahasa-lah wadah organisme kesadaran-kesadaran itu.
“Dalam
rapat-rapat cabang yang tahu bahasa Jawa tentu tak diharuskan berbahasa melayu.
Tetapi kalu tingkatnya sudah Kongres atau tingkat Pusat, atau berhubungan
dengan pusat, tak bisa tidak harus dipergunakan Melayu.” “Mengapa Jawa harus
dikalahkan oleh Melayu?” “Diambil praktisnya, Mas. Sekarang, yang tidak praktis
akan tersingkir. Bahasa Jawa tidak praktis. Tingkat-tingkat di dalamnya adalah
bahasa presentasi untuk menyatakan kedudukan diri, melayu lebih sederhana.
Organisasi tidak membutuhkan pernyataan kedudukan diri. Semua anggota sama, tak
ada yang lebih tinggi atau lebih renadah.”[159]
Pemakaian bahasa melayu benar-benar
diperjuangkan dalam berorganisasi wadah pendidikan dan penyadaran kaum pribumi.
Pram dalam narasi ini menggambarkan kekuatan baru pada kaum bumiputra,
terkhusus pada diri Minke, dalam mencapai persamaan derajat dalam tingkat yang
paling sublime dan dini; yakni pada aras bahasa. Bahasa daerah pun sebenarnya
anti penindasan, tapi yang menjadi masalah adalah bahasa daerah itu
berbeda-beda. Bahasa melayu adalah bahasa persatuan di mana semua orang
mengerti, bukan bahasa yang anti penindasan. Pram di sini terlalu melebih-lebihkan.
Di
kota-kota sepanjang pesisir utara Jawa Barat telah berdiri cabang-cabang dengan
anggota rat-rata empat puluh sampai seratus orang. Di kota-kota pegunungan
memang lebih sendat. Di Tasikmalaya, Garut dan Sukabumi nampak adanya kegiatan mengagumkan.
Garut mencactat sejarah: disini pernah di adakan rapat umum propaganda S.D.I.
rapat umum pertama.[160]
“Organisasi
ini lahir di tanah Hindia sebagai organisasi Pribumi, bukan organisasi segala
bangsa yang bermaksud untuk mrerugikan Pribumi. Tidak ada hak pada siapa pun,
bangsa apa pun anggota atau bukan anggota S.D.I. untuk merugikan Pribumi, baik
pedagangnya atau petaninya, ataupun tukang-tukangnya. Kalau ada cabang yang
punya cara dan jalan sendiri yang sengaja dan diketahui melakukan tindakan
merugikan terhadap pribumi, itu bukan cabang S.D.I. seluruh Hindia dapat
melakukan tindakan serentak terhadap cabang durjana demikian. Aku yakin,
saudara-saudara, dewan pimpinan pusat tidak akan ragu-ragu mengeluarkan
titahnya.”[161]
Minke melihat bahwa bangsa Arab yang
selama ini di pandang sebagai bangsa yang terbelakang oleh orang Eropa ternyata
sebenarnya lebih luas pengetahuan keilmuannya. Di samping itu ekonomi yang di
bangun di Negara Indonesia
Orang Arab, yang sama sekali
tidak pernah mendapat pendidikan Eropa ini, ternyata mempunyai pengetahuan
praktis yang sangat patut untuk kuindahkan dan kupelajari. Putra-putranya ia
kirim ke Universitas Turki, menguasai banyak bahasa modern.[162]
“Pedagang
orang paling giat di antara umat manusia ini, Tuan. Dia orang paling pintar.
Orang menamainya juga saudagar, orang dengan seribu akal. Hanya orang bodoh
bercita-cita jadi pegawai, kerjanya hanya disuruh-suruh seperti budak. Bukan
kebetulan Nabi s.a.w pada mulanya juga pedagang. Pedagang mempunyai pengetahuan
luas tentang ikhwal dan kebutuhan hidup, usaha dan hubungannya. Perdagangan
membikin orang terbebas dari pangkat-pangkat, tak membeda-bedakan sesama
manusia, apakah dia pembesar atau bawahan, bahkan budak pun. Pedagang berpikir
cepat. Mereka menghidupkan yang beku dan menggiatkan yang lumpuh.”[163]
Perjuangan dalam merebut kesamaan
klas, tidak hanya di dukung oleh organisasi semata, tapi juga oleh landasan
organisasi yang kuat. Sehingga progam organisasi untuk memperjuangan kesamaan
hak itu tercapai, dan landasan yang paling kuat adalah agama islam. Minke
memandang bahwa agama Islam agama yang anti penjajahan, ini bisa terbukti
dengan kedatangan para pedagang dari Arab yang berdagang dengan baik-baik.
Tidak seperti Belanda, mereka mengaku ingin berdagang di Indonesia Indonesia Indonesia
“Islam
dan dagang mempunyai landasan lebih luas dan lebih mengikat dari pada indisch.
Pikiran-pikiran Tuan bukan tidak kupertimbangkan. Landasannya tidak ada, kurang
jelas. Setidaknya-tidaknya belum aku lihat, hanya berupa cita-cita, bukan
kenyataan. Memang cita-cita bisa menjadi kenyataan di kemudian hari, tetapi
landasannya tetap kenyataan sosial masakini”.[164]
Islam,
kataku selanjutnya, yang secara tradisional melawan penjajah sejak semula Eropa
datang ke Hindia, dan akan terus melawan selama penjajah berkuasa. Bentuknya
yang paling lunak: menolak kerjasama, jadi pedagang. Tradisi itu patut di
hidupkan dipimpin, tidak boleh mengamuk tanpa tujuan. Tradisi sehebat dan
seperkasa itu adalh modal yang bisa menciptakan
segala kebajikan untuk segala bangsa Hindia[165].
“Teapi
para petani itu adalah saudara-saudara kita sendiri, sebangsa kita sendiri,
yang hendak diperas tanah dan duitnya secara gegabah oleh perusahaan-perushaan
raksas Eropa, Arab dan Cina. Kalau Tuan-tuan membiarkan ini terjadi, Tuan-tuan
membenarkan pemerasan itu, Tuan-tuan membenarkan kejahatan, apa itu di benarkan
dalam Islam? Kan
Minke, sebagai tokoh protagonis.
Membeberkan maksud kedatangan Belanda ke Indonesia
“Eropa datang berdagang kemari, Tuan, tapi
menjauhkan dirinya dari Pribumi. Malah memperdagangkannya.”
“Eropa
datang bukan untuk berdagang dengan kita. Mereka datang dengan meriam dan
bedil.”
“Apa
pun alat yang dibawanya, mereka berdagang.”
“Kalau
sekarang ini aku todong Tuan dengan senapan, aku rampas semua pakaian Tuan,
sehingga tinggal selembar setangan untuk menutup kemaluan, kemudian aku
tinggalkan pada Tuan satu setengah sen, pastilah itu bukan berdagang. Dan
itulah wajah Eropa colonial, sesungguhnya.”
“Tuan
lupa, meriam dan Bedil juga alat berdagang pada jamannya,” bantah Douwager.
“Masih berlaku di banyak tempat sampai sekarang, kalau bangsa sudah ditaklukkan
seperti di Hindia ini, bangsa taklukan dibikin jadi penghasil barang dagangan.
Malah diperdagangkan.”
“Sama
saja, Tuan. Perdagangan terjadi hanya karena suka antara kedua belah pihak yang
berkepentingan. Selama tak ada syarat itu, dan pertukaran terjadi, itu bukan perdagangan,
itu kejahatan”[167] .
Ini adalah awal lahirnya S.I.
Menjelang akhir tahun 1919, pimpinan pusat S.I berhasil menyatukan 22 Serikat
Dagang Indonesia dengan jumlah anggota 77.000 di bawah satu komando[168].
Serikat Dagang Indonesia Indonesia
Sedangkan Sarikat Islam adalah
kepanjangan dari organisasi SDI, yang membedakan SDI dengan SI adalah
perjuangan yang dilakukannya. Jika SDI lebih berkecimpung hanya dalam wilayah
basis ekonomi semata, SI lebih luas cakupan perjuangannya semisal politik.
Perjuangan SI untuk persamaan dalam hal politik bagi masyarakat pribumi, Minke sadar perjuangan persamaan hak tidak
hanya di lakukan dengan mengangkat sejata. Tapi juga harus lewat organisasi
yang kuat, sehingga penekanan terhadap sistem feodal juga di lakukan lewat negosiasi, yang diharapkan terwujudnya
persamaan hak. Hal tersebut dapat dibaca
di dalam cerita di bawah ini:
Dokumen keempat adalah sebuah laporan
panjang dari Sala, memakan tidak kurang dari empat puluh halaman, di tulis oleh
tangan yang mahir, kecil-kecil dan rampak, tapi dalam bahasa Melayu yang sangat
buruk. Laporan itu mencatat tentang terjadinya kegiatan S.D.I. di Sala, yang
menarik perhatian pemerintah putih dan Pribumi: haji Samadi dengan pimpinan
S.D.I. cabang Sala telah mengeluarkan pernyataan, bahwa telah didirikan
perkumpulan bernama Syarikat Islam dengan dia sendiri sebagai pimpinannya.
Tetapi, semua pimpin di dalamnya adalah juga pimpinan S.D.I.[169]
Cabang-cabang S.D.I. segera menyesuaikan
diri dengan menamakan diri Syarikat Islam dalam suatu koperensi darurat di
Sala. Arus anggota baru taka dapat kubendung. Aku mengerti, bahwa saat untuk
berorganisasi telah tiba dalam daftar kebuthan pribumi di Jawa. Tugasku
menghadang ini. Tidak hanya aku saja. Aku kira semua ahli dan penguasa colonial
terheran-heran mengikuti perkembangan Syarikat setelah terjadinya penyerahan
pimpinan dari Minke ke tangan Hadji Samadi.[170]
Sudah tepatkah pandangan Eropa colonial
ini? Bukan saja tidak tepat, juga tidak benar. Tetapi Eropa colonial tidak
berhenti sampai di situ. Setelah Pribumi jatuh dalam kehinaan dan tak mampu
lagi membela dirinya sendiri, dilemparkannya hinaan yang sebodoh-bodohnya.
Mereka mengetawakan penguasa-penguasa Pribumi di Jawa yang menggunakan tahyul
untuk menguasai rakyatnya sendiri, dan dengan demikian tak mengeluarkan biaya
untuk menyewa tenaga-tenaga kepolisian untuk mempertahankan kepentingannya.
Nyai Roro Kidul adalah kreasi Jawa yang gemilang untuk mempertahankan
kepentingan raja-raja Pribumi Jawa. Tapi juga Eropa mempertahankan tahyul:
tahyul tentang hebatnya ilmu pengetahuan agar orang-orang jajahan tak melihat
wajah Eropa, wujud Eropa, yang menggunakannya. Baik penguasa Eropa colonial mau
pun Pribumi sama korupnya[171].
Indische Partij adalah organisasi orang
belanda yang di pimpin oleh H. J. F.M. Sneevliet. Mereka adalah orang-sosialis.
Kelompok ini yang kemudian berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia Indonesia Indonesia
Syarikat aku anggap sebagai gelembung
akibat samudra kehidupan yang telah teraduk unsure-unsur modern, dan pada suatu
kali gelembungan ini akan meletus berpecahan tanpa meninggalkan bekas. Indische
Partij lain lagi. Ia justru mempersatukan unsure-unsur manusia modern di
Hindia, peranakan Eropa dan terpelajar Pribumi sekaligus. Dalam jumlah anggota
ia tidak berarti dibandingkan dengan Syarikat. Dalam kesadaran berpolitik dia
lebih unggul.dalam kesadaran berpolitik dia lebih unggul. Dalam kesadaran
berpolitik Mas Tjokro masih harus banyak belajar dari mereka. Tapi bagaimana
pun dua organisasi itu menyala di angkasa hitam seperti dua bintang, terpisah
jutaan mil satu dari yang lain, tak pernah ada usaha pendekatan, jangankan
persinggungan. Yang satu gemuk dengan kebanyakan anggota dan tak bisa berbuat
apa-apa. Yang lain dengan hanya anggota ratusan orang dan bakal kurus-kering
dirongrong oleh keinginan-keinginan tanpa batas[173].
Di sini Pram
bukan membenci agama Nasrani, tetapi dari mana agama tersebut lahir. Yang
dimaksud disini adalah Belanda, yang menjadi penghisap atas sekian ekonomi bagi
bangsanya. Salah satu tujuan Belanda datang ke Indonesia
Aku tahu, bahwa aku harus mengelakkan
percakapan yang menyudutkan ini. Benar sekali, bahwa pada jamannya agama juga
politik. Bangsa-bangsa Hindia yang Nasarani memang tidak mencari pertengkaran
dengang gubermen yang Nasrani pula, tetapi tulisan-tulisan Raden Mas Minke
menunjukkan contoh-contoh, bahwa juga orang-orang tertentu bisa mencari
pertengkaran dengan bangsanya sendiri, seperti Khouw Ah Soe dan Ang San Mei.
Benar mereka Protestan dan Katholik, tapi mereka bukan karena agama ikut
berusaha menggulingkan dinasti Ching. Mereka digerakkan oleh sesuatu yang lain,
yang bernama Nasionalisme.
Mas Marco
Kartodokromo adalah pencipta semboyan “Sama Rata Sama Rasa”. Semboyan ini di
kalangan rakyat jelata mempunyai kekuatan yang menghidupi, dan semboyan inilah
yang memberikan sumbangan yang tidak sedikit artinya bagi perjuangan untuk
memenangkan kemerdekaan nasional yang ditingkatkan dengan revolusi
nasional sekaligus mengandung di
dalamnya keadilan sosial[174].
Hal tersebut adalah perjuangan orang-orang sosialis.
Organisasi SI mulai pecah, menjadi
dua bagian yaitu SI dan PKI. pada tahun 1926, akhirnya Semaun keluar dari SI
meski dihalang-halangi oleh orang-orang SI yang masih memegang posisi-posisi
puncak. Semaun tetap keluar untuk membuat federasi serikat dagang tandingan
dengan anggota 14 serikat termasuk VSTP atau serikat pekerja kereta api[176].
Ini awal mula organisasi sosialis pertama di Indonesia Indonesia
Mempertentangan dua golongan dari pandangan
dan sikap yang berlain-lainan memang terlalu gampang. Tetapi akibatnya akan
berlarut. Syarikat akan menghadapi mereka sebagai orang Eropa pada umunya, dan
kebencian pukul rata pada Belanda akan menjadi hasilnya. Sedang sayap Marco,
yang selam ini tidak mendapat medan
Ini adalah penggambaran pemogokan
para pekerja, yang didukung oleh PKI, PKI yang melakukan advokasi kepada para
buruh untuk menuntut persamaan hak kepda para pemilik modal. Hal tersebut
sesuai dengan slogan Karl Marx yaitu “ Bersatulah Buruh Sedunia “.
Di Jawa Timur dan Tengah orang
memekik-mekik menuntut kenaikan upah sambil membelot-kerja alias staking.
Pegawai-pegawai pegadaian di beberapa tempat menolak memasuki tempat kerjanya
dan kumpul-kumpul di pelataran, berbaur dengan orang-orang yang hendak
menggadaikan. Buruh beberapa perkebunan kemudian mengikuti[178].
C. Pandangan Pramoedya Ananta
Toer tentang Jurnalistik sebagai Jalan Efektif Membangun Kesadaran
Di sinilah sastra realisme sosialis
mengabdikan dirinya, di bidang tulisan. Hal tersebut sebagai mana yang
diungkapkan oleh Pram sendiri bahwa satsra sosialis lahir dari orang-orang Indonesia
“
Perhitungan tidak meleset. Hanya dengan bahasa Melayu bukan Gubermen, dan di
antara orang-orang bebas, tidak dengan orang-orang dengan jabatan negeri,
organisasi umum di hindia akan bisa menjadi besar dan subur. Beberapa kali aku
harus bekerja keras meyakinkan Samadi, yang lebih menghendaki bahasa Jawa.
Bahasa melayu, semakin jauh dari pengajaran Gubermen, semakin jauh dari
orang-orang feodal, semakin demokratis dan menjadi alat perhubungan yang
nyaman, memang bahasa bebas untuk orang bebas. Dan hanya golongan bebas yang
akan menentukan nasib bangsa-bangsa Hindia, karena salah satu syarat untuk
persatuan bagi bangsa-bangsa ganda ini adalah dekat mendekati atas dasar
demokrasi[180].”
Tulisan di bawah
ini sangat mencerminkan tentang realisme sosialis, metode dasar kesusastraan,
dan kritik sastra Soviet, yang menuntut pengarang untuk memberikan penggambaran
kenyataan yang penuh kebenaran dan konkret secara historis dalam perkembangan
revolusinya. Sementara itu, kebenaran dan konkret historis suatu pelukisan
kenyataan aritistik harus dikombinasikan dengan tugas pendidikan dan pemulihan
ideologi pekerja dengan semangat sosialisme.[181]
Karena mengemban tugas berat untuk memenangkan sosialisme, sering kali sastra
realisme sosialis sangat kering dengan bahasa yang mendayu-dayu terkesan keras,
sehingga membuat tidak nyaman bagi yang membacanya.
Dari semua kegiatan Pribumi itu, ternyata
yang dianggap mahkota kegiatan adalah jurnalistik. Dan barang tentu bukan
jurnalistik sebagaimana dikenal oleh Eropa, tapi menulis di Koran atau majalah
dengan nama terpampang, baik nama benar, nama pena atau inisial. Gejala baru
ini langsung berasal dari Raden Mas Minke, ia pernah mengatakan pada salah
seorang temannya: orang boleh pandai etinggi langit, tapi selama ia tidak
menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Ucapan lain dari
si Gadis Jepara: menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dan jurnalistik gaya
Ini adalah tulisan
Mas Marco Kartodikromo, seorang yang
pernah keluar masuk penjara. Mas Marco Kartodikromo adalah seorang
penganut faham realisme sosialis, dia juga termasuk anggota PKI. Maka tidak
mengherankan jika tulisannya sarat dengan muatan terhadap penderitaan yang
terjadi di masyarakat, serta kritik terhadap sistem kapitalis yang sering membuat
orang menjadi sengsara. Advokasi yang paling ampuh adalah dengan media
jurnalistik, karena lewat jurnalistik faham sosialisme mudah menyebar
kemana-mana. Sebab salah satu tujuan jurnalistik adalah “ Membangun Opini
Publik “. Sehingga keberadaannya sangat di signifikan untuk menyebarkan faham
sosilaisme, dan membangun kritisisme masyarakat.
Dari tulisannya (Mas Marco Kartodikromo)
dapat diketahui apa sesungguhnya yang selama ini hidup dalam sanubarinya.
Pada
suatu hari dia tak mampu bekerja. Bininyapun tidak, karena telah jatuh sakit
terlebih dahulu. Tinggal anaknya yang berumur sembilan tahun yang masih sehat.
Tak urung punggawa desa memaksa anak umur sembilan tahun itu berangkat juga
mewakili bapak dan emaknya.
Anak
ini menangis sepanjang jalan setapak yang empat kilo meter jauhnya itu. Bukan
hanya karena lapar, kakinya disarangi bubul, dan patek meruyak sepenuh badan.
Dalam iring-iringan yang berjalan lambat-lambat itu terdapat perempuan kurus
yang sedang bunting tua, kakek-kakek yang bertongkat dan terbatuk-batuk,
seorang lelaki yang menggendong anak susuan karena emaknya baru saja mati
kelaparan.
Iring-iringan
calon mayat pada beberapa bulan mendatang semua menuju keselatan. Kekebun nila
Gubermen. Kerja paksa. Tanam paksa! Tanpa upah. Cultuurstelsel
Nama
desa itu adalah Cepu. Bukan Cepu yang sekarang. Desa itu miskin. Tetapi bekas
desa ini sekarang telah jadi distrik yang terkaya di Hindia. Disini aku
dilahirkan. Disini pula aku dengarkan cerita orang-orang tua yang dahulu setiap
hari dalam sekian bulan berangkat kekebun nila Gubermen, tanpa upah, tanpa
jaminan, tak sempat menggarap sawah dan ladang sendiri. Dan setiap hari ada
saja diantara mereka berjatuhan mati karena sakit dan lapar.
Desaku
seperti desa-desa lain. Semestinya orang hidup bertani, mencari kayu dihutan,
berternak kambing, sapi, ayam dan dirinya sendiri, dan hidup dalam keluarga
besar. Tetapi cultuurstelsel telah
mencerai beraikan keluarga besar itu dan merampas nasi dan jiwa mereka.
Pendeknya
jangan bayangkan Cepu desaku sebagai Cepu distrik yang sekarang ini. Cepu
desaku dilindungi oleh begitu banyak pohon buah, Cepu distrik dilindungi oleh
tiang-tiang listrik dan telfon.
Sianak
berumur sembilan tahu itu sudah bekerja selama sepuluh hari ketika Ia ditemui
dirumahnya yang kosong dimalam hari. Daun-daunan yang ia kumpulkan dari
perjalanan pulang Ia letakkan diatas lantai tanah . tungku dingin. Tak ada
makanan, tak ada orang. Ia berseru-berseru memanggil-manggil bapak dan emaknya
yang sakit tanpa jawaban. Ia pergi kerumah tetangga-tetangga. Melulu
orang-orang sakit saja yang ada. Yang seperempat dan setengah sakitpun pada
pergi.
Menjelang
subuh bapaknya pulang bergandengan tangan dengan orang-orang lain yang sama
kehabisan tenaga, tunjang menunjang agar tak roboh dan tak tersasar dalam kegelapan. Mereka baru pulang dari menguburkan
emaknya.
Sebulan
kemudian lebih banyak lagi orang dikuburkan semacam itu, termasuk bapaknya
sendiri.
Sibocah
itu terus juga melakukan kerja paksa makannya rumput muda, karena itulah yang
termudah didapatnya sewaktu kerja. Lagi pula daun dan buah muda petai cina itu,
biarpun agak berasa, membikin semua rambutnya rontok, dan dalam keadaan kurus
kering tanpa rambut, orang akan kelihatan seperti setan.
Pada
suatu kali orang mendengar kabar, Gubermen telah menghapuskan kebun nila,
menghapuskan kerja tanam paksa. Tetapi desa itu terus juga melakukan tanam
paksa sampai dua tahun lagi. Dikemudian hari dapat aku ketahui, tanam paksa
setelah Gubermen menghapuskannya adalah untuk kepentingan pembesar-pembesar
setempat, Eropa dan pribumi.
Aku
tak tahu bagaimana jalannya maka tanam paksa akal-akalan setempat itu akhirnya
dihentikan. Mungkin juga karena pembagian hasil yang tidak seimbang. Pendeknya
aku tahu. Itu urusan dewa-dewa yang berkuasa. Maka orang kembali mengerjakan
sawah dan ladang yang telah kembali jadi hutan dan semak-semak. Penduduk telah
berkurang lima
Kemudian
menyusul berita-berita, kebun-kebun Gubermen akan dijadikan kebun swasta. Dan
kebun-kebun itu akan jadi milik orang-orang Eropa. Orang-orang desa boleh
bekerja di sana
Sementara
itu si bocah itu telah berumur sebelas tahun, sudah lebih kuat dari tiga tahun
sebelumnya. Berita-berita itu tak pernah menjadi kenyataan. Yang benar:
tanha-tanah perorangan dan desa malah dirampas oleh Gubermen, termasuk
lima-perenam dari milik desa. Juga
katanya untuk perkebunan swasta. Melihat perampasan itu, petani-petani yang
baru saja bangun dari kematian dan kelaparan, bangkit marah. Di pimpin oleh pak
Samin, seorang desa lain, sebuah pemberontakan tani terjadi.
Si
bocah berumur tiga belas tahun itu menggambungkan diri dengan para pemberontak.
Tapi petani-petani itu dikalahkan dan dikalahkan dengan mudah, oleh polisi
lapangan, yang didatangkan dari kota
Penduduk
lelaki yang terlepas dari penangkapan kembali kedesa semula. Jumlahnya lebih
sedikit lagi, mati dalam banyak pertempuran.
Si
bocah berumur lima
Rasa-rasa
ketenangan dan kedamaian akan berlangsung terus dan tanah-tanah akan
dikembalikan. Ternyata tidak. Tanah-tanah yang dirampas mulai dihutankan dengan
jati. Katanya, tak ada perusahaan Eropa mau mengerjakan tanah rampasan, yang
dianggap terlalu banyak mengandung kapur dan tidak subur itu.
Ternyata
bintang kecelakaan tetap bersinar. Kemudian penduduk diusir dari desa, karena
perusahaan minyak akan mendirikan kantor-kantor dan kilang-kilang di situ.
Penduduk pindah dengan ternaknya, kembali membabat hutan untuk ladang, sawah
dan perumahan. Orang bilang, tanah yang dirampas itu akan diganti dengan uang,
tapi tak seorang pun pernah melihat uang yang dijanjikan tanpa jumlah
disebutkan itu. Bahkan setiap pohon di atas tanah rampasan, katanya, telah
dibayar penuh. Hanya berita belaka.
Desaku
yang sejuk di bawah rerimbunan pohon-pohon buah seperti disulap berubah jadi
tanah lapang. Podok-pondok hilang. Jalan-jalan yang indah dibangun, demikian
juga gedung-gedung. Semua serba indah, hanya bukan milik penduduk desa.
Si
bocah tinggal di desanya yang baru. Disana ia kawin dengan sisa dari
perawan-perawan yang tidak direnggut oleh maut. Dan di antara anak-anak adalah
aku.
Dikemudian
hari, jauh di kemudian hari, dapat kuketahui, bahwa dalam hanya lima tahun,
perusahaan minyak yang bermodal lima
Betapa
anehnya pembagian rezeki dan pembagian nasib bikinan manusia ini. Aku tahu dan
berani membuktikan, bahwa tuan-tuan minyak ini pada mulanya adalah insiyur
Geologi Gubermen di Bandung. Dengan tugas Gubermen mereka melakukan
eksplorasi-eksplorasi di daerah hidup aku, orang tuaku, tetangga dan
sanak-keluarga, di atas tanah nenek-moyangku dilahirkan, dan dikuburkan.
Penduduk desa selalu menyambut pendatang-pendatang itu dengan baik dan ramah,
tak perduli warna kulit dan apa agamanya. Kayu-bakar, kelapa tua dan muda,
buah-buahan kami antarkan ketempat mereka. Setelah sumber ditemukan, mereka
balik kembali ke Bandung, dan : minta keluar dari jabatan Gubermen. Mereka kembali lagi ke Cepu sebagai
nyamuk-nyamuk raksasa yang menyedot darah, daging, tanah kami, dan minyak kami
dalam kandungan bumi nenek-moyangku. Dalam sepuluh tahun perusahaan minyak ini
telah jadi perusahaan berjuta, sedang bekas tuan rumahnya telah kehilangan
tanah dan tetap hidup dalam keadaan yang semakin miskin. Bukan itu saja, dari
petani bebas berbahagia mereka mulai berubah jadi kuli-kuli bekas tamunya.
Ketika
pengeboran-pengeboran baru sedang giat-giatnya dilakukan di sekitar daerah
hidup kami, aku dilahirkan. Bapakku, si bocah berpatek dan berbubul dulu, kini
bukan lagi kuli minyak. Ia jadi lurah. Dan perusahaan minyak menjadi rakus akan
tanah. Mereka takut saingan perusahaan-perusahaan minyak lainnya yang tumbuh
seperti cendawan di sekitar daerah hidup kami. Tanah-tanah yang dirampas mulai
dibayar. Pesaing-pesaing itu takut saling membongkar kejahatannya terhadap
penduduk.
Desa
kami rasa-rasanya telah kehabisan tanah untuk melepas ternak besar kami. Bila
ada salah seekor ternak kami lepas dan memasuki daerah perusahaan minyak,
polisi minyak akan menangkapnya, menyitanya, dan pemiliknya dicari untuk
didenda, seratus kali penghasilan umum dalam sehari, alias ringgit.
Aku
hanya hendak menceritakan, dalam pemerintahan Gubermen masih ada pemerintahan
minyak, dua-duanya harus dipatahkan oleh penduduk desa kami.
Sekarang
ribuan orang dari daerah-daerah lain, segala bangsa, datang mencari penghidupan
di Cepu. Dalam waktu pendek Cepu, yang tadinya terdiri hanya atas tiga desa
berbiak menjadi dua puluh tiga desa, menjadi kota
Hampir-hampir
terjadi pemberontakan lagi di kalangan petani. Mendadak beberapa orang di
antara penduduk desa di tangkapi dan tak kembali lagi untuk selama-lamanya.
Mereka ditangkapi oleh polisi-polisi minyak.
Setelah
itu rasa-rasanya keadaan takkan gelisah lagi. Seakan-akan kembalilah keamanan
yang lama dalam segala kekerdilannya. Baik Gubermen maupun perusahaan minyak
tetap tak berbagi keuntungan dengan penduduk. Dan pada kami tak ada ternak
besar lagi. Peternakan desa pun telah tumpas semasa tanam-paksa.
Kalau
aku seorang Ameri Srikat, Tuan-tuan pembaca yang terhormat, tahulah Tuan-tuan
apa yang akan aku perbuat: tarik pistol dan membela apa yang masih dapat
dibela. Tapi aku hanya seorang bocah pribumi tanpa sarana, tanpa pengetahuan
tentang dunia. Bahkan di mana sesungguhnya desa tempat kelahiranku di
tengah-tengah dunia ini, aku tak tahu. Di mana tempat orang-orang yang
memiskinkan kami aku tak tahu. Aku hanya lulusan sekolah desa tiga tahun,
dididik untuk jadi kuli minyak, bekerja untuk mereka yang telah merampas tanah
leluhurku. Dididik untuk tetap tidak berpengetahuan, dan mematuhi segala apa
saja yang diperintahkan pada kami oleh tuan-tuan kulit putih.
Ketika
bapakku hendak meninggal, ia berpesan dengan sangat:
“
Mereka telah merampas semua dari kita. Jangan, Nak, jangan kau lebih lama jadi
kulinya. Pergi kau ke Bandung
BAB V
PENUTUP
Setelah penulis mengemukakan argumentasi, motodologi,
dan teori-teori seputar realisme sosialis
Pramoedya Ananta Toer yang tertuang dalam novel Tetralogi, maka Bab V ini
penulis akan mengemukakan beberapa
kesimpulan yang menjadi intisari dari skripsi ini. Di samping itu penulis juga
akan memberi kritik dan saran.
A. Simpulan
Sebagai mana telah di uangkapkan dalam Bab I bahwa
penulis merumuskan dua persoalan yang menjadi titik sentral pembahasan, maka
berikut ini adalah jawaban yang penulis gambarkan dalam paragraph-paragraf
berikut ini:
a)
Aliran realisme sosialis adalah salah satu bentuk perjuangan untuk
memenangkan sosialisme, sebab aliran realisme sosialis berkecimpung di bidang
seni. Seni lebih mudah diterima oleh masyarakat pada umumnya, sehingga faham
sosialisme lebih mudah diterima oleh masyarakat. Karena hal tersebut seni
aliran realisme sosialis tidak bisa lepas dari permasalahan yang dihadapi oleh
masyarakat, dan membuat masyarakat berpikir kritis dan juga melakukan gerakan
untuk menentang kapitalis.
b) Realisme sosialis dalam pandangan
Pram pada novel tetralogi, penggambaran terhadap karakter masyarakat yang
tertindas karena system kapitalis yang menjajah mereka (Belanda), serta
bangkitnya kesadaran masyarakat Indonesia
B. Saran-saran
a) Dalam novel teralogi dapat di
lihat dari dua sisi, yang pertama dari segi positifnya. Segi positif dari novel
teralogi 1) Novel tersebut berisikan tentang sejarah Indonesia Indonesia
Segi negatif 1)
Novel tetralogi masih rancau antara tokoh Tirtho Adhi Suryo dengan Pram,
pengalaman pribadi Pram sering kali masuk kedalam cerita novel tersebut. 2)
novel tersebut lebih banyak menceritakan kesedihan dan kekalahan, seakan novel
tersebut pencerminan diri Pram.
b)
Masih banyak hal yang terdapat dalam novel tetralogi belum diangkat penulis dalam skripsi ini. Oleh sebab itu
sehingga masih banyak kekurangan yang terjadi di sana-sini.
c)
Bahwa penelitian ini masih belum sempurna, di perlukan kritik dan saran
dari para pembaca.
DAFTAR PUSTAKA
Ananta Toer, Pramoedya, Bumi Manausia, Cet 9 Yogyakarta :
Hasta Mitra, 2002.
Ananta Toer, Pramoedya, Anak Semua Bangsa, Cet 6 Yogyakarta : Hasta Mitra, 2002.
Ananta Toer, Pramoedya, Jejak Langkah, Cet 4 Yogyakarta :
Hasta Mitra, 2002.
Ananta Toer, Pramoedya, Rumah Kaca, Cet 4 Yogyakarta :
Hasta Mitar, 2002.
Arikuntoa, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan
Praktek, Cet 11, Jakarta
“ Akademisi Ilmu Sosial,
Bacalah Bumi Manusia”, Triyono Lukmantoro, Suara
merdeka.18 Juli 2004.
Malaka, Tan, Madilog, Cet 1 Jakarta
Mills, C Wright, Kuam Marxis Ide-ide Dasar Dan Sejarah
Perkembangan, terj, Imam Muttaqien, Cet
01, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Mintz, Jeanne S, Muhammad, Marx, Marhaen akar sosialisme Indonesia Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2002.
Rangkuti, Bahrum. Pramoedya dan Karya Seninya, Jakarta
Russell, Bertrand, Sejarah Filsafat Barat, terj. Sigit
Jatmiko dkk, Cet. 01, Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2002.
Supriyadi, Eko, Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari’ati, Cet
01, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
Teeuw, A, Citra Manusia Indonesia Jakarta
[1] Georg Lukacs, Realisme Sosialis Terj. Ibe Karyanto ( Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1997), hlm. 52.
[2] Suara Merdeka, 18 Juli
2004, hlm. 18.
[3] Ibid…..
[4] Adhi Asmara, Analisa Ringan Kemelut Bumi Manusia ( Yogyakarta: CV Nur Cahya,
1981), hlm. 15.
[5] Pramoedya Ananta Toer, “Bincang-bincang
dengan Pram”, ON/OFF Media Orang Biasa, 01November
2003, hlm. 27.
[6] Rudolf Mrazek Pramoedya
Ananta Toer dan Kenangan Buru Cet
ke 02, terj. Endi Haryono ( Yogyakarta :
Cermin, 2000). hlm. 1
[7] Suara
Merdeka, 18 Juli 2004, hlm. 18.
[8] Eka Kurniawan, Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis Cet. Ke-2 (Yogyakarta :
Jendela, 2001), hlm 10.
[9] Erich Fromm, Konsep Manusia Menurut Marx, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm 77
[10] Ibid.,
hlm. 79.
[11] Anthony Brewer, Das Kapital Karl Marx, terj. Joebaar Ajoeb (Jakarta: Teplok Press,
1999), hlm, 07
[12] Ahmad Hambali Pandangan Pramoedya Pramoedya Ananta Toer tentang Humanisme Jurusan
Aqidah Filsafat IAIN Sunan Kalijaga 1998
[13] Arif Sarwani Teori Pembebasan dalam Novel Gadis Pantai Jurusan Aqidah Filsafat
IAIN Sunan Kalijaga 2002
[14] A. Teeuw Op. Cit
[15] Bahrum Rangkuti, Pramoedya dan Karya Seninya ( Jakarta : Gunung Agung, 1963)
[16] Adhy Asmara, Analisa Ringan Kemelut Bumi Manusia, Cet I (Yogyakarta: Nur Cahaya,
1981)
[17] Eka Kurniawan, Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis, Cet 02 (Yogyakarta : Jendela, 2001)
[18] Pramoedya Ananta Toer, Relisme Sosialis dan Sastra Indonesia Jakarta
[19] Ibid…hlm.
18.
[20] Ibid….hlm.
28.
[21] Harold H. Titus dkk, Persoalan-persoalan Filsafat terj. M. Rasjidi
( Jakarta: Bulan Bintang, 1984) hlm. 304
[22] Eko Supriyadi, Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari’ati Cet 01 ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2003), hlm. 07.
[23] Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, terj. Soeheba Kramadibrata Cet
01 ( Jakarta: UI-RESS, 1986), hlm. 119.
[24] Metode berasal dari bahasa Yunani methodos sambungan dari kata depan meta (ialah: menuju, melalui, mengikuti,
sesudah), dan kata benda hodos (ialah:
jalan, perjalanan, cara, arah). Jadi
metode berarti: cara berfikir menurut sistem aturan
tertentu. Anton Bekker, Metode-metode
Filsafat, Cet. Ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986),hlm 10.
[25] Tentang sumber data, Suharsimi Arikunto,
mengklasifikasikan menjadi tiga dengan huruf depan P singkatan dari: (1) Person, sumber data berupa orang (2) Place,
sumber data berupa tempat (3) Paper, sumber data berupa simbol. Suharsimi
Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan Praktek, (Edisi Revisi), Cet. Ke-II, (Jakarta: Rineka Cipta,
1998), hlm. 114.
[26] Anton Bakker dan achmad charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, Cet ke-5
(Yogyakarta: Kanisius, 1996).,hlm. 71.
[27] Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi…Op.cit.,hlm. 69.
[28] Anton Bakker, Metode-Metode Filsafat, Op.cit.,hlm. 136.
[29] A. Teeuw, Citra Manusia
Indonesia Dalam Karya Sastra Pramoedya Ananta Toer, Cet-1 (Jakarta
[30] Ibid..
[31] Ibid. hlm. 5.
[32] Ibid
[33] Wawasan,19 September 2004 , hlm.16.
[34] Rudolf Mrazek, Pramoedya
Ananta Toer dan Kenangan Buru ( Yogyakarta :
Cermin, 2000), hlm. 4.
[35] A. Teeuw, Op. Cit. hlm.
15 .
[36] Suara Merdeka, 18 Juli
2004. hlm 23.
[37] A. Teeuw, Op. Cit. hlm
17.
[38] Ibid, hlm 18.
[39] Rudolf Mrazek, Op. Cit, hlm.
25.
[40] Adhy Asmara, Analisa Ringan
Kemelut Bumi Manusia (Yogyakarta:
Nur Cahya, 1981). hlm. 57.
[41] A Teeuw, Op. Cit. hlm.
22.
[42] Wawasan, 19 Maret 2004.
hlm. 16.
[43] Ibid…..
[44] Adhy Asmara, Op. Cit. hlm. 73.
[45] Ibid…, hlm 81.
[46] A Teeuw, Op. Cit. hlm.
40.
[47] Rudolf Mrazek, Op. Cit. hlm.
25.
[48] Ibid…hlm. 27.
[49] Linda Christanty, “ Arus Balik dalam Hidup Pramoedya Ananta Toer”, ON/OOF, XI, September 2003, hlm. 23.
[50] A Teeuw, Op. Cit. hlm.
39.
[51] Astrid Reza Widjaja, “Mengapung dalam Kebisuan”, Op. Cit, hlm. 12.
[52] Bintang timur adalah koran yang terbit pada tahun 1960, rubriknya
bernama Lentera yang dipimpin oleh Pram.
[53] Rudolf Mrazak, Op. Cit, hlm.
69.
[54] Adhy Asmara
[55] Ibid., hlm. 97.
[56] A.Teeuw, Op Cit,hlm. 79.
[57] Adhy Asmara, Op Cit, hlm.
55.
[58] Ibid. hlm.133.
[59]Rudolf Mrazek, Op Cit,
hlm. 63.
[60]Sulastin Sutrisno, Surat-Surat Kartini, Renungan Untuk
Bangsanya, (Jakarta: Jambatan 1979), hlm. 130.
[61]Pramoedya Ananta Toer, Bumi
Manusia, (Yogyakarta : Hastra Mitra 2002),
hlm. 5.
[62] Rudolf Mrazek, Op Cit, hlm. 83.
[64] Ibid,. hlm. 119.
[65] Adhy Asmara, Op Cit, hlm.
91.
[66] A Teeuw, Op Cit, hlm. 51.
[67] Pramoedya Ananta Toer, Bumi
Manusia, (Yogyakarta : Hastra Mitra 2002),
hlm.1.
[68] A Teeuw, Op Cit, hlm.
86.
[69]Adhy Asmara, Op Cit, hlm.
54.
[70]Ibid, hlm. 55.
[71] Adhy Asmara, Op Cit, hlm.
13.
[72] Ibid, hlm. 15.
[73] Ibid…
[74] Eka Kurniawan, op. cit. hlm.
37.
[75] Adhy Asmara, Op Cit, hlm.
146.
[76] A. Teeuw, Op. Cit. hlm.
230.
[77] Ibid,. hlm. 232.
[79] Pramoedya Ananta Toer, Op
Cit, hlm. 405.
[80] Pramoedya Ananta Toer, Anak
Semua Bangsa, (Yogyakarta : Hasta Mitra
2002), hlm. 290.
[81]Pramoedya Ananta Toer, Realisme
Sosialis dan sastra Indonesia Jakarta
[82] Ibid…, hlm 17.
[83] Ibid…., hlm. 18.
[85] Ibid…..hlm 59.
[87] Ibid…..hlm. 29.
[88] Ibid….hlm 31.
[89] Ibid……hlm. 31.
[90] Ibid…..hlm 73 .
[91] Ibid….hlm 108-109.
[92] Ibid……hlm. 111.
[93] Ibid…..hlm. 152- 156
[94] Ibid……hlm. 93.
[95] Ibid…..hlm 157.
[96] Ibid….hlm. 15.
[97] Ibid….hlm. 27.
[98] Pramoedya Ananta Toer, Realisme
sosialis dan sastra Indonesia Jakarta
[99] Pramoedya Ananta Toer, Anak
Semua Bangsa ( Yogyakarta : Hasta Mitra,
2002), hlm. 209.
[100] Ibid…hlm.130-131.
[101] Pramoedya Ananta Toer, op.
cit.,hlm. 174.
[102] Ibid., hlm. 177.
[103] Pramoedya Ananta Toer,. Op.
cit., hlm 209.
[104] Ibid, hlm. 208.
[105] Ibid., hlm. 302-303.
[106] Pramoedya Ananta Toer, Jejak
Langkah (Yogyakarta : hasta Mitra, 2002),
Cet ke-4., hlm.79.
[107] Ibid., hlm. 178-179.
[108] Ibid., hlm. 215.
[109] Ibid., hlm. 38 .
[110] Ibid., hlm. 231.
[111] Ibid., hlm. 294.
[112] Ibid., hlm. 315.
[113] Ibid., hlm. 448.
[115] Ibid., hlm. 423.
[116] Ibid., hlm. 400.
[117] Ibid., hlm. 400-401.
[118] Ibid., hlm. 404.
[119] Ibid., hlm. 407.
[120] Ibid., hlm. 483.
[121] Ibid., hlm. 405.
[122] Pramoedya Ananta Toer, Rumah
Kaca (Yogayakarta: Hasta Mitra, 2002),. hlm. 134.
[123] Ibid., hlm 146.
[124] Pramoedya Ananta Toer, op.
cit. hlm. 77.
[125] Ibid., hlm. 175.
[126] Ibid., hlm. 245.
[127] Ibid., hlm. 291.
[128] Ibid., hlm. 226.
[129] Ibid,. hlm. 352-353.
[130] Ibid….hlm. 246-250.
[131] Georg Lukacs, Op. Cit. hlm.
12.
[132] Pramoedya Ananta Toer, Op.
Cit. hlm. 103-104.
[133] Ibid…hlm. 104.
[134] Ibid…hlm. 105.
[135] Ibid…hlm. 31-31.
[136] D.W. Fokkema dan Elrud Kunne-ibsch Teori sastra abad kedua puluh (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1998) hlm. 106.
[137] Eka kurniawan, Op. Cit. hlm.
55.
[138] Ibid….
[139] Ibe karyanto, Op. Cit. hlm.
59.
[140] Pramoedya Ananta toer, Op.
Cit. hlm. 69.
[141] Ibid…, hlm 40.
[142] Jeanne S. Mintz, Muhammad
Marx, Marhaen Akar Sosialisme Indonesia Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2002) hlm. 251-252.
[143] Georg Lukacs, Realisme
sosialis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997)., hlm. XX.
[144] Pramoedya Ananta Toer, Anak
Semua Bangsa ( Yogyakarta : Hasta Mitra,
2002), hlm. 209.
[145] Ibid…hlm.130-131.
[146] Pramoedya Ananta Toer, op.
cit.,hlm. 174.
[147] Ibid., hlm. 177.
[148] Pramoedya Ananta Toer,. Op.
cit., hlm 209.
[149] Ibid, hlm. 208.
[150] Ibid., hlm. 302-303.
[151] Pramoedya Ananta Toer, Jejak
Langkah (Yogyakarta : hasta Mitra, 2002),
Cet ke-4., hlm.79.
[152] Ibid., hlm. 178-179.
[153] Pramoedya Ananta Toer, Realisme
Sosialis dan Sastra Indonesia Jakarta
[154] Ibid., hlm. 215.
[155] Ibid., hlm. 38 .
[156] Ibid., hlm. 231.
[157] Ibid., hlm. 294.
[158] Ibid., hlm. 315.
[159] Ibid., hlm. 448.
[161] Ibid., hlm. 423.
[162] Ibid., hlm. 400.
[163] Ibid., hlm. 400-401.
[164] Ibid., hlm. 404.
[165] Ibid., hlm. 407.
[166] Ibid., hlm. 483.
[167] Ibid., hlm. 405.
[168] Jeanne S. Mintz, Op, Cit.
hlm. 56.
[169] Pramoedya Ananta Toer, Rumah
Kaca (Yogayakarta: Hasta Mitra, 2002),. hlm. 134.
[170] Ibid., hlm 146.
[171] Pramoedya Ananta Toer, op.
cit. hlm. 77.
[172] Jeanne S. Mintz, Op. Cit.
hlm. 30.
[173] Ibid., hlm. 175.
[174] Pramoedya Ananta Toer, Op.
Cit. hlm. 96.
[175] Ibid., hlm. 245.
[176] Jeanne S. Mintz, Op. Cit,. hlm.
56.
[177] Ibid., hlm. 291.
[178] Ibid,hlm. 184.
[179] Pramoedya Ananta Toer, Op,
Cit. hlm 57.
[180] Ibid., hlm. 226.
[181] D.W. Fokkema dan Elrud Kunne-Ibsch, Op. Cit. hlm. 123.
[182] Ibid,. hlm. 352-353.
[183] Ibid….hlm. 246-250.
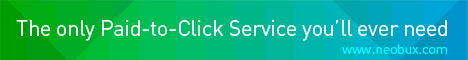


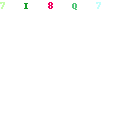


0 komentar:
Post a Comment