EKSISTENSI
KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMKORATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS
DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
TESIS
Untuk Memenuhi sebagai
Persyaratan mencapai derajat S-2
Program Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kenegaraan

Diajukan oleh :
Salamat Simanjuntak
6801/PS/MH/00
PROGRAM PASCA
SARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2003
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Seiring dengan dilaksanakannya program otonomi daerah,
pada umumnya masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam
bentuk peningkatan mutu pelayanan masyarakat, partisipasi masyarakat yang lebih
luas dalam pengambilan kebijakan publik, yang sejauh ini hal tersebut kurang
mendapat perhatian dari pemerintahan pusat. Namun kenyataannya sejak
diterapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah sejak Januari 2001, belum menunjukkan perkembangan yang
signifikan bagi pemenuhan harapan masyarakat tersebut.
Dalam era transisi desentralisasi kewenangan itu telah
melahirkan berbagai penyimpangan kekuasaan atau korupsi, kolusi dan nepotisine
(KKN) termasuk didalamnya bidang politik di daerah, KKN yang paling menonjol
pasca otonomi daerah antara lain semakin merebaknya kasus-kasus politik uang
dalam pemilihan kepala daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
yang tidak memihak pada kesejahteraan rakyat banyak, penggemukan
instansi-instansi tertentu di daerah yang menimbulkan disalokasi anggaran, dan
meningkatkan pungutan-pungutan melalui peraturan-peraturan daerah (perda) yang
memberatkan masyarakat dan tidak kondusif bagi pengembangan dunia usaha di
daerah.
Berbagai pihak menyoroti realitas otonomi daerah yang
rawan terhadap terjadinya KKN tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara
lain :
(1) Program otonomi daerah hanya terbatas pada pelimpahan
wewenang dalam pembuatan kebijakan, keuangan dan administrasi dari pemerintah
pusat ke daerah, tanpa disertai pembagian kekuasaan kepada masyarakat atau
tanpa partisipasi masyarakat secara luas. Dengan perkataan lain, program
otonomi daerah tidak diikuti dengan prograrn demokratisasi yang membuka peluang
keterlibatan masyarakat dalam pengambiian kebijakan uraum di daerah. Karenanya,
program desentralisasi ini hanya memberi peluang kepada para elit lokal
(daerah) baik elit eksekutif maupun elit legislatif untuk mengakses
sumber-sumber ekonomi daerah dan politik daerah, yang rawan terhadap KKN,
perbuatan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang dan atau perbuatan yang
rnelampui batas wewenang;
(2) Tidak adanya institusi
negara yang mampu mengontrol secara efektif
penyimpangan wewenang di daerah. Program otonomi daerah telah memotong struktur hirarki pemerintahan, sehingga tidak efektif lagi kontrol pemerintah pusat ke daerah karena tidak ada lagi hubungan struktural secara langsung memaksakan kepatuhan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kepala daerah, baik bupati maupun Walikota tidak lagi ditentukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan
bertanggungjawab kepada DPRD. Hubungan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak lagi struktural, melainkan fungsional yaitu hanya kekuasaan untuk memberi policy guidance kepada pemerintah daerah.
penyimpangan wewenang di daerah. Program otonomi daerah telah memotong struktur hirarki pemerintahan, sehingga tidak efektif lagi kontrol pemerintah pusat ke daerah karena tidak ada lagi hubungan struktural secara langsung memaksakan kepatuhan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kepala daerah, baik bupati maupun Walikota tidak lagi ditentukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan
bertanggungjawab kepada DPRD. Hubungan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak lagi struktural, melainkan fungsional yaitu hanya kekuasaan untuk memberi policy guidance kepada pemerintah daerah.
(3) Terjadi indikasi KKN yang cukup krusial antara pemerintah
daerah dan DPRD, sehingga kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah
daerah sulit terlaksana, sementara kontrol dari kalangan masyarakat
masih sangat lemah.
Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi
daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel,
merupakan isu yang sangat penting dan strategis. Hal tersebut sesungguhnya
merupakan konsekuensi logis otonomi daerah yang semestinya memungkinkan:
(1)
Semakin dekatnya pelayanan
pemerintahan daerah kepada masyarakat;
(2)
Penyelesaian masalah-masalah di
daerah menjadi lebih terfokus dan mandiri;
(3)
Partisipasi masyarakat menjadi
lebih luas dalam pembangunan daerah;
(4)
Masyarakat melakukan pengawasan
lebih intensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Keempat faktor tersebut hanya dapat
berlangsung dalam suatu pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Pelaksanaan
otonomi daerah tanpa diimbangi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
demokratis dan akuntabel, pada hakekatnya otonomi daerah tersebut telah
kehilangan jati diri dan maknanya.
Pemerintahan daerah yang demokratis
dapat dikaji dari dua aspek, yakni aspek tataran proses maupun aspek tataran
substansinya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dikatakan demokratis secara
proses, apabila pemerintahan daerah yang bersangkutan mampu membuka ruang bagi
keterlibatan masyarakat dalam semua pembuatan maupun pengkritisan terhadap
sesuatu kebijakan daerah yang dilaksanakan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah
dikatakan demokratis secara substansial apabila kebijakan-kebijakan daerah yang
dibuat oleh para penguasa daerah mencerminkan aspirasi masyarakat.
Sesuatu pemerintahan daerah dikatakan akuntabel, apabila
ia mampu menjalankan
prosedur-prosedur yang telah
ada dan dapat mepertanggungjawabkannya kepada
publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kebijakan-kebijakan daerah yang bertentangan dengan
aspirasi masyarakat maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
demikian pula dengan tidak adanya keterpaduan dalam mekanisme pembuatan
kebijakan daerah antara kepala daerah dengan DPRD, menimbulkan permasalahan di
berbagai daerah.
Dengan demikian tidak ada kejelasan mengenai produk hukum
daerah, yang dapat mendukung proses mengalirnya partisipasi masyarakat dalam
setiap proses pembuatan kebijakan daerah dan atau pengkritisan atas suatu
pelaksanaan setiap kebijakan daerah. Dengan perkataan lain tidak ada kejelasan
mengenai pranata hukum daerah yang mengatur mekanisme penyaluran aspirasi
masyarakat guna mewujudkan suatu pemerintahan daerah yang bersih bebas dari
KKN.
Sebagai ilustrasi pemerintahan Kota Yogyakarta secara
perposif dipilih sebagai lokasi penelitian hukum empiris, dengan pertimbangan
bahwa (pemerintahan Kota Yogyakarta merupakan salah satu pemerintahan daerah
yang mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sejajar dengan pemerintahan
daerah lainnya, dalam jajaran dan sistem pemerintahan negara kesatuan Republik
Indonesia. Demikian pula secara perposif ilustrasi obyek kajian dibatasi khusus
eksistensi kebijakan daerah yang demokratis dalam sistem pemerintahan yang
bersih bebas dari KKN.
2. Rumusan Masalah
Bertolak
dari paparan latar belakang masalah, dapat dirumuskan sebagai isu sentral dalam
penelitian ini yaitu : "ketidak jelasan eksistensi kebijakan daerah yang
demokratis dalam sistem pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme", yang kemudian diungkapkan dalam judul penelitian yaitu :
"EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME". Isu sentral tersebut
mengandung berbagai permasalahan, baik permasalahan hukum empiris maupun
permasalahan hukum normatif, baik permasalahan hukum normatif pada lapisan
dogmatik hukum maupun pada lapisan teori hukum.
Dengan
demikian dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut:
1.
Permasalahan hukum empiris, bagaimanakah realisasi
pembuatan kebijakan daerah yang demokratis dalam sistem pemerintahan yang
bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2.
Permasalahan hukum normatif pada lapisan dogmatik hukum,
apakah dalam setiap pembuatan kebijakan daerah telah melibatkan partisipasi
masyarakat, demikian pula apakah produk-produk kebijakan daerah pasca UU No. 22
Tahun 1999 telah mencerminkan aspirasi masyarakat.
3.
Permasalahan hukum normatif pada lapisan teori hukum,
mengapa masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap pembuatan dan evaluasi
kebijakan daerah.
3. Keaslian
Penelitian
Setelah
melakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian dalam
berbagai media, baik cetak maupun elektronik, penelitian tentang eksistensi
kebijakan daerah yang demokratis dalam sistem pemerintahan yang bersih bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme, belum pernah dilakukan penelitian dan dalam
kesempatan ini peneliti berniat untuk melakukan penelitian terhadap
permasalahan tersebut. Dengan demikian penelitian ini adalah asli.
4. Tujuan
Penelitian
Tujuan
penelitian ini meliputi berbagai dimensi antara lain :
a. Tujuan
deskriptif, untuk mengetahui realisasi pembuatan dan atau evaluasi kebijakan
daerah yang demokratis dalam sistem pemerintahan yang bersih bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.
b. Tujuan
kreatif, untuk mengetahui ada tidaknya partisipasi masyarakat dalam setiap
pembuatan kebijakan daerah dan untuk mengetahui aspiratif tidaknya
produk-produk kebijakan daerah pasca UU No. 22 Tahun 1999.
c. Tujuan
inovatif, untuk mengetahui perlu tidaknya masyarakat dilibatkan dalam setiap
pembuatan dan evaluasi kebijakan daerah.
5. Manfaat
Penelitian
Dari
hasil penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat, baik untuk
kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis,
a. Manfaat akademis
Dari
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu
pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum pada khususnya.
b. Manfaat praktis
Dari
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan
wacana bagi para elit eksekuttf dan legislatff dalam pembuatan dan evaluasi
kebijakan daerah, serta bagi masyarakat luas agar menyadari akan hak dan
kewajibannya untuk berperan serta aktif dalam setiap pembuatan dan evaluasi
atas kebijakan-kebijakan daerah.
BAB II
TLNJAUAN PUSTAKA
l. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Dan
Evaluasi Kcbijakan Daerah
Peluang
dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan evaluasi atas kebijakan daerah,
termasuk didalamnya kebijakan daerah di kota Yogyakarta cukup besar dan
strategis. Hal tersebut pada hakekatnya telah diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, antara lain dalam :
a. UU NO. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah
b. PP No. 20
Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Kepmendagri No 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan
Daerah
c. UU No. 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang bersih dan Bebas dari KKN.
Secara
garis besar, amanat bagi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap sesuatu
kebijakan daerah dapat disistematisir sebagai berikut:
a. Setiap
pembuatan kebijakan daerah yang baru, baik berupa keputusan kepala daerah
maupuu peraturan daerah, senantiasa wajib melibatkan masyarakat daerah untuk
berpartisipasi;
b. Setiap
kebijakan daerah yang baru, yang tidak melibatkan masyarakat daerah dapat
menyebabkan kebijakan daerah tersebut dibatalkan oleh pemerintah atasan;
c. Masyarakat
berhak untuk mengkritisi dan mengevaluasi atas sesuatu kebijakan daerah yang
telah ada, dan apabila dipandang perlu dapat mengajukan usul agar kebijakan
daerah yang dinilai oleh masyarakat tidak
sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tuntutan keadaan /zaman, ditinjau kembali dan apabila perlu dapat diusulkan untuk dicabut;
sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tuntutan keadaan /zaman, ditinjau kembali dan apabila perlu dapat diusulkan untuk dicabut;
d. DPRD mempunyai
tugas dan wewenang
untuk menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan
aspirasi masyarakat;
e. Masyarakat
mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang
penyelenggaraan negara (termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah), serta
menyampaikan saran dan pendapat terhadap
kebijakan penyelenggaraan negara (termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah). ( Prasetyo, 2002 : 3)
kebijakan penyelenggaraan negara (termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah). ( Prasetyo, 2002 : 3)
Tantangan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat
dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan daerah di kota Yogyakarta, antara lain
karena (Prasetyo, 2002 : 3-4):
a. Berbagai
peraturan perundangan yang berkaitan erat dengan pembuatan dan evaluasi
kebijakan daerah, tidak mengatur mekanisme partisipasi masyarakat secara rinci
dan tegas. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :
- UU NO.
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- PP No.
20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan Kepmendagri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan
Represif Kebijakan Daerah;
- UU No.
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang bersih dan Bebas dari
KKN; PP No. 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;
- Keppres
No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU;
- Keppres
No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan
Bentuk RUU, R Keppres, Raperda dan Rancangan Keputusan Kepala Daerah;
- Kepmendagri
dan Otonomi Daerah NO. 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah;
- Keputusan
DPRD Kota Yogyakarta No. 3 / K/ DPRD / 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
b. Belum
seluruh komponen masyarakat yang ada memahami akan hak dan kewajibannya, untuk
berpartisipasi dalam pembuatan dan evaluasi atas sesuatu kebijakan daerah di
kota Yogyakarta.
Suatu sikap dan langkah yang telah ditempuh oleh DPRD
menyelenggarakan public hearing perlu diberikan penghargaan. Public Hearing ini
dimaksudkan, untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, guna membahas tentang
sesuatu kebijakan daerah. Namun disayangkan langkah ini belum seluruhnya tepat,
mengingat sifatnya sangat parsial, tidak menentu, dan sangat terbatas. Sebagai
konsekuensinya banyak kebijakan daerah, baik oleh DPRD maupun eksekutif
ternyata bermasalah, karena tidak dapat diikuti oleh masyarakat. Sehubungan
dengan itu, maka hadirnya peraturan daerah di kota Yogyakarta, tentang
mekanisme pembuatan dan evaluasi kebijakan daerah, yang dapat mengakomodir
partisipasi masyarakat secara memadai dan komprehensif, sangat didambakan oleh
banyak kalangan masyarakat. (Prasetyo, 2002 : 4-5)
Urgensi Perda tentang mekanisme partisipasi masyarakat,
yakni berupaya untuk mensistematisasi secara komprehensif dan terpadu,
mekanisme pembuatan dan evaluasi kebijakan daerah dalam satu ketentuan.
Nantinya diharapkan bahwa semua proses pembuatan dan evaluasi suatu kebijakan
daerah mengacu pada satu sumber saja, sebagai konsekuensinya DPRD maupun
eksekutif daerah wajib mengikuti dan melaksanakan peraturan daerah tersebut.
(Suhardi, 2002 : 4)
Perda tentang mekanisme partisipasi masyarakat tersebut,
diharapkan dapat memuat substansi yang penting antara lain (Suhardi, 2002 :4-5):
a. Hak
partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan daerah yang baru maupun usulan
pencabutan kebijakan daerah yang sudah tidak relevan lagi;
b. Meletakkan
kewajiban kepada DPRD maupun eksekutif daerah untuk menampung dan
menindaklanjuti usulan masyarakat;
c. Partisipasi
masyarakat dalam pembahasan naskah akademik
dan Raperda;
d. Sosialisasi
rencana penyusunan dan pembahasan kebijakan daerah kepada publik.
Dengan
demikian partisipasi masyarakat tersebut pada dasarnya meliputi seluruh proses yang
relevan dalam pembuatan sesuatu kebijakan daerah. Dalam hal ini masyarakat
diposisikan sebagai subyek pembuatan kebijakan daerah, sejajar dengan eksekutif
dan legislatif, dan bukan sekedar simbol legitimasi legislatif dan eksekutif
saja.
2. Asas
Legalitas dan Perlindungan
Konsep
negara hukum (rechtsstaat) diintrodusir melalui RR 1854 dan ternyata
dilanjutkan dalam UUD 1945. (Wignjosoebroto, 1994 : 188, Hadjon, 1994 : 4)
Dengan demikian ide dasar negara hukum Pancasila tidaklah lepas dari ide dasar tentang
"rechtsstaat". (Hadjon, 1994 : 4)
Persyaratan
dasar untuk dapat dikategorikan sebagai negara hukum yakni:
- Setiap
tindak pemerintahan harus
didasarkan atas dasar
peraturan
perundang-undangan (wettelijke grondslag). Dengan landasan ini, undang-
undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar
tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan undang-undang
merupakan bagian penting negara hukum, (asas legalitas). - Kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada
satu tangan. (asas
pembagian kekuasaan). - Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum
bagi rakyat dan
sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang, (prinsip
grondrechten) - Bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang
bebas untuk menguji keabsahan (rechtmatigheidstoetsing) tindak
pemerintahan, (pengawasan pengadilan) (Burkens, 1990 : 29, Hadjon, 1994,
ibid.,: 5, Sukismo, 2002,(a):2).
Syarat-syarat
dasar tersebut seyogyanya juga menjadi syarat dasar negara hukum Pancasila.
Untuk hal tersebut kiranya dibutuhkan suatu usaha besar berupa suatu kajian
yang sangat mendasar terutama tentang ide bernegara bangsa Indonesia. Ada
beberapa tulisan awal tentang itu yang barangkali dapat dijadikan acuan awal,
seperti : Negara Hukum Pancasila Dan Teori Bernegara Bangsa Indonesia.
Disamping itu tentunya kita tidak menutup mata terhadap perkembangan konsep
negara hukum yang telah terjadi di berbagai negara, seperti konsep negara hukum
yang telah terjadi di berbagai negara seperti konsep rechlsstaat yang telah
berkembang dari konsep "liberal-democratische rechtsstaat" ke
"sociale rechtsstaat" yang pada dewasa inipun sudah dirasakan bahwa
konsep terakhir itu sudah tidak memadai. (Hadjon, 1994 : 5, B. Sukismo, 2002
(a): 3)
Untuk
mengkategorikan negara hukum, biasanya digunakan dua macam asas, yakni: asas
legalitas dan asas perlindungan atas kebebasan setiap orang dan atas hak-hak
asasi manusia. (Utrecht, 1963 : 310, Sukismo, 2002 (a): 3)
Unsur
utama suatu negara hukum, yakni asas legalitas. Semua tindakan negara harus
berdasarkan dan bersumber pada undang-undang. Penguasa tidak boleh keluar dari
rel-rel dan batas-batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Batas
kekuasaan negara ditetapkan dalam undang-undang. Akan tetapi untuk dinamakan
negara hukum tidak cukup bahwa suatu negara hanya semata-mata bertindak dalam
garis-garis kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. ( Gouw Giok
Siong, 1955 :12-13, Sukismo, 2002 (a): 4) Sudah barang tentu bahwa dalam negara
hukum setiap orang yang merasa hak-hak pribadinya dilanggar, diberi kesempatan
seluas-luasnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan perkaranya itu di
hadapan pengadilan. Cara-cara mencari keadilan itu pun dalam negara hukum
diatur dengan undang-undang. (Rochmat Soemitro, 1976 : 18, Sukismo, 2002 (a):4).
Dalam
negara hukum asas perlindungan nampak antara lain dalam "Declaration of
Independence", bahwa orang yang hidup di dunia ini sebenarnya telah
diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat
dirampas atau dimusnahkan. Hak-hak tersebut yang sudah ada sejak orang
dilahirkan, perlu mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum modern
(Soemitro, 1976 : 18, Sukismo, 2002 (a): 4). Peradilan tidak semata-mata
melindungi hak asasi perseorangan, melainkaa fungsi hukum adalah untuk
mengayomi masyarakat sebagai totalitas, agar supaya cita-cita luhur bangsa
tercapai dan terpelihara. Peradilan mempunyai maksud membina, tidak semata-mata
menyelesaikan perkara. Hakim harus mengadili menurut hukum dan menjalankan
dengan kesadaran akan kedudukan, fungsi dan sifat hukum. Dengan kesadaran bahwa
tugas hakim ialah, dengan bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada Nusa
dan Bangsa, turut serta membangun dan menegakkan masyarakat adil dan makmur
yang berkepribadian Pancasila. (Soemitro, 1976 : 20-21, Sukismo, 2002 (a): 5).
Suatu
negara merupakan negara hukum, semata-mata didasarkan pada asas legalitas.
(Yamin, 1952 : 9, Sukismo, 2002 (a) : 5) Disisi lainnya asas legalitas,
hanyalah merupakan salah satu unsur atau salah satu corak dari negara hukum,
karena disamping unsur asas legalitas tersebut, masih perlu juga diperhatikan
unsur-unsur lainnya, antara lain kesadaran hukum, perasaan keadilan dan
perikemanusiaan, baik bagi rakyat maupun pimpinannya. (Siong, 1955 : 23,
Sukismo, 2002 (a) : 5, Yunanto, 2000 : 4)
Dalam UUD 1945
ada ketentuan yang menjamin hak-hak asasi manusia. Ketentuan tersebut antara
lain:
-
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Ps. 28);
-
Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
(Ps. 28);
-
Hak bekerja dan hidup (Ps. 27 ayat (2));
-
Kemerdekaan agama (Ps. 29 ayat (2));
-
Hak untuk ikut mempertahankan negara (Ps. 30), disini
nampak adanya asas perlindungan.
Dengan
adanya Majelis Pertimbangan Pajak, seseorang dapat mengajukan surat bandingnya
untuk hal-hal dimana ia merasa telah diperlakukan tidak sebagaimana mestinya
oleh pejabat perpajakan. Orang dapat menuntut/mengajukan gugatan kepada negara,
bila oleh negara dilakukan suatu perbuatan yang melawan hukum
(onrechtmatigedaad)., bahwa seseorang dapat melakukan gugatan terhadap
Pemerintah Republik Indonesia, jika putusan pejabat yang berwenang dirasa tidak
adil. (Soemitro, 1976. : 25, Sukismo, 2002 (a) : 5, Ashari, 1999 : 6) Sudah
banyak peraturan-peraturan yang memberi jaminan kepada para warga negara, untuk
menggunakan hak-haknya mengajukan tuntutan-tuntutan di muka pengadilan, bila
hak-hak dasarnya atau kebebasannya dilanggar. ( Ashari, 1999 : 25 - 26,
Sukismo, 2002 (a): 6)
Penghormatan,
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, mendapat tempat utama
dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum; sebaliknya dalam
negara totaliliter tidak ada tempat bagi hak-hak asasi manusia. Istilah
"rechisstaat" mulai populer sejak abad XIX, meskipun pemikiran
tentang itu sudah lama adanya. Istilah "the rule of law" mulai
populer tahun 1885. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya,
terdapat perbedaan antara konsep "rechtsstaat" dengan konsep
"the rule of law", pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya
pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, tetapi keduannya tetap
berjalan dengan sistemnya sendiri yaitu sistem hukum sendiri. Konsep "rechtsstaat"
lahir dari suatu perjuangan menentang absulutisme sehingga sifatnya
revolusioner, sebaliknya konsep "the rule of law" berkembang secara
evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria "rechtssataat" dan
kriteria "the rule of law". Konsep "rechtsstaat" bertumpu atas
sistem hukum kontinental yang disebut "civil law" atau "Modern
Roman Law", sedangkan konsep "the rule of law" bertumpu atas
sistem hukum yang disebut "common law". Karakteristik "civil
law" adalah "administratief', sedangkan karakteristik "common
law" adalah "judicial". Perbedaan karakter yang demikian
disebabkan karena latar belakang dari pada kekuasaan raja. Pada zaman Romawi,
kekuasaan yang menonjol dari raja yakni membuat peraturan melalui dekrit.
Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif,
sehingga pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan tertulis bagi
hakim tentang bagaimana menyelesaikan suatu sengketa. Begitu besar peran
administrasi negara, sehingga tidaklah mengherankan, kalau dalam sistem
kontinental-lah mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut "droit
administratif”, dan intinya adalah hubungan antara administrasi negara dengan
rakyat. Sebaliknya di Inggris, kekuasaan utama dari raja adalah memutus
perkara. Peradilan oleh raja kemudian berkembang menjadi suatu peradilan,
sehingga hakim-hakim peradilan adalah delegasi dari raja, tetapi bukan melaksanakan
kehendak raja. Hakim harus memutus perkara berdasarkan kebiasaan umum Inggris
(the common custom of England), sebagaimana dilakukan oleh raja sendiri
sebelumnya. Dengan demikian nampak bahwa di Eropa peranan administrasi negara bertambah besar, sedangkaa di Inggris
peranan peradilan dan para hakim bertambah besar. Sehubungan dengan latar
belakang tersebut, di Eropa dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi
kekuasaan administrasi negara, sedangkan di Inggris dipikirkan langkah-langkah
untuk mewujudkan suatu peradilan yang adil Dalam perjalanan waktu, konsep
"rechtsstaat" telah mengalami perkembangan dari konsep klasik ke
konsep modern. Sesuai dengan sifat dasarnya, konsep klasik disebut
"klasiek liberale en democratische rechtsstaat", yang sering
disingkat dengan "democratische rechtsstaat". Sedangkan konsep modern
lazimnya disebut "sociale rechtsstaat" atau "sociale
democratische rechtsstaat". (Hadjon, 1987 : 71 -74, Sukismo, 2002 (a): 7
Karakternya
yang liberal bertumpu atas pemikiran kenegaraan dari John Locke, Montesquieu
dan Immanuel Kant. Karakternya yang demokratis bertumpu atas pemikiran
kenegaraan dari J.J. Rousseau tentang kontrak sosial. ( Couwenberg. 1977 : 25,
Daryadi, 2001 : 7)
Konsep
liberal bertumpu atas "liberty" (vrijheid) dan konsep demokrasi
bertumpu atas "equality" (gelijkheid). "Liberty" adalah
"the free selfassertion of each-limited only by the like liberty of
all". Atas dasar itu "liberty" merupakan suatu kondisi yang
memungkinkan pelaksanaan kehendak secara bebas dan hanya dibatasi seperlunya,
untuk menjamin koeksistensi yang harmonis antara kehendak bebas individu dengan
kehendak bebas semua yang lain. Dari sinilah mengalir prinsip selanjutnya yaitu
: "freedom from arbitrary and unreasonable exercise of the power and
authority (Pound, 1957 : 1 - 2. Sukismo, 2002 (a) : 8) Konsep "equality"
mengandung makna yang abstrak dan formal (abstract-farmal eguality) dan dari
sini mengalir prinsip "one man-one vote) (Hadjon, 1987 : 75, Sukismo, 2002
(a): 8)
Konsep-konsep
dasar yang sifatnya liberal dari "rechtssataat" meliputi:
- adanya jaminan
atas hak-hak kebebasan sipil (burgelijke vrijheidsrechten);
- pemisahan
antara negara dengan gereja;
- persamaan
terhadap undang-undang (gelijkheid voor de wet);
- adanya konstitusi tertulis sebagai dasar
kekuasaan negara dan dasar
sistem hukum;
sistem hukum;
- pemisahan
kekuasaan berdasarkan trias politica dan sistem "cheks and balances",
- asas legalitas (heerschappij van de
wet);
- ide
tentang aparat pemerintah dan kekuasaan kehakiman yang tidak
memihak dan netral;
memihak dan netral;
- prinsip perlindungan hukum bagi
rakyat terhadap penguasa;
- prinsip
pembagian kekuasaan, baik teritorial sifatnya maupun vertikal
(sistem desentralisasi maupun federasi). (Couwenberg, 1977 : 30,
Sukismo, 2002 (a): 8)
(sistem desentralisasi maupun federasi). (Couwenberg, 1977 : 30,
Sukismo, 2002 (a): 8)
Konsep
dasar demokratis, "rechtsstaat" dikatakan sebagai "negara
kepercayaan timbal balik" (de staat van het wederzijds vertrowen) yaitu
kepercayaan dari pendukungnya, bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan
disalahgunakan, dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya. (Port -
Donner, 1983 :143, Sukismo, 2002 (a): 9)
Rechtsstaat
mendasarkan atas asas-asas demokratis antara lain:
- asas hak-hak politik (het beginsel
van de politieke grondrechten);
- asas mayoritas;
- asas perwakilan;
- asas pertanggung jawaban;
- asas
publik (openbaarheids beginsef). (Couwenberg, 1977 : 30, Sukismo,
2002 (a): 9)
2002 (a): 9)
Ciri-ciri
"rechtsstaat" adalah:
(1). Adanya
Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
(2). Adanya
pembagian kekuasaan negara, yang meliputi : kekuasaan pembuatan undang-undang
yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman bebas yang tidak hanya menangani
sengketa antara individu rakyat, tetapi juga antara rakyat dan penguasa, dan
pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang (wetmatig bestuur);
(3) Diakui
dan dilingunginya hak-hak rakyat yang sering disebut "vrijheidsrechten van
burger". (Port - Donner, 1983 : 143, Karman, 1992:9)
Ciri-ciri
diatas menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral "rechtsstaat"
adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang bertumpu
atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya konstitusi akan memberikan jaminan
konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian
kekuasaan untuk menghindarkan penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, yang
sangat cenderung kepada penyalah gunaan kekuasaan, berarti pemerkosaan terhadap
kebebasan dan persamaan. Dengan adanya pembuatan undang-undang yang dikaitkan
dengan parlemen, dimaksudkan untuk menjamin bahwa hukum yaug dibuat adalah atas
kehendak rakyat; dengan demikian hukum tersebut tidak akan memperkosa hak-hak
rakyat, tetapi dikaitkan dengan asas mayoritas, kehendak rakyat diartikan
sebagai kehendak golongan mayoritas. Dengan prinsip "wetmatig
bestuur" agar tindak pemerintahan tidak memperkosa kebebasan dan persamaan
(heerschappij van de wet). Dalam konsep "rechtsstaat" yang liberal
dan demokratis, inti perlindungan hukum bagi rakyat adalah perlindungan
terhadap kebebasan individu. Setiap tindak pemerintahan yang melanggar
kebebasan individu, melahirkan hak untuk menggugat di muka peradilan. (Hadjon,
1987 : 76 - 77) Sebutan "sociale rechtsstaat" lebih baik dari pada
sebutan "welvaartsstaat". (Verdam, 1976 : 17) "Sociale rechtsstaat"
merupakan variant dari "liberaal-democratische rechtsstaat"(Hadjon,
1987 : 77)
Variant
dari "sociale rechtsstaat" terhadap "liberaal-democratische
rechtsstaat", antara lain : interpretasi baru terhadap hak-hak klasik dan
munculnya serta dominasi hak-hak sosial, konsepsi baru tentang kekuasaan
politik dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, konsepsi baru tentang makna
kepentingan umum, karakter baru dari "wet" dan “wetgeving”(Couwenberg,
1977 ; 33)
Semula
kebebasan dan persamaan (vrijheid en gelijkheid) dalam konsep liberaal-democratische
rechtsstaat sifatnya yuridis formal, dalam konsep sociale rechtsstaat
ditafsirkan secara riil dalam kehidupan masyarakat (reele maatschappelijke
gelijkheid), bahwa tidak terdapat persamaan mutlak di dalam masyarakat antara
individu yang satu dengan yang lain. (Franken, 1983 : 273, Untung, 1991 : 6)
Dalam
"sociale rechtsstaat" prinsip perlindungan hukum terutama diarahkan
kepada perlindungan terhadap hak-hak sosial, hak ekonomi dan hak-hak kultural.
Dikaitkan dengan sifat hak, dalam "rechtsstaat" yang liberal dan
demokratis adalah "the right to do” dalam "sociale rechtsstaat"
muncul "the right to receive". Dikaitkan dengan sarana perlindungan
hukum, maka makin kompleks sistem perlindungan hukum bagi rakyat. (Meuwissen,
1975:140)
Tugas
negara dalam konsep yuridis "sociale rechtsstaat", disamping
melindungi kebebasan sipil juga melindungi gaya hidup rakyat. (Idenberg, 1983
:27)
Pengaruh
negara terhadap individu menjelma dalam tiga cara yakni : pertama, pengaruh
langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
sosial, kedua, pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari pembentukan aparat
pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian, ketiga,
harapan bahwa problema-problema masyarakat dapat dipecahkan melalui campur
tangan penguasa. (Idenberg, 1983 :28 - 29)
Wacana
murni dan sempit mengenai "the rule of law", inti dari tiga
pengertian dasar yang diketengahkan adalah "common law", sebagai
dasar perlindungan bagi kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan oleh
penguasa. Penolakan kehadiran peradilan administrasi negara adalah sesuai
dengan perkembangan hukum dan kenegaraan di Inggris. Inti kekuasaan raja di Inggris
semula adalah kekuasaan memutus perkara, yang kemudian didelegasikan kepada
hakim-hakim peradilan yang memutus perkara tidak atas nama raja, tetapi
berdasarkan "the common custom of England", sehingga karakteristik
dari "common law" adalah "judicial", sedangkan karakteristik
dari "civil law" (kontinental) adalah "administratif ( Hadjon,
1987: 82)
Konsep
"the rule of law" maupun konsep "rechtsstaat" keduanya
menempatkan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai
titik sentralnya, sedangkan bagi negara Republik Indonesia, yang menjadi titik
sentralnya adalah "keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat
berdasarkan asas kerukunan". Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, dalam
konsep "the rule of law" mengedepankan prinsip "equality before
the law", dan dalam konsep "rechtsstaat" mengedepankan prinsip
"wetmatigheid" kemudian menjadi "rechtmatigheid", Untuk
negara Republik Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah
dan rakyat, yang mengedepankan adalah "asas kerukunan" dalam hubungan
antara pemerintah dan rakyat. Dari asas ini .akan berkembang elemen. lain dari
konsep Negara Hukum Pancasila, yakni terjalinnya hubungan fungsional antara
kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan
peradilan merupakan sarana terakhir, dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah
hanya menekankan hak dan kewajiban saja, tetapi juga terjalinnya suatu
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Elemen Negara Hukum Pancasila adalah:
a. Hubungan fungsional yang proporsional
antara kekuasaan-kekuasaan negara;
b. Prinsip penyelesaian sengketa
secara musyawarah dan
peradilan merupakan sarana terahkir;
c. Keseimbangan
antara hak dan kewajiban.
d. Keseimbangan
hubungan antara pemerintahan dan rakyat berdasarkan
asas kerukunan (Hadjon, 1987 : 82 - 90)
asas kerukunan (Hadjon, 1987 : 82 - 90)
3. Asas
Pengambilan Keputusan
Syarat
minimum demokrasi adalah :
-
pada prinsipnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih;
-
setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas
kebebasan
berpendapat dan berkumpul;
berpendapat dan berkumpul;
-
badan perwakilan rakyat mempengaruhi pengambilan
keputusan melalui
sarana"(mede) beslissings recht" (hak untuk ikut memutuskan) dan atau
melalui wewenang pengawas;
sarana"(mede) beslissings recht" (hak untuk ikut memutuskan) dan atau
melalui wewenang pengawas;
-
asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat
keputusan yang
terbuka;
terbuka;
-
pada prinsipnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam
pemilihan
yang bebas dan rahasia
yang bebas dan rahasia
-
pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih.
(Burkens, 1990
: 82, Hadjon, 1999 : 3)
: 82, Hadjon, 1999 : 3)
Tampilnya asas itu sebenarnya berkaitan dengan asas
pengambilan keputusan dalam ketatenegaraan Belanda yaitu asas mayoritas. Dalam ketatanegaraan
kita prinsip utama dalam pengambilan keputusan adalah asas musyawarah untuk
mufakat (Hadjon, 1999 : 3)
4.
Asas Keterbukaan
Rumusan
secara eksplisit tentang asas keterbukaan tidak ditemukan dalam UUD 1945. Namun
demikian isu keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan telah merebak di tanah
air sejak tahun delapan puluhan dan sebagai realisasinya dalam bidang politik
dan sosial pada tahun 1986 wakil Presiden membuka kotak pos 5000. (Soemardjan,
1995 : 56)
Tanpa
keterbukaan tidak mungkin ada peran serta masyarakat. Meskipun segi-segi
keterbukaan telah mulai mendapat perhatian namun belum nampak suatu pengaturan
dasar tentang makna dan prosedur keterbukaan dalam pelaksanaan pembentukan
peraturan perundang-undangan. Demikian juga halnya peran serta. Tidak heran
kalau ada sementara kalangan lebih mengartikan peranserta sebagai bentuk
partisipasi dalam arti gotong royong peran serta secara fisik. Oleh karena
melalui studi perbandingan dengan hukum tata negara dan hukum administrasi
Belanda ditelaah konsep keterbukaan. Studi perbandingan tidaklah dimaksudkan
untuk mengalihkan hukum Belanda ke Indonesia namun lebih-lebih untuk memahami
konsep itu dan mudah-mudahan akan dapat mempertajam, konsep kita sendiri. (Hadjon,
1999:4)
Makna
utama dari keterbukaan, baik "openheid" maupun
"apenbaar-heid" ("openheid" adalah suatu sikap mental
berupa kesediaan untukmemberi informasi dan kesediaan untuk menerima pendapat
pihak lain; "openbaar-heid" menunjukkan suatu keadaan) sangat penting
artinya bagi pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan
demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas
ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak (staatsrehtelijk
beginsel van behoorlijke bevoegdheidsuitoefening). (Haan, 1986 : 122, Hadjon,
1999 : 4) Begitu pentingnya arti keterbukaan sehingga dapat dikatakan bahwa :
"Openbaarheid is licht, geheimbouding isduisternis". (Hadjon, 1999 :
4)
Dalam
kenyataannya kepustakaan hukum dalam bahasa Indonesa masih langka membahas soal
keterbubukaan, meskipun usaha keterbukaan (seperti telah dikemukakan di atas)
telah dikumandangkan sejak beberapa tahun yang lalu. (Hadjon, 1999: 4)
5. Asas
Demokrasi Partisipasi
Dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hukum tata negara dan hukum
administrasi "keterbukaan" merupakan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang bertumpu atas asas demokrasi (partisipasi). Demokrasi
perwakilan sudah lama dirasakan tidak memadai. Pernyataan seperti yang pernah
diucapkan Prof. Mr. R. Boedisoesetio pada pidato inagurasinya sebagai Guru
Besar Luar Biasa Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas
Hukum Universitas Airlangga yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember
1958 kiranya sudah ketinggalan dalam kehidupan demokrasi modern. Dalam pidato
tersebut dikatakan:
Sekali
angguta-angguta itu terpilih dan terbentuk DPR, maka rakjat yang
berdaulat itu tidak mempunjai wewenang lagi untuk menjatakan kemaunnja........(Budisoesetyo, 1958 : 13, Hadjon, 1999 : 5)
berdaulat itu tidak mempunjai wewenang lagi untuk menjatakan kemaunnja........(Budisoesetyo, 1958 : 13, Hadjon, 1999 : 5)
Apabila
wacana itu diikuti maka setelah rakyat memberikan suaranya pada (hari
pemungutan suara), selanjutnya rakyat itu tidak tahu apa-apa lagi tentang
pelaksanaan pemerintahan. Bagi suatu negara demokrasi pelaksanaan pemilihan
umum bukan satu-satunya instrumen demokrasi. Konsep demokrasi dan instrumennya
telah jauh berkembang. (Hadjon, 1999, ibid,: 5)
Pada
dekade tahun enampuluhan-tujuhpuluhan lahirlah suatu konep demokrasi yang
disebut demokrasi partisipasi, (Akkormans, 1985 : 161, Hadjon, 1999 : 6) Dalam
konsep demokrasi partisipasi rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan
(medebeslissingsrecht, dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan
(besluitvormingsproces) (Haan, 1986 : 140, Hadjon, 1999:6)
6. Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik
Sebagai
pelaksanaan asas keterbukaan dalam pemerintahaan di Belanda,mula-mula melalui
asas "fair play" sebagai salah satu dari apa yang disebut
"algemene beginselen van behoorlijk bestuur", yang dalam praktek
Peradilan TUN di Indonesia dewasa ini dikenal dengan nama "Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik" (AAUPB). Dengan lahirnya wet openbaarheid van
bestuur (WOB) yang efektif sejak tanggal 1 Mei 1980 asas "fair play"
dimasukkan dalam wet tersebut. Dalam WOB dibedakan dua macam keterbukaan pemerintahan,
yaitu keterbukaan aktif dilaksanakan atas prakarsa pemerintah sedangkau
keterbukaan pasif atas permintaan warga masyarakat. (Wijk-Konijnenbelt, 1984 :
42, Hadjon. 1999 : 6)
Pada
dasarnya keterbukaan pemerintahan tidak hanya menyangkut informasi. Keterbukaan
meliputi keterbukaan sidang-sidang badan perwakilan rakyat, keterbukaan informasi;
keterbukaan prosedur; keterbukaan register. Dalam WOB Belanda hanya diatur
tentang keterbukaan informasi saja sebagai dasar hubungan antara pemerintahaan
dan rakyat. (Haan, 1986 : 124, Hadjou, 1999:6)
Arti
penting keterbukaan dalam sidang-sidang badan perwakilan rakyat berkaitan
dengan fungsi pengawasan yang dimiliki badan perwakilan rakyat Keterbukaan
dalam pengambilan keputusan-keputusan politik memungkinkan pengawasan dan bagi
pembuat keputusan akan mendorong sikap berhati-hati dalam pengambilan keputusan
(Burkens, 1990 : 94, Hadjon, 1999 : 6-7)
Sebagai
ilustrasi adanya asas keterbukaan antara lain : "Rapat Paripurna, Rapat
Paripurna Luar Biasa, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia
husus pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali apabila rapat yang bersangkutan
atau Badan Musyawarah memutuskan rapat tersebut bersifat tertutup". (Kep.
DPR RI.No.10/DPR-RI/III/82-83, Ps 96 ayat(l))
7. Konsep
Partisipasi Masyarakat
Sesuatu
hal yang dirasa atau dipandang sangat penting ialah adanya saluran bagi rakyat
untuk menyampaikan aspirasinya melalui DPR Ketentuan tentang dengar pendapat
umum, merupakan sarana yang patut dioptimalkan sehingga pembentukan undang-undang
dan perumusan kebijakan lainnya betul-betul mengikutkan masyarakat. (Hadjon,
1999 : 7) Pemerintahan demokratis mengenal adanya keterbukaan informasi yang
dibedakan atas keterbukaan aktif dan pasif berkaitan dengan dokumen-dokumen
pemerintahan. Keterbukaan informasi dimungkinkan dalam batas-batas tertentu
bagi masyarakat untuk mengetahui dokumen-dokumen pemerintah. Fiksi hukum yang
menyatakan bahwa "setiap orang dianggap mengetahui undang-undang"
tidaklah ada artinya apabila undang-undang tidak dipublikasikan secara luas.
(Duk-Loeb-nicolai, 1981 : 157, Hadjon, 1999 : 7)
Cukup
banyak terjadi masyarakat tidak pernah diberi informasi tentang ketentuaa hukum,
karena disatu sisi kita hanya berpegang pada fiksi hukum dan disisi lain
mungkin karena niat untuk memanfaafkan ketidak tahuan masyarakat tentang suatu
aturan hukum. (Hadjon, 1999 : 7-8)
Eksistensi
keterbukaan prosedur berkaitan dengan "besluitvormingsprocedures" dan
salah satu dari "besluit" yang sangat penting adalah
"beschikking" yang dalam UU No. 5 Tahun 1986 disebut keputusan tata
usaha negara. (Hadjon, 1999 : 9) Keterbukaan penting dalam pemerintahan.
Keterbukaan dalam prosedur pemerintahan memungkinkan masyarakat melakukan :
meeweten (ikut mengetahui); meedenken (ikut memikirkan); meespreken (bermusyawarah);
dan meebeslissen (ikut memutuskan dalam rangka pelaksanaan);
medebeslissingsrecht (hak ikut memutus) (Haan, 1986 : 138, Hadjon, 1999 : 8)
Dalam
prosedur pengambilan keputusan pemerintahan baik menyangkut suatu rencana,
kebijakan, pembentukan peraturan perundang-undangan maupuu suatu keputusan tata
usaha negara, (misalnya izin) asas-asas keterbukaan harus dituangkan dalam
prosedur tersebut.
Asas
keterbukaan dalam suatu prosedur izin, pelaksaaaannya dapat berupa:
- tersedianya sarana "meedenken en meespreken"
baik berupa keberatan,
dengar pendapat atau bentuk lain; - pengumuman keputusan izin.
- keterbukaan isi permohonan. (Hadjon, 1999: 8)
Keterbukaan
prosedur izin di Indonesia sesungguhnya telah diatur dalam ketentuan izin
ganguan yang lazimnya dikenal sebagai HO, namun sangat disesalkan. keterbukaan
prosedur begitu saja diabaikan dalam PERMENDAGRI No. 7 tahun 1993 dalam Rangka
Paket Kebijaksanaan Pemerintah 23 Oktober 1993 (PAKTO 1993). Dalam Pasal 7
PERMENDAGRI tersebut sebagai kelengkapan suatu permohonan izin undang-undang
gangguan pada huruf g diisyaratkan : Persetujuan tetangga/atau masyarakat yang
berdekatan.
Ketentuan
dalam Pasal 7 huruf g diatas disatu sisi bertentangan dengan Ordonansi Gangguan
dan disisi lain telah mengabaikan asas keterbukaan pemerintah, yaitu kewajiban
pejabat yang berwenang untuk mengumumkan isi permohonan di lokasi dimana usaha
itu bakal berdiri, telah diganti dengan persetujuan tetangga. Dengan demikian
asas keterbukaan telah digeser oleh asas tetangga, padahal asas keterbukaan
berupa pengumuman isi permohonan tidak hanya untuk tetangga tetapi untuk siapa
saja pihak ketiga yang berkepentingan (bisa juga LSM) untuk mengajukan
keberatan dalam rangka "meeweten-meedenken-meespreken-meebeslissen".
(Hadjon, 1999 : 8-9)
Register
mengenai kedudukan hukum seseorang (misalnya pendaftaran penduduk; peadaftaran
pemilihan umum), pendaftaran benda-benda tidak bergerak serta pendaftaran
bidang usaha disamping sebagai suatu bentuk informasi, pada sisi lain memiliki
sifat sebagai "bestuurswaarborg". (Haan 1986: 137,Hadjon,1999:9)
Keterbukaan
register di Indonesia dikenal antara lain dalam hukum kadaster yaitu
keterbukaan buku tanah. Keterbukaan seperti itu di satu pihak memang memberikan
informasi kepada masyarakat mengenai hak atas tanah yang sudah didaftarkan dan
sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang sudah
didaftarkan itu. (Hadjon, 1999 : 9)
Salah
satu perwujudan asas demokrasi yakni keterbukaan, bahkan merupakan conditio
sine qua non asas demokrasi. Keterbukaan memungkinkan partisipasi masyarakat
secara aktif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. (Hadjon, 1999 : 9)
Asas
keterbukaan dalam rangka pembentukan peraturan perundangan-undangan yang
demokratis, perlu mendapat perhatian, oleh karena demokrasi perwakilan saja
dewasa ini sudah tidak memadai.
Dalam rangka
hubungan antara pemerintah dan rakyat, kiranya keterbukaan merupakan prioritas
pemikiran untuk mendapat perhatian khusus. Kodifikasi hukum administrasi, umum,
khususnya mengenai prosedur pemerintahan seyogyanya perlu mendapat perhatian,
yang membuka peluang kodifikasi administrasi secara bertahap. Kodifikasi yang
demikian punya arti bagi pelaksanaan asas negara hukum untuk mewujudkan asas
kekuasaan berdasarkan atas hukum secara nyata. Dalam mengantisipasi era
globalisasi usaha tersebut perlu mendapat prioritas karena hukumlah yang
mempunyai peran utama dalam lalu lintas ekonomi global. Pembangunan yang hanya
menempatkan posisi hukum sebagai sarana, diragukan kemampuannya untuk
mewujudkan negara Hukum Republik Indonesia yang intinya adalah mewujudkan cita
hukum (rechts idee). (Hadjon, 1999 : 9-10)
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
1. Tipe
Penelitian
Penelitian
ini merupakan kombinasi antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum
normatif. Masing-masing tipe penelitian tersebut digunakan sesuai dengan
kebutuhannya.
Penelitian
hukum empiris dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam (in depth
interviews) dengan para responden dan nara sumber yang berkompeten dan terkait
dengan masalah yang diteliti (obyek yang diteliti), untuk mendapatkan data
primer dan akan dilakukan pula dengan studi kasus.
Penelitian
hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder
dan atau tersier. Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas
masalah-masalah (isu hukum) yang telah dirumuskan, dapat dipergunakan empat
model pendekatan penyelesaian masalah yaitu pendekatan peraturan
perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan
historis (historical approach), yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan.
Semua pendekatan yang disebutkan di atas diterapkan pada lapisan ilmu hukum
dogmatik dan atau lapisan hukum teoritik sebagai berikut:
(1)
Lapisan Dogmatik Hukum
Pada
lapisan ini uraian mengarah dalam bentuk memaparkan, membandingkan,
menginterpretasikan hukum yang berlaku atau hukum positif. Dalam penelitian ini
analisis mengarah pada ada tidaknya partisipasi masyarakat dalam setiap
pembuatan dan evaluasi kebijakan daerah Kota Yogyakarta dan aspiratif tidaknya
produk-produk kebijakan daerah.Kota Yogyakarta pasca UU No. 22 Tahun 1999.
(2) Lapisan
Teori Hukum
Dalam
lapisan ini dianalisis peraturan perundangan yang ada, apakah telah memberikan
pemahaman sepenuhnya atau memberikan penjelasan bila ada perbedaan tentang semua
obyek atau pengertian aturan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam penelitian ini analisis mengarah pada perlu tidaknya masyarakat
dilibatkan dalam setiap pembuatan dan evaluasi kebijakan daerah Kota
Yogyakarta.
Dalam
pendekatan dari sudut pandang teori bukum, dikenal tiga lapisan ilmu hukum,
yang terdiri dari :
1. Dogmatik hukum
D.H.M.
Meuwissen, memberikan batasan pengertian dogmatik hukum sebagai "....
Memaparkan, menganalisis, mensistimatisasi dan menginterpretasikan hukum yang
berlaku atau hukum positif” (Sukismo, 2002 (b): 15, Meuwissen, 1979 : 660).
M.
Van Hoecke memberikan pengertian doghmatika hukura sebagai: "... cabang
ilmu hukum (dalam arti luas) yang memaparkan, mensistematisasi hukum positif
yang berlaku dalam masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu, dari
sudut pandang normatif” (Gijessels, Hoeke, 1982.: 75).
J.J.H. Bruggink
(Sukismo, 2002 (b): 15-16, Bruggink (alih bahasa Arief Sidharta), 1996
:169-170) mengemukakan pendapatnya bahwa :
"Dengan
bertolak dari kenyataan yang ada dalam hukum pada suatu saat tertentu ia
berkenaan dengan suatu masalah tertentu, hendak menawarkan alternatif
penyelesaian yuridisk yang mungkin. Hal itu dengan sendirinya menyebabkan bahwa
dogmatikus hukum bekerja dari sudut perspektif internal. Ia justru menghendaki
sebagai parisipan yang ikut berbicara (peserta aktif secara langsung) dalam
diskusi yuridik mengemukakan wawasannya tehadap hukum positif. Justru keakraban
dengan sistem hukum yang dipelajarinya, menyebabkan (membuat) ia menjadi dogmatikus
yang berarti.”
2. Teori Hukum Dalam Arti Sempit.
Teori
hukum dalam arti sempit, selanjutnya disebut teori hukum, terletak antara
Dogmatika Hukum dan Filsafat Hukum.
M. Van
Hoecke (Gijssels- Hoecke, 1982:
75) mencoba memperjelas dengan perbedaan
dalam jenis-jenis teori hukum dengan menggunakan pengertian meta teori:
"Meta
teori adalah teori yang didalamnya suatu teori lain direnungkan. Jadi, jenis
teori hukum yang satu dapat ditipikasi sebagai meta teori dari dogmatika Hukum,
dan yang lainnya sebagai teori hukum dari hukum positif. Karena dimungkinkan
lagi adanya teori tentang meta teori (yang disebut meta teori), maka rangkaian
ini dapat dilanjutkan tanpa batas.
M.
Van Hoecke menjelaskan lagi bahwa :
"Ikhwalnya
tidaklah demikian. Sampai pada filsafat hukum, yang seperti akan kita lihat merupakan
teori yang fundamental, kita menemukan titik akhir. Filsafat hukum adalah juga
teori yang merefleksikan teorinya sendiri dan tidak memiliki meta teori diatasnya,
maka ia sendiri harus meneliti masalah-masalah berkenaan dengan sifat keilmuan
dan metodologi Filsafat Hukum. Jadi disini filsafat Hukum harus merefleksi diri
(Sukismo, 2002 (b): 17, Bruggink, 1996 : 171).
Hubungan antara
dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum dalam meta teori-meta teori
seperti telah dijelaskan oleh M. Van Hoecke atau dalam perbedaan tataran
analisis seperti yang dilakukan oleh Meuwissen dan selanjutnya dijelaskan oleh
Bruggink (Sukismo, 2002 (b) : 17, Bruggink, 1996 : 175-176) bahwa Filsafat
Hukum adalah meta teori untuk teori hukum. Mengingat bahwa teori hukum, adalah
teori untuk dogmatika Hukum, maka filsafat Hukum adalah meta teori-meta teori
untuk dogmatika hukum. Tetapi dalam penelitian tesis ini penulis hanya
menganalisis pada lapisan Dogmatik Hukum dan Teori Hukum. Penjelasan yang
senada diungkapkan oleh B. Arief Sidharta dalam disertasinya mensitir pendapat
M. Van Hoecke tentang hubungan antara dogmatika hukum, teori hukum dan Filsafat
Hukum dengan menggunakan konsep meta teori yakni ilmu (disiplin) yang obyek
studinya adalah ilmu lain. Berdasarkan konsep ini, teori hukum terdiri dari dua
jenis :
- Meta teori dogmatika hukum yang mempersoalkan ajaran
ilmu (yang membahas landasan kefilsafatan) dan ajaran metode dari
dogmatika hukum.
- Teori tentang hukum positif yang menelaah pengertian
hukum, pengertian-pengertian
dalam hukum, metodologi hukum
yang mencakup metodologi
pembentukan hukum dan
metodologi penerapan hukum. Filsafat hukum adalah meta teori dari
teori hukum dan meta teori dari dogmatika hukum serta teori tentang hukum (refleksi
tentang hakekat hukum dan keadilan). Filsafat hukum sendiri tidak
mempunyai meta teori, karena sebagai filsafat ia merefleksi dirinya
sendiri untuk mempertanggungjawabkan keberadaannya dan menjelaskan makna
karaktemya (Sukismo, 2002 (b) : 13. Sidharta, 1996 : 141-142. Gijjssels -
Hoecke, 1982 : 76,91-95).
Guna
pengembangan hukum teoritis yang dimaksud oleh Meuwissen, Bruggink mengguaakan
istilah "Teori Hukum dalam arti luas" yang didefinisikan sebagai
"keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual
aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, sistem tersebut sebagian
dipositifkan" (Sukismo, 2002(b): 13. Sidharta, 1996 :142. Bruggink, 1996:
4)
Teori
hukum dalam arti luas ini terdiri atas sosiologi hukum, dogmatika hukum, teori
hukum dalam arti sempit, dan filsafat hukum (Sukismo, 2002 (b): 18, Sidharta,
1996 :142). JJ.H. Bruggink menjelaskan bahwa :
"Teori
hukum itu membedakan diri dari dogmatika hukum, karena ia memiliki penentuan
tujuan yang berbeda sekali, yakni semata-mata teoritikal. Masalah-masalah yang
berkenaan dengan hukum yang mungkin ada atau hukum adil atau berkenaan dengan
keadilan dari hukum, yang dalam filsafat sering menempati posisi sentral. Obyek
teori hukum ini mencakup kegiatan yurisdik seperti pengembangan
(rechtbeofening). Dogmatig hukum, pembentukan hukum dan penemuan hukum. Dalam
bidang ini berbagai jenis teori hukum diberi nama juga teori (dari) ilmu hukum,
dan teori penemuan hukum. Objek yang penting pada bagian ini adalah studi
tentang metode yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan yuridisk tersebut".
"Dari
uraian tadi sudah dikemukakan sesuatu tentang penetapan tentang tujuan teori
hukum Penetapan tujuan teoritikalnya membedakan teori hukum dari dokmatika
hukum, yang diarahkan pada praktek hukum. Teoritikus hukum terutama hendak
memberikan pemahaman tentang objek yang dipelajari. Sebab pemahaman ini
berdampak ke dalam praktek hukum. Walaupun teori hukum tidak mempunyai
kepentingan praktikal secara langsung, tetapi teori hukum tetap penting bagi
praktek hukum, karena turut memerankan peranan yang pasti mempertinggi kualitas
praktek hukum (Sukismo, 2002 (b): 18-19, Bruggink, 1996 : 173-175).
Teori
kebenaran yang mengedepan dan relevan berkaitan dengan penelitian tesis ini
adalah teori kebenaran koherensi. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa pada
prinsipnya orientasi penelitian (kajian) tesis ini mengenai keterkaitan antara
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999,
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2001,
atau lebih konkritnya mengenai keterkaitan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan
Undang-undang 25 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 .
Menurut White,
teori kebenaran koherensi diberi makna/arti sebagai :
"...to
say what is said (usually called a judment, belief, or proposition) is true or false is to say that coheres orfails
coheres with a system of other things which are said; that is a member of a
system whose elements are related to each other by ties of logical implication
as the elements in a system of pure mathematics are related" (Sukismo,
2002 (b): 19, Allan, White, 1970 : 15)
Menurut
Kattsoff, teori kebenaran koherensi diberi makna sebagai :
"...
suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling
berhubungan dengan proposisi lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya
dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita"
(Sukismo,
2002 (b) : 19, Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2001 : 139.
Katsoff, 1954, 1986:19).
Bertolak
dari pendapat dari White dan Kattsoff tersebut yang bernada hampir sama,
dapatlah diungkapkan dengan bahasa yang sederhana, bahwa teori kebenaran koherensi
atau teori kebenaran saling berhubungan yaitu suatu proposisi itu atau makna
dari pernyataan dari suatu pengetahuan bernilai benar bila proposisi itu
mempunyai hubungan ide-ide dari proposisi yang terdahulu yang bernilai benar.
Dengan demikian kebenaran dari pengetahuan itu dapat diuji melalui kejadian-kejadian
sejarah, atau juga pembuktian proposisi itu melalui hubungan logis jika pernyataan
yang hendak dibuktikan berkaitan dengan pernyataan-pernyataan logis atau
matematis (Sukismo, 2002 (b): 20, Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat
UGM, 2001:140).
3. Filsafat Hukum
Filsafat
hukum diidentifikasi (diartikan) sebagai induk dari semua disiplin yurisdik,
karena filsafat hukum membahas masalah-masalah yang paling fundamental yang
timbul dalam hukum. Orang mengatakan juga bahwa filsafat hukum berkenaan dengan
masalah-masalah sedemikian fundamental, sehingga bagi manusia tidak
terpecahkan, karena masalah-raasalah itu akan melampaui kemampuan berfikir
manusia. Filsafat hukum akan merupakan kegiatan yang tdak pemah berakhir,
karena mencoba memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan abadi.
Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan terhadapnya hanya dapat diberikan
jawaban, yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan baru. Filsafat hukum dapat
diberikan definisi sebagai teori tentang dasar-dasar dan batas-batas kaidah
hukum (Sukismo, 2002 (b): 20. Bruggink, 1996.: 175).
Penelitian
ini diarahkan untuk dapat melakukan kajian ilmu hukum dalam dua lapisan ilmu
hukum saja, yakni lapisan Dogmatik Hukum dan Teori Hukum. Sehubungan dengan itu
maka objek penelitian yang telah ditetapkan, dipilah-pilahkan menjadi dua
kelompok lapisan, yakni kelompok lapisan Dogmatik Hukum dan kelompok lapisan
teori hukum, kemudian masing-masing kelompok lapisan keilmuan hukum tersebut dilakukan
pengkajian, sesuai dengan karakternya masing-masing, yakni untuk lapisan
Dogmatik hukum dan lapisan Teori Hukum menggunakan metode normatif. Dalam hal
ini, J.J.H. Bruggink menjelaskan bahwa untuk lapisan Dogmatik hukum konsepnya
berupa "technisch juridisch begripen. Eksplanasinya secara teknis yuridis,
sifat keilmuan normatif, untuk lapisan teori Hukum konsepnya berupa
"algemene begripen", eksplanasinya secara analitis, sifat keilmuannya
normatif (dan dapat pula empiris) (Sukismo., 2002 (b): 21. Hadjon, 1994 : 10).
2. Bahan
Penelitian
Bahan
penelitian yang digunakan pada tipe penelitian hukum empiris berupa hasil
wawancara mendalam (in depth interviews) dengan responden maupun narasumber dan
hasil observasi tentang realisasi pembuatan kebijakan daerah Kota Yogyakarta
yang demokratis dalam sistem pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi kolusi
dan nepotisme.
Bahan
penelitian yang digunakaa pada tipe penelitian hukum normatif berupa bahan
hukum, baik bahan hukum primer (primary sources or authorities), maupun bahan
hukum sekunder (secondary sources or authorities) dan diiengkapi dengan bahan hukum
tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang merupakan data
sekunder.
(1) Bahan hukum primer
a). Pancasila
b). UUD45
c) Ketetapan MPR
d) UU No.22 Tahun 1999
e) Peraturan
perundang-undangan dan asas-asas yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat
dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan daerah Kota Yogyakarta serta sistem
pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme..
(2) Bahan
hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer berupa bahan pustaka seperti buku, majalah,
hasil penelitian, makalah dan lainnya yang terkait dengan kebijakan
daerah yang demokratis dan sistem pemerintahan yang bersih bebas dari
korupsi kolusi dan nepotisme..
dengan bahan hukum primer berupa bahan pustaka seperti buku, majalah,
hasil penelitian, makalah dan lainnya yang terkait dengan kebijakan
daerah yang demokratis dan sistem pemerintahan yang bersih bebas dari
korupsi kolusi dan nepotisme..
(3) Bahan
hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan kelengkapan
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
3. Prosedur
pengumpulan bahan penelitian
Bahan
penelitian berupa data yang diperoleh melalui penelitian hukum empiris baik
melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara maupun melalui
observasi, hasil yang terkumpul di narasikan secara komprehensif dan
sistematis.
Bahan-bahan
hukum yang diperoleh melalui penelitian hukum normatif diinventarisasi,
terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan isu sentral dilakukan identifikasi.
Pengumpulan
bahan hukum primer dilakukan dengan mengadakan penelusuran atau penemuan
kembali melalui daftar petunjuk peraturan yang ada ataupun melalui informasi
resmi lainnya ataupun bahan hukum tersier dilakukan dengan mengadakan
penelusuran melalui katalog hukum yang terdapat di perpustakaan.
Langkah
berikutnya adalah meringkas, mengutip dan mengulas bahan hukum yang telah
dikumpulkan itu hasilnya ditulis dengan menggunakan sistem kartu (card system)
yang terdiri dari : kartu ikhtisar, kartu kutipan dan kartu ulasan atau kartu
analisis, kemudian dipilih dan dihimpun sesuai dengan ketentuan hukum dan atau
asas-asas hukum positif yang mendasarinya untuk disusun secara sistematis guna
mempermudah dalam analisis.
4. Pengolahan
dan Analisis Bahan Penelitian
Bahan
penelitian pada penelitian hukum empiris dikumpulkan dengan observasi dan
mewawancarai para responden serta nara sumber khususnya yang berkaitan dengan
permasalahan (obyek penelitian) hasilnya dianalisis secara kualitatif, kemudian
dituangkan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan tentang realisasi
pembuatan kebijakan daerah Kota Yogyakarta yang demokratis dalam sistem
pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.
Bahan
penelitian pada penelitian hukum normatif berupa bahan hukum yang berkaitan
dengan kebijakan daerah yang demokratis, partisipasi masyarakat dan sistem
pemerintahan yang bersih bebas dari KKN, disusun secara sistematis, kemudian di
klasifikasi sesuai pokok bahasan. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut
dilakukan analisis secara normatif, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh
mengenai jawaban atas permasalahan pada lapisan ilmu dogmatik hukum dan teori
hukum, mengenai ada tidaknya partisipasi masyarakat dalam setiap pembuatan dan
evaluasi kebijakan daerah Kota Yogyakarta dalam sistem pemerintahan yang bersih
bebas dari KKN serta aspiratif tidaknya produk-produk kebijakan daerah Kota
Yogyakarta pasca UU No. 22 Tahun 1999.
Berdasarkan
hasil penelitian, baik penelitian hukum empiris maupun penelitian hukum normatif
dapat ditarik kesimpulan dan diajukan saran seperlunya.
5. Pertanggungjawaban
Sistematika Penulisan
Penulisan
hasil penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab, yakni Bab I, Bab II, Bab
III, Bab IV dan Bab V. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi
sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika ini disusun berdasarkan urutan
langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka kegiatan penelitian ini.
Penulisan
bab-bab tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :
Judul: EKSISTENSI
KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS
DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME
BAB I: PENDAHULUAN,
merupakan penjelasan awal yang berisi tentang : latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan hasil penelitian, dengan
demikian diharapkan penelitian ini dapat selalu mengacu dan berjalan sesuai
dengan hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya.
BABII: TINJAUAN
PUSTAKA, merupakan uraian sistematis bahan pustaka yang akan dijadikan kerangka
teori pada tipe penelitian hukum empiris, dan atau akan dijadikan bahan hukum
utama pada tipe penelitian hukum normatif.
BAB III: METODE
PENELITIAN, merupakan uraian tentang tata cara yang ditempuh dalam
melakukan penelitian sebagai
bentuk pertanggungjawaban ilmiah, yang memuat tentang : tipe penelitian,
bahan penelitian, prosedur pengumpulan bahan penelitian, serta pengolahan dan
analisis bahan penelitian.
BAB IV: HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan analisis dan bahasan terhadap bahan
penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung, guna mendapatkan
jawaban atas masalah-masalah yang telah dirumuskan, dipaparkan lebih lanjut
dalam sub-sub bab yakni:
1. Realisasi
Pembuatan Dan Evaluasi Kebijakan Daerah
1.1. Mekanisine
Dan Prosedur Pembuataa Kebijakan Daerah
1.2. Peranserta Masyarakat
Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah
1.3. Eksistensi
Pemerintahan Daerah Yang Bersih Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme
2. Aspirasi Dan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembuatan
Kebijakan Daerah Pasca Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
2.1 Kebijakan Daerah Yang Aspiratif
Kebijakan Daerah Pasca Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
2.1 Kebijakan Daerah Yang Aspiratif
2.2 Kebijakan
Daerah Yang Demokratis
2.3 Keterbukaan
Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah
3. Legalitas Dan
Perlindungan Hukum Dalam
Pembentukan Kebijakan Daerah
3.1 Prinsip
Negara Hukum Dalam Pembentukan Kebijakan
Daerah
Daerah
3.2 Legalitas
Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah
3.3 Perlindungan Hukum
Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah
BAB V: PENUTUP, memuat kesimpulan dan saran
seperlunya
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis
dan pembahasan terhadap bahan penelitian yang dilakukan selama penelitian
berlangsung, baik data dari hasil penelitian hukum empiris maupun bahan hukum
dari hasil penelitian hukum normatif, guna mendapatkan jawaban atas masalah-masalah
yang telah dirumuskan, dipaparkan lebih lanjut dalam sub-sub bab sebagai
berikut:
1. Realisasi
Pembuatan Kebijakan Daerah
1.1 Mekanisme
Dan Prosedur Pembuatan Kebijakan Daerah
Kebijakan
diberikan makna sebagai kumpulan keputusan mengenai:
a. Pedoman pelaksanaan tindakan atau
kegiatan tertentu;
b. Pengaturan mekanisme tindakan untuk
mencapai tujuan dan sasaran;
c. Penciptaan
situasi yang mengarah ke kondisi-kondisi untuk menciptakan
dukungan implementasi (Suwandi, 2001:10).
dukungan implementasi (Suwandi, 2001:10).
Daerah
diberikan makna sebagai propinsi dan atau kabupaten/kota yang otonom, sebagai
pengejawantahan dan atau perwujudan dari amanat UU No. 22 Tahun 1999 tentang
otonomi daerah. Sebagai ilustrasi dalam penelitian ini secara perposif yang
dimaksud daerah adalah pemerintahan kota Yogyakarta pada khususnya dan
pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya. Ilustrasi ini
didasarkan atas pertimbangan bahwa UU No. 22 Tahun 1999 adalah bersifat
nasional, dengan demikian maka pemilihan pemerintahan kota Yogyakarta pada
khususnya dan pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya
sebagai ilustrasi yang diharapkan, dasar hukum pembuatannya, langkah-langkah
yang harus dilaksanakan, sanksi-sanksi tertentu akibat pelanggaran terhadap
materi yang diatur didalamnya, sasaran utamanya (Suhardi; 2002 : 6).
Secara
umum kebijakan daerah yang berupa Kepda dibuat dengan mendasarkan pada amanat
suatu Perda dan atau amanat peraturan perundang-undangan tertentu, bahkan dapat
juga mendasarkan pada ketentuan hukum administrasi tidak tertulis yakni asas
kebebasan bertindak (freies ermessen), yang selama ini banyak dilaksanakan
dalam praktek pemerintahan termasuk didalamnya pemerintahan daerah (Wawancara
dengan staf DPRD).
Pembuatan
kebijakan daerah yang berupa Perda melibatkan Pemerintah Kota dalam ilustrasi
ini Pemerintah Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut Pemkot) dan dewan
Perwakilaa Rakyat Daerah Kota ilustrasi ini DPRD Kota Yogyakarta (selanjutnya
disebut DPRD Kota atau DPRD). Dari hasil observasi dapat dideskripsikan tentang
mekanisme dan prosedur pembuatan kebijakan daerah yang dikemas dalam bentak
Perda.
Walikota
menetapkan Perda atas persetujuan DPRD, sebagai tindak lanjut atas suatu
Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Raperda). Raperda dapat berasal
dari Walikota atau berupa usul dari DPRD. Raperda yang berasal dari Walikota
disampaikan pada Pimpinan DPRD dengan Nota Pengantar Walikota. Raperda yang
berasal dari usul DPRD beserta penjelasannya, disampaikan secara tertulis
kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya Raperda yang diterima oleh Pimpinan DPRD
tersebut, baik yang berasal dari usulan Walikota maupun yang berasal dari usulan
DPRD oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD. Apabila ada dua
atau lebih Raperda yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan
lebih dahulu adalah Raperda yang diterima lebih dahulu, dan Raperda yang
diterima kemudian dipergunakan sebagai pembanding (Tatip DPRD, 1999, Pasal 199,
120, 121).
Pembahasan
Raperda dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila Panitia
Musyawarah menentukan lain. Empat tahapan pembicaraan tersebut meliputi : tahap
pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, kesemuanya dalam Rapat
Paripurna DPRD. Sebelum dilakukan pembicaraan tahap kedua, tahap ketiga, dan
tahap keempat diadakan rapat fraksi terlebih dahulu, Tahapan-tahapan
pembicaraan dalam forum Rapat DPRD berkaitan dengan Raperda, dalam prakteknya
berisi muatan-muatan sebagai berikut:
(1)
Dalam hal Raperda berasal atas usulan Walikota, tahapan-tahapan
pembicaraan selengkapnya yakni tahap pertama berupa penjelasan Walikota dalam Rapat
Paripuma DPRD terhadap Raperda yang diusulkan Walikota, tahap kedua berupa
pemandangan umum dalam Rapat Paripuma DPRD oleh para Anggota yang membawakan
suara fraksinya terhadap Raperda yang diusulkan oleh Walikota, tahap ketiga
berupa jawaban Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD terhadap pemandangan umum
para anggota terhadap Raperda yang berasal dari usulan Walikota, tahap keempat
berupa : laporan hasil pembicaraan Panitia khusus (Pansus), pendapat akhir
fraksi-fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya, penetapan keputusan, pemberian
kesempatan kepada Walikota untuk menyampaikan sambutan
terhadap pengambilan keputusan
tersebut;
(2) Dalam hal
Raperda berasal dari usulan DPRD, tahapan-tahapan pembicaraan selengkapnya
yakni tahap pertama berupa penjelasan Pimpinan Komisi/Pimpinan Rapat Gabungan dalam
Rapat Paripurna DPRD terhadap Raperda yang diusulkan oleh DPRD, tahap kedua
berupa pendapat Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD terhadap Raperda yang
diusulkan oleh DPRD, tahap ketiga berupa jawaban Pimpinan Komisi atau Pimpinan
Rapat Gabungan Komisi atas nama DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD terhadap
pendapat Walikota berkenaan dengan Reperda yang diusulkan DPRD, tahap keempat
berupa : laporan hasil pembicaraan dalam rapat komisi atau gabungan komisi,
pendapat akhir yang disampaikan oleh Walikota, penetapan keputusan, pemberian
kesempatan kepada Walikota untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan
keputusan tersebut. Pembicaraan- Pembicaraan yeng bertahap tersebut, baik
Raperda atas usulan Walikota maupun atas usulan DPRD, sebelum pembicaraan tahap
keempat, maka didahului dengan Rapat Panitia Khusus yang dilakukan bersama-sama
dengan pejabat yang ditunjuk Walikota (wawancara dengan staf Setwan DPRD Kota
Yogyakarta, Tatip DPRD, 1999, Pasal 122,123, l24, 125,126).
Pembicaraan-
pembicaraan secara bertahap dalam forum rapat DPRD tersebut, baik mengenai
Raperda atas usulan Walikota maupun atas usulan DPRD, sebelum memasuki
pembicaraan tahap keempat, didahului dengan rapat Panitia Khusus (Pansus) yang
dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk Walikota (Wawancara dengan
staf Setwan DPRD Kota-Yogyakarta, Tatip DPRD, 1999, Pasal 127).
Prosedur
pembuatan Raperda dapat dibedakan antara Raperda yang dibuat Pemerintah Kota
maupun Raperda yang dibuat oleh DPRD, yakni sebagai berikut:
(1) Raperda
yang dibuat oleh Pemerintah Kota dilakukan dengan tiga model,
yakni pertama sistem top down artinya Raperda tersebut disusun atas dasar
ide-ide dan atau niatan-niatan politik jajaran pemerintahan kota dari
jajaran paling atas sampai jajaran yang paling bawah, kedua dengan sistem
bottom up artinya Raperda tersebut disusun atas ide-ide dan atau niatan-
niatan politik jajaran pemerintah daerah dari yang bawah secara
hierarkhies sampai yang paling atas, ketiga dengan sistem kombinasi
antara top down dan bottom up, artinya memadukan dan mensinergikan
antara sistem top down dan bottom up dengan memanfaatkan secara
optimal segi-segi positif dan mengeliminir sedemikian rupa segi-segi negatif dari masing-masing sistem tersebut, untuk kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan Raperda oleh Pemerintah Kota;
yakni pertama sistem top down artinya Raperda tersebut disusun atas dasar
ide-ide dan atau niatan-niatan politik jajaran pemerintahan kota dari
jajaran paling atas sampai jajaran yang paling bawah, kedua dengan sistem
bottom up artinya Raperda tersebut disusun atas ide-ide dan atau niatan-
niatan politik jajaran pemerintah daerah dari yang bawah secara
hierarkhies sampai yang paling atas, ketiga dengan sistem kombinasi
antara top down dan bottom up, artinya memadukan dan mensinergikan
antara sistem top down dan bottom up dengan memanfaatkan secara
optimal segi-segi positif dan mengeliminir sedemikian rupa segi-segi negatif dari masing-masing sistem tersebut, untuk kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan Raperda oleh Pemerintah Kota;
(2) Raperda yang dibuat oleh DPRD,
prosedumya sebagai berikut:
a sekurang-kurangnya
3 (tiga) orang Anggota DPRD yang tidak hanya
terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa
pengaturan sesuatu urusan Daerah;
terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa
pengaturan sesuatu urusan Daerah;
b. Usul
prakarsa pengaturan sesuatu urusan Daerah tersebut, disampaikan kepada Pimpinan
DPRD dalam bentuk Raperda disertai dengan
penjelasan secara tertulis;
penjelasan secara tertulis;
c. Usul
prakarsa pengaturan sesuatu urusan Daerah tersebut diberi nomor
pokok oleh Sekretariat DPRD;
pokok oleh Sekretariat DPRD;
d. Usul prakarsa
pengaturan sesuatu urusan Daerah
tersebut oleh
Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah
mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah;
Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah
mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah;
e. Dalam
Rapat Paripurna DPRD, Anggota DPRD yang mengusulkan
diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa
pengaturan sesuatu urusan Daerah tersebut;
diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa
pengaturan sesuatu urusan Daerah tersebut;
f. Pembicaraan
mengenai sesuatu usul prakarsa pengaturan sesuatu
urusan Daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
f.a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
urusan Daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
f.a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
f.b. Walikota untuk memberikan pendapat;
f.c. Anggota
DPRD yang mengusulkan, memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD lainnya
dan pendapat Walikota.
g. Pembicaraan
diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa pengaturan sesuatu urusan Daerah dari Anggota-Anggota DPRD tersebut
menjadi prakarsa DPRD;
h. Tatacara pembahasan
Raperda atas prakarsa
DPRD mengikuti ketentuan yang
berlaku dalam pembahasan Raperda;
i. Selama usul prakarsa pengaturan sesuatu urusan
Daerah belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan
atau mencabutnya kembali (Wawancara dengan staf Setwan DPRD; Tatp DPRD, 1999,
Pasal 14).
Dari
paparan tersebut dapatlah diketahui antara lain :
a.
Setiap kebijakan daerah harus dibuat dalam bentuk kemasan
hukum baik berupa Kepda maupun Perda
b.
Setiap Kebijakan daerah yang dibuat oleh pemerintah
daerah melalui Kepala Daerah dalam bentuk Kepda harus dapat
dipertanggungjawabkan setiap saat
c.
Setiap kebijakan daerah yang dibuat dalam bentuk Perda,
Raperdanya datang (berasal) dari Pemerintah Daerah maupun dari DPRD
1.2.
Peran serta
Masyarakat Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah
Suatu
kebijakan daerah yang merupakan kumpulan keputusan mengenai : pedoman
pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu: Pengaturan mekanisme tindakan
untuk mencapai tujuan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara
merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara
Negara yang bersih. Hubungan antara Penyelenggara Negara dan Masyarakat
dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara
yang meliputi : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas
akuntabilitas (wawancara dengan Staf Setwan DPRD, UU No. 28/1999, pasal 8).
Makna
asas-asas umum penyelenggaraan negara tersebut, masing-masing adalah:
a. Asas kepastian
hukum yakni asas dalam
negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
Penyelengara Negara;
b. Asas
tertib penyelenggaraan negara yakni asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian
Penyelenggara Negara;
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian
Penyelenggara Negara;
c. Asas
kepentingan umum yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara
yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
d. Asas
keterbukaan yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, serta tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara;
e. Asas
proporsionalitas yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antar hak dan
kewajiban Penyelengaraan Negara;
f. Asas profesionalitas yakni
asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Asas
akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (wawancara dengan Staf Setwan DPRD, UU No. 28/1999,
Penjelasan Pasal 3).
hasil akhir dari Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (wawancara dengan Staf Setwan DPRD, UU No. 28/1999,
Penjelasan Pasal 3).
Peluang
dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan, dan evaluasi atas kebijakan daerah,
termasuk didalamnya kebijakan daerah di kota Yogyakarta cukup besar dan.
strategis. Hal tersebut pada hakekatnya telah diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, antara lain dalam:
a. UU NO. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah
b. PP
No. 20 Tahun 2001 teatang Pembinaan dan
Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kepmendagri No. 41 Tahun
2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kepmendagri No. 41 Tahun
2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah
c. UU No. 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang
bersih dan Bebas dari KKN.
bersih dan Bebas dari KKN.
Secara
garis besar, amanat bagi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap sesuatu
kebijakan daerah dapat disistematisir sebagai berikut :
a. Setiap
pembuatan kebijakan daerah yang baru, baik berupa keputusan
kepala daerah maupun peraturan daerah, senantiasa wajib melibatkan
masyarakat daerah untuk berpartisipasi;
kepala daerah maupun peraturan daerah, senantiasa wajib melibatkan
masyarakat daerah untuk berpartisipasi;
b. Setiap
kebijakan daerah yang baru, yang tidak melibatkan masyarakat
daerah dapat menyebabkan kebijakan daerah tersebut dibatalkan oleh
pemerintah atasan;
daerah dapat menyebabkan kebijakan daerah tersebut dibatalkan oleh
pemerintah atasan;
c. Masyarakat
berhak untuk mengkritisi dan mengevaluasi atas sesuatu
kebijakan daerah yang telah ada, dan apabila dipandang perlu dapat
mengajukan usul agar kebijakan daerah yang dinilai oleh masyarakat tidak
sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tuntutan keadaan / zaman,
ditinjau kembali dan apabila perlu dapat diusulkan untuk dicabut;
kebijakan daerah yang telah ada, dan apabila dipandang perlu dapat
mengajukan usul agar kebijakan daerah yang dinilai oleh masyarakat tidak
sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tuntutan keadaan / zaman,
ditinjau kembali dan apabila perlu dapat diusulkan untuk dicabut;
d. DPRD mempunyai
tugas dan wewenang
untuk menampung dan
menindaklanjuti aspirasi daerah dan aspirasi masyarakat;
menindaklanjuti aspirasi daerah dan aspirasi masyarakat;
e. Masyarakat mempunyai
hak untuk mencari,
memperoleh, dan
memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara (termasuk
penyelenggaraan pemerintahan daerah), serta menyampaikan saran dan
pendapat terhadap kebijakan penyelenggaraan negara (termasuk
penyelenggaraan pemerintahan daerah). (Prasetyo, 2002 :3)
memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara (termasuk
penyelenggaraan pemerintahan daerah), serta menyampaikan saran dan
pendapat terhadap kebijakan penyelenggaraan negara (termasuk
penyelenggaraan pemerintahan daerah). (Prasetyo, 2002 :3)
Tantangan
yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan evaluasi
kebijakan daerah di kota Yogyakarta, antara lain karena (Pasetyo, 2002 : 3-4):
a. Berbagai
peraturan perundangan yang berkaitan erat dengan pembuatan dan evaluasi
kebijakan daerah, tidak mengatur mekanisme partisipasi masyarakat secara rinci
dan tegas. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:
- UU NO. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;
- PP No.
20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kepmendagri No. 41
Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kepmendagri No. 41
Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
- UU No.
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang bersih dan Bebas dari
KKN;
- PP No. 1
Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
DPRD;
DPRD;
- Keppres
No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan
RUU;
RUU;
- Keppres
No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan
Bentuk RUU, R Keppres, Raperda dan Rancangan Keputusan Kepala Daerah;
- Kepmendagri
dan Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah;
- Keputusan
DPRD Kota Yogyakarta No. 3 / K/ DPRD / 1999
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
b. Belum
seluruh komponen masyarakat yang ada memahami akan hak dan kewajibannya, untuk
berpartisipasi dalam pembuatan dan evaluasi atas sesuatu kebijakan daerah di
kota Yogyakarta
Suatu
sikap dan langkah yang telah ditempuh oleh DPRD menyelenggarakan public hearing
perlu diberikan penghargaan. Public Hearing ini dimaksudkan, untuk mendapatkan
masukan dari masyarakat, guna membahas tentang sesuatu kebijakan daerah. Namun
disayangkan langkah ini belum seluruhnya tepat, mengingat sifatnya sangat
parsial, tidak menentu, dan sangat terbatas. Sebagai konsekuensinya banyak
kebijakan daerah, baik oleh DPRD maupun eksekutif ternyata bermasalah, karena
tidak dapat diikuti oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka hadirnya
peraturan daerah di kota Yogyakarta, tentang mekanisme pembuatan dan evaluasi
kebijakan daerah, yang dapat mengakomodir partisipasi masyarakat secara memadai
dari komprehensif sangat didambakan oleh banyak kalangan masyarakat. (Prasetyo,
2002 :4-5)
Urgensi
Perda tentang mekanisme partisipasi masyarakat, yakni berupaya untuk
mensistematisasi secara komprehensif dan terpadu, mekanisme pembuatan dan
evaluasi kebijakan daerah dalam satu ketentuan. Nantinya diharapkan bahwa semua
proses pembuatan dan evaluasi suatu kebijakan daerah mengacu pada satu sumber
saja, sebagai konsekuensinya DPRD maupun eksekutif daerah wajib mengikuti dan
melaksanakan peraturan daerah tersebut. (Suhardi, 2002 : 4)
Perda
tentang mekanisme partisipasi masyarakat tersebut, diharapkan dapat memuat
substansi yang penting antara lain (Suhardi, 2002 : 4-5):
a. Hak
partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan daerah yang
baru maupun usulan pencabutan kebijakan daerah yang sudah tidak
relevan lagi;
baru maupun usulan pencabutan kebijakan daerah yang sudah tidak
relevan lagi;
b. Meletakkan
kewajiban kepada DPRD maupun eksekutif daerah untuk
menampung dan menindaklanjuti usulan masyarakat;
menampung dan menindaklanjuti usulan masyarakat;
c. Partisipasi masyarakat dalam pembahasan naskah akademik
dan
Raperda;
Raperda;
d. Sosialisasi
rencana penyusunan dan pembahasan kebijakan daerah
kepada publik.
kepada publik.
Dengan
demikian partisipasi masyarakat tersebut pada dasamya meliputi seluruh proses
yang relevan dalain pembuatan sesuatu kebijakan daerah. Dalam hal ini
masyarakat diposisikan sebagai subyek pembuatan kebijakan daerah, sejajar
dengan eksekutif dan legislatif dan bukan sekedar simbol legitimasi legislatif
dan eksekutif saja.
Sampai
saat ini Perda tentang Mekanisine Partisipasi Masyarakat yang ditunggu-tunggu
dan sangat didambakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta belum muncul. Namun
perkembangan terakhir cukup menggembirakan, karena jajaran pemerintahan Kota
Yogyakarta sudah mulai menaruh perhatian yang serius mengenai arti pentingnya
peran serta masyarakat terhadap kuantitas dah kualitas produk-produk hukum
jajaran pemerintahan daerah Kota Yogyakarta, yang memuat kebijakan-kebijakan
daerah Kota Yogyakarta, yakni memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara mengajukan usul, saran, pendapat,
tanggapan atas sesuatu kebijakan Pemda Kota Yogyakarta secara kritis dan
konstruktif melalui email, hotline yang khusus diadakan untuk kepentingan
partisipasi masyarakat tersebut (Observasi). Dengan demikian dapat diketahui
bahwa :
a. Perda
tentang Mekanisme Partisipasi Masyarakat untuk mengkritisi
kebijakan-kebijakan jajaran Pemda Kota Yogyakarta sampai saat ini
belum eksis;
kebijakan-kebijakan jajaran Pemda Kota Yogyakarta sampai saat ini
belum eksis;
b. Telah ada
kesadaran jajaran Pemda Kota Yogyakarta yang layak
mendapatkan penghargaan, karena telah merintis dan membuka jalan
dapat dilakukannya partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi secara
kritis dan konstruktif melalui email dan hot line;
mendapatkan penghargaan, karena telah merintis dan membuka jalan
dapat dilakukannya partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi secara
kritis dan konstruktif melalui email dan hot line;
c. Eksistensi
peran serta masyarakat cukup strategis untuk mengukur dan
mengevaluasi kuantitas dan kualitas kebijakan-kebijakan yang
ditempuh jajaran Pemda Kota Yogyakarta (legislatif dan eksekutif)
mengevaluasi kuantitas dan kualitas kebijakan-kebijakan yang
ditempuh jajaran Pemda Kota Yogyakarta (legislatif dan eksekutif)
1.3 Eksistensi Pemerintahan Daerah Yang
Bcrsih Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme
Dalam
sistem negara kesatuan, eksistensi pemerintahan daerah merupakan sub sistem
dalam sistem pemerintahan nasional. Dengan demikian pemerintahan daerah merupakan
bagian yang tak terpisahkan dengaa pemerintahan pusat, oleh karenanya prinsip
dan paradigma pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
yang berlaku terhadap pemerintahan nasional, juga berlaku terhadap pemerintahan
daerah pada hakekatnya juga merupakan penyelenggaraan negara, penyelenggara
daerah (DPRD dan Eksekutif Daerah) juga merupakan penyelenggara negara
(Suprapto, 2002:7)
Penyelenggara
daerah dan atau penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan
dalam penyelenggaraan daerah atau penyelenggaraan negara untuk mencapai
cita-cita bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana
tercantum dalam UUD 1945 (Sukismo, 2002 : 11).
Untuk
mewujudkan penyelenggara daerah dan atau penyelenggara negara yang mampu
menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung
jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan daerah (Subardi, 2001 : 12).
Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar penyelenggara
negara dan atau antar penyelenggara daerah melainkan juga antar penyelenggara
negara dan atau antar penyelenggara daerah dengan pihak lain yang dapat merusak
sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, sehingga untuk itu
diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya (Santoso, 2001:17).
Dari
berbagai paparan tersebut dapatlah diketahui bahwa:
a. Eksistensi
pemerintahan daerah merupakan sub sistem pemerintahan
nasional;
nasional;
b. Tuntutan
dan tantangan untuk terselenggaranya pemerintahan nasional
yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme berlaku dan relevan
pula bagi pemerintahan daerah;
yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme berlaku dan relevan
pula bagi pemerintahan daerah;
c. Indikasi
terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya
dalam jajaran pemerintahan pusat, melainkan juga dalam jajaran pemerintahan daerah.
dalam jajaran pemerintahan pusat, melainkan juga dalam jajaran pemerintahan daerah.
Penyelenggara
negara, termasuk didalamnya penyelenggara daerah adalah penyelenggara negara
dan atau penyelenggara daerah yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan
negara dan atau daerah dan terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
serta perbuatan tercela lainnya (Bardo, 2001 : 5).
Korupsi
adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan pidana (Suyudi, 2001 : 9).
Kolusi
adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara
negara termasuk didalamnya penyelenggara daerah atau antara penyelenggara
negara termasuk didalamnya penyelenggara daerah dengan pihak lain yang
merugikan orang lain, masyarakat, negara dan atau daerah (Suryanto, 2002 : 11):
Nepotisme
adalah setiap perbuatan penyelenggara negara termasuk didalamnya penyelenggara
daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau
kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan atau daerah (Badri,
2001:6).
Asas
umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang
menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk
mewujudkan penyelenggara negara termasuk didalamnya penyelenggara
daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Badrun,
2002:5).
menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk
mewujudkan penyelenggara negara termasuk didalamnya penyelenggara
daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Badrun,
2002:5).
Dari
berbagai uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa :
a. Penyelenggara daerah merupakan sub
sistem penyelenggara negara;
b. Asas-asas umum
penyelenggaraan negara berlaku
juga terhadap
penyelenggaraan daerah;
penyelenggaraan daerah;
c. Indikasi
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya terjadi dalam jajaran
pemerintahan nasional semata, melainkan dapat pula terjadi dalam
jajaran pemerintahan daerah;
jajaran pemerintahan daerah;
d. Harapan
untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme berlaku pula terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme berlaku pula terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
e. Penyelenggara daerah meliputi eksekutif
daerah dan legislatif daerah.
2. Aspirasi Dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembuatan Kebijakan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
2.1 Kebijakan
Daerah Yang Aspiratif
Peran
serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk didalamnya
penyelenggaraan daerah, merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut
mewujudkan penyelenggara negara termasuk didalamnya penyelenggara daerah yang
bersih. Hubungan antar penyelenggara negara termasuk didalamnya penyelenggara
daerah dengan masyarakat, dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas
umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas : kepastian hukum, tertib
penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,
profesionalitas dan akuntabilitas (Supriyadi, 2002 : 8).
Peran
serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:
a. Hak mencari,
memperoleh, dan memberikan
informasi tentang
penyelenggaraan negara, termasuk didalamnya penyelenggaraan
daerah;
penyelenggaraan negara, termasuk didalamnya penyelenggaraan
daerah;
b. Hak untuk
memperoleh pelayanan yang
sama dan adil
dari
penyelenggara negara dan atau dari penyelenggara daerah;
penyelenggara negara dan atau dari penyelenggara daerah;
c. Hak
menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab
terhadap kebijakan penyelenggara negara dari atau terhadap kebijakan
penyelenggara daerah;
terhadap kebijakan penyelenggara negara dari atau terhadap kebijakan
penyelenggara daerah;
d. Hak
memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan
laiknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut;
demikian pula dalam hal diminta hadir dalara proses penyelidikan,
penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan
saksi ahli, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak-hak masyarakat untuk berperan serta terhadap kebijakan-
kebijakan negara dan atau kebijakan-kebijakan daerah tersebut,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial
lainnya (Sugiri, 2002 : 6).
laiknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut;
demikian pula dalam hal diminta hadir dalara proses penyelidikan,
penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan
saksi ahli, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak-hak masyarakat untuk berperan serta terhadap kebijakan-
kebijakan negara dan atau kebijakan-kebijakan daerah tersebut,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial
lainnya (Sugiri, 2002 : 6).
Maksud
dan tujuan digalakkannya peran serta masyarakat dalam pembentukan dan evaluasi
kebijakan daerah, adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan daerah yang bersih. bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih
bergairah melaksanakan penyelenggaraan daerah dengan tetap mentaati rambu-rambu
yang berlaku (Badrun, 2002 : 9).
Peran
serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan
penyelenggara negara atau penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum,
moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya masyarakat
mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara atau
penyelenggaraan daerah, namun hak tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memberikan batasan-batasan
untuk masalah-masalah tertentu dijamin kerahasiaannya (Sunarto, 2002 : 11).
Dari
berbagai uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa :
a. Setiap kebijakan daerah senantiasa
harus aspiratif;
b. Setiap
pembuatan kebijakan daerah harus memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat
untuk berpartisipasi;
c. Partisipasi
masyarakat mempunyai andil atau kontribusi yang cukup
signifikan untuk mencegah dan mengeliminir terjadinya praktek
korupsi, kolusi dan neopotisme dalam pembentukan kebijakan-
kebijakan daerah.
signifikan untuk mencegah dan mengeliminir terjadinya praktek
korupsi, kolusi dan neopotisme dalam pembentukan kebijakan-
kebijakan daerah.
Suatu
hal yang dirasa atau dipandang sangat penting ialah adanya saluran bagi rakyat
untuk menyampaikan aspirasinya melalui DPR atau DPRD. Ketentuan tentang dengar
pendapat umum, merupakan sarana yang patut dioptimalkan, sehingga pembentukan
peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan-kebijakan daerahnya betul-betul
mengikut sertakan masyarakat (Hadjon, 1999 : 7).
Dengan
demikian dapat diketahui bahwa untuk pembentukan kebijakan daerah yang baik
rakyat perlu diberikan akses untuk menyalurkan aspirasinya secara baik, lancar
dan transparan melalui wakil-wakil rakyat di DPR maupun DPRD setempat.
2.2 Kebijakan
Daerah Yang Demokratis
Legitimasi
rakyat terhadap kebijakan-kebijakan daerah merupakan prasyarat terealisirnya demokratisasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan daerah dapat dikategorikan
demokratis apabila penyusunan dan penetapannya telah mendapatkan dukungan
rakyat daerah secara proporsional dan komprehensif. Keterlibatan rakyat daerah
dalam berpartisipasi terhadap rencana pembentukan dan pelaksanaan kebijakan
daerah, akan memberikan nilai tambah tersendiri terhadap kuantitas dan kualitas
kebijakan daerah yang bersangkutan (Badri, 2001 : 8).
Syarat
minimum demokrasi adalah :
- pada prinsipnya setiap orang
mempunyai hak untuk dipilih;
- setiap
orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan
berpendapat dan berkumpul
berpendapat dan berkumpul
- badan perwakilan
rakyat mempengaruhi pengambilan keputusan
melalui sarana" (mede) beslissings recht" (hak untuk ikut
memutuskan) dan atau melalui wewenang pengawas;
melalui sarana" (mede) beslissings recht" (hak untuk ikut
memutuskan) dan atau melalui wewenang pengawas;
- asas
keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan
yang terbuka;
yang terbuka;
- pada
prinsipnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam
pemilihan yang bebas dan rahasia
pemilihan yang bebas dan rahasia
- pada
dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih. (Burkens,
1990 : 82, Hadjon, 1999 : 3)
1990 : 82, Hadjon, 1999 : 3)
Tampilnya
asas itu sebenamya berkaitan dengan asas pengambilan keputusan datam
ketatanegaraan Belanda yaitu asas mayoritas. Dalam ketatanegaraan kita prinsip
utama dalam pengambilan keputusan adalah asas musyawarah untuk mufakat. (Hadjon,
1999 : 3)
Dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hukum tata negara dan hukum
administrasi "keterbukaan" merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan
yang bertumpu atas asas demokrasi (partisipasi). Demokrasi perwakilan sudah
lama dirasakan tidak memadai. Pernyataan seperti yang pernah diucapkan Prof.
Mr. R. Boedisoesetio pada pidato inagurasinya sebagai Guru Besar Luar Biasa
Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas
Airlangga yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 1958 kiranya sudah
ketinggalan dalam kehidupan demokrasi modern. Dalam pidato tersebut dikatakan:
Sekali
angguta-angguta itu terpilih dan terbentuk DPR, maka
rakjat yang berdaulat itu tidak mempunjai wewenang lagi untuk
menjatakan kemaunnja....... (Budisoesetyo, 1958 :13, Hadjon, 1999 : 5)
rakjat yang berdaulat itu tidak mempunjai wewenang lagi untuk
menjatakan kemaunnja....... (Budisoesetyo, 1958 :13, Hadjon, 1999 : 5)
Apabila
wacana itu diikuti maka setelah rakyat memberikan suaranya pada (hari
pemungutan suara), selanjutnya rakyat itu tidak tahu apa-apa lagi tentang
pelaksanaan pemerintahan. Bagi suatu negara demokrasi pelaksanaan pemilihan
umum bukan satu-satunya instrumen demokrasi. Konsep demokrasi dan instrumennya
telah jauh berkembang. (Hadjon, 1999, ibid,: 5)
Pada
dekade tahun enampuluhan-tujuhpuluhan lahirlah suatu konsep demokrasi yang
disebut demokrasi partisipasi. (Akkormans, 1985 : 161, Hadjon, 1999 : 6) Dalam
konsep demokrasi partisipasi rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan
(medebeslissingsrecht, dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan (besluitvormingsproces)
(Haan, 1986 : 140, Hadjon, 1999 : 6)
Dari
berbagai uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa :
a. Setiap
kebijakan daerah memerlukan dukungan dan legitimasi rakyat
daerah setempat;
daerah setempat;
b. Legitimasi
dan dukungan rakyat daerah terhadap kuantitas dan kualitas
kebijakan daerah dapat terealisir apabila rakyat daerah diberikan ruang
dan kesempatan yang cukup untuk ikut memutuskan
(medebeslissingsrecht), dalam proses pengambilan keputusan
pemerintahan (besluitvormingsproces) dalam rangka pembentukan
kebijakan daerah;
kebijakan daerah dapat terealisir apabila rakyat daerah diberikan ruang
dan kesempatan yang cukup untuk ikut memutuskan
(medebeslissingsrecht), dalam proses pengambilan keputusan
pemerintahan (besluitvormingsproces) dalam rangka pembentukan
kebijakan daerah;
c. Ciri
demokrasi modern tidak cukup diwakili oleh DPR atau DPRD saja
melainkan harus melibatkan rakyat daerah secara proporsional dan komprehensif dalam persiapan, perencanaan, dan implementasi kebijakan daerah yang bersangkutan.
melainkan harus melibatkan rakyat daerah secara proporsional dan komprehensif dalam persiapan, perencanaan, dan implementasi kebijakan daerah yang bersangkutan.
2.3 Keterbukaan
Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah
Kebijakan
daerah dapat berdampak positif maupun negatif terhadap rakyat daerah maupun
terhadap daerah otonom yang bersangkutan. Dampak positif dari suatu kebijakan
daerah tidak relevan untuk diperdebatkan, karena hal tersebut merupakan suatu
kewajiban bagi penyelenggara daerah (eksekutif dan DPRD) untuk mewujudkan
kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi daerah dan rakyat daerah yang
bersangkutan. Yang relevan untuk dikaji dan diantisipasi adalah kemungkinan
timbulnya dampak negatif atas sesuatu kebijakan daerah terhadap daerah dan
rakyat daerahnya. Dalam rangka mengantisipasi dan mengeliminir timbulnya dampak
negatif atas sesuatu kebijakan daerah, dipandang perlu, untuk mengadopsi dan mengimplimentasikan
asas keterbukaan dalam setiap perencanaan, pembentukan dan pelaksanaan sesuatu
kebijakan daerah (Sarosa, 2001: 12).
Rumusan
secara eksplisit tentang asas keterbukaan tidak ditemukan dalam UUD 1945. Namun
demikian isu keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan telah merebak di tanah
air sejak tahun delapan puluhan dan sebagai realisasinya dalam bidang politik
dan sosial pada tahun 1986 wakil Presiden membuka kotak pos 5000. (Soemardjan,
1995 : 56)
Tanpa
keterbukaan tidak mungkin ada peran serta masyarakat. Meskipun segi-segi
keterbukaan telah mulai mendapat perhatian namun belum nampak suatu pengaturan
dasar tentang makna dan prosedur keterbukaan dalam pelaksanaan pembentukan
peraturan perundang-undangan. Demikian juga halnya peran serta. Tidak heran
kalau ada sementara kalangan lebih mengartikan peranserta sebagai bentuk
partisipasi dalam arti gotong royong peran serta secara fisik. Oleh karena
melalui studi perbandingan dengan hukum tata negara dan hukum administrasi
Belanda ditelaah konsep keterbukaan. Studi perbandingan tidaklah dimaksudkan untuk
mengalihkan hukum Belanda ke Indonesia namun lebih-lebih untuk memahami konsep
itu dan mudah-mudahan akan dapat mempertajam, konsep kita sendiri. (Hadjon,
1999 : 4)
Makna
utama dari keterbukaan, baik "openheid" maupun “apenbaar-heid”
("openheid" adalah suatu sikap mental berupa kesediaan untuk memberi
informasi dan kesediaan untuk menerima pendapat pihak lain;
"openbaar-heid" menunjukkan suatu keadaan) sangat penting artinya
bagi pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan
demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas
ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak (staatsrehielijk
beginsel van behoorlijke bevosgdheidsuitoefening). (Haan, 1986 : 122, Hadjon,
1999 : 4) Begitu pentingnya arti keterbukaan sehingga dapat dikatakan bahwa :
"Openbaarheid is licht, geheimbouding is duisternis". (Hadjon, 1999 :
4)
Dalam
kenyataannya kepustakaan hukum dalam bahasa Indonesa masih langka membahas soal
keterbukaan, meskipun usaha keterbukaan (seperti telah dikemukakan di atas)
telah dikumandangkan sejak beberapa tahun yang lalu. (Hadjon, 1999 : 4)
Sebagai
pelaksanaan asas keterbukaan dalam pemerintahaan di Belanda,mula-mula melalui
asas "fair play" sebagai salah satu dari apa yang disebut
"algemene beginselen van behoorlijk bestuur", yang dalam praktek
Peradilan TUN di Indonesia dewasa ini dikenal dengan nama "Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik" (AAUPB). Dengan lahirnya wet openbaarheid van
bestuur (WOB) yang efektif sejak tanggal 1 Mei 1980 asas "fair play"
dimasukkan dalam wet tersebut. Dalam WOB dibedakan dua macam keterbukaan
pemerintahan, yaitu keterbukaan aktif
dilaksanakan atas prakarsa pemerintah sedangkan keterbukaan pasif atas
permintaan warga masyarakat. (Wijk-Konijnenbelt, 1984 : 42. Hadjon,
1999:6)
dilaksanakan atas prakarsa pemerintah sedangkan keterbukaan pasif atas
permintaan warga masyarakat. (Wijk-Konijnenbelt, 1984 : 42. Hadjon,
1999:6)
Pada
dasarnya keterbukaan pemerintahan tidak hanya menyangkut informasi. Keterbukaan
meliputi keterbukaan sidang-sidang badan perwakilan rakyat; keterbukaan
informasi; keterbukaan prosedur; keterbukaan register. Dalam WOB Belanda hanya
diatur tentang keterbukaan informasi saja sebagai dasar hubungan antara
pemerintahaan danrakyat. (Haan, 1986 :124, Hadjon, 1999 : 6)
Arti
penting keterbukaan dalam sidang-sidang badan perwakilan rakyat berkaitan
dengan fungsi pengawasan yang dimiliki badan perwakilan rakyat. Keterbukaan dalam
pengambilan, keputusan-keputusan politik memungkinkan pengawasan dan bagi
pembuat keputusan akan mendorong sikap berhati-hati dalam pengambilan keputusan
(Burkens, 1990 : 94, Hadjon, 1999 : 6-7)
Sebagai
ilustrasi adanya asas keterbukaan antara lain : "Rapat Paripurna, Rapat
Paripurna Luar Biasa, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia khusus
pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali apabila rapat yang bersangkutan atau
Badan Musyawarah memutuskan rapat tersebut bersifat tertutup". (Kep. DPR RI
No. 10/DPR-RI/III/82-83, Ps96 ayat(l))
Dari
uraian-uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa :
a. Kebijakan
daerah dapat berdampak positif dan dapat pula berdampak
negatif terhadap daerah maupun rakyat daerahnya;
negatif terhadap daerah maupun rakyat daerahnya;
b. Keterbukaan
dalam perencanaan, pembentukan dan implementasi
sesuatu kebijakan daerah berimplikasi secara langsung maupun tidak
langsung terhadap kuantitas dan kualitas kebijakan daerah yang
bersangkutan;
sesuatu kebijakan daerah berimplikasi secara langsung maupun tidak
langsung terhadap kuantitas dan kualitas kebijakan daerah yang
bersangkutan;
c. Keterbukaan memberikan
akses yang cukup
signifikan untuk pendidikan
politik rakyat daerah guna menghasilkan kebijakan daerah yang aspiratif,
partisipatif dan demokratis.
Pemerintahan
demokratis mengenal adanya keterbukaan informasi yang dibedakan atas
keterbukaan aktif dan pasif berkaitan dengan dokumen-dokumen pemerintahan.
Keterbukaan informasi dimungkinkan dalam batas-batas tertentu bagi masyarakat
untuk mengetahui dokumen-dokumen pemerintah. Fiksi hukum yang menyatakan bahwa "setiap
orang dianggap mengetahui undang-undang" tidaklah ada artinya apabila
undang-undang tidak dipublikasikan secara luas. (Duk-Loeb-nicolai, 1981 : 157,
Hadjon, 1999 : 7)
Cukup
banyak terjadi masyarakat tidak pernah diberi informasi tentang ketentuan
hukum, karena disatu sisi kita hanya berpegang pada fiksi hukum dan disisi lain
mungkin karena niat untuk memanfaatkan ketidak tahuan masyarakat tentang suatu
aturan hukum. (Hadjon, 1999 : 7-8)
Eksistensi keterbukaan prosedur berkaitan dengan "besluitvormingsprocedures"
dan salah satu dari "besluit" yang sangat penting adalah "beschikking"
yang dalam UU No. 5 Tahun 1986 disebut keputusan tata usaha negara. (Hadjon, 1999
: 9) Keterbukaan penting dalam pemerintahan. Keterbukaan dalam prosedur
pemerintahan memungkinkan masyarakat melakukan : meeweten (ikut mengetahui); meedenken
(ikut memikirkan); meespreken (bermusyawarah); dan meebeslissen (ikut memutuskan
dalam rangka pelaksanaan); medebeslissmgsrecht (hak ikut memutus) (Haan, 1986
:138, Hadjon, 1999 :8)
Dalam
prosedur pengambilan keputusan pemerintahan baik menyangkut suatu rencana,
kebijakan, pembentukan peraturan penmdang-undangan maupun suatu keputusan tata
usaha negara, (misalnya izin) asas-asas keterbukaan harus dituangkan dalam
prosedur tersebut.
Asas
keterbukaan dalam suatu prosedur izin, pelaksanaannya dapat berupa:
1. tersedianya
sarana "meedenken en meespreken" baik berupa keberatan, dengar pendapat
atau bentuk lain;
2. pengumuman
keputusan izin.
3. keterbukaan isi permohonan. (Hadjon,
1999: 8)
Keterbukaan
prosedur izin di Indonesia sesungguhnya telah diatur dalam ketentuan izin
ganguan yang lazimnya dikenal sebagai HO, namun sangat disesalkan, keterbukaan
prosedur begitu saja diabaikan dalam PERMENDAGRI No. 7 tahun 1993 dalam Rangka
Paket Kebijaksanaan Pemerintah 23 Oktober 1993 (PAKTO 1993). Dalam Pasal 7
PERMENDAGRI tersebut sebagai kelengkapan suatu permohonan izin undang-undang gangguan
pada huruf g diisyaratkan : Persetujuan tetangga/atau masyarakat yang berdekatan.
Ketentuan
dalam Pasal 7 huruf g diatas disatu sisi bertentangan dengan Ordonansi Gangguan
dan disisi lain telah mengabaikan asas keterbukaan pemerintah, yaitu kewajiban
pejabat yang berwenang untuk mengumumkan isi permohonan di lokasi dimana usaha
itu bakal berdiri, telah diganti dengan persetujuan tetangga. Dengan demikian
asas keterbukaan telah digeser oleh asas tetangga, padahal asas keterbukaan
berupa pengumuman isi permohonan tidak hanya untuk tetangga tetapi untuk siapa
saja pihak ketiga yang berkepentingan (bisa juga LSM) untuk mengajukan
keberatan dalam rangka "meeweten-meedenken-meespreken-meebeslissen".
(Hadjon, 1999 : 8-9)
Register
mengenai kedudukan hukum seseorang (misalnya pendaftaran penduduk; pendaftaran
pemilihan umum), pendaftaran benda-benda tidak bergerak serta pendaftaran
bidang usaha disamping sebagai suatu bentuk informasi, pada sisi lain memiliki
sifat sebagai "bestuurswaarborg". (Haan 1986 : 137, Hadjon, 1999:9)
Keterbukaan
register di Indonesia dikenal antara lain dalam hukum kadaster yaitu
keterbukaan buku tanah. Keterbukaan seperti itu di satu piliak memang
memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak atas tanah yang sudah didaftarkan
dan sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang sudah
didaftarkan itu. (Hadjon, 1999: 9)
Salah
satu perwujudan asas demokrasi yakni keterbukaan, bahkan merupakan conditio
sine qua non asas demokrasi. Keterbukaan memungkinkan partisipasi masyarakat
secara aktif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. (Hadjon, 1999 : 9)
Asas
keterbukaan dalam rangka pembentukan peraturan perundangan-undangan yang
demokratis, perlu mendapat perhatian, oleh karena demokrasi perwakilan saja
dewasa ini sudah tidak memadai.
Dalam
rangka hubungan antara pemerintah dan rakyat, kiranya keterbukaan merupakan
prioritas pemikiran untuk mendapat perhatian khusus. Kodifikasi hukum
administrasi umum, khususnya mengenai prosedur pemerintahan seyogyanya perlu
mendapat perhatian, yang membuka peluang kodifikasi administrasi secara
bertahap. Kodifikasi yang demikian punya arti bagi pelaksanaan asas negara
hukum untuk mewujudkan asas kekuasaan berdasarkan atas hukum secara nyata, Dalam
mengantisipasi era globalisasi usaha tersebut perlu mendapat prioritas.
3. Legalitas Dan Perlindungan Hukum Dalam
Pembentukan Kebijakan Daerah
3.1 Prinsip
Negara Hukum Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah
Dalam
setiap kegiatan perencanaan dan pembentukan kebijakan daerah yang kemasannya
dalam bentuk pranata hukum daerah, maka senantiasa harus didasarkan atas
pranata hukum. Kebijakan daerah apapun nama dan bentuknya, selalu didasarkan
atas wewenang pemerintahan yang sah. Wewenang pemerintahan dalam khasanah hukum
publik sering diidentikan dengan kekuasaan, dan perolehannya dapat secara
atribusi, delegasi, mandat dan atau dekonsentrasi (Suripto, 2001 : 9).
Penggunaan
wewenang pemerintahan dalam perencanaan dan pembentukan kebijakan daerah
senantiasa harus dilakukan secara cermat, akurat dan akuntabel Hal ini mengingat
bahwa penggunaan wewenang pemerintahan secara tidak tepat, bisa berakibat fatal
antara lain dapat digolongkan sebagai:
a. Abus de droit;
b. Willekeur;
c. Detoumement de povoir;
d. Ultra Vires (Sukismo, 2003 : 5).
Konsep
negara hukum (rechtsstaat) diintrodusir melalui RR 1854 dan terayata
dilanjutkan dalam UUD 1945. (Wignjosoebroto, 1994 : 188, Hadjon, 1994 : 4)
Dengan demikian ide dasar negara hukum Pancasila tidaklah lepas dari ide dasar
tentang "rechtsstaat". (Hadjon, 1994 : 4)
Persyaratan
dasar untuk dapat dikategorikan sebagai negara hukum yakni:
1. Setiap
tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan
perundang-undangan (wettelijke grondslag). Dengan landasan ini,
undang-undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan
tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini
pembentukan undang-undang merupakan bagian penting negara
hukum, (asas legalitas).
perundang-undangan (wettelijke grondslag). Dengan landasan ini,
undang-undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan
tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini
pembentukan undang-undang merupakan bagian penting negara
hukum, (asas legalitas).
2. Kekuasaan
negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
(asas pembagian kekuasaan).
(asas pembagian kekuasaan).
3. Hak-hak
dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat
dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang, (prinsip grondrechten).
dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang, (prinsip grondrechten).
4. Bagi
rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk
menguji keabsahan (rechtmatigheidstoetsing) tindak pemerintahan,
(pengawasan pengadilan ) (Burkens, 1990 : 29, Hadjon, 1994,
ibid.,: 5, Sukismo, 2002, (a): 2).
menguji keabsahan (rechtmatigheidstoetsing) tindak pemerintahan,
(pengawasan pengadilan ) (Burkens, 1990 : 29, Hadjon, 1994,
ibid.,: 5, Sukismo, 2002, (a): 2).
Syarat-syarat
dasar tersebut seyogyanya juga menjadi syarat dasar negara hukum Pancasila.
Untuk hal tersebut kiranya dibutuhkan suatu usaha besar berupa suatu kajian
yang sangat mendasar terutama tentang ide bernegara bangsa Indonesia. Ada
beberapa tulisan awal tentang itu yang barangkali dapat dijadikan acuan awal,
seperti :
Negara Hukum
Pancasila Dan Teori Bernegara Bangsa Indonesia. Disamping itu tentunya kita
tidak menutup mata terhadap perkembangan konsep negara hukum yang telah terjadi
di berbagai negara, seperti konsep negara hukum yang telah terjadi di berbagai
negara seperti konsep rechtsstaat yang telah berkembang dari konsep
"liberal-democratische rechtsstaat" ke "sociale
rechtsstaat" yang pada dewasa inipun sudah dirasakan bahwa konsep terakhir
itu sudah tidak memadai. (Hadjon, 1994 : 5, Sukismo, 2002 (a): 3)
Dari
uraian-uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa :
a. Penggunaan
wewenang pemerintahan dalam perencanaan dan
pembentukan kebijakan daerah senantiasa harus tepat, cermat dan
selektif;
pembentukan kebijakan daerah senantiasa harus tepat, cermat dan
selektif;
b. Penggunaan wewenang
pemerintahan dalam perencanaan
dan, pembantukan kebijakan daerah secara tidak tepat dapat berakibat fatal dan
kontra produktif;
c. Dalam negara
hukum setiap tindakan
dan atau kegiatan
penyelenggara daerah, senantiasa harus bersendikan pranata
hukum,
penyelenggara daerah, senantiasa harus bersendikan pranata
hukum,
3.2 Legalitas
Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah
Untuk
mengkategorikan negara hukum, biasanya digunakan dua macam asas, yakni : asas
legalitas dan asas perlindungan atas kebebasan setiap orang dan atas hak-hak
asasi manusia. (Utrecht, 1963 :310,Sukismo,2002(a):3)
Unsur
utama suatu negara hukum, yakni asas legalitas. Semua tindakan negara harus
berdasarkan dan bersumber pada undang-undang. Penguasa tidak boleh keluar dari
rel-rel dan batas-batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Batas
kekuasaan negara ditetapkan dalam undang-undang. Akan tetapi untuk dinamakan
negara hukum tidak cukup bahwa suatu negara hanya semata-mata bertindak dalam
garis-garis kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. ( Gouw Giok
Siong, 1955 :12-13, Sukismo, 2002 (a): 4) Sudah barang tentu bahwa dalam negara
hukum setiap orang yang merasa hak-hak pribadinya dilanggar, diberi kesempatan
seluas-luasnya untuk mencari keadilan dengan mengajukau perkaranya itu di
hadapan pengadilan. Cara-cara mencari keadilan itu pun dalam negara hukum
diatur dengan undang-undang. (Rochmat Soemitro, 1976 .18, Sukismo, 2002 (a):
4).
Pembentukan
kebijakaa daerah yang sewenang-wenang (willekeur) maksudnya ialah penggunaan
wewenang pemerintahan dalam pembentukan kebijakan daerah yang tidak rasional
dalam arti tidak dapat diterima oleh akal sehat. Pembentukan kebijakan daerah
dengan cara menyalah gunakan wewenang (detournement de pouvoir} maksudnya
adalah penggunaan kekuasaan dengan cara membiarkan tujuan dari wewenangnya
sendiri. Sedangkan yang di maksud dengan ultra vires (melampaui batas wewenang)
dalam pembentukan kebijakan daerah adalah pembentukan kebijakan daerah dimana
wewenang yang digunakan sebagai dasar pembentukannya pada hakekatnya bukan
untuk pembentukan kebijakan daerah yang bersangkutan. Yang paling fatal yakni
abus de droit, dalam hal ini wewenang pemerintahan digunakan untuk menabrak
atau melawan pranata hukum yang ada (Sukismo, 2002: 14).
Dari
uraian-uraian tersebut dapatlah dikatahui bahwa :
a. Legalitas erat kaitannya dengan negara
hukum;
b. Setiap
kegiatan pembentukan kebijakan daerah, senantiasa harus
dicarikan dasar hukumnya.
dicarikan dasar hukumnya.
3.3 Perlindungan
Hukum Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah.
Terhadap
Kebijakan daerah yang pembentukannya tidak sah
, atau tidak didasarkan atas wewenang pemerintah secara tepat, akurat
dan adil maka kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan perlu dan relevan
memperoleh perlindungan hukum (Sunaryo, 2002 : 12).
Dalam
negara hukum asas perlindungan nampak antara lain dalam "Declaration of
Independence", bahwa orang yang hidup di dunia ini sebenarnya telah
diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat
dirampas atau dimusnahkan. Hak-hak tersebut yang sudah ada sejak orang
dilahirkan, perlu mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum modern
(Soemitro, 1976 : 18, Sukismo, 2002 (a): 4). Peradilan tidak semata-mata
melindungi hak asasi perseorangan, melainkan fungsi hukum adalah untuk
mengayomi masyarakat sebagai totalitas, agar supaya cita-cita luhur bangsa
tercapai dan terpelihara. Peradilan mempunyai maksud membina, tidak semata-mata
menyelesaikan perkara. Hakim harus mengadili menurut hukum dan menjalankan
dengan kesadaran akan kedudukan, fungsi dan sifat hukum. Dengan kesadaran bahwa
tugas hakim ialah, dengan bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada Nusa
dan Bangsa, turut serta membangun dan menegakkan masyarakat adil dan makmur
yang berkepribadian Pancasila. (Soemitro, 1976 : 20-21, Sukismo, 2002 (a): 5).
Suatu
negara merupakan negara hukum, semata-mata didasarkan pada asas legalitas.
(Yamin, 1952 : 9, Sukismo, 2002 (a): 5) Disisi lainnya asas legalitas, hanyalah
merupakan salah satu unsur atau salah satu corak dari negara hukum, karena
disamping unsur asas , legalitas tersebut, masih perlu juga diperhatikan
unsur-unsur lainnya, antara lain kesadaran hukum, perasaan keadilan dan perikemanusiaan,
baik bagi rakyat maupun pimpinannya. (Siong, 1955 : 23, Sakismo, 2002 (a): 5,
Yunanto, 2000 :4)
Dalam
UUD 1945 ada ketentuan yang meajamin hak-hak asasi manusia. Ketentuan tersebut
antara lain:
- Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
(Ps. 28);
- Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan
(Ps- 28);
(Ps- 28);
- Hak bekerja dan hidup (Ps. 27 ayat
(2));
- Kemerdekaan agama (Ps. 29 ayat (2));
- Hak
untuk ikut mempertahankan negara (Ps. 30), disini nampak adanya asas
perlindungan
Dengan
adanya Majelis Pertimbangan Pajak, seseorang dapat mengajukan surat bandingnya
untuk hal-hal dimana ia merasa telah diperlakukan tidak sebagaimana mestinya
oleh pejabat perpajakan. Orang dapat menuntut/mengajukan gugatan kepada negara,
bila oleh negara dilakukan suatu perbuatan yang melawan hukum
(onrechtmatigedaad), bahwa seseorang dapat melakukan gugatan terhadap
Pemerintah Republik Indonesia, jika putusan pejabat yang berwenang dirasa tidak
adil. (Soemitro, 1976.: 25, Sukismo, 2002 (a) : 5, Ashari, 1999 : 6) Sudah
banyak peraturan-peraturan yang memberi jaminan kepada para warga negara, untuk
menggunakan hak-haknya mengajukan tuntutan-tuntutan di muka pengadilan, bila
hak-hak dasarnya atau kebebasannya dilanggar. ( Ashari, 1999 : 25 - 26,
Sukismo, 2002 (a): 6)
Penghormatan,
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, mendapat tempat
utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum; sebaliknya
dalam negara totaliliter tidak ada tempat bagi hak-hak asasi manusia. Istilah
"rechtsstaat" mulai populer sejak abad XIX, meskipun pemikiran
tentang itu sudah lama adanya. Istilah "the rule of law" mulai
populer tahun 1885. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya,
terdapat perbedaan antara konsep "rechtsstaat" dengan konsep "the
rule of law", pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu
sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asai
manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, tetapi keduannya tetap berjalan
dengan sistemnya sendiri yaitu sisterti hukum sendiri. Konsep "rechtsstaat"
lahir dari suatu perjuangan menentang absulutisme sehingga sifatnya
revolusioner, sebaliknya konsep "the rule of law" berkembang secara
evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria "rechtssataat" dan
kriteria "the rule of law". Konsep "rechtsstaat" bertumpu
atas sistem hukum kontinental yang disebut "civil law" atau
"modern Roman Law", sedangkan konsep "the rule of law"
bertumpu atas sistem hukum yang disehul "common law". Karakteristik
"civil law" adalah "administratief', sedangkan karakteristik
"common law" adalah "judicial". Perbedaan karakter yang
demikian disebabkan karena latar belakang dari pada kekuasaan raja. Pada zaman
Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja yakni membuat peraturan melalui
dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat
administratif sehingga pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan
tertulis bagi hakim tentang bagaimana menyelesaikan suatu sengketa. Begitu besar
peran administrasi negara, sehingga tidaklah mengherankan, kalau dalam sistem
kontinental-lah mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut "droit
administratif', dan intinya adalah hubungan antara administrasi negara dengan
rakyat Sebaliknya di Inggris, kekuasaan utama dari raja adalah memutus perkara.
Peradilan oleh raja kemudian berkembang menjadi suatu peradilan, sehingga
hakim-hakim peradilan adalah delegasi dari raja, tetapi bukan melaksanakan
kehendak raja. Hakim harus memutus perkara berdasarkan kebiasaan umum Inggris
(the common custom of England), sebagaimana dilakukan oleh raja sendiri
sebelumnya. Dengan demikian nampak bahwa di Eropa peranan administrasi negara
bertambah besar, sedangkan di Inggris peranan peradilan dan para hakim
bertambah besar. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, di Eropa dipikirkan
langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara, sedangkan di
Inggris dipikirkan langkah-langkah untuk mewujudkan suatu peradilan yang adil.
Dalam perjalanan waktu, konsep "rechtsstaat" telah mengalami perkembangan
dari konsep klasik ke konsep modern. Sesuai dengan sifat dasarnya, konsep klasik
disebut "klasiek liberale en democratische rechtssataat", yang sering
disingkat dengan "democratische rechtsstaat". Sedangkan konsep modern
lazimnya disebut "sociale rechtsstaat" atau "sociale
democratische rechtsstaat". (Hadjon, 1987 : 71 - 74, Sukismo, 2002 (a): 7
Karakternya
yang liberal bertumpu atas pemikiraa kenegaraan dari John Locke, Montesquieu
dan Immanuel Kant. Karakternya yang demokratis bertumpu atas pemikiran
kenegaraan dari J.J. Rousseau tentang kontrak sosial. ( Couwenberg. 1977 : 25,
Daiyadi,2001:7)
Konsep
liberal bertumpu atas "liberty" (vrijheid) dan konsep demokrasi
bertumpu atas "eguality" (gelijkheid). "Liberty" adalah "the
free selfassertion of each-limited only by the like liberty of all". Atas
dasar itu "liberty" merupakan suatu kondisi yang memungkinkan
pelaksanaan kehendak secara bebas dan hanya dibatasi seperlunya, untuk menjamin
koeksistensi yang harmonis antara kehendak bebas individu dengan kehendak bebas
semua yang lain. Dari sinilah mengalir prinsip selanjutnya yaitu :
"freedom from arbitrary and unreasonable exercise of the power and
authority (Pound, 1957 : 1 - 2, Sukismo, 2002 (a) : 8) Konsep
"eguality" mengandung makna yang abstrak dan formal (abstract-formal equality)
dan dari sini mengalir prinsip "one man-one vote) (Hadjon, 1987 : 75,
Sukismo, 2002 (a): 8)
Konsep-konsep
dasar yang sifatnya liberal dari "rechtssataat" meliputi:
- adanya jaminan
atas hak-hak kebebasan
sipil (burgelijke vrijheidsrechten);
- pamisahan antara negara dengan
gereja;
- persamaan
terhadap undang-undang (gelijkheid voor de wei);
adanya konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan
dasar sistem hukum;
adanya konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan
dasar sistem hukum;
- pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica
dan sistem "cheks and balances";
- asas legalitas (heerschappij van de
wet);
- ide
tentang aparat pemerintah dan kekuasaan kehakiman yang
tidak memihak dan netral;
tidak memihak dan netral;
- prinsip
perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa;
- prinsip pembagian
kekuasaan, baik teritorial sifatnya maupun vertikal (sistem desentralisasi maupun
federasi). (Couwenberg,1977: 30, Sukismo, 2002 (a): 8)
Konsep
dasar demokratts, "rechtsstaat" dikatakan sebagai "negara
kepercayaan timbal balik" (de staat van het wederzijds vertrowen) yaitu
kepercayaan dari pendukungnya, bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan
disalahgunakan, dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya. (Port -
Donner, 1983 : 143, Sukismo, 2002 (a): 9)
Rechtsstaat
mendasarkan atas asas-asas demokratis antara lain:
- asas hak-hak politik (het beginsel
van de politieke grondrechten);
- asas mayoritas;
- asas perwakilan;
- asas pertanggungjawaban;
- asas
publik (openbaarheids beginsel). (Couwenberg, 1977 : 30,
Sukismo, 2002 (a): 9)
Sukismo, 2002 (a): 9)
Cin-ciri
"rechtsstaat" adalah:
(1) Adanya
Konstitusi yang memuat ketentuan
tertulis tentang
hubungan antara penguasa dan rakyat;
hubungan antara penguasa dan rakyat;
(2) Adanya
pembagian kekuasaan negara, yang meliputi : kekuasaan
pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen. Kekuasaan kehakiman bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat, tetapi juga antara rakyat dan penguasa, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang (wetmatig bestuur);
pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen. Kekuasaan kehakiman bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat, tetapi juga antara rakyat dan penguasa, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang (wetmatig bestuur);
(3) Diakui
dan dilingunginya hak-hak rakyat yang sering disebut "vrijheidsrechten van
burger". (Port - Donner, 1983 : 143, Karman, 1992 :9)
Ciri-ciri
diatas menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral "rechtsstaat"
adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang bertumpu
atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya konstitusi akan memberikan jaminan
konstitusional terhadap asas kebebasan dari persamaan. Adanya pembagian
kekuasaan untuk menghindarkan penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, yang
sangat cenderung kepada penyalah gunaan kekuasaaa, berarti pemerkosaan terhadap
kebebasan dan persamaan. Dengan adanya pembuatan undang-undang yang dikaitkan
dengan parlemen, dimaksudkan untuk menjamin bahwa hukum yang dibuat adalah atas
kehendak rakyat; dengan demikian hukum tersebut tidak akan memperkosa hak-hak
rakyat, tetapi dikaitkan dengan asas mayoritas, kehendak rakyat diartikan
sebagai kehendak golongan mayoritas. Dengan prinsip "welmatig bestuur"
agar tindak pemerintahan tidak memperkosa kebebasan dan persamaan (heerschappij
van de wet). Dalam konsep "rechtsstaat" yang liberal dan demokratis,
inti perlindungan hukum bagi rakyat adalah perlindungan terhadap kebebasan
individu. Setiap tindak pemerintahan yang melanggar kebebasan individu,
melahirkan hak untuk menggugat di muka peradilan. (Hadjon, 1987 : 76 - 77)
Sebutan
"sociale rechtsstaat" lebih baik dari pada sebutan
"welvaartsstaat". (Verdam, 1976 : 17) "Sociale rechtsstaat"
merupakan variant dari "liberaal-democratische rechtsstaat" (Hadjon,
1987 :77)
Variant
dari "sociale rechtsstaat" terhadap "liberaal-democratische
rechtsstaat", antara lain : interpretasi baru terhadap hak-hak klasik dan
munculnya serta dominasi hak-hak sosial, konsepsi baru tentang kekuasaan
politik dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, konsepsi baru tentang makna
kepentingan umum, karakter baru dari "wet"dan wetgeving" (Couwenberg,
1977 :33)
Semula
kebebasan dan persamaan (vrijheid en gelijkheid) dalam konsep
liberaal-democratische rechtsstaat sifatnya yuridis formal, dalam konsep
sociale rechtsstaat ditafsirkan secara riil dalam kehidupan masyarakat (reele
maatschappelijke gelijkheid), bahwa tidak terdapat persamaan mutlak di dalam
masyarakat antara individu yang satu dengan yang lain. (Franken, 1983 : 273,
Untung, 1991 :6)
Dalam
"sociale rechtsstaat" prinsip perlindungan hukum terutama diarahkan
kepada perlindungan terhadap hak-hak sosial, hak ekonomi dan hak-hak kultural.
Dikaitkan dengan sifat hak, dalam "rechtsstaat" yang liberal dan
demokratis adalah "the right to do", dalam "sociale
rechtsstaat" muncul "the right to receive". Dikaitkan dengan
sarana perlindungan hukum, maka makin kompleks sistem perlindungan hukum bagi
rakyat. (Meuwissen, 1975:140)
Tugas
negara dalam konsep yuridis "sociale rechtsstaat", disamping
melindungi kebebasan sipil juga melindungi gaya hidup rakyat. (Idenberg, 1983 :
27)
Pengaruh
negara terhadap individu menjelma dalam tiga cara yakni : pertama, pengaruh
langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
sosial, kedua, pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari perabentukan aparat
pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian, ketiga.
harapan bahwa problema-problema masyarakat dapat dipecahkan melalui campur
tangan penguasa. (Idenberg, 1983 : 28 - 29)
Wacana
murni dan sempit mengenai "the rule of law", inti dari tiga
pengertian dasar yang diketengahkan adalah "common law", sebagai
dasar perlindungan bagi kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan oleh
penguasa. Penolakan kehadiran peradilan administrasi negara adalah sesuai
dengan perkembangan hukum dan kenegaraan di Inggris. Inti kekuasaan raja di
Inggris semula adalah kekuasaan memutus perkara, yang kemudian didelegasikan
kepada hakim-hakim peradilan yang memutus perkara tidak atas nama raja, tetapi
berdasarkan "the common custom of England", sehingga karakterisrik
dari "ccmmon law'"adalah "judicial", sedangkan karakteristik dari
"civil law" (kontinental) adalah "administratif ( Hadjon, 1987:
82)
Konsep
"the rule of law" maupun konsep "rechtsstaat" keduanya
menempatkan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai
titik sentralnya, sedangkan bagi negara Republik Indonesia, yang menjadi titik
sentralnya adalah "keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat
berdasarkan asas kerukunan". Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, dalam
konsep "the rule of law" mengedepankan prinsip "eguality before
the law", dan dalam konsep "rechtsstaat" mengedepankan prinsip
"wetmatigheid" kemudian menjadi "rechtmatigheid". Untuk
negara Republik Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara
pemerintah dan rakyat, yang mengedepankan adalah "asas kerukunan"
dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dari asas ini akan berkembang
elemen lain dari konsep Negara Hukum Pancasila, yakni terjalinnya hubungan
fungsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara
musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir, dan tentang hak-hak
asasi manusia tidaklah hanya menekankan hak dan kewajiban saja, tetapi juga
terjalinnya suatu keseimbangan antara hak
dan kewajiban. Elemen Negara Hukum Pancasila adalah :
a. Hubungan fungsional
yang proporsional antara
kekuasaan-kekuasaan negara;
b Prinsip
penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana
terahkir;
c Keseimbangan
antara hak dan kewajiban.
Keseimbangan hubungan
antara pemerintahan dan rakyat
berdasarkan asas kerukunan (Hadjon, 1987 : 82 - 90)
Dari
berbagai uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa :
a. Setiap warga
masyarakat suatu daerah
berhak memperoleh
perlindungan hukum atas dibentuknya suatu kebijakan daerah yang
merugikaa dirinya;
perlindungan hukum atas dibentuknya suatu kebijakan daerah yang
merugikaa dirinya;
b. Kewenangan
pemerintahan yang dijadikan dasar pembentukan
kebijakan daerah harus jelas asal-usulnya serta ruang lingkup
kewenangannya.
kebijakan daerah harus jelas asal-usulnya serta ruang lingkup
kewenangannya.
c. Hal asasi
warga suatu daerah merupakan hak dasar yang layak
dapat dipertahankan dalam keadaan apapun juga untuk mengantisipasi akibat-akibat yang timbul dari dibentuk dan diberlakukannya suatu kebijakan daerah.
dapat dipertahankan dalam keadaan apapun juga untuk mengantisipasi akibat-akibat yang timbul dari dibentuk dan diberlakukannya suatu kebijakan daerah.
BAB V
PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis
hasil penelitian dan
pembahasan dapatlah disimpulkan
antara lain :
1) a. Perda
tentang mekanisme partisipasi masyarakat
untuk
Mengkritisi
kebijakan-kebijakan jajaran Pemda Kota Yogyakarta sampai saat ini belum eksis,
namun telah ada usaha-usaha untuk merintis dan membuka jalan kearah dapat
dilakukannya partisipasi masyarakat secara kritis dan konstruktif melalui email
dan hot line;
b. Harapan
untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih terbebas dari KKN
terayata masih dihantui dan dibayang-bayangi adanya indikasi praktek KKN tidak
hanya dapat terjadi dalam jajaran pemerintahan pusat. melainkan dapat pula
terjadi dalam jajaran Pemda.
2) a. Partisipasi
masyarakat mempunyai kontribusi yang cukup signifikan
Untuk
mencegah dan mengeliminir terjadinya praktek KKN dalam pembentukan
kebijakan-kebijakan daerah, namun patut disesalkan sampai saat ini partisipasi
masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat terealisir;
b. Keterbukaan
memberikan akses yang cukup signifikan untuk pendidikan politik rakyat daerah
guna menghasilkan kebijakan daerah yang aspiratif, partisipatif dan demokratis.
3) a. Penggunaan wewenang
pemerintahan dalam perencanaan
Dan pembentukan
kebijakan daerah secara tidak tepat dapat berakibat fatal dan kontra produkif,
dan oleh karenanya partisipasi
masyarakat mutlak diperlukan eksistensinya.
b. Hak asasi
warga masyarakat suatu daerah merupakan hak dasar, yang layak memperoleh
perlindungan hukum dan dapat dipertahankan dalam keadaan apapun juga, untuk
mengantisipasi akibat-akibat yang timbul dari dibentuk dan diberlakukannya
suatu kebijakan daerah.
2. Saran
Saran
yang dapat diajukan dari penelitian ini antara lain :
a. Agar
Perda tentang mekanisme partisipasi masyarakat untuk mengkritisi perencanaan
dan pembentukan kebijakan daerah dalam jajaran Pemda Kota Yogyakarta segera
dapat direalisir;
b. Agar
segera ditempuh upaya-upaya kreatif dan dinamis untuk memberdayakan masyarakat guna
berpartisipasi mengeleminir dan
memberantas praktek-praktek KKN dalam setiap kebijakan daerah, baik langsung
maupun tidak langsung dalam jajaran Pemda Kota Yogyakarta
c. Agar
jajaran Pemda Kota
Yogyakarta dapat memanfaatkan wewenang
pemerintahan untuk merencanakan dan membentuk kebijakan daerah secara optimal,
tepat, efektif dan efisien.
Daftar Pustaka :
Ashari 1999, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa
makalah disampaikan pada seminar sehari diselenggarakan oleh Forum Nusantara
Bersatu, pada tanggal 10 April 1999 di Klaten
Attamimi, A. Hamid S., 1990, Peranan Keputusan Presiden
Republik Indonesia, disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta
Akkormans, P.W.C., 1985, Algemene Begrippen Van
Staatsrecht, deel I, W.EJ. Tjeenk, Zwole
Burkens, M.C., 1990, Beginselen van de Democratische
Rechtsstaat, Tjeenk Willink, Zwole
Burkens, M.C., 1990, Beginselen van de democratische
rechtsstaat, W.EJ. Tjeenk Willing, Zwolle in samenwerking met het Nederlans
Institut voor Sociaal en Economisch Recht, NISER
Budisoesetyo, R., 1958, Kedaulatan Rakyat Dalam Hukum
Positip indonesia, Pidato, diucapkan pada peresmian jabatan guru besar luar
biasa dalan mata pelajaran hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan pada
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, di Surabaya, pada hari Rabu tanggal 10
November 1958
Bruggink, J.J.H., (alih bahasa Arief Sidharta), 1996,
Refleksi Tentang hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung
Couwenberg, S.W., 1977, Westers Staatsrecht als
Emancipatie Proces, Samson, Alphen aan de Rijn
Daryadi 2001, Perjanjian Masyarakat, makalah disampaikan
pada seminar nasional diselenggarakan oleh Forum Cinta Bangsa, pada tanggal 10
Januari 2001 di Surabaya
Duk-Loeb-nicolai, 1981,Bestuursrecht, Bowar-boek : 157
Meuwissen, D.H.M., 1979, Viff Stellingen Over Recht
Filosofie, in : Een beeld van Recht, Ars Aequi
Meuwissen, D.H.M., l975,Elementen van Staatsrecht, Tjeenk
Willink, Zwolle
Pound, Roscoe, 1957, The Development of Constitutional
Guanrantiees of Liberty, Yale University Press, New Haven London
Port, C.W. van der, - bewerkt door AM. Donner, 1983,
Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, ll e druk, Tjeenk Willink, Zwolle
Prasetyo, 2002, Otonomi Daerah Dan Permasalahannya,
Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Forum
Peneliti Daerah pada tanggal 10 Agustus 2002 di Yogyakarta
Siong, Gouw Giok, 1955, Pengertian Tentang Negara Hukum,
Keng Po, Jakarta
Soemitro, Rochmat 1976, Peradilan Administrasi Dalam
Hukum Pajak Di Indonesia, cet. ke - IV, PT. ERESCO, Jakarta-Bandung
Sukismo. B., 2002 (a), Aspek Politik Hukum Dalam
Pembentukan Peraturan Perundangan Yang Demokratis, makalah disampaikan pada
seminar sehari yang diselenggarakan oleh Forum Peduli Keadilan Masyarakat Banyumas,
pada tanggal 9 Mei 2002 di Purwokerio.
Sukismo, B., 2002 (b), Ilustrasi Model Penulisan Hukum
Normatif, makalah, disampaikan pada seminar sehari yang diselenggarakan oleh Forum
Peduli Keadilan Masyarakat Banyumas, pada tanggal 9 Mei 2002, di Purwokerto.
Sidharta; B., Arief, 1996, Refleksi Tentang Fondasi Dan
Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Hukum Nasional
Indonesia, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
Suhardi, 2002, Kebijakan Daerah Yang Partisipasif,
Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Forum
Peduli Daerah pada tanggal l2 Agustus2002 di Surakarta
Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2001,
Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Edisi Kedua, Cet.
Pertama, Liberty,Yogyakarta.
Utrecht, 1963, Pengantar Hukum Administrasi Negara
Indonesia , PT. Ichtiar, Jakarta
Untung 1991, Demokrasi Liberal, makalah disampaikan pada
seminar nasional
diselenggarakan oleh Pusat Kajian Politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli
1991 diSurabaya
diselenggarakan oleh Pusat Kajian Politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli
1991 diSurabaya
Verdam, P.J., 1976, Nederlandse Rechtsgeshiedenis 1795 -
1975, Samson, Alphen aan den Rijn.
Vlies, I.C. Van der., 1984, Het Wetsbegrip en Beginselen
van Behoorlijk Regelgeving, Vuga, S-Gravenhage
Wijk-Konijnenbelt, Van., 1984, Hoofdstukken van
adminisiratief recht, vijfde druk,
Vuga, S-Gravenhage
Vuga, S-Gravenhage
Wignjosoebroto, Soetandijo, 1994, Sejarah Hukum, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta
White, R. Allan, 1970, Truth : Problem in philosophy,
Doubleday E. Company, New York
Wintoko,
2000, Keadilan Sejati,
makalah disampaikan pada
seminar sehari diselenggarakan oleh Forum Peduli Rakyat pada tanggal 9
Juni 2000 di Klaten
Yamin, Muh., 1952, Proklamasi dan Konstituante Republik
Indonesia, Cet ke-2, PT. Djambatan, Jakarta
Yunanto, 2000, Asas Legalitas, makalah disampaikan pada
seminar sehari diselenggarakan oleh Forum Nusantara pada tanggal 5 Mei 2000 di Surakarta
Badrun. 2005, Mendambakan Pemerintahan Yang Bersih,
Pelita Press Jakarta
Suwandi, 2001, Manajemen Pemerintahan, Presto Press,
Bandung
Suprapto, 2002, Sistem Pemerintahan Nasional, PT. Index,
Jakarta
Sukismo, 2002 Menyimak Otonomi Daerah, Sari Press,
Surabaya
Sukismo, 2003, Manajemen Wewenang Pemerintahan, Sari
Press, Surabaya
Subardi, 2001, Sistem Otonomi, Cakra, Surakarta
Santoso, 2001, Hubungan Ideal Pemerintah Pusat dan
Daerah, Langgeng Press, Bandung
Suyudi, 2001, Melacak Liku-Liku Koruptor, Cindra Press,
Semarang
Suyanto, 2002, Sepak Terjang Koruptor, Cemerlang Press,
Surakarta Supriyadi 2002, Sistem Partisipasi Moderen, PT.
Duta Aksara, Surabaya
Sugiri, 2002, Perlindungan Perburuhan, Pelita Press,
Jakarta
Sunarto, 2002, Hak Patisipasi Rakyat, Pelita Press,
Jakarta
Sarosa,2001, Strategi Daerah, Pelita Press, Jakarta
Soemardjan, 1995, Pilar-Pilar Demokrasi, Candra Press,
Pati
Suripto,2001, Strategi Kebijakan Daerah, Candra Press,
Pati
Sunaryo,2002,Sistem Kontrol Kebijakan Pemerintahan, Sari
Press, Surabaya
Yunanto, 2000,Negara Hukum Dan Negara Kekuasaan, Candra
Press, Pati
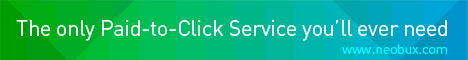


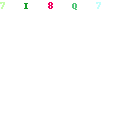


0 komentar:
Post a Comment