Persepsi Guru Matematika Terhadap Pelaksanaan Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK) Mata Pelajaran Matematika Di SMA Negeri 1 Makassar .
Skripsi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar.
ABSTRAK
Penelitian
ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif yang meneliti satu variabel tanpa
membandingkan dengan variabel yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana persepsi guru matematika terhadap pelaksanaan Kurikulum
Berbasis Kompetensi (KBK) mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Makassar . Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah
seluruh guru mata pelajaran matematika SMA Negeri 1 Makassar yang mengajar di
kelas X dan Kelas XI sebanyak 5 orang. Untuk memperoleh data tentang persepsi
guru matematika terhadap pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika di SMA
Negeri 1 Makassar maka digunakan angket (kuesioner). Data hasil penelitian
diolah dengan menggunakan analisis kuatitatif deskriptif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa persepsi guru matematika terhadap pelaksanaan KBK mata
pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Makassar berada pada kategori baik. Dari
hasil wawancara dengan guru matematika menyatakan bahwa faktor-faktor yang
mendukung pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Makassar
adalah; (1) siswa memiliki buku pegangan yang sesuai dengan tuntutan KBK, dan
penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi, (2) siswa mempunyai kesadaran
tinggi untuk proaktif serta lebih antusias dalam proses belajar, (3) laboratorium
komputer dan OHP yang sudah tersedia, (4) siswa dituntut untuk belajar mandiri,
dan (5) penilaian per-kompetensi dasar yang memudahkan guru dalam menentukan
ketuntasan belajar siswa, pelaksanaan program remedial serta penilaian dari
beberapa aspek. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru matematika dalam
pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika adalah; (1) penjabaran materi
pelajaran dan uji kelayakan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup, tidak semua
guru yang mengajar pernah mengikuti pelatihan atau seminar tentang KBK, (2)
buku paket dan modul yang masih sedikit jumlahnya, (3) sebagian siswa yang
kurang memiliki kesadaran untuk mempergunakan waktu di luar sekolah, (4)
sebagian siswa cenderung hanya mengikuti pekerjaan atau tugas temannya, siswa
kurang mampu mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya,
dan (5) jumlah siswa yang banyak dalam satu kelas.
ABSTRACT
This
study was quantitative descriptive research focusing on one variable without
comparing with other variables. It aimed to know how mathematics teachers’
perception toward the implementation of the competence-based curriculum of
school mathematics at SMA Negeri 1 Makassar. Data were gathered using a
questionnaire. Data were analyzed using quantitative descriptive analysis. The
results of this research showed that the mathematics teachers’ perceptions
toward the implementation of the competence-based curriculum of school
mathematics at SMA Negeri 1 Makassar were categorized as good. Based upon the
result of interviewing the mathematics teachers, it was found that the factors
supporting the implementation of the school mathematics curriculum were: (1)
students possessed handbooks which were relevant to the requirements of the
curriculum, and teachers implemented various instructional strategies; (2)
students were highly aware of being active an enthusiastic during the lesson;
(3) the availability of OHP and computer laboratory; (4) students were demanded
to learn independently; and (5) the implementation of per-competence assessment
which enabled teachers to easily determine the level of students’ mastery in
learning, to conduct remedial program, and to assess some aspects. Problems
encountered by the mathematics teachers in implementing the curriculum of
school mathematics were: (1) the formulation of lesson materials and the
administration of feasibility test required adequate fund and time; only some
teachers have followed of seminar or training on the competence-based
curriculum, (2) the lack of teaching materials including textbooks and learning
modules, (3) some students were not aware of the utilization of time to learn
outside school time, (4) some students tended to copy their peers’ assignments,
student were less able to develop and apply their knowledge, and (5) the big
number of students within a classroom.
KATA PENGANTAR
A.

Alhamdulillahi rabbil ’alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang
telah memberikan petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar.
Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai hambatan
dan tantangan. Tetapi berkat usaha, kerja keras, dorongan dari berbagai pihak
serta senantiasa diiringi dengan do’a, penulis dapat mengatasi semuanya
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih tergolong jauh dari
kesempurnaan sebagaimana layaknya suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan
segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya
membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan serta
dukungan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. oleh karena
itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada:
1.
Bapak Prof.Dr.H.M.Idris Arief, M.S., Rektor Universitas
Negeri Makassar .
2.
Bapak Drs.H.Muhammad Noor, M.S., Dekan Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar.
3.
Bapak Dr. Hamzah Upu, M.Ed., Ketua Jurusan
Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam Universitas Negeri Makassar
4.
Bapak Drs. Darwing Paduppai, M. Pd, Sekretaris Jurusan
Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
5.
Bapak Drs. H. Mappaita Muhkal, M.Pd., Kepala
Laboratorium Jurusan Matematika Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar
6.
Bapak Drs. Suhartono, selaku Pembimbing I dan Drs. H.
Bernard, M.S., selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan
bimbingannya selama penulisan skripsi ini.
7.
Bapak Drs. Hisyam Ihsan, M.Si., Penasehat Akademik yang
senantiasa yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingannya selama
penyelesaian studi kami.
8.
Bapak dan Ibu dosen jurusan Matematika Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam UNM Makassar yang telah memberikan bekal dan dorongan
selama perkuliahan.
9.
Para Staff/Pegawai Administrasi dan perpustakaan
jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNM yang telah
memberikan pelayanan hingga penulis menyusun tugas akhir ini.
10.
Bapak Drs. Herman Hading, M.Pd., Kepala Sekolah SMA
Negeri 1 Makassar, yang telah memberikan izin dan bantuannya kepada penulis.
11.
Ibu Dra. Hj. Nursiah Kas. dan Guru SMA Negeri 1
Makassar yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis selama
pengambilan data.
12.
Bapak Dr. Djunaidi Dedikasih M. Dachlan, MS. dan Ibu
Dra. Sani Silwana, M.Ph., serta Bapak/Ibu/Sdr (i) keluarga besar Tompo Tikka,
yang dengan ikhlas membantu dalam bentuk moril dan materil demi kesuksesan
penulis.
13.
Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2001; Hasisah, Asriyati,
Nur Alam, Yunus, Amin, Bahar, Muh. Saleh, Irwan, Herman, dan semua rekan-rekan
yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu.
14.
Rekan-rekan mahasiswa Bima; Hadi, Udin, Subhan, Muslim,
Muis, Irwan, Santi, Farida, Ati, Dani, Nurhaidah, S.Pd. dan semua rekan-rekan
yang lain seperjuangan penulis dalam kehidupan di tanah rantau.
15.
Teristimewa buat Ayahanda Usman (Almarhum) dan Ibunda
tercinta Hatijah, saudara-saudaraku H.M.Fadil, Fatmah, Ruhyati, zaidin, dan
Junari, serta seluruh keluarga yang telah mendo’akan dan merelakan segalanya
demi kesuksesan penulis.
Akhirul Qalam, segalanya penulis kembalikan kepada Allah SWT, sebagai
konsekuensi penghambaan secara totalitas semata-mata kepada-Nya. Semoga
keikhlasan dan bantuan yang telah diberikan walau sekecil biji dzarrahpun
memperoleh ganjaran di sisi-Nya (Amin).
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN
JUDUL ... i
HALAMAN
PERSETUJUAN ….......................................................................... ii
MOTTO
............................................................................................................. iii
ABSTRAK . iv
KATA
PENGANTAR .. v
DAFTAR ISI
……………………………………………………………………. viii
DAFTAR TABEL ……........................................................................................ x
DAFTAR
LAMPIRAN.......................................................................................... ix
A.
Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1
B.
Rumusan Masalah ................................................................................. 4
C.
Tujuan Penelitian ................................................................................... 4
D.
Manfaat Penelitian ................................................................................ 4
A.
Tinjauan Pustaka.................................................................................... 6
B.
Kerangka Berpikir ............................................................................... 29
BAB
III METODE PENELITAN ………........................................................... 31
A.
Variabel Penelitian .............................................................................. 31
B.
Devinisi Operasional Variabel ............................................................. 31
C.
Objek Penelitian .................................................................................. 31
D.
Teknik Pengumpulan Data .................................................................. 32
E.
Teknik Analisis Data …....................................................................... 33
BAB
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN …....................................................... 37
A.
Penyajian Hasil Analisis Data ............................................................. 37
B.
Pembahasan Hasil Penelitian .............................................................. 42
BAB
V. KESIMPULAN DAN SARAN …........................................................ 47
A.
Kesimpulan ......................................................................................... 47
B.
Saran 48
DAFTAR
PUSTAKA ........................................................................................... 49
RIWAYAT
HIDUP …........................................................................................... 51
LAMPIRAN-LAMPIRAN.................................................................................. 52
LAMPIRAN
A INSTRUMEN PENELITIAN.................................................... 52
LAMPIRAN
B HASIL ANALISIS DATA ….................................................... 62
LAMPIRAN
C SURAT-SURAT …..................................................................... 68
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan
Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan Kurikulum 1994 20
Tabel 3.1 Keadaan
Guru Matematika Kelas X dan Kelas XII SMA Negeri 1 Makassar … 32
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN
A: Instrumen Penelitian
LAMPIRAN
B: Hasil Analisis Data
LAMPIRAN
C: Surat-Surat
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan adalah penentu terbesar
perkembangan masa depan bangsa. Makin besar perhatian kita terhadap bidang
pendidikan, ditambah lagi dengan ketepatan arah pendidikan yang dicanangkan,
niscaya akan membawa bangsa atau daerah tersebut pada tingkat kemajuan yang
memadai, sehingga tidak akan tertinggal atau ditinggalkan oleh bangsa lain.
Pendidikan di Indonesia dewasa ini masih jauh tertinggal dibanding pendidikan
di negara lain. Untuk mengantisipasi hal tersebut salah satu aspek yang perlu
diperhatikan adalah materi atau yang biasa disebut kurikulum.
Kurikulum dalam suatu sistem pendidikan merupakan
komponen yang penting. Dikatakan demikian karena kurikulum merupakan penuntun
dalam proses belajar mengajar (PBM) di sekolah. Oleh karena itu kurikulum
selalu dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam
faktor-faktor yang mendasarinya. Tujuan pendidikan dapat berubah secara
fundamental bila suatu negara yang dijajah menjadi negara yang merdeka,
sehingga dengan sendirnya kurikulum pun harus mengalami perubahan yang
menyeluruh.
|
Kurikulum dapat pula mengalami perubahan bila
terdapat pendirian baru mengenai proses belajar mengajar, sehingga timbul
berbagai bentuk kurikulum. Perubahan dalam masyarakat, eksplosi ilmu
pengetahuan, dan lain-lain mengharuskan adanya perubahan kurikulum.
Perubahan-perubahan itu menyebabkan kurikulum yang berlaku tidak lagi relevan,
dan ancaman serupa ini akan senantiasa dihadapi setiap kurikulum, betapapun
relevannya pada suatu saat.
Agar pendidikan memiliki relevansi dengan perkembangan zaman, maka
perlu sekali praktek pendidikan diarahkan pada pendidikan yang berbasis
kompetensi. Artinya praktek pendidikan dapat membekali siswa sejumlah
keterampilan (life skill). Dengan life skill, yang tidak
semata-mata mengandalkan kemampuan akademik melainkan juga non akademik, siswa
dapat memaknai perjalanan hidupnya dengan kearifan.
Berkaitan dengan life skill, para guru atau pendidik harus
dapat menguasai keterampilan tertentu, sehingga para siswa dapat difasilitasi
untuk meningkatkan keterampilan dasarnya menjadi suatu keterampilan yang lebih
tinggi. Santoso (dalam Qomari Anwar, 2002) mengatakan bahwa tugas penting
seorang pendidik atau guru ialah menguasai keterampilan melatih, dan membimbing
siswa supaya mau dan mampu secara cermat dan tekun melakukan observasi terhadap
berbagai peristiwa atau persoalan yang terjadi di sekelilingnya.
Dalam rumusan tujuan pembelajaran, life skill didefinisikan sebagai
suatu kecakapan mengaplikasikan kemampuan dasar keilmuan atau kejuruan dalam
kehidupan sehari-hari, sehingga bermakna dan bermanfaat bagi peningkatan taraf
kehidupannya serta harkat dan martabatnya, dan juga memberikan manfaat bagi
masyarakat dan lingkungannya (Suderadjat : 2004).
Sekolah sebagai sebuah masyarakat kecil (mini society) yang merupakan wahana pengembangan peserta didik
dituntut untuk menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis (democratic instruction) agar terjadi
proses belajar mengajar yang menyenangkan (joyfull
learning). Dengan iklim yang demikian, pendidikan diharapkan mampu
melahirkan calon-calon penerus pembangunan masa depan yang sabar, kompeten,
mandiri, kritis, rasional, cerdas, kreatif, dan siap menghadapi berbagi macam
tantangan, dengan tetap bertawakal terhadap Sang penciptanya. Untuk kepentingan
tersebut diperlukan perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pendidikan
nasional, yang dipandang oleh berbagai pihak sudah tidak efektif, dan tidak
mampu lagi memberikan bekal, serta tidak dapat mempersiapkan peserta didik
untuk bersaing dengn bangsa-bangsa lain di dunia. Perubahan mendasar tersebut
berkaitan dengan kurikulum, yang dengan sendirinya menuntut dan mempersyaratkan
berbagai perubahan pada komponen-komponen pendidikan lain.
Berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang dapat membekali peserta didik dengan
berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman, guna menjawab tantangan
arus globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan
sosial, lentur, dan adaptif terhadap berbagai perubahan.
KBK diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa, khususnya
dalam bidang pendidikan, dengan mempersiapkan peserta didik melalui
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap sistem pendidikan secara
efektif, efisien dan berhasil guna.
Sejak tahun anggaran 2000/2001 Pusat Kurikulum Balitbang Diknas
telah melakukan pengembangan KBK. Mulai tahun ajaran 2001/2002 KBK diimplementasikan
secara terbatas dalam bentuk mini piloting di beberapa daerah/sekolah. Daerah
yang dijadikan mini piloting yaitu Sidoarjo di Jawa Timur, Bandung di Jawa
Barat, Serang di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta dan di DKI Jakarta
(Siskandar: 2003). Sementara pemerintah kota Makassar merencanakan untuk
memberlakukan KBK pada tahun pelajaran 2003/2004, namun masih banyak sekolah
yang belum memberlakukannya, dan pelaksanaannya masih dalam tahap uji coba
(Nuryadi: 2004). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah seorang guru
Matematika SMA Negeri 1 Makassar, terdapat beberapa persepsi guru tentang
pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Makassar.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi guru matematika terhadap
pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mata pelajaran matematika di
SMA Negeri 1 Makassar ?”.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi guru matematika
terhadap pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mata pelajaran
matematika di SMA Negeri 1 Makassar .
D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya informasi tentang pelaksanaan Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK) mata pelajaran
matematika di SMA Negeri 1 Makassar , maka
manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Kepala Sekolah SMA Negeri 1
Makassar dapat digunakan sebagai informasi sekaligus sebagai acuan dalam
pengambilan kebijakan terhadap pelaksanaan KBK di SMA Negeri 1 Makassar pada
umumnya dan mata pelajaran matematika pada khususnya.
2. Bagi para pendidik khususnya
guru-guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Makassar dapat dijadikan
sebagai acuan dalam meningkatkan kreatifitas mengajarnya.
3.
Bagi
penulis sendiri di samping sebagai latihan dalam usaha penyumbangan buah
pikiran secara tertulis, juga sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan
diri untuk terjun ke lapangan.
BAB II
 TINJAUAN
PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR
TINJAUAN
PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR
B. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Kurikulum Berbasis
Kompetensi
Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang
dirumuskan oleh pakar-pakar kurikulum sejak dulu sampai dewasa ini. Istilah
kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni “Curriculae”, artinya jarak
yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Kurikulum merupakan salah satu alat
untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus merupakan pedoman dalam
pelaksanaan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum disusun harus
berdasarkan falsafah dan pandangan hidup bangsa.
Dalam pengembangan kurikulum, masing-masing ahli
kurikulum melihat dari sisi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mengarah
pada satu tujuan yang sama. “Lazimnya kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk
melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab
lembaga pendidikan beserta stafnya” (Nasution 1999: 5).
Soetjipto (1999:148) mengemukakan bahwa kurikulum adalah
seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya
yang tersususun secara sistematik dan dipedomani oleh sekolah dalam kegiatan
mendidik siswanya.
Kurikulum adalah seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003
tentang sistem pendidikan, 2003: 5)
Menurut Oemar Hamalik (2003: 22) mengemukakan bahwa
“Kurikulum dalam arti luas meliputi komponen-komponen yaitu tujuan pendidikan, tujuan instruksional,
alat dan metode instruksional, pemilihan dan pembimbingan siswa, materi
program, evaluasi dan staf pelaksanaan”.
Lebih rinci lagi Hilda Taba (S. Nasution ; 2003)
mengemukakan bahwa:
“Pada hakikatnya tiap kurikulum
merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak agar berpartisipasi sebagai
anggota yang produktif dalam masyarakatnya. Tiap kurikulum, bagaimanapun
polanya, selalu mempunyai komponen-komponen tertentu, yakni pernyataan tentang
tujuan dan sasaran, seleksi dan organisasi bahan dan isi pelajaran, bentuk dan
kegiatan belajar dan mengajar, dan akhirnya evaluasi hasil belajar”
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum secara
luas adalah suatu rencana atau bahan tertulis yang sengaja disusun untuk
dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan
yang berada di sekolah. Jadi kurikulum tidak hanya merupakan seperangkat mata
pelajaran tetapi menyangkut pula bagaimana pelajaran itu diorganisasikan
menjadi pengalaman yang berharga bagi siswa.
Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan,
keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan
bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus
memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu.
Kompetensi diartikan sebagai
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah
menjadi bagian dari dirinya, sehingga dapat melakukan perilaku-perilaku
kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya (Mulyasa, 2004: 38).
Sejalan dengan itu, Finc dan Crukinton (Mulyasa, 2004:
38) mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas,
keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.
Menurut Sudjatmiko (2003) untuk menjadi kompeten dalam bidang tertentu, seseorang harus
secara konsisten dan terus menerus menunjukkan kompetensi dalam bidang tersebut
dalam cara berpikir dan berperilaku/bertindak sehari-hari.
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan suatu
format yang menetapkan apa yang diharapkan dapat dicapai siswa dalam setiap tingkatan. Rumusan
kompetensi dalam KBK adalah suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan dapat
diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam setiap tingkatan kelas dan
sekolah dan sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara bertahap
dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten.
KBK merupakan pergeseran penekanan dan isi (apa yang
tertuang) ke kompetensi (bagaimana harus berpikir, belajar dan melakukan) dalam
kurikulum. Oleh karena itu guru dan siswa diharapkan dapat mengetahui apa yang
harus dicapai dan sejauh mana efektivitas belajar dicapai.
KBK dapat diartikan sebagai suatu
konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan
(kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya
dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi
tertentu (Mulyasa, 2004: 39).
Menurut Sudjatmiko (2003), KBK pada dasarnya
merupakan format atau standar yang menetapkan kompetensi apa yang diharapkan
dapat dicapai siswa dalam setiap tingkatan kelas atau jenjang tertentu agar memiliki
kecakapan hidup sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian,
kurikulum ini merupakan pergeseran penekanan dari isi (apa yang tertuang) ke
kompetensi (bagaimana berpikir, bersikap, belajar dan melakukan).
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
KBK memfokuskan pada perolehan kompetensi-kompetensi oleh peserta didik karena
itu kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi, dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan
sedemikian rupa, sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau
keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan.
2. Karakteristik Kurikulum Berbasis
Kompetensi
Karakterstik KBK antara lain mencakup seleksi kompetensi
yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan kesuksesan pencapaian kompetensi, dan
pengembangan sistem pembelajaran.
Depdiknas (2002) yang dikutip oleh Mulyasa (2004)
mengemukakan bahwa KBK memiliki karakteristik: (a) menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara
individual maupun klaksikal, (b) berorientasi pada hasil belajar (learning
outcomes) dan keberagaman, (c) penyampaian dalam pembelajaran menggunakan
pendekatan dan metode yang bervariasi, (d) sumber belajar bukan hanya guru,
tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif, dan (e)
penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau
pencapaian suatu kompetensi.
Mulyasa (2004: 43) mengungkapkan bahwa karakteristik kurikulum
berbasis kompetensi, yaitu:
a. Sitem belajar dengan modul.
KBK menggunakan modul sebagai sistem pembelajaran. Dalam
hal ini, modul merupakan paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian
pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematik untuk
membantu peserta didik mencapai tujuan belajar.
Senada dengan definisi di atas, Erman Suherman, dkk.
(2003: 258) mengungkapkan bahwa modul adalah suatu paket pembelajaran yang
memuat suatu unit konsep pembelajaran yang dapat dipelajari oleh siswa sendiri
(self instruction). Sedangkan menurut Mulyasa (2004) bahwa modul adalah
pernyataan satuan pembelajaran dengan tujuan-tujuan, pre tes aktivitas belajar
yang memungkinkan peserta didik memperoleh kompetensi yang belum dikuasai dari
hasil pre tes, dan mengevaluasi kompetensinya untuk mengukur keberhasilan
belajar. Tujuan utama sistem modul adalah untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pembelajaran di sekolah, baik waktu, dana, fasilitas, maupun tenaga
guna mencapai tujuan secara optimal.
b. Menggunakan keseluruhan sumber
belajar.
Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) guru tidak
lagi berperan utama dalam proses pembelajaran karena pembelajaran dapat
dilakukan dengan mendayagunakan aneka ragam sumber belajar. Sumber belajar
adalah segala sesuatu yang dapat memberi kemudahan kepada peserta didik dalam
memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, dalam
proses belajar mengajar. Sumber belajar tersebut antara lain:
1) Manusia, yaitu orang yang
menyampaikan pesan secara langsung, seperti: guru.
2) Bahan, yaitu sesuatu yang mengandung
pesan pembelajaran, seperti: buku, peta, film pendidikan, dan lain-lain.
3) Lingkungan, yaitu ruang dan tempat
di mana sumber-sumber dapat berinteraksi dengan para peserta didik, misalnya:
perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, dan lain-lain.
4) Alat dan peralatan, yaitu sumber
belajar untuk memproduksi dan memainkan sumber-sumber lain. Alat dan peralatan
untuk memproduksi, misalnya: kamera untuk memproduksi foto, dan tape recorder
untuk rekaman. Sedang alat dan peralatan untuk memainkan sumber lain, misalnya
komputer, proyektor film, televisi, dan radio.
5) Aktivitas, yaitu sumber belajar yang
biasanya merubah kombinasi antara suatu teknik dengan sumber lain untuk
memudahkan belajar, misalnya: pengajaran berprograma merupakan kombinasi antara
teknik penyajian bahan dengan buku, contoh lainnya seperti simulasi dan
karyawisata.
c. Pengalaman lapangan.
KBK lebih menekankan pada pengalaman lapangan untuk
mengakrabkan hubungan antara guru dengan peserta didik. Keterlibatan anggota
tim guru dalam pembelajaran di sekolah memudahkan mereka untuk mengikuti
perkembangan yang terjadi selama peserta didik mengikuti pembelajaran. Di
samping itu, pengalaman lapangan dapat sistematis melibatkan masyarakat dalam
pengembangan program, aktivitas dan evaluasi pembelajaran.
d. Strategi belajar individual
personal.
KBK mengusahakan strategi belajar individual personal.
Belajar individual adalah belajar berdasarkan tempo belajar peserta didik,
sedangkan belajar personal adalah interaksi edukatif berdasarkan keunikan
peserta didik: bakat, minat dan kemampuan (personalisasi).
e. Kemudahan belajar.
Kemudahan belajar dalam KBK diberikan melalui kombinasi
antara pembelajaran individual personal dengan pengalaman lapangan, dan
pembelajaran secara tim (team teaching). Hal tersebut dilakukan melalui
berbagai saluran komunikasi yang dirancang untuk itu, seperti video, televisi,
radio, buletin, jurnal, dan surat
f. Belajar tuntas.
Belajar tuntas dalam KBK merupakan strategi pembelajaran
yang dapat dilaksanakan di dalam kelas, dengan asumsi bahwa di dalam kondisi
yang tepat semua peserta didik akan mampu belajar dengan baik dan memperoleh
hasil belajar secara maksimal terhadap seluruh bahan yang dipelajari. Agar
semua peserta didik memperoleh hasil belajar secara maksimal, pembelajaran
harus dilaksanakan dengan sistimatis.
3. Pengembangan Kurikulum Berbasis
Kompetensi
Pengembangan KBK memfokuskan pada kompetensi tertentu,
berupa paduan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat didemonstrasikan
oleh peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya.
a.
Tingkat pengembangan kurikulum.
1)
Pengembangan kurikulum tingkat Nasional
2)
Pengembangan kurikulum tingkat lembaga
3)
Pengembangan kurikulum tingkat bidang studi
(penyusunan silabus)
4)
Pengembangan kurikulum tingkat satuan bahasan
(modul)
b.
Prinsip-prinsip pengembangan Kurikulum Berbasis
Kompetensi.
Sesuai dengan kondisi negara, kebutuhan masyarakat, dan berbagai
perkembangan serta perubahan yang berlangsung dewasa ini, maka dalam
pengembangan KBK perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip
yaitu: (1) keimanan, nilai dan budi pekerti luhur, (2) penguatan integrasi
nasional, (3) keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika, (4)
kesamaan memperoleh kesempatan, (5) abad pengetahuan dan teknologi
informasi,(6) pengembangan keterampilan
untuk hidup, (7) belajar sepanjang hayat, (8) berpusat pada anak dengan
penilaian yang berkelanjutan dan komperhensif , dan (9) pendekatan menyeluruh
dan kemitraan.
4. Landasan Penerapan Kurikulum
Berbasis Kompetensi
Suderadjat (2004) mengatakan
bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia melalui pembelajaran dalam
bentuk aktualisasi potensi peserta didik menjadi suatu kemampuan atau
kompetensi. Dalam istilah kompetensi, potensi adalah kemampuan yang masih
terpendam, dan dalam istilah potensi, kompetensi adalah potensi yang telah
aktual. Sudrajat melanjutkan bahwa potensi seseorang akan berubah menjadi
kompetensi melalui proses belajar dan berlatih.
Kurikulum yang diterapkan di suatu negara tidak terlepas dari kebutuhan bangsa, masyarakat pemakai
(Martinis Yamin, 2005: 128–129), maka kurikulum di Indonesia
a.
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999
yang menegaskan perlunya didiversifikasi kurikulum yang dapat melayani
keanekaragaman sumber daya manusia, kemampuan siswa, sarana pembelajaran, dan
budaya daerah.
b.
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 (Pasal 4) tentang
pemerintahan daerah yang menegaskan adanya kewenangan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
c.
Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
nomor 20 tahun 2003 Bab IX (pasal 35) ayat (1) bahwa standar pendidikan terdiri
atas isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus
ditingkatkan secara berencana dan berkala. Ayat (2) standar nasional pendidikan
digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, pengelolaan, pembiayaan. Demikian juga pada Bab X (pasal 36) ayat
(2) kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan
prinsip diversifikasi sesusai dengan satuan pendidikan, potensi, daerah, dan
peserta didik.
5. Implementasi Kurikulum Berbasis
Kompetensi
Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep,
kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak
baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.
Berdasarkan definisi dari implementasi tersebut, maka implementasi KBK dapat
didefinisikan sebagai suatu proses penerapan ide, konsep dan kebijakan
kurikulum (kurikulum potensial) dalam suatu aktivitas pembelajaran, sehingga
peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu, sebagai hasil
interaksi dengan lingkungan. Implementasi kurikulum juga dapat diartikan
sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam pembelajaran.
Dalam garis besarnya implementasi KBK mencakup tiga
kegiatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan
evaluasi.
a. Pengembangan program.
Pengembangan KBK mencakup pengembangan program tahunan,
program semester, program modul (pokok bahasan), program mingguan dan harian,
program pengayaan dan remedial, serta program bimbingan dan konseling.
1)
Program tahunan.
Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap
kelas, yang dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran, karena merupakan
pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya.
2)
Program semester.
Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak
dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut.
3)
Program modul (pokok bahasan).
Program modul dikembangkan dari setiap kompetensi dan pokok bahasan yang
akan disampaiakan.
4) Program
mingguan dan harian.
Program mingguan dan harian merupakan penjabaran dari program semester
dan program modul yang bertujuan untuk membantu kemajuan belajar peserta didik.
5)
Program pengayaan dan remedial
Program pengayaan dan remedial merupakan pelengkap dan penjabaran dari
program mingguan dan harian.
6)
Program bimbingan dan konseling.
Program
bimbingan dan konseling merupakan program yang wajib diberikan oleh sekolah
kepada peserta didik yang menyangkut pribadi, sosial, belajar dan karier.
b. Pelaksanaan pembelajaran.
Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi
antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku
ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama
adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku
bagi peserta didik. Oleh karena itu, dalam melakukan pembelajaran guru
memerlukan berbagai strategi. Strategi pembelajaran pada KBK hendaknya
menggunakan pendekatan dan metode yang bervariatif (konstruktivisme,
inquiry, discovery, contextual learning) sehingga: (1) siswa lebih aktif,
(2) iklim pembelajaran menyenangkan, (3) fungsi guru bergeser dari pemberi
informasi menjadai fasilitator, (4) materi terkait dengan lingkungan siswa, (5)
siswa terbiasa mencari informasi dari berbagai sumber, dan (6) menggeser
paradigma pembelajaran dari “teaching” menjadi “learning”.
c. Evaluasi hasil belajar.
Evaluasi hasil belajar dalam implementasi KBK dilakukan
dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan
dan sertifikasi, benchmarking, dan penilaian program.
Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan
umum, dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses
pembelajaran dalam satuan bahasan atau kompetensi tertentu. Ulangan harian
minimal dilakukan tiga kali dalam tiap semester.
Ulangan umum dilaksanakan setiap akhir semester, dengan
bahan yang diujikan yaitu; ulangan umum semester pertama soalnya diambil dari
materi semester pertama, ulangan umum semester kedua soalnya merupakan gabungan
dari materi semester pertama dan kedua, dengan penekanan pada materi semester
kedua.
Ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan.
Bahan-bahan yang diujikan meliputi seluruh materi modul yang telah diberikan,
dengan penekanan pada bahan-bahan yang diberikan pada kelas-kelas tinggi.
Sementara penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan
hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan
balik untuk perbaikan proses pembelajaran, dan penentuan kenaikan kelas.
Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan
membaca, menulis dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program
pembelajaran (program remedial). Tes kemampuan dasar dilakukan pada setiap
tahun.
Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi,
dilakukan pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran, guna mendapatkan gambaran
secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam
satuan waktu tertentu.
Benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang
berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan.
Ukuran keunggulan dapat ditentukan di tingkat sekolah, daerah, atau nasional.
Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga peserta didik dapat
mencapai satuan tahap keunggulan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan
usaha dan keuletannya.
Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan
Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Penilaian
program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi
dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan
perkembangan masyarakat, dan kemajuan jaman.
6. Peranan Kepala Sekolah dan Guru
dalam pengembangan kurikulum
a. Kepala Sekolah.
Keberhasilan KBK dengan beberapa indikatornya sangat
ditentukan oleh kepala sekolah dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan
menselaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala
sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat
mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang
dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, kepala sekolah
dituntut memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu
mengambil keputusan dan prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah.
Untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah harus mampu
memobilisasi sumber daya sekolah. Dalam kaitannya dengan perencanaan dan
evaluasi program sekolah, pengembangan kurikulum, pembelajaran, pengelolaan
ketenagaan, sarana dan sumber belajar, keuangan, pelayanan siswa, hubungan
sekolah dengan masyarakat, dan penciptaan iklim sekolah.
b. Guru.
Guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya
terhadap keberhasilan penerapan KBK, bahkan sangat menentukan berhasil-tidaknya
peserta didik dalam belajar. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa hal yang
harus dipahami guru dari peserta didik, antara lain: kemampuan potensi, minat,
hoby, sikap, kepribadian, kebiasaan, catatan kesehatan, latar belakang
keluarga, dan kegiatannya di sekolah. Moh. Uzer Usman (2001) mengatakan bahwa
guru berperan sebagai pengelola proses belajar mengajar.
Agar implementasi KBK berhasil memperhatikan perbedaan
individual, maka guru perlu memperhatikan hal-hal berikut: (1) mengurangi
metode ceramah, (2) memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik,
(3) mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya, serta disesuaikan
dengan mata pelajaran, (4) bahan harus dimodifikasi dan diperkaya, (5)
menghindari ragu untuk berhubungan dengan spesialist, bila ada peserta didik
yang mempunyai kelainan, (6) menggunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat
penilaian dan membuat laporan, (7) mengingat bahwa peserta didik tidak
berkembang dalam kecepatan yang sama, (8) mengusahakan mengembangkan situasi
belajar yang memungkinkan setiap anak bekerja dengan kemampuannya masing-masing
pada tiap pelajaran, dan (9) mengusahakan untuk melibatkan peserta didik dalam
berbagai kegiatan.
7. Perbedaan dan keunggulan Kurikulum
2004 dengan Kurikulum 1994
a. Perbedaan KBK dengan Kurikulum 1994.
Perbedaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan kurikulum
1994 disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 2. 1
Perbedaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan Kurikulum 1994.
|
NO
|
KURIKULUM 1994
|
KBK
|
|
1
|
||
|
2
|
Standar akademis yang diterapkan secara
seragam bagi setiap peserta didik.
|
Standar akademis yang memperhatikan perbedaan
individu, baik kemampuan, kecepatan belajar maupun konteks sosial budaya.
|
|
3
|
Berbasis konten, sehingga peserta didik
dipandang sebagai kertas putih yang perlu ditulis dengan sejumlah ilmu
pengetahuan.
|
Berbasis kompetensi, sehingga peserta didik
berada dalam proses perkembangan yang berkelanjutan dari seluruh aspek
kepribadian, sebagai pemekaran terhadap kompetensi-kompetensi bawaan sesuai
dengan kesempatan belajar yang ada dan diberikan oleh lingkungan.
|
|
4
|
Pengembangan kurikulum dilakukan secara
desentralisasi sehingga pemerintah bersama-sama menentukan standar pendidikan
yang dituangkan ke dalam kurikulum.
|
|
|
5
|
Materi yang dikembangkan dan diajarkan di
sekolah sering kali tidak sesuai dengan potensi sekolah, kebutuhan dan
kemampuan peseta didik, serta kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah.
|
Sekolah diberi keleluasaan untuk menyusun dan
mengembangkan silabus mata pelajaran sehingga dapat mengakomodasi potensi
sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakata
sekitar sekolah.
|
|
6
|
Guru merupakan yang menentukan segala sesuatu
yang terjadi di dalam kelas.
|
Guru sebagai fasilitator yang bertugas
mengkondisikan lingkungan untuk memberikan kemudahan belajar peserta didik.
|
|
7
|
Pengetahuan, keterampuilan, dan sikap
dikembangkan melalui latihan, seperti latihan mengerjakan soal.
|
Pengetahuan, keterampuilan, dan sikap
dikembangkan berdasarkan pemahaman yang akan membentuk kompetensi individual.
|
|
8
|
Pembelajaran cenderung hanya dilakukan di
dalam kelas, atau dibatasi oleh 4 dinding kelas.
|
Pembelajaran yang dilakukan mendorong
terjadinya kerja sama antara sekolah, masyarakat, dan dunia kerja dalam
membentuk komposisi peserta didik.
|
|
9
|
Evaluasi nasional yang tidak dapat menyentuh
aspek-aspek kepribadian peserta didik.
|
Evaluasi berbasis kelas, yang menekankan pada
proses dan hasil belajar.
|
Sumber:
Mulyasa; 2004
b. Keunggulan KBK.
KBK mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan
dengan model-model lain, yaitu: (1) pendekatan KBK bersifat alamiah,
(konseptual) karena berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakekat peserta
didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya
masing-masing, dalam hal ini peserta didik merupakan subjek belajar, dan proses
belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami
berdasarkan standar kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan, (2) KBK
mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain penguasaan ilmu pengetahuan,
dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam
kehidupan sehari-hari serta mengembangkan aspek-aspek kepribadian dapat
dilakukan secara optimal berdasarkan kompetensi tertentu, (3) bidang-bidang
studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat
menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan.
8. Pengembangan silabus dalam KBK
Penyusunan silabus dapat dilakukan dengan melibatkan
para ahli atau instansi yang relevan di daerah setempat seperti tokoh
masyarakat, instansi pemerintah, instansi swasta termasuk perusahaan dan
industri, dan perguruan tinggi. Bantuan dan bimbingan teknisi untuk penyusunan
silabus sepanjang diperlukan dapat diberikan oleh pusat kurikulum.
a. Prosedur pengembangan silabus KBK.
Untuk memberi kemudahan kepada daerah dan sekolah dalam
mengembangkan silabus maka dirasakan perlu menyajikan prosedur pengembangan
silabus KBK, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan revisi.
1) Perencanaan. Dalam perencanaan ini
tim pengembang silabus mengumpulkan informasi dan reverensi, serta
mengidentifikasi sumber belajar termasuk nara
2) Pelaksanaan. Pelaksanaan penyusunan
silabus dapat dilakukan dengan langkah-langkah yaitu; merumuskan kompetensi dan
tujuan pembelajaran, serta menentukan materi pembelajaran yang memuat
kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator hasil belajar; menentukan metode
dan teknik pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran; dan menentukan alat
penilaian berbasis kelas sesuai dengan misi KBK.
3)
Revisi. Draft silabus yang
telah dikembangkan perlu diuji kelayakannya melalui analisis kualitas silabus,
penilaian ahli, dan uji lapangan. Berdasarkan uji kelayakan kemudian dilakukan
revisi. Revisi ini pada hakikatnya perlu dilakukan secara kontinyu dan
berkesinambungan, sejak awal penyusunan draft sampai silabus tersebut
dilaksanakan dalam situasi belajar yang sebenarnya
b. Peran dan Tanggung Jawab Berbagai
Pihak dalam Pengembangan Silabus.
Pihak-pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab secara langsung
dalam pengembangan silabus dalam pengembangan KBK adalah pusat pengembangan
kurikulum (Puskur) Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi,
Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten, serta sekolah yang akan
mengimplementasikan KBK, sesuai dengan kapasitas dan proporsinya masing-masing.
9. Hambatan penerapan Kurikulum
Berbasis Kompetensi
Beberapa faktor yang dapat menjadi sumber
penghambat dalam proses penerapan KBK mata pelajaran matematika yaitu pertama,
dari segi guru sebagai unsur utama yang bertugas sebagai pendidik dalam proses
belajar mengajar di kelas. Guru harus mempunyai kualifikasi kompetensi
mengajar, meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam penggunaan metode
dan pengelolaan kelas. Untuk mencapai tujuan KBK secara maksimal, guru perlu
meningkatkan kemampuannya dengan cara mengikuti penataran-penataran,
pelatihan-pelatihan, atau seminar-seminar tentang penerapan KBK.
Kedua, siswa sebagai subjek belajar dalam pelaksanaan pengajaran
dapat merupakan suatu sumber hambatan dalam penerapan, misalnya: tingkat
kecerdasan, kreativitas, minat, dan jumlah yang tidak sesuai dengan daya
tampung ruangan.
Ketiga, sarana dan prasarana dapat juga menjadi sumber hambatan
penerapan KBK, misalnya: fasilitas gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium
komputer, dan penggunaan alat peraga. Keempat, dari segi alokasi waktu yang
merupakan salah satu unsur penghambat dalam penerapan KBK. Kelima, evaluasi
atau penilaian yang merupakan proses yang sistematis untuk mengetahui tingkat
keberhasilan dan efisiensi suatu pembelajaran, namun sering juga menjadi
penghambat dalam penerapan KBK.
10. Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata
Pelajaran Matematika
a. Pengertian matematika.
Istilah mathematics (Inggris), mathematik (Jerman), mathematique
(Perancis), matematico (Itali), matematiceski (Rusia), atau mathematick
(Belanda) berasal dari perkataan latin mathematica, yang mulanya diambil
dari perkataan Yunani, mathematike, yang berarti “relating to
learning”. Perkataan mathematike berhubungan sangat erat dengan
sebuah kata lainnya yang serupa, yaitu mathanein yang mengandung arti
belajar (berpikir). Jadi berdasarkan etimologis (Elea Tinggih dalam Erman
Suherman, 2003:16), perkataan matematika berarti “ilmu pengetahuan yang
diperoleh dengan bernalar”.
James dan
James (1976) dalam kamus matematikanya mengatakan bahwa matematika adalah ilmu
tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang
berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke
dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis dan geometri.
Johnson dan
Rising (1972) dalam bukunya mengatakan bahwa matematika adalah pola pikir, pola
mengorganisasikan, pembuktian yang logik, matematika itu adalah bahasa yang
menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat,
representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai
ide dari pada mengenai bunyi. Sementara Reys, dkk. (1984) mengatakan bahwa
matematika adalah telaah tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola
pikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat.
Berdasarkan
pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa ciri yang sangat penting dalam
matematika adalah disiplin berpikir yang didasarkan pada berpikir logis,
konsisten, inovatif dan kreatif.
b. Fungsi dan tujuan.
Matematika
berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan dan
menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari
melalui pengukuran dan geometri, aljabar, peluang dan statistik, kalkulus dan
trigonometri. Matematika juga berfungsi mengembangkan kemampuan
mengkomunikasikan gagasan melalui model matematika yang dapat berupa kalimat
matematika dan persamaan matematika, diagram, grafik atau tabel.
Tujuan umum pendidikan matematika ditekankan kepada siswa untuk
memiliki:
1)
Kemampuan yang berkaitan dengan matematika yang
dapat digunakan dalam memecahkan masalah matematika, pelajaran lain ataupun
masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata.
2)
Kemampuan menggunakan matematika sebagai alat
komunikasi.
3)
Kemampuan menggunakan matematika sebagai cara
bernalar yang dapat dialihgunakan pada setiap keadaan, seperti berpikir kritis,
berpikir logis, berpikir sistematis, bersifat objektif, bersifat jujur,
bersifat disiplin dalam memandang dan menyelesaikan suatu masalah.
c. Ruang lingkup.
Standar kompetensi matematika merupakan seperangkat kompetensi
matematika yang dibukukan dan harus ditunjukkan oleh siswa pada hasil
belajarnya dalam mata pelajaran matematika. Standar ini dirinci dalam komponen
kompetensi dasar beserta hasil belajarnya, indikator dan materi pokok untuk
setiap aspeknya. Pengorganisasian dan pengelompokan materi pada materi
didasarkan menurut disiplin ilmunya atau didasarkan menurut kemahiran atau
kecakapan yang hendak dicapai. Aspek atau ruang lingkup materi pada standar
kompetensi matematika adalah bilangan, pengukuran dan geometri, aljabar,
trigonometri, peluang dan statistik, dan kalkulus.
d. Standar Kompetensi Mata Pelajaran
Matematika.
Untuk mata
pelajaran matematika di SMA, telah dirumuskan sembilan standar kompetensi
(Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Ditjen. Dikdasmen, Depdiknas; 2003:2)
sebagai berikut:
1)
Menggunakan operasi dan sifat serta sifat
manipulasi aljabar dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan bentuk
pangkat, akar, dan logaritma; persamaan kuadrat dan fungsu kuadrat; sistem
persamaan linear-kuadrat; pertidaksamaan satu variabel; logika matematika.
2)
Menggunakan perbandingan fungsi, persamaan, dan
identitas persamaan trigonometri dalam pemecahan masalah.
3)
Menggunakan sifat dan aturan geometri dalam
menentukan kedudukan titik, garis dan bidang; jarak; sudut; dan volum.
4)
Menggunakan aturan statistika dalam menyajikan
dan meringkas data dengan berbagai cara serta memberi tafsiran; menyusun dan
menggunakan kaidah pencacahan dalam menentukan banyak kemungkinan; dan
menggunakan aturan peluang dalam menentukan dan menafsirkan peluang kejadian
majemuk.
5)
Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang
rumus trigonometri dan menyusun bukti.
6)
Menyusun dan menggunakan persamaan lingkaran
beserta garis singgungnya; menggunakan algoritma pembagian, teorema sisa, dan
teorema faktor dalam pemecahan masalah; menggunakan operasi dan manipulasi
aljabar dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi dan
fungsi invers.
7)
Menggunakan konsep limit fungsi dan turunan
dalam pemecahan masalah.
8)
Menggunakan konsep integral dalam pemecahan
masalah.
9)
Merancang dan menggunakan model matematika
program linear serta menggunakan sifat dan aturan yang berkaitan dengan
barisan, deret, matriks, vektor, transformasi, fungsi eksponen dan logaritma
dalam pemecahan masalah.
e. Pengorganisasian materi.
Kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan
standar kompetensi mata pelajaran
matematika yang harus diketahui,
dilakukan dan dimahirkan oleh setiap siswa pada setiap tingkatan. Kerangka ini
disajikan dalam empat komponen utama, yaitu: 1) standar kompetensi, yaitu
tujuan yang hendak dicapai oleh peserta didik setelah melakukan proses belajar
mengajar untuk suatu materi pokok sesuai dengan tingkat pendidikan yang telah
ditentukan secara nasional, 2) kompetensi dasar, yaitu kompetensi minimal yang
harus dipahami oleh peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar, 3)
indikator, yaitu alat untuk mengukur panguasaan peserta didik terhadap suatu
kompetensi dasar, dan 4) materi pokok, yaitu materi pelajaran yang disajikan
kepada peserta didik berupa penjabaran sub pokok bahasan dari awal semester
sampai akhir semester secara terstruktur.
C. Kerangka Berpikir
Setelah
memperhatikan beberapa uraian yang telah disusun di atas, ada beberapa hal yang
menjadi landasan berpikir dan selanjutnya mengarahkan penulis untuk merumuskan
data sebagai bahan penelitian ini. Adapun landasan berpikir itu adalah:
kurikulum merupakan bahan tertulis yang berisi uraian tentang program
pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun. Proses
KBK dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai,
sikap, dan minat peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk
kamahiran, ketepatan dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab.
Pelaksanaan
KBK menuntut guru untuk lebih profesional dalam merancang ataupun menganalisis
semua perangkat-perangkat persiapan proses belajar mengajar, sehingga dapat
tercapai tujuan yahng diharapkan. Sebagai tenaga pendidik, guru perlu mendapat
perhatian utama di samping kurikulumnya, karena baik buruknya suatu kurikulum
bergantung pada aktivitas dan kreativitas guru dalam menjabarkan dan
merealisasikan kurikulum tersebut. KBK merupakan kurikulum yang baru dikenal
beberapa tahun terakhir ini, sehingga perlu mendapat perhatian dan tanggapan
yang serius. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui dan
mendeskripsikan tentang persepsi guru matematika terhadap pelaksanaan KBK khususnya mata pelajaran matematika di SMA Negeri
1 Makassar . Data yang diperoleh dalam
penelitian ini akan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.
BAB III
 METODE
PENELITIAN
METODE
PENELITIAN
A. Variabel dan Desain Penelitian
Inti kegiatan dalam penelitian ini adalah variabel persepsi guru
matematika terhadap pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mata
pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Makassar .
Oleh karena itu peneliti hanya ingin mengkaji satu variabel atau tidak mengkaji
hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggambarkan persepsi guru
matematika terhadap pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Makassar .
B. Devinisi Operasional Variabel
Untuk menghindari terjadinya persepsi atau intepretasi yang
berlainan antara penulis dengan pembaca, maka dianggap perlu untuk merumuskan
variabel penelitian secara operasional.
Persepsi guru matematika
terhadap pelaksanaan KBK matapelajaran matematika adalah pendapat atau
pandangan guru matematika terhadap pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika di
SMA Negeri 1 Makassar .
C. OBJEK PENELITIAN
|
Sesuai dengan rumusan masalah dalam
penelitian ini, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah guru yaitu
seluruh guru matematika yang mengajar di kelas X dan kelas XI sebanyak 5 orang
yang ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini:
Tabel
3.1. Keadaan guru matematika kelas X dan kelas XI SMA Negeri 1 Makassar
|
No
|
Guru
|
Mengajar di kelas
|
Mengikuti pelatihan/seminar/
penataran tentang KBK
|
|
|
|
|
|
Pernah
|
Tidak Pernah
|
|
1.
2.
3.
4.
5.
|
Guru I
Guru II
Guru III
Guru IV
Guru V
|
X1, X,2 X3
X4,
X,5 X6, X7
XI IPA1, XI IPA2, XI IPA3
XI IPA4,
XI IPA5, XI IPA6
XI IPS1,
XI IPS2, XI IPA7
|
Ö
Ö
Ö
-
Ö
|
-
-
-
Ö
-
|
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1.
Angket (kuesioner).
Angket
(kuesioner) adalah seperangkat pernyataan yang harus diisi oleh responden untuk
mengubah keterangan menjadi data, serta dapat pula digunakan untuk mengungkap
pengalaman yang dialami guru dalam melaksanakan KBK. Angket tersebut
menggunakan Skala Likert dengan lima alternatif pilihan yaitu Sangat Setuju
(SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju
(STS), dengan skor
untuk pernyataan positif (favourable) adalah SS = 5, S
= 4, R = 3, TS = 2, dan STS = 1 dan sebaliknya untuk pernyataan negatif (unfavourable).
2.
Wawancara
Wawancara
merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk
memberikan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan permasalahan penelitian.
Pedoman wawancara diberikan kepada 2 orang guru, yaitu masing-masing seorang
guru dari kelas X dan kelas XI yang dipilih secara acak. Wawancara yang
diberikan secara langsung kepada guru dalam bentuk wawancara terbuka yang
berisi beberapa pertanyaan tentang persepsi guru matematika terhadap
faktor-faktor pendukung pelaksanaan KBK serta hambatan-hambatan yang dihadapi
guru matematika dalam pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika SMA Negeri 1
Makassar.
E. TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik
analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif
deskriptif. Teknik analisis kuantitatif
deskriptif yaitu meliputi tabel persentase dan statistik skor mengenai
rata-rata (mean), standar deviasi, variansi, nilai maksimum, nilai
minimum, kemiringan (skewness), dan kecembungan (kurtosis) serta
pengkategorian karakteristik skor variabel persepsi guru matematika terhadap
pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Makassar.
Kriteria yang
digunakan untuk menentukan kategori skor hasil penelitian adalah skala Lima Lima lima
0% - 39%
dikategorikan sangat rendah
40% - 54%
dikategorikan rendah
55% - 74%
dikategorikan sedang
75% - 89%
dikategorikan tinggi
90% - 100%
dikategorikan sangat tinggi
Berdasarkan kriteria di atas, maka kriteria yang digunakan untuk
menentukan kategori skor persepsi guru matematika terhadap pelaksanaan KBK
adalah konversi lima Lima
Di mana:
R : Skor yang diperoleh
NP : Nilai persen
S : Skor maksimum ideal, yaitu skor yang diperoleh
jika semua butir dijawab maksimal oleh responden atau jumlah butir soal dikali
dengan skor tertinggi.
Kategori skor persepsi guru setelah diubah ke batas-batas skor
berdasarkan skala lima
0 – 49,38
dikategorikan sangat buruk
49,39 – 68,10
dikategorikan buruk
68,11 – 93,10
dikategorikan sedang
93,11 – 111,85
dikategorikan baik
11,86 – 125
dikategorikan sangat baik
Kategori skor persepsi guru setelah diubah ke batas-batas skor
berdasarkan skala lima
Kategori persepsi guru tentang pelaksanaan KBK tentang kebijakan
dalam KBK, di mana jumlah soal sebanyak 6 butir soal dengan skor tertinggi 5
diperoleh skor maksimum idealnya 30. Sehingga
kriteria yang digunakan untuk menentukan kategori skor persepsi guru
adalah sebagai berikut:
0 – 11,85
dikategorikan sangat buruk
11,86 – 16,35
dikategorikan buruk
16,36 – 22,35
dikategorikan sedang
22,36 – 26,85
dikategorikan baik
26,86 – 30,00
dikategorikan sangat baik
Kategori persepsi guru tentang pelaksanaan KBK tentang sumber dan
sarana pendidikan; metode dan strategi belajar mengajar; dan siswa sebagai
subjek belajar, di mana jumlah soal sebanyak 5 butir soal dengan skor tertinggi
5 diperoleh skor maksimum idealnya 25. Sehingga
kriteria yang digunakan untuk menentukan kategori skor persepsi guru
adalah sebagai berikut:
0 – 9,82 dikategorikan sangat buruk
9,83 – 13,63 dikategorikan buruk
13,64 – 18,63 dikategorikan sedang
18,64 –22,38 dikategorikan baik
22,39 – 25,00 dikategorikan sangat baik
Kategori persepsi guru tentang pelaksanaan KBK tentang
evaluasi/penilaian, di mana jumlah soal sebanyak 4 butir soal dengan skor
tertinggi 5 diperoleh skor maksimum idealnya 20. Sehingga kriteria yang digunakan untuk menentukan
kategori skor persepsi guru adalah sebagai berikut:
0 – 7,9 dikategorikan sangat buruk
8,0 – 10,9 dikategorikan buruk
11,0 – 14,9 dikategorikan sedang
15,0 – 20,0 dikategorikan baik
22,39 – 25,00 dikategorikan sangat baik
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
|
|
A. Penyajian Hasil Analisis Data
Data yang
dihasilkan dalam penelitian ini adalah data tentang persepsi guru matematika
terhadap pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mata pelajaran
matematika, faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan KBK mata pelajaran
matematika, dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru matematika dalam
pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Makassar.
1.
Hasil Angket Persepsi Guru
Matematika Terhadap Pelaksanaan Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK) Mata Pelajaran Matematika
Pada bagian
ini disajikan hasil angket yang telah diisi oleh guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Makassar mengenai
persepsi guru matematika terhadap pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika di
SMA Negeri 1 Makassar , seperti disajikan pada
lampiran B.
|
Tabel 4.2
pada lampiran B merupakan hasil analisis statistik deskriptif skor
persepsi guru matematika terhadap pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika,
yang menunjukkan bahwa dari jumlah sampel 5 orang memperoleh skor rata-rata
persepsi guru matematika terhadap pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika
adalah 105 dari skor ideal 125, dengan skor tertinggi 108 dan skor terendah 100
serta standar deviasi 3,317. Hal ini juga didukung oleh koefisien kemiringan
kurva (skewness) adalah –0,822 dan koefisien kecembungan (kurtosis) sebesar 0,140.
Jika skor variabel persepsi guru tersebut dikelompokkan ke dalam
lima kategori, maka diperoleh distribusi frekuensi dan presentase seperti
ditujukan pada Tabel 4.4 pada lampiran B, terlihat bahwa tidak ada persepsi
guru yang berada pada kategori sangat buruk, buruk, sedang, maupun sangat baik,
tetapi semua (100%) persepsi guru berada pada kategori baik.
Jika data skor persepsi guru tentang pelaksanaan KBK dianalisis
dengan analisis statistik deskriptif untuk tiap indikator, maka digambarkan
seperti pada Tabel 4.5 pada lampiran B.
Tabel 4.5. menggambarkan hasil analisis deskriptif skor persepsi
guru matematika tentang kebijakan dalam KBK. Dari 5 orang responden diperoleh
skor rata-rata 25,80 dari skor ideal 30, dengan modus 27, skor tertinggi 28 dan
skor terendah 23 serta standar deviasi 2,17 yang didukung oleh koefisien
kemiringan kurva (skewness) –0,559 dan koefisien kecembungan (kurtosis) –2,368.
Hasil analisis deskriptif skor persepsi guru matematika tentang
sumber dan sarana pendidikan diperoleh bahwa dari 5 orang responden diperoleh
skor rata-rata 20,60 dari skor ideal 25, dengan modus 19, skor tertinggi 23 dan
skor terendah 19 serta standar deviasi 1,82 yang didukung oleh koefisien
kemiringan kurva (skewness) 0,567 dan koefisien kecembungan (kurtosis) -2,231.
Hasil analisis deskriptif skor persepsi guru matematika tentang
metode dan strategi belajar mengajar diperoleh bahwa dari 5 orang responden
diperoleh skor rata-rata 21,80 dari skor ideal 25, dengan modus 21 dan 22, skor
tertinggi 23 dan skor terendah 21 serta standar deviasi 0,84 yang didukung oleh
koefisien kemiringan kurva
(skewness) 0,512 dan
koefisien kecembungan (kurtosis) adalah –6,12.
Hasil analisis deskriptif skor persepsi guru matematika tentang
siswa sebagai subjek belajar diperoleh bahwa dari 5 orang responden diperoleh
skor rata-rata 21,00 dari skor ideal 25, dengan modus 20 dan 22, skor tertinggi
22 dan skor terendah 20 serta standar deviasi 1,00 yang didukung oleh koefisien
kemiringan kurva (skewness) adalah 0,00 dan koefisien kecembungan (kurtosis)
sebesar –3,00.
Hasil analisis deskriptif skor persepsi guru matematika tentang
evaluasi/peskoran diperoleh bahwa dari 5 orang responden diperoleh skor
rata-rata 15,80 dari skor ideal 20, dengan modus 16, skor tertinggi 17 dan skor
terendah 14 serta standar deviasi 1,10 yang didukung oleh koefisien kemiringan
kurva (skewness) adalah -1,293 dan koefisien kecembungan (kurtosis) sebesar
2,917.
2.
Hasil Wawancara dengan
Guru Matematika Tentang Faktor-Faktor Pendukung dan Faktor-faktor Penghambat
Pelaksanaan KBK Mata Pelajaran Matematika
Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan dua orang guru yang
mengajar di kelas X dan kelas XI yang diwawancarai secara terpisah yaitu
sebagai berikut:
a.
Hasil wawancara dengan
guru matematika yang mengajar di kelas X
1)
Kegiatan belajar mengajar
Faktor pendukung pelaksanaan KBK
dari segi kegiatan belajar mengajar adalah siswa memiliki buku pegangan
yang sesuai dengan KBK sehingga kegiatan menyalin/dikte diminimalisir dalam
kegiatan belajar mengajar. Sedangkan faktor penghambatnya adalah penjabaran
materi pelajaran dalam pengembangan kompetensi dan uji kelayakan membutuhkan
biaya dan waktu yang cukup.
2) Siswa sebagai subyek belajar
Faktor pendukung pelaksanaan KBK
dari segi siswa sebagai subyek belajar adalah siswa mempunyai kesadaran
tinggi untuk proaktif dan lebih mandiri dalam belajar. Sedangkan faktor
penghambatnya adalah masih ada sebagian siswa yang masih mengharapkan
pemberitahuan secara langsung atau transfer ilmu dari guru tanpa mau berusaha secara
mandiri untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.
3) Sarana dan sumber belajar
Faktor pendukung pelaksanaan KBK
dari segi sarana dan sumber belajar adalah laboratorium komputer dan OHP
yang sudah tersedia di sekolah. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah
buku paket dan modul di sekolah masih minim.
4) Alokasi waktu
Faktor pendukung pelaksanaan KBK
dari segi alokasi waktu adalah siswa dituntut untuk belajar di sekolah
dan di luar sekolah.
5) Evaluasi/penilaian
Faktor pendukung pelaksanaan KBK dari segi evaluasi/penilaian adalah
dalam melakukan penilaian, guru melakukan penilaian per kompetensi dasar
sehingga guru tidak merasa kesulitan dalam menentukan ketuntasan belajar siswa.
Selain itu, pelaksanaan program remedial yang dilakukan secara lisan maupun
tulisan yang dilakukan pada saat jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran.
Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih ada sebagian siswa cenderung hanya
mengikuti pekerjaan temannya dalam mengerjakan tugas untuk suatu kompetensi
dasar, sehingga sulit untuk mengetahui ketuntasannya terhadap suatu kompetensi
dasar.
b.
Hasil wawancara dengan
guru matematika yang mengajar di kelas XI
1) Kegiatan belajar mengajar.
Faktor pendukung pelaksanaan KBK dari segi kegiatan belajar mengajar
adalah penggunaan strategi pembelajaran yang tidak monoton tetapi lebih
bervariasi sesuai kreatifitas guru untuk mengembangkan potensi peserta didik.
Sedangkan faktor penghambatnya adalah tidak semua guru yang mengajar pernah
mengikuti pelatihan atau seminar tentang KBK sehingga pemahaman guru tentang
KBK belum terlalu mendalam.
2) Siswa sebagai subyek belajar.
Faktor pendukung pelaksanaan KBK dari segi siswa sebagai subyek
belajar adalah siswa lebih antusias dalam proses belajar mengajar karena guru
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan maupun mengembangkan potensi
yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah
kondisi siswa yang heterogen sehingga guru harus memperhatikan kondisi
masing-masing siswa dalam pembelajaran.
3) Sarana dan sumber belajar
Faktor pendukung pelaksanaan KBK dari segi sarana dan sumber belajar
adalah laboratorium komputer yang sudah ada serta OHP yang sudah disediakan di
setiap ruang kelas. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah buku paket
matematika di perpustakaan yang masih minim.
4) Alokasi waktu
Faktor pendukung pelaksanaan KBK dari segi alokasi waktu adalah
siswa dituntut untuk belajar mandiri baik pada jam pelajaran maupun di luar jam
pelajaran.
5) Evaluasi/penilaian
Faktor pendukung pelaksanaan KBK dari segi evaluasi/penilaian adalah
penilaian tidak hanya dari ujian tulisan tetapi juga dari aspek-aspek yang lain
seperti keaktifan, penampilan dan lain-lain. Sedangkan faktor penghambatnya
adalah jumlah siswa yang banyak dalam satu kelas sehingga guru memerlukan waktu
dan tenaga yang cukup untuk melakukan penilaian kepada siswa satu persatu berdasarkan beberapa aspek
penilaian.
B. Pembahasan Hasil Penelitian
Dari hasil analisis di atas, maka berikut ini akan diuraikan
pembahasan penelitian yang sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah
dalam penelitian ini:
1. Persepsi guru matematika terhadap Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Matematika
Tabel 4.2. pada lampiran B merupakan hasil analisis
statistik deskriptif skor persepsi guru matematika terhadap pelaksanaan KBK
mata pelajaran matematika, yang menunjukkan bahwa dari jumlah sampel 5 orang
memperoleh skor rata-rata persepsi guru matematika terhadap pelaksanaan KBK
mata pelajaran matematika adalah 105 (kategori baik) dari skor ideal 125 (sangat
baik), dengan nilai tertinggi 108 dan nilai terendah 100 serta standar deviasi
3,317. hal ini juga didukung oleh koefisien kemiringan kurva (skewness) sebesar
–0,822 yang berarti distribusi skor persepsi guru mempunyai kemiringan negatif,
yang menggambarkan bahwa kebanyakan guru mempunyai persepsi baik terhadap
pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Makassar. selain
kemiringan kurva, juga didukung oleh koefisien kecembungan (kurtosis) sebesar
0,140 < 3 yang berarti rata-rata persepsi guru berdistribusi dengan model
platikurtik atau mendatar, yang menggambarkan bahwa adanya sebaran frekuensi
yang agak tersebar merata pada seluruh interval skor persepsi guru matematika
terhadap pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Makassar.
Sedangkan secara keseluruhan persepsi guru berada pada kategori baik, sehingga
dapat dikatakan bahwa persepsi guru matematika terhadap pelaksanaan KBK mata
pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Makassar adalah baik.
Jika data skor persepsi guru tentang pelaksanaan KBK dianalisis
dengan analisis statistik deskriptif untuk tiap indikator, maka digambarkan
seperti pada Tabel 4.5 pada lampiran B.
Tabel 4.5. menggambarkan hasil analisis deskriptif skor persepsi
guru matematika tentang kebijakan dalam KBK. Dari 5 orang responden memperoleh
skor rata-rata 25,80 (kategori baik) dari skor ideal 30, dengan tertinggi 28
dan skor terendah 23 serta standar deviasi 2,17. Hasil analisis deskriptif skor
persepsi guru matematika tentang sumber dan sarana pendidikan diperoleh bahwa
dari 5 orang responden memperoleh skor rata-rata 20,60 (kategori baik) dari
skor ideal 25, dengan skor tertinggi 23 dan skor terendah 19 serta standar
deviasi 1,82. Hasil analisis deskriptif skor persepsi guru matematika tentang
metode dan strategi belajar mengajar diperoleh bahwa dari 5 orang responden
memperoleh skor rata-rata 21,80 (kategori baik) dari skor ideal 25, dengan skor
tertinggi 23 dan skor terendah 21 serta standar deviasi 0,84. Hasil analisis
deskriptif skor persepsi guru matematika tentang siswa sebagai subjek belajar
diperoleh bahwa dari 5 orang responden memperoleh skor rata-rata 21,00
(kategori baik) dari skor ideal 25, dengan skor tertinggi 22 dan skor terendah
20 serta standar deviasi 1,00. Hasil analisis deskriptif skor persepsi guru
matematika tentang evaluasi/peskoran diperoleh bahwa dari 5 orang responden
memperoleh skor rata-rata 15,80 (kategori baik) dari skor ideal 20, dengan skor
tertinggi 17 dan skor terendah 14 serta standar deviasi 1,10.
2. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika
Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor-faktor yang
mendukung pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika yaitu; siswa memiliki buku
pegangan sehingga kegiatan menyalin/dikte diminimalisir dalam kegiatan belajar
mengajar, dan penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang tidak monoton
tetapi lebih bervariasi sesuai kreatifitas guru untuk mengembangkan potensi
peserta didik; buku pegangan yang dimiliki siswa berupa buku berdasarkan KBK
yang harus dimiliki oleh tiap siswa; siswa mempunyai kesadaran tinggi untuk
proaktif dan lebih mandiri dalam belajar, serta siswa lebih antusias dalam
proses belajar mengajar karena guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menemukan maupun mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa,
dalam hal ini siswa lebih antusias baik dalam mengajukan pertanyaan, menjawab
pertanyaan, maupun menanggapi suatu masalah; laboratorium komputer yang sudah
tersedia serta OHP yang sudah disediakan di setiap ruang kelas; siswa dituntut
untuk belajar di sekolah dan di luar sekolah, dan siswa dituntut untuk belajar
mandiri baik pada jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran; guru melakukan
penilaian per kompetensi dasar sehingga guru tidak merasa kesulitan dalam
menentukan ketuntasan belajar siswa, pelaksanaan program remedial yang
dilakukan secara lisan maupun tulisan yang dilakukan pada saat jam pelajaran
maupun di luar jam pelajaran/di rumah, serta penilaian tidak hanya dari ujian
tulisan tetapi juga dari aspek-aspek yang lain seperti keaktifan, penampilan
dan lain-lain.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru matematika dalam penerapan KBK mata pelajaran matematika
Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor-faktor yang
menghambat pelaksanaan KBK mata pelajaran yaitu; penjabaran materi pelajaran
dalam pengembangan kompetensi dan uji kelayakan membutuhkan biaya dan waktu
yang cukup, tidak semua guru yang mengajar pernah mengikuti pelatihan atau
seminar tentang KBK sehingga pemahaman guru tentang KBK belum terlalu mendalam,
di mana dari lima orang guru matematika yang diteliti hanya empat orang guru
yang pernah mengikuti penataran atau pelatihan atau seminar tentang KBK; masih
ada sebagian siswa yang masih mengharapkan pemberitahuan secara langsung atau
transfer ilmu dari guru tanpa mau berusaha secara mandiri untuk mengembangkan
potensi yang mereka miliki, kondisi siswa yang heterogen sehingga guru harus
memperhatikan kondisi masing-masing siswa dalam pembelajaran; buku paket dan
modul yang masih sedikit jumlahnya; terdapat sebagian siswa yang kurang
memiliki kesadaran untuk mempergunakan waktu di luar sekolah sehingga
penguasaannya terhadap suatu kompetensi dasar terhambat; sebagian siswa
cenderung hanya mengikuti pekerjaan temannya dalam mengerjakan tugas untuk
suatu kompetensi dasar, sehingga sulit untuk mengetahui ketuntasannya terhadap
suatu kompetensi dasar, siswa kurang mampu mengembangkan life skill dalam
mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya, serta jumlah siswa yang banyak
dalam satu kelas sehingga guru memerlukan waktu dan tenaga yang cukup untuk
melakukan penilaian kepada siswa satu persatu berdasarkan beberapa aspek
penilaian.
BAB V
KESIMPULAN
DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1.
Persepsi guru matematika
terhadap pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mata pelajaran
matematika di SMA Negeri 1 Makassar adalah baik. Hal ini didukung oleh sarana
dan prasarana pembelajaran yang cukup memadai seperti laboratorium komputer,
OHP, serta alat peraga matematika lainnya, kesadaran masing-masing siswa dengan
lebih semangat untuk belajar serta kreatif dalam mengembangkan potensinya.
2.
Faktor-faktor yang mendukung
pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Makassar adalah
sebagai berikut:
§ Siswa memiliki buku pegangan khususnya buku yang sesuai dengan
tuntutan KBK sehingga kegiatan menyalin/dikte dapat diminimalisir dalam
kegiatan, dan penggunaan strategi pembelajaran yang tidak monoton tetapi lebih
bervariasi sesuai kreatifitas guru untuk mengembangkan potensi peserta didik.
§
|
Siswa mempunyai kesadaran tinggi untuk
proaktif dan lebih mandiri dalam belajar, serta siswa lebih antusias dalam
proses belajar mengajar karena guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menemukan maupun mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa.
§
Laboratorium komputer yang
sudah tersedia serta OHP yang sudah disediakan di setiap ruang kelas.
§
Guru melakukan penilaian per
kompetensi dasar sehingga guru tidak merasa kesulitan dalam menentukan
ketuntasan belajar siswa, pelaksanaan program remedial yang dilakukan secara
lisan maupun tulisan yang dilakukan pada saat jam pelajaran maupun di luar jam
pelajaran/di rumah, serta penilaian tidak hanya dari ujian tulisan tetapi juga
dari aspek-aspek yang lain seperti keaktifan, penampilan dan lain-lain.
3.
Hambatan-hambatan yang dihadapi
oleh guru matematika dalam pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika di SMA
Negeri 1 Makassar adalah:
§
Penjabaran
materi pelajaran dalam pengembangan kompetensi dan uji kelayakan membutuhkan
biaya dan waktu yang cukup, tidak semua guru yang mengajar pernah mengikuti
pelatihan atau seminar tentang KBK sehingga pemahaman guru tentang KBK belum
terlalu mendalam.
§
Masih ada
sebagian siswa yang masih mengharapkan pemberitahuan langsung atau transfer
ilmu dari guru tanpa mau berusaha secara mandiri untuk mengembangkan potensi
yang mereka miliki, kondisi siswa yang heterogen sehingga guru harus
memperhatikan kondisi masing-masing siswa dalam pembelajaran.
§
Buku paket
dan modul yang masih minim.
§
Masih ada sebagian siswa yang
kurang memiliki kesadaran untuk mempergunakan waktu di luar sekolah sehingga
penguasaannya terhadap suatu kompetensi dasar terhambat.
§
Sebagian siswa cenderung hanya
mengikuti pekerjaan temannya dalam mengerjakan tugas untuk suatu kompetensi
dasar, sehingga sulit untuk mengetahui ketuntasannya terhadap suatu kompetensi
dasar, siswa kurang mampu mengembangkan life skill dalam mengaplikasikan
pengetahuan yang dimilikinya, serta jumlah siswa yang banyak dalam satu kelas
sehingga guru memerlukan waktu dan tenaga yang cukup untuk melakukan penilaian
kepada siswa satu persatu berdasarkan beberapa aspek penilaian.
B. Saran
1.
Dari pihak kepala sekolah SMA Negeri 1 Makassar
hendaknya sosialisasi mengenai KBK kepada guru perlu ditingkatkan baik melalui
penataran, pelatihan-pelatihan, atau seminar-seminar tentang pelaksanaan KBK.
2.
Keberhasilan KBK sangat ditentukan oleh beberapa pihak
seperti kepala sekolah, guru, dan siswa sehingga diperlukan sikap positif,
kesadaran, dan kesiapan untuk menerima model pendekatan baru pada KBK.
3.
Dari pihak sokolah hendaknya memperhatikan kondisi
perpustakaan agar memperbanyak buku paket dan modul khususnya untuk mata
pelajaran matematika yang sesuai dengan tuntutan KBK.
4.
Untuk wakil kepala sekolah khususnya bidang kesiswaan
agar jumlah siswa dalam satu kelas perlu
diperhatikan sesuai dengan kapasitas dan kondisi kelas.
DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Qomari. 2002. Reorientasi Pendidikan
dan Profesi Keguruan. Jakarta
Ali, Muhammad. 2002. Guru Dalam Proses
Belajar Mengajar. Bandung
Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Ditjen.
Dikdasmen, Depdiknas. 2003. Kurikulum 2004. Pedoman Khusus Pengembangan
Silabus dan Penilaian Mata pelajaran Matematika.
Hamalik, Oemar. 2003. Kurikulum dan
Pembelajaran. Jakarta
Hasnidar. 2004. Studi Tentang Hambatan Guru
Dalam Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata pelajaran Matematika SMA Di
Kota Makassar ). Skripsi. FMIPA UNM Makassar .
Mulyasa, E. 2004. Kurikulum Berbasis
Kompetensi. Konsep, Karakteristik, Implementasi dan Inovasi. Bandung
Nasution. S. 2003. Asas-Asas
Kurikulum. Jakarta. Bumi Aksara.
Nurhadi. 2003. Pembelajaran Kontekstual
(Contextual Teaching and Learning/CTL) dan Penerapannya Dalam KBK.
Malang.Universitas Negeri Malang
Nuryadi. 2004. Studi Tentang Pelaksanaan
Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Mata pelajaran Matematika (Kasus SMU Negeri
3 Makassar ). Skripsi. FMIPA UNM Makassar .
Purwanto, Ngalim. 1994. Prinsip-Prinsip dan
Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung
Pusat Kurikulum. 2001. Kurikulum Berbasis
Kompetensi Mata pelajaran Matematika Sekolah Menengah Umum. Jakarta
Siskandar. 2003. Pelayanan
Profesional Kurikulum 2004 Departemen Pendidikan Nasional (On
Line), (www. Google.com, Diakses 6 April 2005 ).
Soetjipto. 1999. Profesi Keguruan. Jakarta
Suderadjat, Hari. 2004. Implementasi
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Bandung
Sudjatmiko. 2003. Kurikulum Berbasis
Kompetensi Dalam Menunjang Kecakapan Hidup Siswa. Jakarta
Suherman, Erman. dkk. 2003. Strategi
Pembelajaran Matematika Kontemporer. Bandung
Sukmadinata, Nana Syaodih. 2001. Pengembangan
Kurikulum Teori dan Praktek. Bandung
Usman, Moh. Uzer. 2001. Menjadi Guru
Profesional. Bandung
Yamin, Martinis. 2005. Strategi Pembelajaran
Berbasis Kompetensi. Jakarta
RIWAYAT HIDUP
Wahyudin, lahir di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima,
tanggal 22 Agustus 1981, anak kelima pasangan Ayah yang bernama Usman (Alm) dan Ibu yang bernama Hatijah.
Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pada tahun 1988 di SDN
INP. Na’e Sape dan tamat pada tahun 1994. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sape dan tamat
pada tahun 1997. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan
pendidikan di SMA Negeri 1 Sape dan tamat pada tahun 2000.
Pada tahun yang sama penulis mencoba mengikuti UMPTN,
namun tidak lolos sehingga penulis mengambil inisiatif untuk mendaftarkan diri
di IAIN Alauddin Makassar pada Fakultas Tarbiyah tepatnya Jurusan Pendidikan
Agama Islam (PAI) Strata Satu. Setelah satu tahun menjadi mahasiswa IAIN
Alauddin Makassar, penulis mencoba lagi mengikuti UMPTN tahun 2001 dan diterima
di Universitas Negeri Makassar pada Fakultas MIPA tepatnya di Jurusan
Matematika Program Studi Pendidikan Matematika. Adapun organisasi yang pernah
digeluti oleh penulis selama menjadi mahasiswa yaitu MPMJ Jurusan Matematika
FMIPA UNM dan SCMM FMIPA UNM.
ANGKET PERSEPSI GURU MATEMATIKA TERHADAP PELAKSANAAN
KURUKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) UNTUK MATA PELAJARAN MATEMATIKA
Kepada
Yth. Bapak/Ibu Guru Mata pelajaran matematika
Dengan hormat.
Dalam rangka menyelesaikan tugas
akhir studi saya di perguruan tinggi, maka saya bermaksud mengadakan penelitian
tentang Pelaksanaan Kurikulum 2004 (sekarang dikenal dengan
Kurikulum Berbasis Kompetensi) mata
pelajaran Matematika di sekolah Bapak. Oleh karena itu, saya memohon keikhlasan
Bapak/Ibu Guru meluangkan waktunya untuk mengisi angket ini sesuai dengan
pengalaman di lapangan. Angket ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan
penilaian tugas dan profesi Bapak/Ibu Guru. Atas kesediaan Bapak/Ibu Guru saya ucapkan
banyak terima kasih.
E. A. Informasi Umum
Nama : ………………………….
Mengajar
di kelas : ………………………….
Pendidikan
terakhir : ………………………….
Mengikuti
penataran/diklat tentang KBK: Pernah/Tidak Pernah *)
*)
Coret yang tidak perlu
B. Petunjuk Pengisian
Bacalah baik-baik setiap butir yang
disediakan dan jawablah setiap pertanyaan dengan memberikan tanda cek (Ö ) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia untuk setiap
pernyataan di bawah ini dengan keterangan sebagai berikut:
SS :
Untuk jawaban Sangat Setuju
S :
Untuk jawaban Setuju
R :
Untuk jawaban Ragu-Ragu
TS :
Untuk jawaban Tidak Setuju
STS :
Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju
|
No
|
Pernyataan
|
Alternatif Jawaban
|
||||
|
SS
|
S
|
R
|
TS
|
STS
|
||
A. Tentang kebijakan dalam KBK |
||||||
|
1
|
KBK merupakan salah satu upaya
pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam menguasai ilmu
dan teknologi.
|
|
|
|
|
|
|
2
|
KBK khususnya pada mata pelajaran
matematika dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang
sesuai dengan tuntutan zaman.
|
|
|
|
|
|
|
3
|
KBK adalah kurikulum yang kurang
cocok diterapkan untuk menghadapi era globalisasi dan perkembangan IPTEK
walaupun peserta didik dibekali dengan kompetensi-kompetensi tertentu.
|
|
|
|
|
|
|
4
|
KBK tidak memberi peluang bagi
siswa untuk mencari, mengolah dan menemukan sendiri pengetahuan walaupun
melalui bimbingan guru.
|
|
|
|
|
|
|
5
|
KBK dapat mengembangkan kemampuan
dan keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bidang kehidupan sehari-hari
bagi siswa.
|
|
|
|
|
|
|
6
|
KBK tidak dapat dilaksanakan di
semua jenjang pendidikan pada semua mata pelajaran, khususnya pada mata
pelajaran matematika.
|
|
|
|
|
|
B. Tentang sumber dan sarana pendidikan |
||||||
|
7
|
Buku mata pelajaran matematika
yang mengacu pada KBK kurang mengarahkan siswa untuk memahami kompetensi yang
harus dikuasai.
|
|
|
|
|
|
|
8
|
KBK khususnya mata pelajaran matematika
membutuhkan sumber daya dan sarana pendidikan (seperti perpustakaan,
laboratorium, komputer) yang memadai.
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Dalam pelaksanaan KBK sumber
belajar bagi siswa bukan hanya dari guru yang sedang mengajar di dalam kelas.
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Dalam pelaksanaan KBK bahan
belajar yang utama bagi guru beragam seperti buku, brosur, majalah, peta,
bahkan lingkungan sekitar yang dipilih sesuai dengan kompetensi yang hendak
dicapai.
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Dalam pelaksanaan KBK media yang
bervariasi (seperti komputer, laboratorium, OHP dan lain-lain) kurang
berpengaruh dalam menunjang pencapaian kompetensi yang diharapkan.
|
|
|
|
|
|
C. Tentang metode dan strategi belajar mengajar |
||||||
|
12
|
Metode mengajar dalam KBK kurang
mampu membangkitkan semangat siswa untuk lebih aktif, khususnya untuk mata
pelajaran matematika.
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Suasana pembelajaran dalam KBK
lebih bervariasi dengan mengkombinasikan antara kegiatan belajar
perseorangan, berpasangan, kelompok dan klaksikal.
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Menurut paradigma pembelajaran
dalam KBK khususnya pembelajaran matematika, posisi guru yang paling cocok
adalah sebagai fasilitator.
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Strategi pembelajaran dalam KBK
membuat guru menjadi kaku dalam mengajar.
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Pembelajaran modul hanya
menghambat pencapaian kompetensi bagi siswa.
|
|
|
|
|
|
D. Tentang siswa sebagai subyek belajar |
||||||
|
17
|
KBK sangat memperhatikan perbedaan
kondisi siswa sebagai subjek belajar, meliputi perbedaan dalam minat,
kemampuan, gaya belajar dan lain-lain.
|
|
|
|
|
|
|
18
|
KBK membuat siswa sulit
memahami materi pelajaran matematika yang diajarkan.
|
|
|
|
|
|
|
19
|
KBK membuat siswa kurang antusias
dalam mengikuti pelajaran matematka.
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Dalam KBK untuk pelajaran
matematika, ruang kelas diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan
keragaman cara siswa belajar dan bekerja baik secara perorangan, berpasangan
atau kelompok.
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Cara mengajar guru yang diterapkan
pada KBK dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
|
|
|
|
|
|
E. Tentang evaluasi/penilaian |
||||||
|
22
|
Dalam melakukan penilaian, selain
oleh guru juga dilakukan oleh teman sekelas atau teman kelas lain.
|
|
|
|
|
|
|
23
|
Remedial tidak mampu membantu
siswa yang belum tuntas pada suatu kompetensi dasar manjadi tuntas.
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Penilaian per kompetensi dasar
membantu guru untuk mengatahui siswa yang sudah tuntas dan belum tuntas untuk
suatu kompetensi dasar.
|
|
|
|
|
|
|
25
|
Dalam melakukan penilaian, guru
harus memperhatikan ketiga ranah (kognitif, afektif dan psikomotorik) yang
dicapai oleh siswa.
|
|
|
|
|
|
Kisi-kisi angket persepsi guru matematika terhadap pelaksanaan KBK
mata pelajaran matematika
|
No
|
Pernyataan
|
Jenis pernyataan
|
|
|
Favorable
|
Unfavorable
|
||
A. Tentang kebijakan dalam KBK |
|||
|
1
|
KBK merupakan salah satu upaya
pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam menguasai ilmu
dan teknologi.
|
Ö
|
–
|
|
2
|
KBK khususnya pada mata pelajaran
matematika dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang
sesuai dengan tuntutan zaman.
|
Ö
|
–
|
|
3
|
KBK adalah kurikulum yang kurang
cocok diterapkan untuk menghadapi era globalisasi dan perkembangan IPTEK
walaupun peserta didik dibekali dengan kompetensi-kompetensi tertentu.
|
–
|
Ö
|
|
4
|
KBK tidak memberi peluang bagi
siswa untuk mencari, mengolah dan menemukan sendiri pengetahuan walaupun
melalui bimbingan guru.
|
–
|
Ö
|
|
5
|
KBK dapat mengembangkan kemampuan
dan keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bidang kehidupan sehari-hari
bagi siswa.
|
Ö
|
–
|
|
6
|
KBK tidak dapat dilaksanakan di
semua jenjang pendidikan pada semua mata pelajaran, khususnya pada mata
pelajaran matematika.
|
–
|
Ö
|
B. Tentang sumber dan sarana pendidikan |
|||
|
7
|
Buku mata pelajaran matematika
yang mengacu pada KBK kurang mengarahkan siswa untuk memahami kompetensi yang
harus dikuasai.
|
–
|
Ö
|
|
8
|
KBK khususnya mata pelajaran
matematika membutuhkan sumber daya dan sarana pendidikan (seperti
perpustakaan, laboratorium, komputer) yang memadai.
|
Ö
|
–
|
|
9
|
Dalam pelaksanaan KBK sumber
belajar bagi siswa bukan hanya dari guru yang sedang mengajar di dalam kelas.
|
Ö
|
–
|
|
10
|
Dalam pelaksanaan KBK bahan
belajar yang utama bagi guru beragam seperti buku, brosur, majalah, peta,
bahkan lingkungan sekitar yang dipilih sesuai dengan kompetensi yang hendak
dicapai.
|
Ö
|
–
|
|
11
|
Dalam pelaksanaan KBK media yang
bervariasi (seperti komputer, laboratorium, OHP dan lain-lain) kurang
berpengaruh dalam menunjang pencapaian kompetensi yang diharapkan.
|
–
|
Ö
|
C. Tentang metode dan strategi belajar mengajar |
|||
|
12
|
Metode mengajar dalam KBK kurang mampu
membangkitkan semangat siswa untuk lebih aktif, khususnya untuk mata
pelajaran matematika.
|
–
|
Ö
|
|
13
|
Suasana pembelajaran dalam KBK lebih
bervariasi dengan mengkombinasikan antara kegiatan belajar perseorangan,
berpasangan, kelompok dan klaksikal.
|
Ö
|
–
|
|
14
|
Menurut paradigma pembelajaran dalam KBK
khususnya pembelajaran matematika, posisi guru yang paling cocok adalah
sebagai fasilitator.
|
Ö
|
|
|
15
|
Strategi pembelajaran dalam KBK membuat guru
menjadi kaku dalam mengajar.
|
–
|
Ö
|
|
16
|
Pembelajaran modul hanya menghambat
pencapaian kompetensi bagi siswa.
|
–
|
Ö
|
D. Tentang siswa sebagai subyek belajar |
|||
|
17
|
KBK sangat memperhatikan perbedaan kondisi
siswa sebagai subjek belajar, meliputi perbedaan dalam minat, kemampuan,
|
Ö
|
–
|
|
18
|
KBK membuat siswa sulit memahami
materi pelajaran matematika yang diajarkan.
|
–
|
Ö
|
|
19
|
KBK membuat siswa kurang antusias dalam
mengikuti pelajaran matematka.
|
–
|
Ö
|
|
20
|
Dalam KBK untuk pelajaran matematika, ruang
kelas diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan keragaman cara siswa
belajar dan bekerja baik secara perorangan, berpasangan atau kelompok.
|
Ö
|
–
|
|
21
|
Cara mengajar guru yang diterapkan pada KBK
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
|
Ö
|
–
|
E. Tentang evaluasi/penilaian |
|||
|
22
|
Dalam melakukan penilaian, selain oleh guru
juga dilakukan oleh teman sekelas atau teman kelas lain.
|
Ö
|
–
|
|
23
|
Remedial tidak mampu membantu siswa yang
belum tuntas pada suatu kompetensi dasar manjadi tuntas.
|
–
|
Ö
|
|
24
|
Penilaian per kompetensi dasar membantu guru
untuk mengatahui siswa yang sudah tuntas dan belum tuntas untuk suatu
kompetensi dasar.
|
Ö
|
–
|
|
25
|
Dalam melakukan penilaian, guru harus
memperhatikan ketiga ranah (kognitif, afektif dan psikomotorik) yang dicapai
oleh siswa.
|
Ö
|
–
|
Pedoman wawancara untuk guru tentang faktor-faktor
pendukung serta hambatan-hambatan yang dihadapi guru matematika sehubungan
dengan pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Makassar
1. Mengenai kegiatan belajar mengajar
Efektifitas proses belajar mengajar
sangat ditentukan oleh beberapa hal seperti penjabaran indikator pencapaian
hasil belajar, skenario pembelajaran/silabus, penggunaan strategi pembelajaran,
pengembangan silabus dan lain-lain. Apa saja yang mendukung pelaksanaan KBK dan
hambatan-hambatan apa yang anda hadapi dalam upaya mencapai proses belajar
mengajar yang lebih efektif sesuai
dengan tuntutan KBK?
2. Mengenai siswa sebagai subyek belajar
Salah satu hal yang membedakan
antara KBK dengan kurikulum sebelumnya yaitu siswa dipandang sebagai subyek
belajar sehingga segala aspek yang dialami, dimiliki atau dibutuhkan oleh siswa
harus diperhatikan. Apa saja yang mendukung pelaksanaan KBK dan
hambatan-hambatan apa yang anda hadapi dalam pelaksanaan KBK dari segi siswa
sebagai subyek belajar?
3. Mengenai sarana dan sumber belajar.
Dalam penerapan KBK khususnya mata
pelajaran matematika, sarana dan sumber belajar sangat penting guna mendukung
efektifitas proses belajar mengajar. Apa saja yang mendukung pelaksanaan KBK
dan hambatan-hambatan apa yang anda hadapi sehubungan dengan hal itu?
4. Mengenai alokasi waktu
Dalam pengembangan silabus, alokasi
waktu untuk setiap pokok bahasan sudah ditentukan terlebih dahulu. Apa saja
yang mendukung pelaksanaan KBK dari segi alokasi waktu dan apakah anda menemukan
hambatan sehubungan dengan alokasi waktu yang diberikan untuk mencapai suatu
kompetensi dasar dalam pembelajaran?
5. Mengenai evaluasi/penilaian
Evaluasi hasil belajar dalam KBK
dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, benchmarking (patokan keberhasilan di tingkat yang lebih tinggi),
serta penilaian program. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan KBK dari
segi penilaian dan penilaian yang mana yang merupakan hambatan bagi anda dalam
melakukan evaluasi?
Hasil wawancara dengan guru matematika kelas X tentang
faktor-faktor pendukung serta hambatan-hambatan yang dihadapi guru matematika
sehubungan dengan pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika
di SMA Negeri 1 Makassar
1. Mengenai kegiatan belajar mengajar
Pendukung : Masing-masing
siswa memiliki buku pegangan sehingga kegiatan menyalin/dikte diminimalisir
dalam kegiatan belajarmengajar
Penghambat : Penjabaran
materi pelajaran dalam pengembangan kompetensi dan uji kelayakan membutuhkan
biaya yang cukup
2. Mengenai siswa sebagai subyek belajar
Pendukung : Siswa mempunyai
kesadaran tinggi untuk proaktif dan lebih mandiri dalam belajar
Penghambat : Masih ada
sebagian siswa yang masih mengharap “suapan” atau transfer ilmu dari guru tanpa
mau berusaha secara mandiri untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.
3. Mengenai sarana dan sumber belajar.
Pendukung : Laboratorium
komputer dan OHP yang sudah tersedia.
Penghambat : Buku paket dan
modul yang masih minim.
4. Mengenai alokasi waktu
Pendukung : Siswa dituntut
untuk belajar di sekolah dan di luar sekolah
Penghambat : Ada
5. Mengenai evaluasi/penilaian
Pendukung : Dalam
pelaksanaannya, guru melakukan penilaian per kompetensi dasar sehingga guru
tidak merasa kesulitan dalam menentukan ketuntasan belajar siswa; pelaksanaan
program remedial yang dilakukan secara lisan maupun tulisan yang dilakukan pada
saat jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran/ di rumah.
Penghambat : Sebagian siswa
cenderung hanya mengikuti pekerjaan temannya dalam mengerjakan tugas untuk
suatu kompetensi dasar, sulit untuk mengetahui ketuntasannya terhadap suatu
kompetensi dasar; siswa kurang mampu mengembangkan life skill dalam
mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya.
Hasil wawancara dengan guru matematika kelas XI tentang
faktor-faktor pendukung serta hambatan-hambatan yang dihadapi guru matematika
sehubungan dengan pelaksanaan KBK mata pelajaran matematika
di SMA Negeri 1 Makassar
1. Mengenai kegiatan belajar mengajar
Pendukung : Penggunaan
strategi pembelajaran yang tidak monoton tetapi lebih bervariasi sesuai
kreatifitas guru untuk mengembangkan potensi peserta didik
Penghambat : Tidak semua
guru yang mengajar pernah mengikuti pelatihan atau seminar tentang KBK sehingga
pemahaman guru tentang KBK belum terlalu mendalam.
2. Mengenai siswa sebagai subyek belajar
Pendukung : Siswa lebih
antusias dalam proses belajar mengajar karena guru memberikan kesempatan
kesempatan kepada siswa untuk menemukan maupun mengembangkan potensi yang
dimiliki oleh masing-masing siswa.
Penghambat : Kondisi siswa
yang heterogen sehingga guru harus memperhatikan kondisi masing-masing siswa
dalam pembelajaran.
3. Mengenai sarana dan sumber belajar.
Pendukung : Laboratorium
komputer yang sudah tersedia dan OHP yang sudah disediakan di setiap ruang
kelas.
Penghambat : Buku paket
matematika di perpustakaan yang masih minim.
4. Mengenai alokasi waktu
Pendukung : Siswa dituntut
untuk belajar mandiri baik pada jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran.
Penghambat : Tidak ada
5. Mengenai evaluasi/penilaian
Pendukung : Penilaian tidak
hanya dari ujian tulisan tetapi juga dari aspek-aspek yang lain seperti
keaktifan, penampilan dan lain-lain.
Penghambat : Jumlah siswa yang
banyak dalam satu kelas sehingga guru memerlukan waktu dan tenaga yang cukup
untuk melakukan penilaian kepada siswa satu persatu berdasarkan beberapa aspek
penilaian.
Tabel 4.1
Skor hasil angket persepsi guru matematika terhadap pelaksanaan KBK mata
pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Makassar
|
Resp.
|
NOMOR BUTIR
|
å
|
||||||||||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
||
|
1
|
4
|
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
4
|
4
|
3
|
5
|
3
|
4
|
4
|
5
|
4
|
5
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
105
|
|
2
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
4
|
4
|
5
|
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
1
|
3
|
5
|
5
|
108
|
|
3
|
4
|
5
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
4
|
5
|
5
|
2
|
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
4
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
108
|
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
5
|
104
|
|
5
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
100
|
Tabel
4.2 Persentase skor hasil angket persepsi guru matematika terhadap pelaksanaan
KBK mata pelajaran matematika
di SMA Negeri 1 Makassar
|
No.
Butir
|
Jawaban
|
Jumlah
|
|
No.
Butir
|
Jawaban
|
Jumlah
|
||||||||||||||||||||
|
SS
|
S
|
R
|
TS
|
STS
|
|
SS
|
S
|
R
|
TS
|
STS
|
||||||||||||||||
|
f
|
%
|
f
|
%
|
f
|
%
|
f
|
%
|
f
|
%
|
f
|
%
|
|
f
|
%
|
f
|
%
|
f
|
%
|
f
|
%
|
f
|
%
|
f
|
%
|
||
|
1
|
1
|
20%
|
3
|
60%
|
1
|
20%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
14
|
3
|
60%
|
2
|
40%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
2
|
3
|
60%
|
2
|
40%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
15
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
4
|
80%
|
1
|
20%
|
5
|
100%
|
|
3
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
1
|
20%
|
2
|
40%
|
2
|
40%
|
5
|
100%
|
|
16
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
1
|
20%
|
1
|
20%
|
3
|
60%
|
5
|
100%
|
|
4
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
17
|
0
|
0%
|
4
|
80%
|
1
|
20%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
5
|
4
|
80%
|
1
|
20%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
18
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
4
|
80%
|
1
|
20%
|
5
|
100%
|
|
6
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
4
|
80%
|
1
|
20%
|
5
|
100%
|
|
19
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
4
|
80%
|
1
|
20%
|
5
|
100%
|
|
7
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
1
|
20%
|
4
|
80%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
20
|
2
|
40%
|
3
|
60%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
8
|
2
|
40%
|
3
|
60%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
21
|
2
|
40%
|
3
|
60%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
9
|
3
|
60%
|
1
|
20%
|
1
|
20%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
22
|
0
|
0%
|
3
|
60%
|
1
|
20%
|
0
|
0%
|
1
|
20%
|
5
|
100%
|
|
10
|
3
|
60%
|
2
|
40%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
23
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
1
|
20%
|
4
|
80%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
11
|
0
|
0%
|
1
|
20%
|
1
|
20%
|
3
|
60%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
24
|
1
|
20%
|
4
|
80%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
12
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
2
|
40%
|
3
|
60%
|
5
|
100%
|
|
25
|
3
|
60%
|
2
|
40%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
13
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
0
|
0%
|
5
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F.
Tabel 4.3
Statistik Skor Persepsi guru matematika terhadap Pelaksanaan Kurikulum Berbasis
Kompetensi Matapelajaran Matematika di SMA Negeri 1 Makassar
|
|
|
Frequency
|
Percent
|
Valid
Percent
|
Cumulative Percent
|
|
|
Valid
|
100
|
1
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
|
|
|
104
|
1
|
20.0
|
20.0
|
40.0
|
|
|
|
105
|
1
|
20.0
|
20.0
|
60.0
|
|
|
|
108
|
2
|
40.0
|
40.0
|
100.0
|
|
|
|
Total
|
5
|
100.0
|
100.0
|
|
|
G.
Nilai Statistik
|
N
|
Valid
|
5
|
|
|
|
Missing
|
0
|
|
|
Mean
|
|
105.0000
|
|
|
Std. Error of Mean
|
|
1.4832
|
|
|
Median
|
|
105.0000
|
|
|
Mode
|
|
108.00
|
|
|
Std. Deviation
|
|
3.3166
|
|
|
Variance
|
|
11.0000
|
|
|
Skewness
|
|
-.822
|
|
|
Std. Error of Skewness
|
|
.913
|
|
|
Kurtosis
|
|
.140
|
|
|
Std. Error of Kurtosis
|
|
2.000
|
|
|
Range
|
|
8.00
|
|
|
Minimum
|
|
100.00
|
|
|
Maximum
|
|
108.00
|
|
|
Sum
|
|
525.00
|
|
D.
CHART

Tabel
4.4 Kategori Skor, Distribusi Frekuensi dan Presentase Persepsi Guru Matematika
Terhadap Pelaksanaan KBK Mata Pelajaran Matematika.
|
Skor
|
Kategori
|
Frekuensi
|
Persentase
|
|
0
– 49,38
49,39 – 68,10
68,11 – 93,10
93,11 – 111,85 11,86 – 125
|
Sangat
buruk
Buruk
Sedang
Baik
Sangat
baik
|
0
0
0
5
0
|
0
0
0
100%
0
|
|
Jumlah
|
5
|
100%
|
|
H.
Tebel 4.5. Hasil
Analisis Statistik Deskriptif Skor Persepsi Guru Matematika Terhadap
Pelaksanaan KBK Mata Pelajaran Matematika Untuk Tiap Indikator.
Statistik
|
Indikator
|
||||
|
Kebijakan
dalam KBK
|
Sumber
dan sarana pendidikan
|
Metode
dan strategi mengajar
|
Siswa
sebagai subjek belajar
|
Evaluasi/
penilaian
|
|
|
Mean
|
25.80
|
20.60
|
21.80
|
21.00
|
15.80
|
|
Median
|
27.00
|
20.00
|
22.00
|
21.00
|
16.00
|
|
Mode
|
27
|
19
|
21
|
20
|
16
|
|
Std.
Dev.
|
2.17
|
1.82
|
0.84
|
1.00
|
1.10
|
|
Variance
|
4.70
|
3.30
|
0.70
|
1.00
|
1.20
|
|
Skewness
|
-0.559
|
0.567
|
0.512
|
0.000
|
-1.293
|
|
Kurtosis
|
-2.368
|
-2.231
|
-0.612
|
-3.000
|
2.917
|
|
Range
|
5
|
4
|
2
|
2
|
3
|
|
Minimum
|
23
|
19
|
21
|
20
|
14
|
|
Maximum
|
28
|
23
|
23
|
22
|
17
|
|
Sum
|
129
|
103
|
109
|
105
|
79
|
I.
J.
Tabel 4.6. Tabel
Frekuensi Dan Histogram Skor Persepsi Guru Matematika Tentang Kebijakan Dalam KBK
|
|
|
Frequency
|
Percent
|
Valid Percent
|
Cumulative Percent
|
|
|
Valid
|
23
|
1
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
|
|
|
24
|
1
|
20.0
|
20.0
|
40.0
|
|
|
|
27
|
2
|
40.0
|
40.0
|
80.0
|
|
|
|
28
|
1
|
20.0
|
20.0
|
100.0
|
|
|
|
Total
|
5
|
100.0
|
100.0
|
|
|

K.
Tabel 4.7.
Frekuensi dan Histogram Skor Persepsi Guru Matematika Tentang Siswa Sebagai Subyek Belajar
|
|
|
Frequency
|
Percent
|
Valid
Percent
|
Cumulative
Percent
|
|
|
Valid
|
19
|
2
|
40.0
|
40.0
|
40.0
|
|
|
|
20
|
1
|
20.0
|
20.0
|
60.0
|
|
|
|
22
|
1
|
20.0
|
20.0
|
80.0
|
|
|
|
23
|
1
|
20.0
|
20.0
|
100.0
|
|
|
|
Total
|
5
|
100.0
|
100.0
|
|
|
L. 
M.
N.
Tabel 4.8.
Frekuensi Dan Histogram Skor Persepsi Guru Matematika Tentang Sarana dan Sumber
Belajar
|
|
|
Frequency
|
Percent
|
Valid Percent
|
Cumulative Percent
|
|
|
Valid
|
21
|
2
|
40.0
|
40.0
|
40.0
|
|
|
|
22
|
2
|
40.0
|
40.0
|
80.0
|
|
|
|
23
|
1
|
20.0
|
20.0
|
100.0
|
|
|
|
Total
|
5
|
100.0
|
100.0
|
|
|
O. 
P.
Q. Tabel 4.9. Frekuensi dan Histogram Skor Persepsi guru
matematika tentang Alokasi Waktu
|
|
|
Frequency
|
Percent
|
Valid Percent
|
Cumulative Percent
|
|
|
Valid
|
20
|
2
|
40.0
|
40.0
|
40.0
|
|
|
|
21
|
1
|
20.0
|
20.0
|
60.0
|
|
|
|
22
|
2
|
40.0
|
40.0
|
100.0
|
|
|
|
Total
|
5
|
100.0
|
100.0
|
|
|
R. 
S.
T.
Tabel 4.10.
Frekuensi dan Histogram Skor Persepsi guru matematika tentang Evaluasi/Penilaian
|
|
|
Frequency
|
Percent
|
Valid Percent
|
Cumulative Percent
|
|
|
Valid
|
14
|
1
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
|
|
|
16
|
3
|
60.0
|
60.0
|
80.0
|
|
|
|
17
|
1
|
20.0
|
20.0
|
100.0
|
|
|
|
Total
|
5
|
100.0
|
100.0
|
|
|
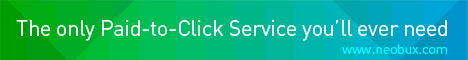



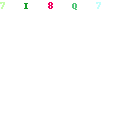


0 komentar:
Post a Comment